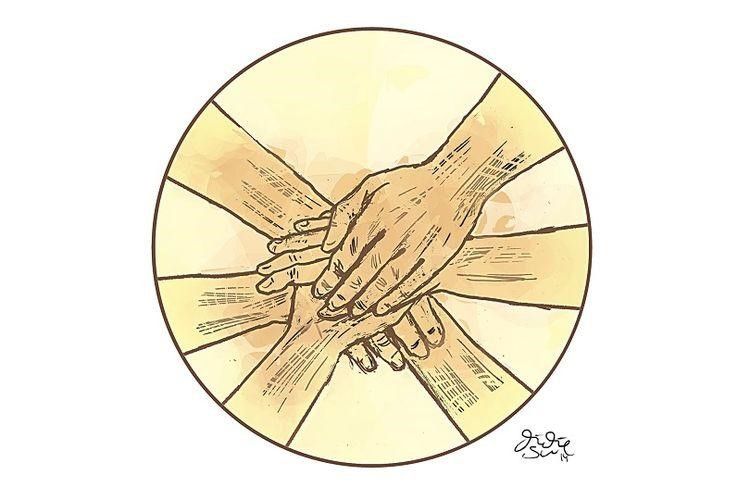Aku ini butiran debu yang tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Terbang melayang, bergantung pada hembusan angin yang membawaku ke mana-mana. Termasuk ke sebuah pesantren di pinggiran Jakarta seperti siang ini.
Ya, tepat siang ini. Aku menempel pada rambut seorang anak muda yang sibuk berorasi di tengah-tengah lingkaran besar. Beberapa pemuda lain yang kurang lebih sebaya duduk tepekur mendengarkan.
"Mereka sembarangan saja menyebut kita "oknum", Akhi. Oknum santri, oknum orang Islam. Juga menyebut pesantren kita pesantren abal-abal, pesantren radikal. Padahal kitalah pemurni ajaran Islam! Barisan kitalah yang nanti akan terpilih sebagai barisan yang masuk surga, bukan yang lain. KEMENAG itu tahu apa tentang ajaran Islam yang murni. Betul, Akhi?!"
Suaranya bergemuruh penuh amarah. Tangannya mengepal ke udara perlambang semangat muda, darah muda yang menggelegak.
"Betul. Shodaqta, Ustaz!" jawab para pemuda yang melingkarinya kompak.
Agitasi yang mereka sebut "taushiyah" itu terus berlanjut, terus dan terus. Kian lama kian membara. Api dan tombak berluncuran dari lisan tajamnya.
Aku tak kuasa menyimak rentetan kata-kata yang deras meluncur bagai air terjun. Hingga aku terhenyak saat seorang pemuda dari lingkaran menyelak bicara, "Jadi kita berjihad saja ya, Ustaz?!"
"Setuju. Angkat senjata, habisi mereka. Habisi mereka dan antek-anteknya. Habis perkara!" imbuh pemuda yang lain.
"Cincang mereka pade. Makdikipe!"
"Allahu Akbar!" pekik yang lain yang duduk di pojokan.
Seketika ruangan pesantren kecil itu riuh dengan teriakan takbir yang silih berganti. Energi yang demikian besar yang menghempaskanku pada kenangan masa lalu. Dj vu.
Sekian tahun lalu. Ratusan purnama silam. Aku ingat betul ketika itu aku terpuruk dalam kondisi serupa. Bedanya, di dalam sebuah gereja, jauh di timur Indonesia sana. Tepatnya di salah satu bangku di baris terdepan.
Kala itu seorang pendeta tampak berkhutbah di depan jemaatnya. Sebagian berwajah garang dengan pita merah di tangan dan kepala. Beberapa tampak membawa parang dan tombak tajam.
"Tuhan tahu kita yang paling benar. Kita domba terpilih, dan merekalah para domba tersesat. Maka akan runtuh langit jika kita tidak bernyali menghabisi mereka. Malu kita pada anak cucu kita kelak jika Kerajaan Kristus tidak tegak di tanah-Nya sendiri. Beranikah kalian, Wahai Laskar Kristus, untuk tegakkan Kerajaan Kristus?!"
"So pasti, Bapa. Haleluya!"
"Haleluya!"
"Pukimai mereka. Para pendatang yang tak tahu diri!"
Energi kebencian yang besar, luncuran kata-kata bertenaga, dan teriakan perjuangan yang sama-sama atas nama Tuhan. Tak sadarkah mereka bahwa Tuhan itu satu? Kenapa harus berseteru?
Sebagai butiran debu yang juga makhluk Tuhan, kendati tak dianggap oleh manusia, aku bingung dengan kelakuan para manusia itu. Andai aku punya kepala, mungkin aku akan pening memikirkannya. Untung saja Tuhan tak kasih aku kepala sehingga aku tak perlu pusing memikirkan mereka, para makhluk ekstremis. Tuhan takdirkan aku terbang saja, berkelana terhembus angin. Berpindah-pindah ke mana Tuhan menakdirkanku hinggap dan menetap.
Senandika ini mungkin akan terus berlanjut hingga jika seorang sastrawan mungkin akan bisa menuliskan curahan butiran debu ini sebagai novel berjudul "Ratapan Butiran Debu".
Meskipun aku tak yakin novel tersebut akan laris terjual atau best seller. Justru kemungkinan besar akan dirazia para ekstremis itu. Ah, untunglah aku hanya butiran debu!
Dan takdir Tuhan menerbangkanku lagi meninggalkan pinggiran Jakarta yang panas meranggas. Angin, sang sahabat setia, tak banyak berkata-kata. Ia hanya membawaku kemana-mana, tanpa banyak bincang.
Termasuk juga saat meninggalkanku di depan sebuah toko televisi di pusat kota Jakarta. Ada beberapa calon pembeli masuk melihat-lihat. Tampak sebuah pesawat televisi berukuran besar menyala. Rupanya sedang ada acara gelar wicara (talkshow).
"Bagaimana pendapat Anda tentang gerakan ekstremisme agama yang marak belakangan ini, Profesor?"
Demikian pertanyaan sang penyiar jelita kepada seorang bapak berkacamata yang tampaknya bijak.
"Fenomena gerakan ekstremisme agama ini bukan fenomena tunggal di Indonesia saja. Di belahan dunia lain pun ada, termasuk juga di Amerika Serikat. Ini fenomena global. Dan ekstremisme atau gerakan anti-moderasi beragama itu ada di semua agama. Senantiasa ada kutub-kutub ekstrem di setiap agama. Ini juga bagian dari dialektika peradaban antara kalangan puritan yang semata-mata hanya berpatokan pada tafsir tradisional kitab suci dan kalangan moderat yang juga memandang lebih luas lebih dari sekadar tafsir tersebut..."
" ... Wajar saja, sepanjang mereka tidak menempuh jalan kekerasan. Komitmen mereka pada sikap anti-kekerasan itulah yang akan menentukan seperti apa penilaian publik pada aspirasi mereka yang ramai mereka perjuangkan dengan militan," urai sang profesor dengan rentetan kata-kata mutakhir nan canggih dengan santun.
Aku tepekur mendengarnya. Juga aku sedih. Bukan karena terharu, tetapi karena tidak bisa memahami sebagian besar perkataan sang profesor bijak.
Andai aku punya kepala, mungkin aku akan pening memikirkannya. Untung saja Tuhan tak kasih aku kepala sehingga aku tak perlu pusing berpikir.
Tapi sejenak aku terhenyak.
Bukankah kaum ekstremis di mana pun itu punya kepala? Mengapa mereka tidak memikirkan apa yang dikatakan sang profesor bijak? Lantas buat apa mereka punya kepala jika tidak tahu apa fungsinya?
Ah, andai aku punya kepala, mungkin aku akan pening memikirkannya. Untung saja Tuhan tak kasih aku kepala sehingga aku tak perlu pusing berpikir. Toh, aku ini hanya butiran debu...
Jakarta, 17 Desember 2021
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H