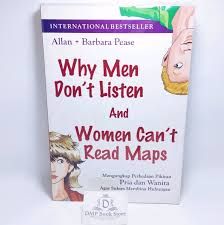Mungkin ia memang tidak tahu atau tidak mengerti. Sekolahnya hanya sampai kelas 5 Sekolah Rakyat (sebutan SD saat itu).
Tapi ia tentu memahami bahwa puteranya butuh istirahat. Mungkin ia tidak mengerti apa yang ditulis puteranya ini, tapi ia memahami betapa puteranya punya potensi.
Barangkali itulah yang membuat ibu memotivasiku untuk langsung mengikuti ujian kelulusan Madrasah Ibtidaiyyah (setara SD) sementara aku masih kelas 4 SD. Waktu itu kebijakan pemerintah Orde Baru memungkinkan hal tersebut.
Sebagaimana lazimnya anak Betawi di era 80-an, aku bersekolah ganda dalam waktu yang bersamaan. Pagi di SD Negeri, dan siang sampai sore di Madrasah Diniyah untuk belajar ilmu agama. Kami menyebutnya Sekolah Arab.
Selepas Maghrib, ada pengajian anak-anak yang dibimbing seorang ustaz di dekat rumah.
Selepas Isya, sebetulnya ada pelajaran tambahan bela diri silat Betawi dari sang ustaz.
Tapi aku lebih sering absen. Sebab biasanya selepas latihan silat, aku terlalu lelah dan langsung terkapar tidur.
Padahal aku suka sekali menonton film di TVRI (satu-satunya stasiun TV di Indonesia saat itu) yang saat itu hanya ditayangkan di ujung program, sekitar pukul 11 malam.
Hanya perempuan yang bisa memahami?
Ujian kelulusan yang diikuti murid kelas 6?
Aku setengah mati menolak dorongan ibu. Perasaan tidak mampu dan minder mendominasi diri.