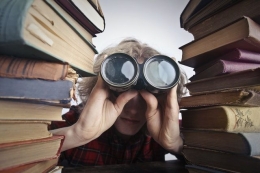Pernahkah kamu ketika ada seseorang sedang mempresentasikan karyanya kemudian kamu berpikir dalam hati "saya juga bisa kalau hanya begitu saja." Perasaan ini muncul karena kamu menganggap kamu lebih tahu mengenai topik tersebut. Pernah?
Atau pernahkah kamu sedang dalam kondisi mood yang tidak baik kemudian kamu bersikap negatif kepada rekan atau kolega kamu di kantor. Pernah?
Contoh lain yang lebih kasual misalnya, kondisi cuaca saat ini panas sekali kemudian kamu singgah di minimarket kesayangan kamu. Kemudian kamu tanpa pikir panjang mengambil beberapa minuman dingin yang sebenarnya kamu juga tidak terlalu suka.
Ini kamu lakukan karena otak kamu sedang panas. Emosi kamu sedikit naik, jadi kamu pikir lebih baik minum sesuatu yang dingin. Padahal tidak semua minuman dingin itu akan kamu habiskan. Pernah?
Contoh aktual misalnya, kamu sedang menonton pertandingan sepak bola Euro 2020 di saluran favorit kamu dan ketika kamu emosi karena salah satu pemain dari tim kesayangan kamu gagal menendang bola masuk ke gawang lawan, kamu jadi berteriak "begitu saja tidak bisa sih!", pernah?
Saya pernah. Begini ceritanya, saat itu saya sedang dalam perjalanan pulang dari kantor dan kebetulan hari itu saya lelah sekali. Banyak meeting dan drama yang terjadi di kantor.
Dalam perjalanan pulang tersebut, perut saya terasa lapar sekali. Kemudian saya mampir sejenak di salah satu minimarket. Saking laparnya saya membeli banyak sekali snack dan roti. Melebihi dari yang seharusnya saya butuhkan.
Otak saya terpedaya oleh rasa "lapar" yang tadi saya rasakan. Padahal mungkin dengan sepotong roti dan satu botol air putih sudah cukup untuk mengganjal rasa lapar saya. Saya pun tiba di rumah dengan banyak sekali makanan yang sebenarnya tidak saya perlukan.
Jika kamu pernah mengalami hal-hal di atas atau seperti yang saya alami, maka kamu mengalami sesuatu hal yang di dalam behavioral science disebut dengan Empathy Gap.
Bias kognitif yang terjadi di otak kita yang membuat otak kita terpedaya dengan kondisi emosional saat kita melakukan tindakan tersebut.
Kalau dalam contoh sepak bola di atas, karena kita sedang emosi dengan mudah kita mencerca tim kesayangan kita. Padahal jika kita yang berada di posisi mereka belum tentu kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan.
Mari kita urai satu per satu benang merah empathy gap ini dengan logis agar kita bisa terhindar dan tetap bisa bergerak maju.
Apa Itu Empathy Gap?
Beberapa definisi muncul dari riset-riset mengenai empathy gap ini, jika disimpulkan adalah bias yang muncul karena otak kita salah mengambil respon terhadap pengaruh berbagai keadaan mental pada perilaku kita sendiri dan membuat keputusan yang hanya memuaskan emosi, perasaan, atau keadaan kita saat itu (referensi 1).
Bias ini dikenal juga dengan bias hot-cold empathy gap. Hot disini merujuk pada terjemahan secara metafora "panas", yaitu kondisi emosi kita yang sedang marah, lapar, sakit, lapar (seperti contoh cerita saya di atas) yang mempengaruhi logika dan tingkat rasionalitas kita. (referensi 2).
Cold di sini merujuk kepada kondisi emosi kita yang sedang adem atau tidak dalam kondisi marah dan yang lainnya di atas. Ketika kita dalam kondisi cold maka titik ini akan mampu membuat kita berpikir dengan jernih.
Kenapa mengetahui hal ini menjadi penting? Alasannya adalah dengan kita tahu cara kerja empathy gap ini maka kita bisa berpikir dan misalnya duduk sejenak menarik nafas sebelum kita mengambil keputusan.
Saya pikir banyak orang yang tidak sadar kondisi mental dan emosi mereka ketika sedang dalam proses pengambilan keputusan. Yang sering terjadi adalah penyesalan di kemudian hari.
Misalnya, kita tiba di rumah dalam keadaan senewen karena kena omelan atasan, kemudian anak kita berlari-lari menyapa dan mendekati kita dengan maksud mengajak bermain, respon yang muncul dari kita malah amarah.
Setelah kita marah-marah ke anak kita dan dia menangis baru kita menyesali setelah mata kita menatap mata anak kita. Dia hanya ingin bermain dengan kita.

Tiga orang peneliti yaitu George Loewenstein, Ted O’Donoghue dan Matthew Rabin memberikan pandangan bahwa kondisi mental kita pada saat tertentu tersebut akan menjadi panduan bagi perilaku kita pada saat tertentu itu pula.
Jika pandangan ini saya elaborasi lebih lanjut, ini artinya adalah apa pun sikap atau hasil pengambilan keputusan kita akan sangat tergantung pada kondisi mental kita tepat pada momen sikap atau pengambilan keputusan tersebut terjadi.
Momen tersebut yang akan menjadi ancar-ancar bagi sikap kita ke depan. Jadi jangan heran ketika sikap kita emosional selalu marah-marah, orang lain dengan mudah akan memprediksi itulah sikap kita di masa mendatang.
Ini juga sebabnya ibu saya selalu memberi nasihat jika kepala sedang panas, jangan langsung masuk rumah. Anjuran ini sangat selaras dengan konsep empathy gap ini.
Jika kita melihat dari sudut pandang pemasaran misalnya, empathy gap ini akan membuat kita melakukan pembelian yang tidak rasional.
Dalam contoh cerita saya di atas, sikap saya ketika lapar menjadi tidak rasional. Jika kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap bias ini maka akan sangat berbahaya.
Kita bisa jadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak rasional dan di luar nalar. Padahal kita tidak bermaksud demikian. Sikap kita yang tidak rasional tersebut bisa berujung kepada tindakan yang menyakitkan dan tidak menyenangkan bagi orang lain.

Setiap hari kita pasti mengambil puluhan bahkan ratusan keputusan. Puluhan dan ratusan keputusan tersebut kemudian akan membentuk pola dan perilaku sosial kita.
Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan tindakan kita adalah emosi (referensi 3). Sehingga jika kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap emosi ini maka akan sangat berpengaruh ke hasil akhir tindakan kita.
Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai berikut:
1. Coba tempatkan diri kita di posisi tersebut
Mencoba menempatkan diri kita seandainya kita di posisi yang tidak mengenakkan tersebut bagaimana rasanya. Ibu saya selalu memberi wejangan "jangan mencubit kalau tidak mau dicubit," yang artinya kita coba benar-benar berempati yang sejati.
Sulit memang. Saya pikir ini salah satu kebiasaan yang gampang diomongkan tapi susah dilaksanakan. Dalam cerita saya di atas harusnya saya bisa menempatkan diri dengan tidak rakus memborong banyak snack dan roti. Padahal sampai rumah juga tidak saya makan.
Seandainya saya menempatkan diri di posisi orang-orang yang benar-benar membutuhkan makanan mungkin akan lebih baik.
2. Melatih diri melihat dari perspektif yang berbeda
Ini terkait dengan poin nomor satu. Jika kita mampu memposisikan diri dalam situasi dan posisi tersebut, maka otomatis kita akan mampu melihat perspektif lain yang tadinya belum terlihat.
Terkadang ini memang tidak menyenangkan. Saya pribadi mengakui hal tersulit adalah melihat dari perspektif lain. Beberapa kali saya terjebak emosi dan perasaan tidak menyenangkan ketika mendapat umpan balik atau kritik.
Terkadang saya gagal paham juga. Namun satu yang saya pahami adalah saya harus bisa melakukan kontrol terhadap apa yang bisa saya kontrol, yaitu emosi dan perspektif saya.
Keberhasilan kita melihat perspektif yang berbeda inilah yang akan membuat kita mampu melakukan kontrol diri sendiri. Jadi menurut saya ini adalah hubungan resiprosikal.
Keberhasilan kita untuk melihat perspektif orang lain adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Namun respon orang lain terhadap perspektif kita adalah tentunya juga merupakan tanggung jawab masing-masing pribadi.
Kita memang seharusnya memahami perspektif orang lain. Namun kita tidak bisa melakukan kontrol terhadap perspektif orang lain ketika mereka mencoba memahami perilaku sosial kita.
3. Banyak Membaca
Mungkin ada yang bertanya-tanya apa hubungannya mengatasi empathy gap ini dengan banyak membaca. Banyak membaca di sini bukan hanya terbatas pada bahan bacaan berupa buku, tapi bisa dalam bentuk artikel di Kompasiana.
Dengan banyak membaca dari buku-buku berkualitas dan banyak penulis yang berkumpul di Kompasiana, kita menjadi belajar untuk memahami sudut pandang mereka ketika melihat suatu fenomena sosial.
Dengan banyak membaca kita juga bisa secara persisten menjaga proses koheren otak kita untuk menganalisa suatu fenomena berdasarkan apa yang kita baca.
Membaca juga dapat memperluas jendela gagasan dan kemampuan dialektika kita untuk membaca argumentasi dengan perspektif yang berbeda.
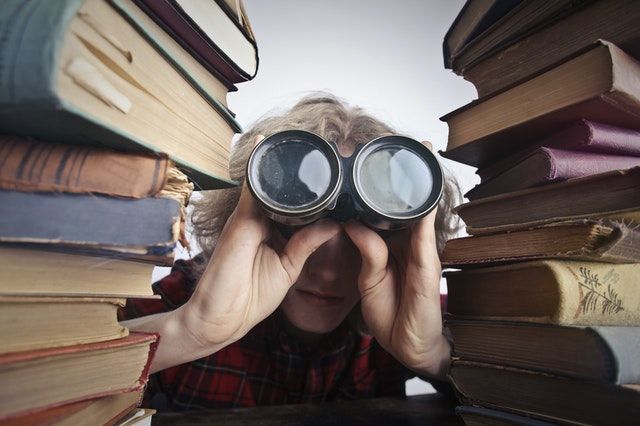
Setiap hari kita membuat keputusan dan semua keputusan tersebut pada akhirnya membentuk perilaku sosial kita. Di era saat ini dimana sudah ada predictive analysis, kita harus benar-benar memikirkan setiap konsekuensi dari perilaku sosial kita.
Salah satu faktor utama yang dapat membuat bias keputusan kita adalah emosi. Paradoksnya adalah emosi pula yang membuat kita sanggup memahami perspektif lain dari sebuah perilaku sosial.
Ketika kita dalam kondisi bahagia pasti sulit memahami perasaan orang yang sedang bersedih. Jika kita sedang berada di atas angin pasti tidak mudah melihat yang sedang di bawah roda kehidupan.
Memang sulit memahami perspektif orang lain sampai kita benar-benar berada di posisi orang tersebut. Namun tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar memahami sudut pandang yang mungkin akan lebih meluaskan horizon dan relung pemikiran kita.
Salam Hangat
Referensi tambahan:
1. Sayette, M. A., Loewenstein, G., Griffin, K. M., & Black, J. J. (2008). Exploring the cold-to-hot empathy gap in smokers. Psychological science Journal.
2. Verdone, M. (2019). Stress and the Hot-Cold Empathy Gap.
3. Loewenstein, G. (2005). Hot-cold empathy gaps and medical decision making. Health psychology Journal.
4. Uhl, M. (2011). Challenging the intrapersonal empathy gap: An experiment with self-commitment power (No. 2011, 019). Jena Economic Research Papers.
5. Kristjánsson, K. (2010). The empathy gap: building bridges to the good life and the good society.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI