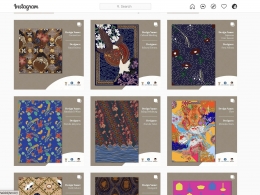Sembari membatik, saya ngobrol dengan ibu pembatik (maaf saya lupa nama beliau) disana.
Beliau bercerita kalau dulu pembatik di museum tersebut jumlahnya cukup banyak, namun kini hanya beliau satu-satunya yang membatik di museum tersebut. Anak-anaknya tidak ada lagi yang tertarik untuk membatik.
"Kurang menghasilkan", begitulah jawaban beliau, saat saya bertanya mengapa anak-anaknya tidak ada yang mau membatik.
Alasan lainnya dikemukakan oleh salah satu pembatik Batik Tulis Oey Soey Tjoen, adalah kotor dan malas. Sedangkan anaknya yang satu lagi bisa membatik, namun kurang berkualitas. Mengingat membatik diperlukan rasa seni dan kesabaran yang tinggi.

Ah, kalau diingat-ingat lagi, saat saya mengikuti workshop membuat batik, memang perlu kesabaran yang tinggi. Belum lagi rasanya panas sekali harus duduk didekat lilin malam yang dipanaskan.
Hanya saja sungguh disayangkan kalau membatik tidak lagi diminati oleh anak muda Indonesia.
Capai-capai "bergontokan" dengan negeri tetangga kala itu, yang sempat mau mengakui Batik sebagai budaya asli negerinya. Hingga akhirnya diakui juga oleh UNESCO, eh, bisa jadi menghilang begitu saja karena minimnya minat anak muda meneruskan seni membatik.
Duh, amit-amit, jangan sampai hal ini terjadi.
Tapi disela kekhawatiran tersebut, ternyata ada juga pembatik muda yang sangat mencintai seni batik.