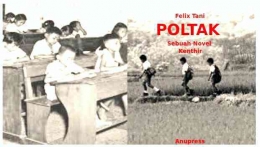"Saya menganggit novel Poltak selayaknya melukis dengan teknik mosaik." -Felix Tani
Mungkin ada pembaca novel Poltak di Kompasiana bertanya-tanya. "Apakah ini novel, atau kumpulan cerpen, atau serial humor?"
Sebagai penganggit, saya harus bilang, Poltak ditulis sebagai sebuah novel. Sekurangnya, saya niatkan sebagai novel.
Tapi, tukas pembaca lagi, mengapa tidak terkesan sebagai sebuah novel? Mengapa justru terbaca sebagai seri cerita yang terpisah-pisah. Setiap nomor bisa berdiri sendiri sebagai sebuah cerita.
Novel Poltak itu memang bisa dibaca secara anarkis. Bisa mulai dari depan, tengah, atau belakang. Secara runtut ataupun loncat-loncat. Sesukamu.
Ujungnya akan sama saja. Kisah tentang kesahajaan hidup seorang anak kecil bernama Poltak. Seorang anak Batak kelahiran kampung Panatapan.
Kisahnya terfokus pada pengalaman-pengalaman sosial biasa seorang anak kecil. Pada usia prasekolah dan semasa sekolah di sebuah SD Negeri di Hutabolon.
Panatapan dan Hutabolon, keduanya pseudonim, yang menjadi ajang geografis novel itu adalah dua kampung kecil di Tanah Batak.
Sebelum mulai menulis novel Poltak, saya sudah membaca empat novel yang berkisah tentang masa kanak-kanak. Khususnya masa sekolah dasar. Saya membaca Matilda-nya Roald Dahl, Totto Chan-nya Tetsuko Kuroyanagi, Duabelas Pasang Mata-nya Sakae Tsuboi dan, tentu saja, Laskar Pelangi-nya Andrea Hirata.
Keempatnya adalah novel hebat yang mustahil ditiru. Jujur, saya sangat terinspirasi oleh novel-novel itu. Sambil menyadari mustahil bisa menulis sehebat itu.
***
Saya bukanlah seorang penulis fiksi. Saya besar dalam tradisi penulisan sains, non-fiksi. Sekalipun itu dua tradisi literasi yang bisa saling menginspirasi, tapi jelas berjalan di dua rel paralel. Sekat demarkasinya tegas.
Pertanyaan besar bagi saya saat memutuskan menulis Poltak adalah soal teori dan metode. Dengan tuntunan teori dan metode macam apa saya harus menuliskannya?
Saya bingung. Benar-benar bingung. Sedikitpun saya tak punya pengetahuan tentang teori dan metode sastra.
Saya cuma punya pemikiran akan menulis kisah masa kecil Poltak di masa lalu berdasar pandangan masa kini. Dengan konsekuensi pikiran, perkataan, dan tindakan tokoh Poltak mungkin akan melampaui zamannya. Itu semacam pengabaian terhadap prinsip konjektur konsistensi-diri dari fisikawan Igor D. Novikov.
Tapi bagaimana caranya?
Sampai pada suatu titik buntu, saya mendadak teringat pelajaran melukis dengan teknik mosaik sewaktu sekolah di seminari pada pertengahan 1970-an.
Itu seperti anekdot Newton kejatuhan buah apel. Maka jadilah hukum gravitasi Newton. Atau Archimedes berendam dalam bak mandi. Maka jadilah Hukum Archimedes.
Teknik mosaik sendiri adalah melukis dengan cara menyusun ratusan bahkan ribuan keping-keping unik kecil warna-warni sehingga membentuk sebuah lukisan utuh. Kelak teknik mosaik itu mengilhami permainan lukisan passel (puzzle).
Eureka!
Maka jadilah saya mulai menulis nomor-nomor novel Poltak sebagai keping-keping unik sebuah lukisan mosaik. Novel Poltak saya andaikan sebagai sebuah lukisan mosaik. Citra seutuhnya baru dapat diketahui nanti setelah keping terakhir dilekatkan.
Dengan mengambil teknik mosaik itu sebagai cara tulis, sejatinya saya sudah menerapkan anarkisme metodologi ala filsuf Paul Feyerabend. Artinya, metode apa saja boleh dalam sastra.
Karena pendekatan tulisnya seperti itu, maka izinkan saya menyebut Poltak sebagai sebuah "novel mosaik". Dia adalah produk anarkisme metodologi.
Apakah hal itu sesuatu yang baru dalam khasanah sastra? Jujur, saya tidak tahu.
Yang kutahu, sampai hari ini saya sudah menganggit 97 keping (nomor) dari novel mosaik Poltak itu. Barangkali tak sampai sepuluh keping atau nomor lagi, maka novel mosaik itu akan selesai.
Dan bila nomor terakhir sudah selesai, saya berharap, para pembaca Poltak akan dapat menerima bahwa mereka memang sedang membaca sebuah novel yang seutuhnya.
Seperti citra indah lukisan mosaik baru akan terlihat setelah keping terahir dilekatkan, demikian pula keindahan novel mosaik Poltak akan terasakan setelah nomor terakhir menutupnya.
Saya sudah menuliskan proses kreatifku di sini. Itu sebagai pertanggung-jawaban. Sekaligus pertinggal bila ikhwal metode itu suatu saat hilang dari ingatan. Juga, barangkali, sebagai kontribusi metode dalam dunia sastra. Mana tahu ada manfaatnya bagi pembaca, bukan?
Ah, maafkanlah. Si tua ini sudah terlalu banyak bertutur. Lupa bahwa kamu mungkin bukan salah seorang dari sedikit pembaca setia novel Poltak.
Mauliate. Horas jala gabe. (eFTe)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H