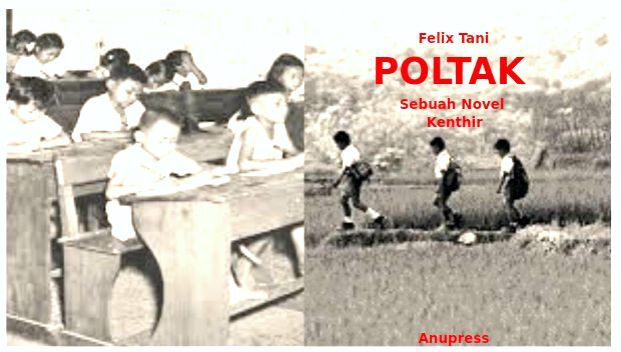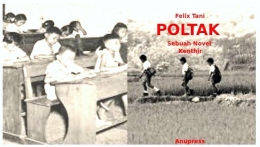Hidup masih tetap kegembiraan anak kecil bagi Poltak. Kendati sejatinya tak seringan saat semasa kakeknya masih ada. Kini Poltak harus mulai mengerjakan urusan-urusan yang tadinya dilakukan kakeknya.
Di sawah, dia harus membantu neneknya mencangkul, membajak, menggaru, meninggikan pematang, dan mengatur aliran air irigasi. Itu pekerjaan-pekerjaan baru disamping membantu tanam padi, menghalau burung, dan panen.
Walau hari-harinya terasa semakin sibuk, Poltak tak pernah merasakan itu sebagai beban. Dia menganggapnya sebagai konsekuensi dari pertambahan usianya.
"Jangan jadi Si Butong Mangan," kata neneknya menasihati. Berulangkali. Si Butong Mangan, seseorang yang takmau berkerja, maunya cuma makan (mangan) kenyang (butong). Itu julukan paling memalukan, kalau bukan nista, bagi seorang petani Batak.
"Babi kita Si Butong Mangan, Ompung," tukas Poltak, mencoba bela diri di saat virus malas menyergap.
"Babi digemukkan untuk dijual kelak. Kau mau Ompung jual nanti?" Poltak langsung kaku lidah.
Taksudi jadi Si Butong Mangan. Itu jugalah motif Poltak ikut mencari kayu bakar ke hutan pinus sore itu, sepulang sekolah.
Bersama Poltak ada Binsar dan Bistok, tentu saja. Ditambah lima orang anak Panatapan lainnya. Dumaria, Rugun, Tioria, Ringkot, dan Lambok. Dumaria, tertua di antara semua anak itu, bertindak sebagai pimpinan. Dia kakak Binsar, karena itu terbilang namboru untuk Poltak.
Seorang pimpinan diperlukan untuk memastikan anak-anak pencari kayu bakar itu tak tercerai-berai di hutan pinus. Semua anak harus berada dalam jangkauan pengawasannya.
"Sudah banyak kau dapat, Poltak?" teriak Binsar, bertanya. Poltak berada agak jauh dari posisinya, sedang memanjat sebatang pohon pinus.
"Sedikit lagi, Binsar! Ada ranting kering di sini!"
"Jangan banyak-banyak! Nanti terlalu berat, tambah pendek pula kau!" ledek Bistok. Entah di mana posisinya.
Anak-anak Panatapan terbiasa mencari ranting kering di hutan pinus untuk keperluan kayu bakar. Caranya bisa menggunakan galah pengait atau memanjat pohon untuk mematahkan ranting-ranting kering. Anak perempuan pakai galah, anak laki memanjat.
"Oiii! Sudah sore! Cukup dulu! Kita pulang!" Dumaria berteriak mengingatkan. Itu berarti semua anak hurus berkumpul di titik yang sudah ditentukan sebelumnya.
"Sudah kumpul semua? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bah! Kurang satu orang! Kita kan berdelapan tadi!" Dumaria kebingungan. Cemas karena hitungan tak genap delapan.
"Delapan!" Poltak berteriak sambil melontarkan buah pinus, tepat jatuh di ubun-ubun Dumaria.
"Bah, jangan kurangajar kau sama namboru, Poltak!" tegur Dumaria. Tak urung dia terkikik juga karena lupa menghitung dirinya sendiri.
Mereka jalan beriring pulang dari tengah hutan pinus sambil menyunggi ikatan kayu bakar di kepala masing-masing. Dumaria berada di posisi paling belakang, untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal di dalam hutan.
"Namboru, aku kencing dulu." Poltak minta ijin berhenti kencing sebentar. Diturunkannya ikatan kayu bakar dari kepala, lalu disandarkan pada batang pohon pinus di tepi jalan tikus.
"Jangan lama-lama, Poltak. Namboru tunggu kau!"
"Olo, namboru!"
Matahari sudah sangat condong ke barat, sekitar pukul empat sore, ketika rombongan anak-anak pencari kayu bakar itu tiba kembali di Panatapan.
"Bah! Duma! Poltak di mana?" Nenek Poltak berteriak menanyakan keberadaan Poltak. Dumaria dan Binsar baru saja menurunkan kayu bakar dari atas kepala.
"Bah! Barusan sudah sampai juga, kan, inangtua!" Dumaria kaget tak alang kepalang. Darahnya terasa menyembur dari jantung ke kepalanya.
Tadi, sehabis Poltak kencing, Dumaria jelas-jelas melihat anak itu menyunggi kembali kayu bakar di atas kepalanya, lalu berjalan di depannya tanpa bicara. Setiba di jalan besar, jalan raya Trans-Sumatera, dia memang tak memperhatikan Poltak lagi. Pikirnya semua anak sudah keluar dari hutan, Panatapan sudah tampak, jadi sudah aman.
"Bah. Ya, sudah, kalau begitu." Nenek Poltak segera bergegas masuk ke dalam rumah, setelah Dumaria menjelaskan kejadian di tengah hutan pinus tadi. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan.
Sementara itu, di tengah hutan pinus, Poltak berteriak-teriak memanggil Dumaria, namborunya.
"Namboru! Namboru! Namboru!" Tidak ada jawaban. Hanya gema teriakannya yang bersahut-sahutan di kejauhan. Setelah itu sepi yang mencekam. Ditingkahi desau pucuk-pucuk pinus ditiup angin sore.
Ditinggal Dumaria, Poltak memutuskan untuk berjalan mengejar namboru dan teman-temannya. Tapi, setelah sekian lama berjalan, ternyata dia menemukan dirinya berada kembali di tempat dia tadi kencing. Tidak kunjung keluar dari dalam hutan pinus.
Panik dan rasa takut menyergap Poltak. Bulu romanya berdiri, kepalanya terasa membesar. Suasana di bawah hutan pinus terasa menakutkan. Mulai agak gelap dan dingin. Bunyi tongkeret terdengar bersahut-sahutan. Pertanda matahari sebentar lagi terbenam.
"Ompung, tolonglah aku." Poltak berseru dalam hati terdalam, mohon pertolongan kepada neneknya.
"Kalau tersesat di hutan, diam saja. Tunggu pertolongan. Jangan berjalan, sebab bisa tersesat semakin jauh." Neneknya pernah memberi nasihat itu.
Kemungkinan seseorang tersesat di dalam hutan pinus itu memang sangat besar. Lantai hutan itu agak gelap, karena sinar matahari terhalang tajuk pinus yang rapat dan lebat. Semua pohon pinus tampak seragam, ukuran dan jaraknya satu sama lain terlihat sama sama saja. Jika salah ambil langkah, maka ada kemungkinan seseorang bukannya keluar dari tengah hutan, tapi masuk semakin jauh ke tengah.
Poltak diam duduk di tempat. Berdoa dalam hati. Dia yakin, sangat yakin, neneknya akan datang menolongnya.
"Amang, pahompuku. Ikut ompung. Kita pulang sekarang." Tiba-tiba saja nenek Poltak sudah berdiri di hadapannya. Tanpa bicara lagi, neneknya mengangkat ikatan kayu bakar, menyungginya, lalu berjalan menyusuri jalan tikus yang tadi tak terlihat oleh Poltak.
"Ompung!" Poltak berteriak gembira. Hendak memeluk neneknya. Tapi neneknya sudah balik badan dan langsung berjalan pulang. Diam seribu bahasa. "Ompung marah," batin Poltak. Dia memutuskan untuk diam saja mengekor neneknya.
Langit di barat sudah lembayung saat Poltak dan neneknya tiba di mulut jalan masuk ke Panatapan. Matahari sebentar lagi akan terbenam sempurna.
"Amang, kau pulang duluan, ya. Bawa ini kayu bakar. Ompung mau ke makam ompungdolimu sebentar." Nenek Poltak meletakkan ikatan kayu bakar di atas kepala Poltak. Lalu ompungborunya berjalan mendaki lereng bukit ke arah makam kakek Poltak berada.
"Olo, ompung." Poltak mengiyakan. Lalu berjalan menyunggi kayu bakar menuju Panatapan, sekitar limaratus meter jauhnya dari mulut jalan masuk.
"Poltak, pahompuku! Mauliate Tuhan! Pahompuku selamat sampai di rumah." Nenek Poltak menyambut cucunya itu di depan rumah. Memeluknya erat, menumpahkan airmata syukur dan sukacita.
"Ompung, cepat kali sampai di rumah." Poltak kebingungan. Sebab jarak dari kuburan kakeknya ke rumah lebih jauh dibanding jarak dari mulut jalan masuk kampung.
"Ompung dari tadi menunggumu di rumah, amang. Ayo, masuk ke rumah, sudah senja." Nenek Poltak merengkuh bahu cucu kesayangannya lalu menuntunnya naik ke dalam rumah. (Bersambung)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI