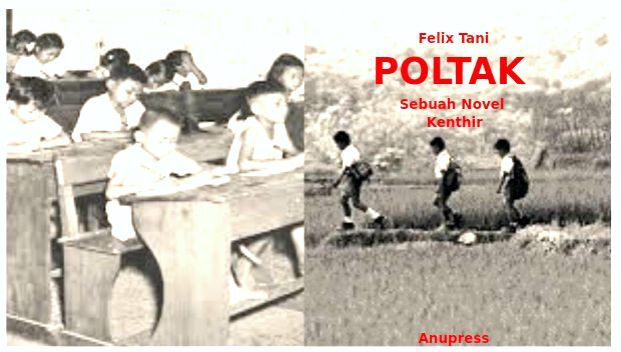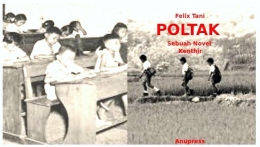Hidup masih tetap kegembiraan anak kecil bagi Poltak. Kendati sejatinya tak seringan saat semasa kakeknya masih ada. Kini Poltak harus mulai mengerjakan urusan-urusan yang tadinya dilakukan kakeknya.
Di sawah, dia harus membantu neneknya mencangkul, membajak, menggaru, meninggikan pematang, dan mengatur aliran air irigasi. Itu pekerjaan-pekerjaan baru disamping membantu tanam padi, menghalau burung, dan panen.
Walau hari-harinya terasa semakin sibuk, Poltak tak pernah merasakan itu sebagai beban. Dia menganggapnya sebagai konsekuensi dari pertambahan usianya.
"Jangan jadi Si Butong Mangan," kata neneknya menasihati. Berulangkali. Si Butong Mangan, seseorang yang takmau berkerja, maunya cuma makan (mangan) kenyang (butong). Itu julukan paling memalukan, kalau bukan nista, bagi seorang petani Batak.
"Babi kita Si Butong Mangan, Ompung," tukas Poltak, mencoba bela diri di saat virus malas menyergap.
"Babi digemukkan untuk dijual kelak. Kau mau Ompung jual nanti?" Poltak langsung kaku lidah.
Taksudi jadi Si Butong Mangan. Itu jugalah motif Poltak ikut mencari kayu bakar ke hutan pinus sore itu, sepulang sekolah.
Bersama Poltak ada Binsar dan Bistok, tentu saja. Ditambah lima orang anak Panatapan lainnya. Dumaria, Rugun, Tioria, Ringkot, dan Lambok. Dumaria, tertua di antara semua anak itu, bertindak sebagai pimpinan. Dia kakak Binsar, karena itu terbilang namboru untuk Poltak.
Seorang pimpinan diperlukan untuk memastikan anak-anak pencari kayu bakar itu tak tercerai-berai di hutan pinus. Semua anak harus berada dalam jangkauan pengawasannya.
"Sudah banyak kau dapat, Poltak?" teriak Binsar, bertanya. Poltak berada agak jauh dari posisinya, sedang memanjat sebatang pohon pinus.
"Sedikit lagi, Binsar! Ada ranting kering di sini!"