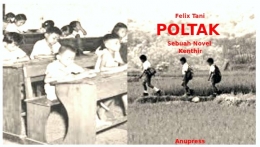"Apa ini, Alogo!" Suara Guru Barita menggelegar.
"Huruf sambung, Gurunami," jawab Alogo tak yakin. Mendadak hatinya kisut.
Hari itu murid-murid kelas dua belajar menulis huruf sambung. Guru Barita sudah menuliskan contoh di papan tulis. Kalimat peribahasa "Mati semut karena manisan."
"Huruf sambung ompungmu!" sentak Guru Barita. "Ini bukan huruf sambung! Tapi huruf-huruf kau kasi garis sambung!" Guru Barita meradang.
Rupanya Alogo tidak menulis kata dan kalimat dengan huruf-huruf sinambung. Tapi ditulisnya dulu huruf miring secara terpisah satu persatu. Baru setelah itu antara satu dan lain huruf dalam tiap suku kata dibubuhkannya garis sambung.
Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, karya Alogo itu huruf sambung juga namanya. Sekurangnya bisa disebut inovasi baru dalam teknik penulisan huruf sambung.
Anak-anak sekelas menertawakan Alogo. Kecuali Poltak. Bukan karena dia berempati. Bukan. Tapi karena bengkak di tenggorokan merintangi ledakan tawanya.
"Kalau aku tak congok, tak beginilah jadinya. Pasti sudah sembuh." Poltak menyesali dirinya.
Rangkaian peristiwa beberapa hari lalu berputar seperti film di kepalanya.
"Kau pasti tarhirim. Kau ingin makan apa, amang," tanya neneknya, hari Kamis minggu lalu, sore hari.
Tarhirim, sangat ingin makan sesuatu tapi tak kesampaian. Itu diagnosa neneknya atas gejala bengkak di tenggorokan Poltak. Alasannya, Poltak tidak demam. Pembengkakan itu juga tak menimbulkan rasa sakit. Cuma menyebabkan kesulitan bicara.