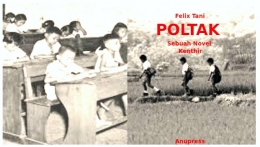"Bistok!Pantaslah kemiri habis! Kau pake marpinse rupanya! Kalah pula kau!"
Nai Basaria, ibu Bistok, membureas, marah-marah bikin kacau. Onggokan biji kemiri di tengah garis lingkar di halaman rumah diraupnya semua.
"Ini kemiri untuk bumbu masak! Bukan untuk marpinse!"
Poltak, Binsar, dan Bistok tegak diam berdiri pasrah di halaman rumah Bistok. Permainan pinse, pengisi pakansi sekolah, langsung berhenti.
Marpinse itu adu ketrampilan. Biji kemiri taruhan, lima biji per pemain, dionggokkan dalam garis lingkaran di tanah. Lalu, setelah suit menentukan giliran main, onggokan kemiri ditembak menggunakan biji kemiri gacok dari jarak duapuluh langkah. Jika onggokan kena dan ada biji kemiri keluar dari garis lingkaran, maka biji itu menjadi hak petembak.
Bistok memang petembak yang payah. Bidikannya selalu meleset sehingga kemirinya selalu pindah tangan kepada Poltak dan Binsar. Itu sebabnya dia menguras habis kemiri milik ibunya untuk modal main.
"Kita mengumpul buah makadamia saja. Nanti sore toke makadamia ke sini." Poltak usul, sekaligus mengingatkan rencana kegiatan pakansi mereka.
Tak perlu perdebatan. Sejurus kemudian tiga sekawan itu sudah berlarian masuk ke hutan makadamia di seberang jalan raya, sebelah barat Panatapan, lengkap dengan karung ukuran sedang di tangan masing-masing.
"Kalau sudah dapat duit, kita beli limun, ya." Usul Bistok sambil mencari dan memunguti buah makadamia jatuh di lantai hutan.
"Aku mau dua botol, bah! Biar tambah pintar!" Binsar menyahuti.
"Bah. Dasar kau congoklah, Binsar!" Tukas Poltak, disambut gelak tawa bertiga.
"Kita tak perlu lagilah pintar. Kita, kan, sudah naik kelas," lanjut Poltak. Gelak tawa semakin riuh.
Lantai hutan makadamia itu sangat teduh lagi sejuk. Tajuk pepohonan yang sangat rapat dan rimbun sempurna menghambat terpaan sinar matahari. Teduh dan sejuk itu bikin tiga sekawan semakin betah mencari buah makadamia.
"Sudah dapat banyak kau, Poltak?" Binsar ingin tahu.
"Baru setengah karung!"
"Aku juga!" timpal Bistok.
"Aku mau panjat saja. Mau kurontokkan buahnya dari atas." Poltak menaksir satu pohon makadamia yang buahnya lebat dan sudah tua.
Dalam sekejap Poltak, seperti seekor monyet, sudah berada di atas pohon makadamia itu. Dia berdiri di dahan yang berbuah lebat, sekitar enam meter di atas permukaan tanah.
Mengikuti cara Poltak, Binsar dan Bistok juga sudah berada di atas pohon makadamia pilihan masing-masing.
Bunyi dedaunan fan ranting bergesekan dikuti hujan buah tua berjatuhan ke lantai hutan terdengar riuh saat tiga sekawan itu menggoyang dahan-dahan makadamia. Dari satu dahan pindah menggoyang dahan lain. Sampai semua buah tua di pohon jatuh ke tanah.
Tiba-tiba, terdengar bunyi "kraaak ... krash krash ... buk ... kresek kresek kresek."
"Amangoi amang!" disusul teriakan kesakitan dari Poltak.
"Binsar! Lihat itu! Poltak jatuh dari pohon!" Bistok berteriak panik.
"Bah! Poltak! Kau tak mati, kan?" Binsar turun melorot cepat dari atas pohon dan berlari mendekati Poltak yang terduduk linglung di lantai hutan. Dalam sekejap Bistok mendekat juga.
"Jangan mati dulu kau, Poltak. Kita belum minum limun." Bistok berteriak, asal berteriak, panik.
"Matamulah limun. Sakit kali pun leherku. Tak bisa tegak lurus kepalaku." Poltak menyumpah lalu mengeluh. Kepalanya teleng ke kiri.
Poltak tidak waspada. Dia salah berpegangan pada ranting kering. Jatuhlah dia seperti nangka busuk dari ketinggian sekitar enam meter.
Beruntung pohon makadamaian yang dipanjatnya tumbuh di tanah miring. Karena itu dia tidak jatuh tegak lurus. Tapi menggelosor mengikuti kemiringan lantai hutan kira-kira sepuluh meter jauhnya.
Itu sebuah kemujuran. Tidak fatal akibatnya. Hanya cidera pada leher sehingga kepala Poltak jadi teleng.
"Cukuplah. Kita pulang saja sekarang!" usul Bistok.
"Bah, rugilah. Kita kumpul dulu buah-buah jatuh ini."
Poltak menolak, lalu memunguti buah-buah makadamia yang baru dirontokkannya. Dia berjuang menahan rasa sakit di leher dengan kepala teleng.
Binsar dan Bistok tak mau rugi juga. Mereka kembali ke pohon masing-masih dan memunguti buah-buah yang tadi berjatuhan.
Lumayan. Ditambah buah hasil perontokan, karung-karung tiga sekawan itu terisi hampir tigaperempatnya.
Toke buah makadamia, orang Sorpea, sudah hadir di mulut jalan masuk Kampung Panatapan. Siap bertransaksi dengan para pemungut buah makadamia, anak-anak Panatapan dan Robean.
Poltak, Binsar, dan Bistok juga ikut bertransaksi. Hasilnya, masing-masing mendapat tiga ringgit atau Rp 7.5.
Toke itu sudah menentukan harga. Sekarung penuh ukuran sedang harganya Rp 10. Jika terisi hanya tigaperempat karung, berarti Rp 7.5 atau tiga ringgit. Dibayarkan tunai dengan tiga lembar uang pecahan seringgit.
"Bah! Kenapa pula kepalamu teleng, amang?" Kakek Poltak bertanya heran dan cemas saat Poltak pulang ke rumah dengan kepala teleng dan uang tiga ringgit dalam genggaman.
"Jatuh dari pohon makadamia, Ompung."
"Bah. Ayolah kita ke rumah Ompung Toruan. Biar diurut lehermu itu." Kakek Poltak bergegas mengeluarkan sepeda dari dalam rumah.
"Oi, Ompung ni Poltak! Leher cucu kita terkilir. Jatuh dari pohon. Kami ke Toruan dulu." Kakek Poltak berteriak memberitahu nenek Poltak yang sedang memetik kopi di kebun belakang.
"Olo!" terdengar sahutan nenek Poltak dari kejauhan. Sementara Poltak sudah membonceng kakeknya, bersepeda ke Kampung Toruan, ke rumah neneknya dari pihak ibu, seorang dukun urut sohor.
"Bah. Tak apa-apa. Cuma urat lehermu yang bergeser. Sebentar pasti sembuh." Ompung Toruan memberi diagnosa. Dilanjutkanurut urat leher, menggunakan minyak urut dengan ramuan herbal.
"Poltak, kalau sudah selesai diurut, nanti temui ompung di kedai, ya?" Kakek Poltak beringsut keluar rumah dan pergi ke kedai di tepi jalan. Sebab tidak elok berada di rumah besannya yang sudah menjanda itu.
Tak perlu waktu lama bagi Ompung Toruan untuk mengembalikan urat leher Poltak yang bergeser itu ke tempat semula. Cukup selama dua penghisapan rokok. Rasa sakit di leher Poltak langsung hilang. Kepalanya tidak teleng lagi. Itulah gunanya punya nenek seorang dukun urut sakti.
"Bah. Sudah selesai, ya, amang. Sini, masuk dulu." Poltak dipanggil kakeknya masuk ke dalam kedai, seusai dia menjalani pengobatan urut.
"Oi, beri dulu sebotol limun untuk pahompuku ini." Kakek Poltak berteriak kepada pemilik kedai.
"Ah, nasib mujur takkan ke mana." Poltak tersenyum lebar, hatinya bersorak gembira.
"Ternyata, tak perlu kerja keras untuk mendapatkan sebotol limun. Cukuplah dengan cara jatuh dari pohon makadamia." Poltak membathin sambil meneguk cairan merah berkarbonasi itu dengan kenikmatan tak terperi. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H