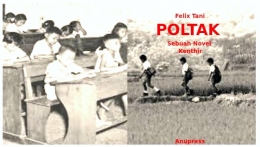Poltak benci perkelahian. Sebab itu menyakitkan. Bisa bikin gigi goyah. Atau hidung berdarah. Sekurangnya pipi atau mata lebam. Apa gunanya semua itu.
Lain soal bila pertandingan. Ada aturan main. Ada juri. Dengan begitu, risiko cidera bisa ditekan. Itu yang Poltak mau.
Tapi anak-anak SD Hutabolon, laki-laki, umumnya lebih suka perkelahian. Bukan pertandingan. Berkelahi itu laki, bertanding itu perempuan. Itu anggapan mereka.
"Dasar darahmu darah ayam." Jonder melecehkan Poltak. Hanya karena Poltak menolak tantangannya berkelahi.
"Berdarah ayam" berarti pengecut, penakut. Itu penghinaan terbesar. Tak ada anak laki Batak yang sudi dicap begitu.
Tapi Poltak menulikan telinga. "Tak ada gunanya berkelahi," bathinnya, sambil melangkah keluar komplek sekolah bersama Binsar dan Bistok. Mereka baru saja bubar sekolah.
Jonder dan temannya, Adian dan Jojor, mengekor di belakang mereka. Tiga anak itu sekampung di Sorpea, kampung yang terletak antara Hutabolon dan Panatapan.
"Poltak berdarah ayam! Berdarah ayam! Ayam!" Jonder dan kedua temannya berteriak-teriak mengejek dari belakang.
"Jangan berkelahilah. Tanding." Bistok menawar.
"Bah, Poltak perempuan, ya. Cantik kali!" Jonder semakin menjadi-jadi.
Jonder rupanya masih menyimpan rasa marah pada Poltak. Karena dulu, saat pelajaran Agama dari Guru Gayus, merasa dipersamakan Poltak dengan ular pembohong. Poltak sudah melupakan soal itu. Tapi Jonder masih menyimpannya dalam hati.
Suatu perkelahian, menurut pikiran Jonder, dapat menyelesaikan soal itu. Dia bernafsu membuat gigi Poltak goyah. Sekurangnya, hidungnya berdarah. Begitu baru impas.
"Sudah, kau terima saja tantangannya." Binsar mendorong Poltak.
"Bah, tak usahlah. Tak guna berkelahi." Poltak masih teguh pada pendirian.
"Oi, Poltak! Ayam betinalah kau!" Jonder melontarkan hinaan terakhir.
Ya, hinaan terakhir karena, sekejap kemudian, darah Poltak sudah muncrat ke ubun-ubun. Dia tak bisa terima dihina sebagai ayam betina.
Bagi Poltak, ini sudah masalah harga diri. Berkelahi memang sakit. Tapi harus dijalani demi harga diri. Begitu pikiran Poltak.
"Ke Peabolak! Kita berkelahi di sana!"
Poltak menerima tantangan Jonder. Tegas. Tak ada tanda dia berdarah ayam. Jonder kaget. Tak menyangka Poltak berani menerima tantangannya.
Dalam perjalanan ke Peabolak, Poltak berpikir keras. Strategi berkelahi macam apa yang harus dijalankannya.
Secara fisik, tubuh Poltak lebih kecil, pendek dan sedikit berisi, dibanding Jonder. Untuk memenangi perkelahian, Poltak harus menggunakan strategi yang cerdik.
"Kalau lawanmu lebih besar, kau harus jaga jarak." Demikian amangudanya, Parandum, pernah melatihnya beladiri. "Usahakan menghindar ke samping. Kalau ada kesempatan, langsung sepak pelirnya. Atau perutnya."
Begitulah, dalam tiga sore, Poltak dilatih Parandum beladiri dengan senjata utama tendangan. Untuk melatih kekuatan tendangan, Poltak diharuskan menghajar anakan pohon pisang sampai tumbang. "Itu tendangan karate," kata amangudanya.
"Tinju kiri, kau masuk rumah sakit. Tinju kanan, kau masuk liang kubur." Jonder menebar perang urat syaraf. Dia yakin bisa membereskan Poltak dengan satu dua pukulan.
Rombongan kecil berkepala dan berhati panas itu tiba di Peabolak. Tempat ini adalah padang penggembalaan kerbau untuk warga Sorpea. Di tengah padang itu terbentang Peabolak, semacam danau kecil.
Poltak dan Jonder kini sudah berhadap-hadapan di lapangan rumput. Di belakang masing-masing, berdiri teman-teman mereka untuk menyemangati. Di latar belakang, terbentang Peabolak dengan permukaan air berkilauan. Lebih jauh lagi, tampak hamparan sawah bertingkat. Lalu, di kejauhan, terlihat puncak Gunung Simarnaung. Sungguh, sebuah ajang kelahi yang indah.
Mendadak Jonder menyerang Poltak. Gaya kelahinya pungpang, menyeruduk sambil kedua tinjunya silih-berganti diayunkan ke depan. Persis anak kerbau yang menyerudukkan tanduknya kiri-kanan.
Terbiasa mengelak dari serudukan anak kerbau, Poltak cekatan menghindar ke samping kiri. Kesiur angin pukulan tangan kanan Jonder menerpa hidungnya. Jonder hadap kanan, kembali melontarkan tinjunya sambil merunduk.
Poltak menghindar lagi ke kiri lalu, secepat kilat, mengirim sebuah tendangan keras ke rusuk kanan Jonder.
Jonder mengaduh keras. Berhenti sejenak. Membungkuk memegangi rusuk kanannya dengan kedua tangan.
Poltak tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa ampun, sebuah sepakan keras dikirim telak ke selangkangan Jonder.
Jonder meraung kesakitan. Tersungkur ke tanah sambil memegangi selangkangannya. Perlawanannya terhenti.
"Pamangus! Lari!" Tiba-tiba Binsar berteriak keras, sambil menunjuk ke arah utara, lalu lari tunggang-langgang ke arah kampung Sorpea.
Bistok, Alogo, dan Togu langsung lompat. Lalu ikut tunggang-langgang di belakangcBinsar.
Poltak melihat ke arah utara. Di kejauhan terlhat seorang laki-laki berjalan ke arah mereka sambil membawa karung goni. Konon, itu ciri pamangus, penculik anak kecil untuk tumbal pembangunan jembatan atau gedung bertingkat.
"Jonder! Ayo! Lari!" Poltak disergap ketakutan dan balik badan untuk lari.
"Poltak! Tolonglah aku!"
Jonder meraung dan mengiba. Minta tolong. Dia masih meringkuk menahan sakit di tanah. Pipinya basah oleh air mata.
Poltak urung lari. Berbalik menatap Jonder. Belas kasihnya terbit. Dia segera membantu Jonder berdiri. Lalu menggandeng, tepatnya menyeret, lawannya itu lari terbirit-birit menyelamatkan diri.
Sejak saat itu tidak ada lagi sakit hati antara Jonder dan Poltak. (Bersambung)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H