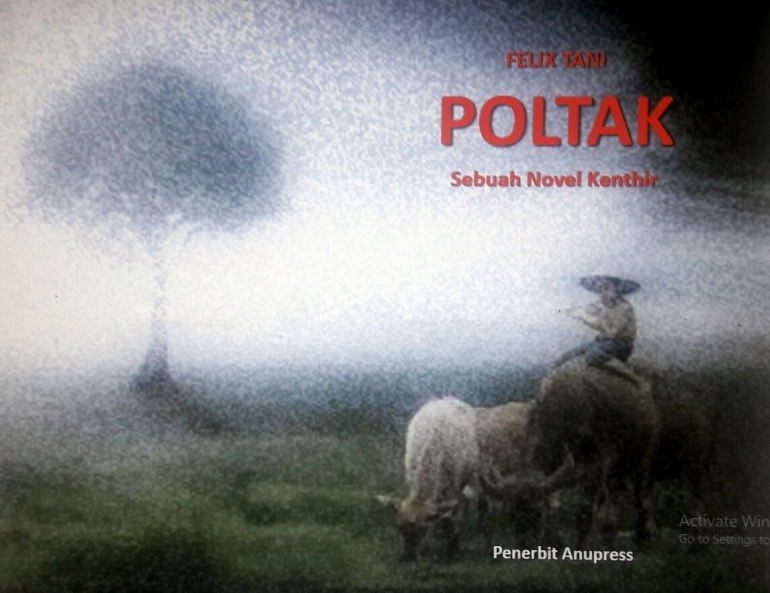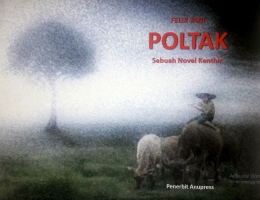Setelah panen terbitlah pesta. Dari pesta adat, pesta gotilon, syukuran panen sampai gondang naposo, pesta muda-mudi. Begitulah budaya agraris Batak Toba. Tak terkecuali dengan warga kampung Panatapan.
"Ompungni Poltak, besok sore kita ke Hutabolon. Menginap di sana." Ujaran kakek Poltak terdengar seperti maklumat. "Lusa kita manulangi Among dan Inong. Siapkanlah keperluan kita," lanjutnya. Tak perlu dirinci. Nenek Poltak sudah paham apa saja yang perlu dibawa.
Selepas pembicaraan dengan kedua orangtuanya di Hutabolon, kakek Poltak telah berkirim surat kepada adik-adiknya di Sumatera Timur. Memberi tahu kesediaan orangtua mereka untuk menjalani adat manulangi. Sekaligus mengingatkan agar mereka datang pada hari baik yang telah ditetapkan sesuai parhalaan, penanggalan Batak.
Seminggu yang lalu kakek Poltak sudah mendapat surat balasan dari adik-adiknya. Memberitahu kesediaan mereka untuk hadir menjalankan adat manulangi di Hutabolon.
Surat-menyurat itu terlaksana lewat jasa supir bus jurusan Toba-Medan. Kakek Poltak, dengan imbalan uang rokok, menitipkan surat untuk adiknya kepada supir bus itu. Supir bus menjatuhkan surat di depan sebuah kedai, di tempat yang telah ditentukan di Sumatera Timur. Lalu pemilik kedai, lewat seseorang, meneruskan surat itu ke alamat tujuan. Hal sebaliknya berlaku pula untuk surat balasan.
Sungguh, mereka tak memerlukan Kantor Pos. Supir bus sangat bisa diandalkan. Sejauh pengalaman, tak pernah ada surat yang tak sampai ke tujuan.
Hari besok cepat tiba. Cukup dengan mengantar matahari tenggelam di barat lalu menyambutnya kembali nongol di timur.
Semua anak dan menantu dari kakek-nenek buyut Poltak, dan beberapa orang anak mereka, sudah berkumpul di rumah besar Hutabolon. Suasana sungguh ramai. Tawa dan sapa silih berganti.
"Oi, Poltak, sudah besar kau, amang." Berulang kali ucapan itu diterima Poltak dari para kakek-neneknya yang bermukim di Sumatera Timur. Juga dari para amangudanya. Semua ramah pada Poltak. Semua memujinya elok rupa. Kecuali jika ingusnya sedang meler.
Tapi bukan keramahan itu, bukan pula segala pujian, yang bikin hati Poltak berbunga-bunga. Melainkan uang. Ya, uang.
Tiga orang kakeknya yang datang dari Sumatera Timur memberinya uang, serupiah masing-masing. Lalu seorang neneknya, anak perempuan buyutnya, memberi serupiah juga. Kakeknya yang tinggal di Hutabolon menambahkan satu rupiah. Sehingga Poltak punya kekayaan lima rupiah.
"Banyak kalilah uangmu, Poltak." Kakek Poltak nomor dua, bapak Si Binsar, menyanjung. "Ini, Ompung tambah serupiah. Nah, kaya raya kayu sekarang." Poltak menerima dengan gembira, "Mauliate, Ompung."
Kekayaan Poltak kini membengkak menjadi enam rupiah. Luar biasa. Dia percaya kata-kata kakeknya. Dirinya kaya raya kini. Mendadak.
Kakek nomor dua itu, walau tetangga rumah di Panatapan, baru kali ini memberi uang kepada Poltak. Tak mau kalah pamor dia dari adik-adiknya yang datang dari Sumatera Timur itu. Begitulah cara para kakek bersaing mengasihi cucunya.
Sebagai cicit sulung buyutnya, status Poltak memang istimewa. Sama seperti status bapaknya, cucu pertama untuk buyutnya. Mereka adalah penerus pertama garis darah keluarga. Karena itu namanya akan selalu disebut.
Terlebih dalam adat manulangi. Poltak dan bapaknya wajib hadir. Anak pertama, cucu pertama, dan cicit pertama adalah penanda hagabeon, keturunan yang besar, dan hasangapon, kemuliaan.
Malam cepat tiba di Hutabolon. Lampu petromaks dinyalakan. Memberi terang, juga kehangatan di tengah kepungan dingin udara malam.
Semua orang siap dengan sarung dan selimut. Perlengkapan wajib untuk tidur di kampung pengunungan.
"Poltak, sini ompung simpan uangmu. Biar tak hilang." Nenek Poltak menawarkan jasa simpan duit.
"Tidak, Ompung. Aku kantongi saja." Poltak menolak. Enam lembaran merah mata uang serupiahan itu dilipat dan disimpannya di saku baju.
Melihat uang merah di dalam saku, meraba dan merasakan tekstur kertasnya, adalah kenikmatan tersendiri. Takada anak kecil yang bisa merasakan itu di Panatapan dan Hutabolon. Hanya Poltak.
"Ya, sudah. Jangan menangis kalau uangmu hilang." Nenek Poltak mengingatkan. Seolah sudah tahu apa yang akan terjadi.
Semua anggota keluarga besar buyut Poltak tidur di ruang utama rumah bolon milik buyut Poltak. Itu adalah tidur yang demokratis. Semua menghampar di atas tikar di satu ruangan. Perempuan di satu belahan ruang. Laki-laki di belahan lainnya. Termasuk Poltak.
Hari lusa juga cepat tiba. Tak perlu berlelah-lelah menantinya. Cukup dengan tidur nyenyak, maka seperti halnya besok, hari lusa pasti akan tiba dengan sendirinya.
"Uangku hilang! Ompung! Hilang! Uangku!" Tiba-tiba Poltak menjerit, menangis meraung, memanggil neneknya. Memecah hening di remang ruang.
Ayam jantan baru saja berkokok untuk kedua kalinya. Orang-orang masih tidur nyenyak. Beberapa orang mengorok. Pasti tidak sedang memikirkan uang enam rupiah.
"Ompung! Uangku hilang!" Lagi, jerit tangis Poltak. Lebih keras dari sebelumnya. (Bersambung)