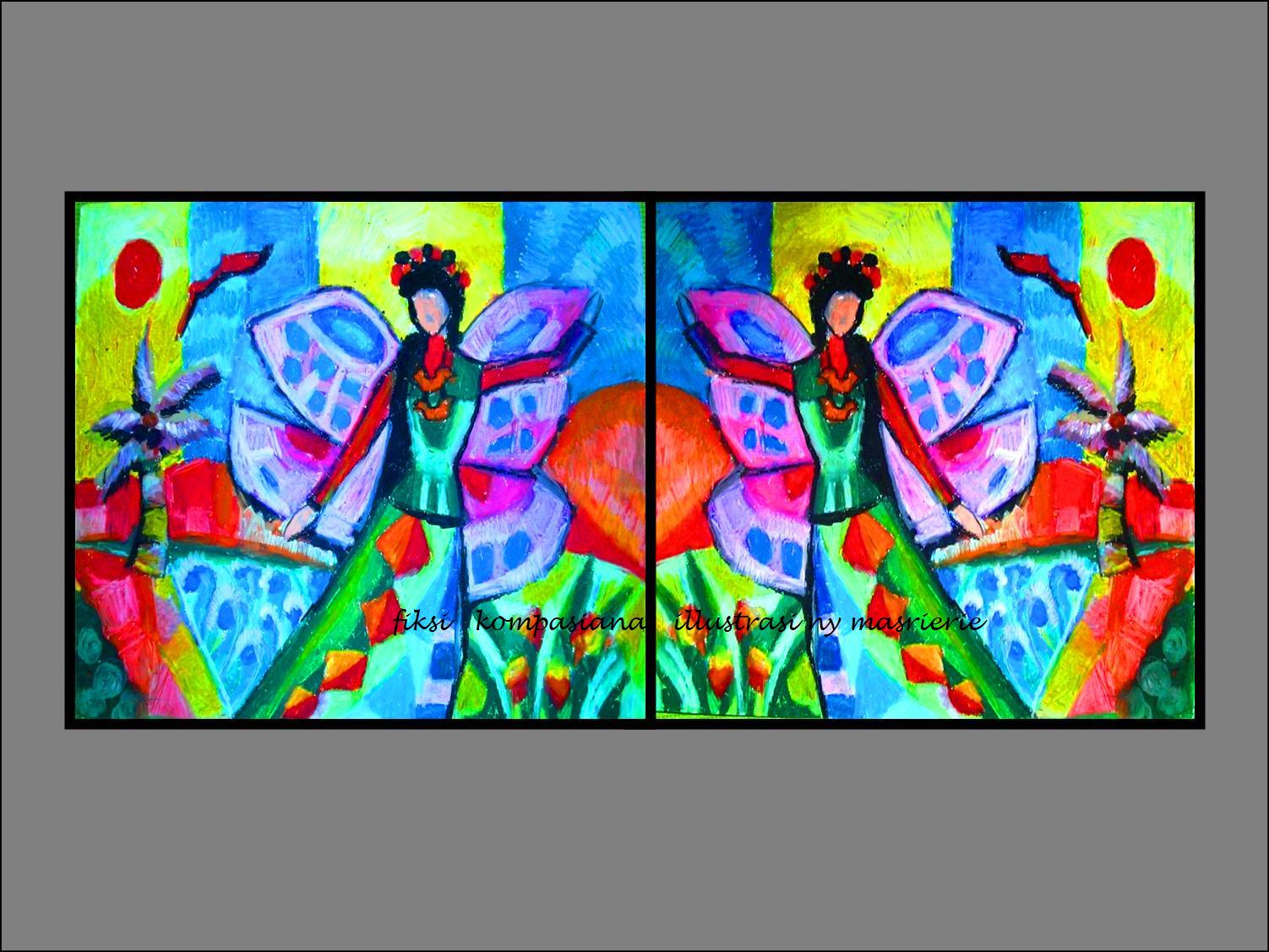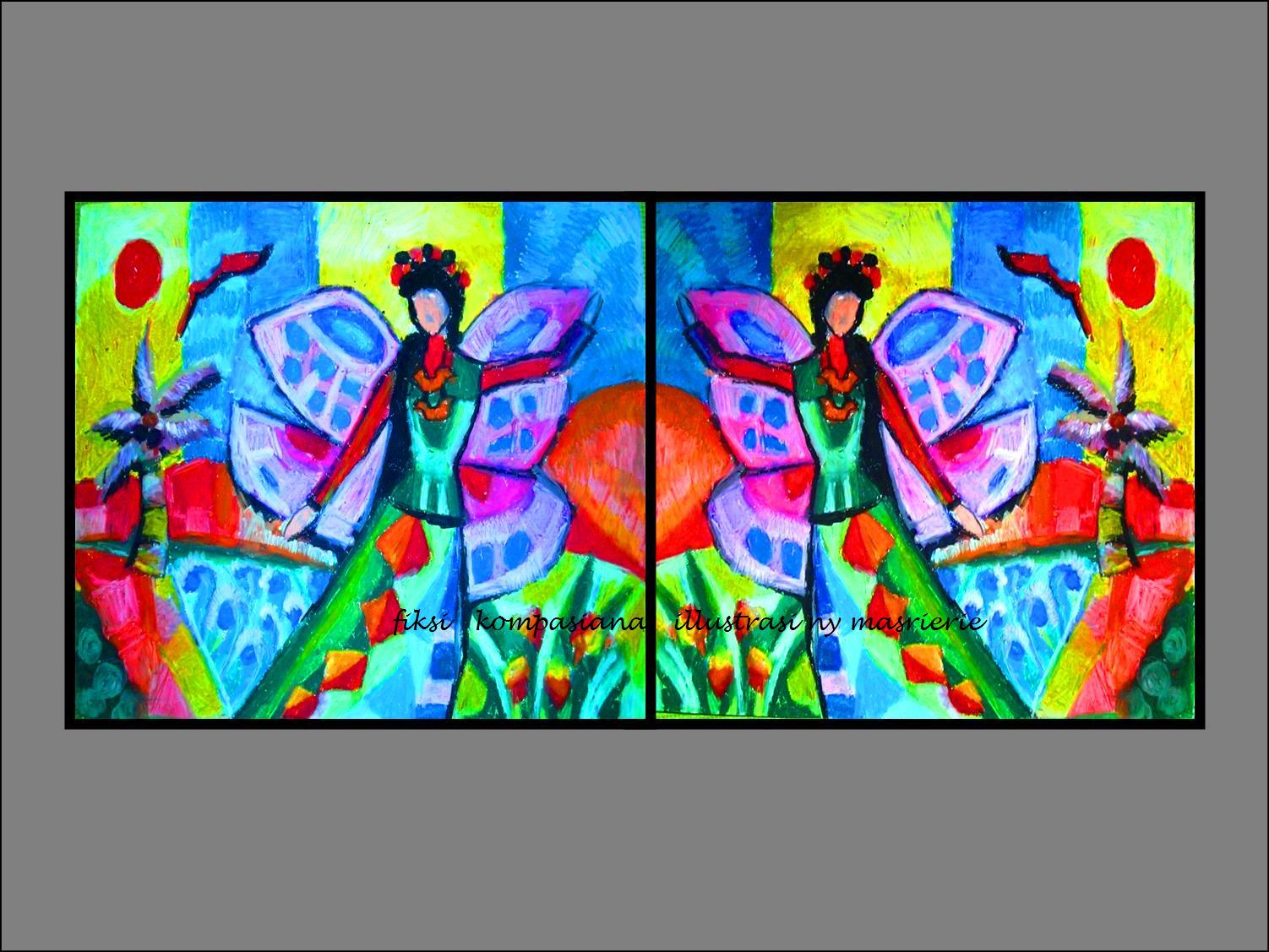Aku pulang menjelajah kemarau. Menyusuri samarnya senja. Inna, anakku, Bunda ingin melihatmu menyingkap tirai batik itu. Seperti selalu terekam oleh Bunda, masa kecilmu, sorak riang berlari memelukku. Setiap Bunda baru pulang dari pasar.
Ah, rindunya Bunda akan rumah masa kecil itu. Yang kita tinggalkan jauh di masa silam. Tawamu Nak, dan kecantikan kulit putihmu itu, menjadikan Bunda lupa pada keletihan . Kau selalu menjadi bidadari yang menggemaskan.
Bunda lupa atas sisi suram puluhan tahun kesetiaan Bunda mengabdikan diri kepada kalian. Di rumah yang Bunda selalu rindukan untuk pulang.
Pada setiap jam 2 malam, di rumah itu Bunda belum pernah absen untuk bangun menerjang kantuk. Jujur, inginnya masih berleha sejenak di atas kasur. Itu tak mungkin, Bunda mulai meracik sayuran untuk membuat tumisan atau sayur bening. Dan menggoreng tempe balut tepung kesukaanmu. Atau tahu telur bertabur cabai dan daun bawang yang gurih kesukaan Abah. Buat kalian santap sahur.
Jelang berbuka puasa, dapur kita selalu saja ramai. Karena saat Bunda memasak untuk berbuka, kau juga duduk di lantai main masak-masakan.
Inna, Bunda memendam rindu akan ruang rumah itu.
Rumah dimana Bunda tak pernah absen untukmu, dan untuk Abah. Untuk Aa Andri, Aa Raka, dan kau. Pernahkah satu hari saja dalam puluhan tahun itu Bunda absen menyiapkan sarapan, makan siang dan makan malam? Coba sebutkan berapa kali Bunda membiarkan cucian baju bertumpuk?
Inna buah hatiku, mulai dari menyikat kamar mandi, membersihkan selokan, menyapu halaman, menanam bunga dan sayuran, hingga memboncengmu naik motor saat kau sekolah. Kapan Bunda pernah absen dari semua itu sayang?
Rumah yang selalu saja riuh sejak matahari belum terbit, menyiapkan sarapanmu. Menyiapkan bekal Abah ke kantor, menyiapkan nasi timbel untuk Aamu ke kampus. Betul sayang, semua pekerjaan yang tak pernah mendapat penghargaan dari kebanyakan orang.
Kalau Abah mengijinkan, tentunya Bunda tetap akan menjadi pengajar di perguruan tinggi. Tapi Abahmu lebih suka Bunda berkutat di dapur, kamar andi, kebun , rumah… dan menyusuri jalan-jalan raya mengantar jemput kalian dengan motor.
Maaf sayang, selalu menceritakan Rumah itu. Karena Bunda enggan mengingat rumah terakhir kita.
Rumah terakhir kita terlalu dekat dengan rumah Nenekmu, rumah Uak-uakmu, rumah bibi-bibimu. Kakak dan adik Abahmu.
Rumah dimana kau menangis merangkul kaki Bunda. Kau memaksa Bunda untuk kembali kepada Abahmu. Lalu Bunda memurkaimu, sehingga tubuhmu terbanting. Maaf , setelah Abah menceraikan Bunda, ternyata Bunda menemukan kebahagiaan.
“Bunda, mana belas kasihan Bunda. Abah sedang sakit. Di rumah nenek ia terlantar. Inna tak mungkin harus terus mengurus Abah di rumah nenek. Rumah yang mirip neraka itu… Rumah dimana amarah selalu meraja lela tak terkendali…. Rumah dimana diktator yang bernama Nenek itu mengumbar wajah masamnya….Kasihan Abah…..” kau meratap kelu.
Bukan … bukan Bunda tak sayang padamu Nak. Bunda kasihan padamu. Tapi rasa cinta dan kasih sayang Bunda pada Abahmu, sudah pernah menjadi rasa luka mendalam, ketakutan tak terkira, derita demi derita. Rodi, kerja paksa, dan tidak ada penghargaan, dari Abah, apalagi dari nenekmu.
Tiga puluh tahun menjadi istri Abah, pernahkan satu kali saja Abah memandang Bunda dengan lembut dan mesra? Bunda lebih dianggap sebagai seorang pembantu saja. Abahmu tidak pernah melindungi dan membela Bunda saat Nenekmu menindas Bunda. Saat Uak-uak dan Bibi-bibimu menjadikan Bunda pesakitan.
Bunda hidup terseok dalam kemiskinan. Keprihatinan. Dan ternyata selama 30 tahun gaji Abah sebagian besar diberikan kepada Nenek dan Uak Bibimu. Sementara tubuh Bunda terus digerogoti penyakit dan keletihan.
Ketika Abahmu pensiun , mendapat pesangon miliaran, nenekmulah yang menyuruh Abah menceraikan Bunda. Tidak hujan tidak angin. Lalu Abahmu pindah ke rumah ibu kesayangannya. Sampai depositonya ludes. Menjadi miskin dan sakit.
Tapi sungguh ajaib. Tiga puluh tahun tertekan, beberapa bulan semenjak Abah menceraikan…. Tiba-tiba Bunda menemukan kebahagiaan. Bunda merasa tidak punya lagi kewajiban untuk menjadi ‘pembantu’ bagi mertua dan para ipar.
Sampai hari yang naas itu tiba. Inna, saat Abahmu sakit, kau meratap dan memaksa membawa Abah ke rumah baru kita. Bunda membuat tubuhmu terbanting.
Abah marah dan memukul Bunda. Seperti sering ia lakukan dulu demi membela ibunya. Abah selalu dihantui ketakutan dan rasa berdosa jika ia menyayangi istri. Seolah ia tengah mengkhianati ibunya.
Maafkan Inna sayang, ini malam-malam Ramadhan terakhir. Bunda merindukanmu…. Bunda ingin minta maaf karena kemarahan itu….
Gema takbir melantun dari langgar. Kau menangis tersedu sayang. Mengapa saling memaafkan harus menunggu sebuah tragedi dulu terjadi….?
“Bunda…. Besok hari Raya Iedul Fitri, tunggu Inna ya Bunda…. Tunggu Aa. Kami rindu menziarahi makammu…. Nanti setelah menjenguk Abah di penjara…., Abah menyesali perbuatannya… setelah kau tiada… Nenek , Uak dan Bibi, mudah-mudahan mereka juga menyesal… …. ” suaramu pilu terisak.
Lantunan ayat suci Al Qur’an itu menjadi cahaya kesejukan yang menyelimuti Bunda. Binar kedamaian dari sejuta doamu sayang.
Setidaknya , sesal dan maaf itu akhirnya terbit juga di hati ayahmu dan keluarga besarnya sayang. Percayalah, Bunda selalu memaafkan kalian, sepedih apapun Bunda disakiti.
NB : Untuk membaca karya peserta lain silahkan menuju akun Fiksiana Community (sertakan link akun Fiksiana Community) Fiksiana Community
Silahkan bergabung di group FB Fiksiana Community
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H