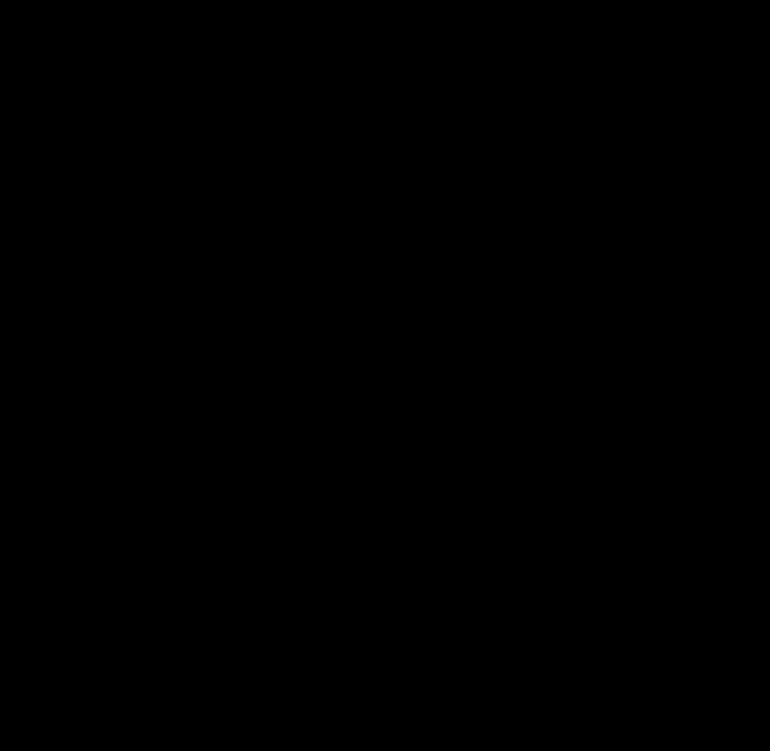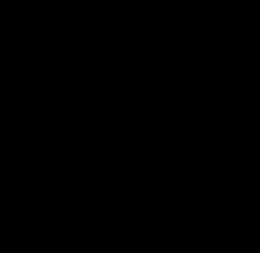Butuh waktu sekitar lima menit menunggu pintu dibuka.
Mata Emak mengerjap-ngerjap memandang silau obor yang kubawa. Seolah sudah mengerti maksud kedatanganku, ia langsung membalikkan tubuhnya, berjalan terhuyung menuju dapur . Aku mempersilahkan Mamat duduk di ruang tamu. Sementara menunggu, aku melirik arloji yang melingkar di lenganku. Masih jam dua pagi.
Lama kami menunggu Emak sambil terkantuk-kantuk. Mamat yang sejak awal sudah kehilangan suara kini terlentang di kursi, menciptakan suara naganya. Mendekur. Aku terkesiap saat seorang menyentuh bahuku. Emak yang masih membiarkan rambut --yang mulai memutih-tergelung sekenanya, sudah berdiri membawa buntalan nasi. "Nasinya tadi masak setengah kilo cukup kan? " Kata Emak sambil meletakkan buntalan di atas meja. "Seadanya saja sama mi."
Rasa kantuk semalaman karena tak tidur membuatku enggan menanggapi Emak. Maka setelah menggapai tubuh Mamat yang membujur, aku menjinjing buntalan itu. Meninggalkan Emak yang terkantuk-kantuk menutup pintu. Melanjutkan tidur.
Kang Marto masih berjibaku di depan mulut tobong. Memasukkan kayu-kayu ke dalamnya, menjaga nyala api agar tetap besar . Ia tak memerdulikan keringat mengucur membasahi tubuhnya yang hitam kerempeng. Bahkan ia tak mau memakai kaosnya saat memikuli kayu ke depan mulut tobong. Uap panas api pun tak dirasa, ia hanya nyengir saat ujung api menjilat mukanya. "Yang penting bata bisa cepat matang, cepat juga diangkut pemborong." Jawabnya saat kusuruh memakai kaos.
Aku hanya duduk beralaskan pelepah daun pisang yang berjarak tiga meter dari mulut tobong. Mamat dan Udin langsung menyerbu nasi panas dan mi buatan Emak. Keduanya rakus menyergap tanpa menawari aku sebagai anak Emak dan Kang Marto sebagai Boss-nya. Aku yang tak enak hati dengan Kang Marto akhirnya berseru;"Istirahat dulu Kang! Dimakan nasinya mumpung masih panas." Kang Marto tak menggapi. Ia malah bergegas menuju tumpukan kayu bakar, memilah, lalu memasukkannya ke mulut tobong.
(***)
Ini sudah hari ke dua puluh lima saat Warsih --Tengkulak beras-, datang ke rumah menagih utang. Warsih datang ke rumah dengan seorang laki-laki berbadan tegap berkulit hitam. Entah siapa aku tak kenal. Setahuku suaminya Haji Sanusi berbadan kecil, berkulit putih, kemana-mana selalu memakai peci.
Kata Warsih hutang Kang Marto tidak banyak. Tiga bulan lalu saat musim sawah Kang Marto pinjam uang sejuta setengah. Nanti kalau sudah panen dibayar pakai beras, satu kilonya dihargai tiga ribu rupiah. Kang Marto bersedia membayar dua kali lipatnya. "Ini sudah panen Mak, kapan bisa segera dilunasi?" Katanya menagih. Emak terdiam sekian lama. Memandangi halaman rumah dengan tatapan mata kosong.
Kang Marto pun hanya menelungkupkan mukanya ke atas dua pahanya yang di tekuk merapat. Emak tak berucap apa pun. Emak baru tahu, biaya penggarapan sawah musim ini uangnya dari Warsih. Meski Emak tidak tahu kapan Kang Marto meminjam uang, tapi Emak tahu, biaya menggarap sawah tidahlah murah. Untuk biaya pembajakan saja sudah dua ratus ribu per seperempat Hektar. Harga pupuk juga tidak mau kompromi, selain tenaga pemborongnya juga minta naik. Belum lagi biaya perawatan yang semuanya butuh uang kontan.
Maka setelah Warsih tenggelam dari pandangan-meninggalkan pesan sebulan lagi datang-, perlahan Kang Marto mengangkat mukanya lalu berujar; "Harga bata di Baturaja sedang mahal.Sebaliknya harga beras kalau musim panen merosot."
"Aku sudah ketemu Maman anaknya Pak Puh Marno. Katanya dia mau bantu ngasih pinjaman lima juta buat modal. Buat beli cetakan, beli plastik, bayari tenaga kerja, sekalian beli kayu. Nanti kalau bata sudah matang Maman yang ambil." Desis Kang Marto seraya menundukkan pandangannya ke lantai dalam-dalam.
Aku terdiam melirik Emak mengkerutkan kening. Tak selayaknya perempuan kurus berusia enam puluhan itu memikirkan hal-hal semacam ini. Namun dalam keluarga kami Emak lah yang selalu mengambil keputusan. Sering keputusan itu diambil saat Kang Marto memberi usulan mendesak. Entahlah, mungkin Emak percaya kalau Kang Marto bisa mengatasi masalah kami, atau Emak yang memang sudah tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan ini. Dan aku akan selalu mendukung Emak.
"Warsih gimana?" Suara Emak serak menghilang di langit-langit.
"Masih satu bulan lagi. Cukuplah untuk membuat bata sebanyak-banyaknya. Mumpung Wawan masih liburan, nanti bisa tiap hari bantu. Iya kan Wan?" Kang Marto menatapku. Aku mengangguk.
"Mulai pendaftaran kuliahmu kapan to Wan?" Tanya Emak padaku. " Adikmu Wakit juga butuh lima juta lho buat Wisuda nanti Mar. Biaya kost-nya juga sudah nunggak tiga bulan katanya"
"Biaya kuliahmu berapa Wan?" Tanya Kang Marto ketus. Mengarahkan pandangannya padaku.
"Lima Juta-an Kang!"
"Apa begini saja Mak, sawahnya kita gadaikan saja. Nanti uangnya buat Wakit. Yang penting lulus kuliah dulu dari pada telat terus ditunda tahun depan. Kan malah tambah biaya. "Kalau per hektarnya empat juta setahun, berarti nanti kita gadai selama dua tahun. Cukuplah untuk Wakit."
"Ehm, nanti biaya kuliah Wawan nunggu bata sudah laku saja, Mak. Itung-itung Wawan kerja dulu ke Kang Marto." Kataku seolah-olah berbicara dengan diriku sendiri.
"Bagaimana Mak? Biaya Wawan bareng sama bayar ke Bu Warsih" Tanya Kang Marto mendesak.
Emak tak berujar apapun. Matanya menatap kosong pada dinding rumah yang masih terlihat bata tersusun. Dinding yang sejak mendiang Bapak meninggal belum sempat kami lapisi dengan semen. Setahun yang lalu Bapak sudah mengumpulkan uang untuk merenofasi rumah. Namun rencana itu urung lantaran Bapak keburu dipanggil Sang Khaliq. Lalu uangnya kami gunakan mengurus jenazah Bapak, sisanya yang tak cukup untuk merenofasi rumah akhirnya di kirimkan Emak ke Kang Wakit yang kebetulan sedang ujian tengah semester.
Untungnya Bapak pergi dengan meninggalkan warisan pada seorang janda anak tiganya berupa sepetak sawah. Meski penghasilan yang terkatung-katung, namun mampu membuat Kang Wakit anak nomor duanya kuliah jurusan hukum. Sedang aku berencana kuliah di Jogja jurusan Informatik. Kang Marto yang tidak pernah mengenyam pendidikan bekerja keras membiayai kami. Ia tak pernah memerhatikan dirinya sendiri, bekerja keras hingga badanya kecil kerempeng dan berkulit hitam. Terkadang aku bertanya-tanya dalam hati, di usianya yang tiga puluh lima tahun, kiranya siapakah wanita yang akan menerimanya, menemani Emak memasak di dapur.
(***)
Hawa panas dari mulut tobong perlahan menghilang, menciptakan aroma tanah liat terpanggang matang. Aku masih duduk di bawah pohon mangga yang berjarak tiga meter dari mulut tobong, memerhatikan Kang Marto yang masih sibuk membersihkan sisa-sisa lembur semalaman. Badanya yang kerempeng terlihat lihai menarik sisa kayu yang masih berasap, menumpuknya di bawah pohon mangga. Ia lincah memindah kayu-kayu itu tanpa memerdulikan rambut dan mukanya putih penuh abu.
Mamat dan Udin sebagai pemborong seharusnya yang melakukan pekerjaan itu masih tertelengkup berselimut terpal di sampingku. Sinar mentari pun mulai menyeruak menghangati wajahku yang terasa kaku dan rambutku yang seakan penuh abu, mengantarkan hari ke dua puluh enam dimana beberapa hari lagi Warsih berjanji akan menemui Kang Marto. Sudah terbayang di benakku tumpukan uang seratusan tiga puluh lembar untuk Warsih. Meski aku sedikit tak rela jika tiga lembar uang seratusan di berikan Mamat dan Udin yang kerjanya hanya tidur-tiduran semalaman. Aku melirik benci pada dua anak yang masih tengkurap di sampingku.
Sepagi ini Maman sudah datang menepati janjinya. Ia melenggak menghampiri Kang Marto setelah memarkir sepeda buntutnya sembarangan. Aku yang merasa berkepentingan mendaftar kuliah mendekati mereka berdua. Kuperkirakan dua puluh ribu biji bata yang sudah matang akan segera diangkut.
"Besok sudah bisa di tarik Man." Kata Kang Marto saat menjabat tangan. "Kuhitung yang bisa diangkut sekitar dua puluh ribuan."
"Ehm, wah kualitas batamu bagus bener Mar. Ini warna merahnya rata, jenis yang paling disukai di Baturaja." Katanya memuji sampel yang di sodorkan Kang Marto.
"Terimakasih Man." Aku dan Kang Marto kompak menimpali.
"Tapi harga sekarang lagi turun Mar, kata boss harga turun jadi duaratus lima puluh ribu, lagi musim hujan pula jadi belum bisa angkut. Dua piluh rubu nanti buat pinjaman kemarin. Gimana Mar?"
"Apa...? Sama saja kayak padi kalau begitu. "
"Beda Mar. Kalau bisnis bata ngomong berapa duitpun sama aku bisa cepet cair." Ujar Maman sedikit berbisik di telinga Kang Marto.
"Jadi bisa bantu Man ? Kemarin kan aku sudah ngomong kalau bulan ini lagi butuh dana banyak. Ke Warsih dan Wawan sekitar delapan juta."
"Bulek juga sudah ngomong Mar. Jangan kuatir saudaramu ini bisa bantu. Aku juga sudah ngomong sama si boss, delapan jutanya hari ini juga sudah ku bawa. Bayarnya setelah bakar lagi bulan depan."
(***)
"Bagaimana Mak?" Kata kang Marto mendesak.
"Itu kan sawah warisan Bapak, dosa nanti kita. Dosa...!" Sahut Emak dengan muka cemas.
"Kata orang-orang tanah didekat hutan tidak cocok untuk padi, tak salah kalau dijual semua. Anggap saja sawah itu bukan Warisan Bapak! Toh boss Maman siap bantu kita. Mending usaha bikin bata" Kata Kang Marto beberapa kali mendesak yang kemudian suaranya lenyap dilangit-langit.