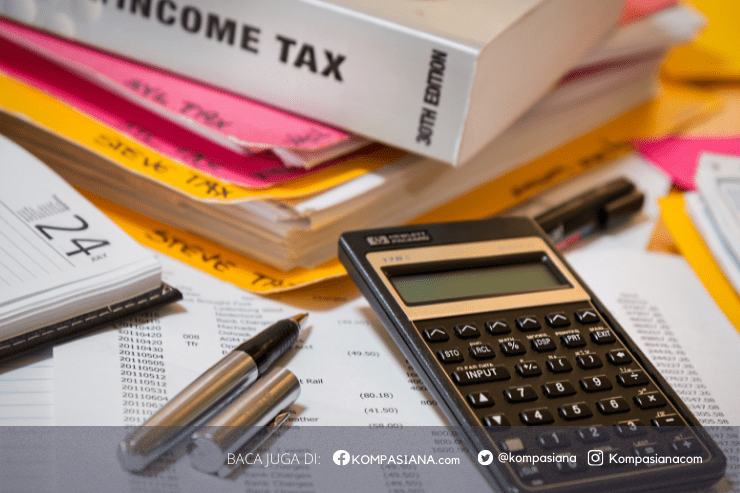Pemerintah, seperti sebuah orkestra yang tak sepenuhnya teratur, memutuskan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Alasan yang dikedepankan jelas: menambal penerimaan negara dan mengecilkan defisit anggaran. Semua ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sebuah bingkai besar reformasi fiskal yang digadang-gadang untuk menjaga kestabilan ekonomi negeri dalam jangka panjang.
Namun, keputusan itu, seperti simfoni yang kehilangan nada dasar, disambut dengan kritik tajam. Ekonomi sedang lesu. Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, sudah seperti lilin yang meredup. Pemerintah membela diri dengan menyebut kebijakan ini berlandaskan asas keadilan: barang kebutuhan pokok seperti tepung terigu, minyak goreng curah, atau Minyakita, dan gula industri hanya dikenai sebagian tarif PPN, dengan satu persen di antaranya ditanggung oleh pemerintah (DTP).
Tetapi ada yang terasa ganjil. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU yang sama, pemerintah sebenarnya memiliki ruang gerak---kemampuan untuk menetapkan tarif dalam rentang 5 hingga 15 persen melalui Peraturan Pemerintah. Ini bukan langkah yang wajib, melainkan pilihan. Ironi lain menggantung di udara: pajak karbon, yang seharusnya diberlakukan sejak 2022, masih sekadar janji yang membeku dalam ruang kebijakan.
Semua ini terjadi di tengah angka-angka yang terus mencemaskan. Pada triwulan III 2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,91 persen secara tahunan, bahkan terkontraksi 0,48 persen secara triwulanan. Deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024, ditambah laporan Bank BRI[1] bahwa omzet UMKM menurun hingga 60 persen, adalah bukti bahwa masyarakat tengah bergulat dengan hari-hari yang kian berat. Di tengah situasi ini, kenaikan PPN adalah palu yang menghantam tembok yang sudah retak.
Kebijakan ini, pada akhirnya, memaksa kita untuk bertanya: di mana letak keadilan ketika angka-angka besar bertemu dengan napas kecil orang-orang biasa?
Pemerintah, dalam upayanya menutup defisit anggaran, memilih jalan yang terlihat mudah namun penuh duri: menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini mungkin tampak logis di atas kertas, tetapi tak bisa disangkal, ada opsi-opsi lain yang terabaikan. Potensi penerimaan pajak dari sektor tambang ilegal, misalnya, belum sepenuhnya disentuh. Dalam sektor sawit saja, Hasyim, Dewan Pembina Gerindra pernah menyebut angka Rp300 triliun yang menguap dari pengemplangan pajak. Tetapi, alih-alih mendahulukan upaya ini, langkah menaikkan tarif PPN tetap menjadi pilihan utama.[2]
Lalu ada soal perbandingan. Merunut data Emedia DPR RI, tarif PPN Indonesia yang kini di angka 11 persen sudah lebih tinggi daripada Malaysia dan Singapura, yang masing-masing menetapkan 8 dan 9 persen. Dengan kenaikan menjadi 12 persen, Indonesia akan bersanding dengan Filipina sebagai negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara---posisi yang membawa beban, bukan kebanggaan.[3]
Kebijakan, pada akhirnya, bukan hanya perkara angka, tetapi juga cerita tentang dampak. Seperti riak air, kenaikan tarif ini akan menjalar, mengguncang konsumsi rumah tangga, menekan daya beli, dan menggoyahkan sendi-sendi ekonomi. Ketika tarif PPN naik dari 10 menjadi 11 persen pada 2022, inflasi melonjak dari 1,56 persen menjadi 4,21 persen. Sekarang, dengan rencana kenaikan menjadi 12 persen pada 2025, inflasi diproyeksikan menyentuh 4,11 persen. Konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor ekonomi, diperkirakan akan melambat, bahkan mungkin terhenti.[4]
Dan tak hanya inflasi yang menanti di ujung kebijakan ini. Ada juga pre-emptive inflation---fenomena di mana pelaku usaha menaikkan harga barang dan jasa lebih awal, sebagai langkah antisipasi. Menjelang akhir 2024 hingga awal 2025, ekspektasi harga akan memuncak, sebagian karena tradisi libur akhir tahun, sebagian lagi karena bayang-bayang tarif baru. Pada akhirnya, efek domino ini akan merambat pada indeks harga konsumen, yang diperkirakan naik 0,14 persen, hingga konsumsi rumah tangga yang berpotensi turun 0,37 persen.
Di sisi lain, menurut temuan Celios Think Tank dampak pada PDB tak kalah mencemaskan. Kenaikan tarif PPN ke 12 persen bisa memangkas PDB hingga Rp65,33 triliun, meninggalkan jejak luka pada ekonomi yang seharusnya tumbuh. Bahkan konsumsi rumah tangga, komponen paling vital dalam roda ekonomi kita, menunjukkan angka yang menyusut drastis---dari kontribusi positif pada tarif rendah menjadi minus Rp40,68 triliun pada tarif tertinggi.[5]
Semua ini adalah catatan tentang paradoks: sebuah kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan, tetapi justru mengguncang. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun tajam: dalam upaya memperbaiki anggaran, siapa yang sesungguhnya menanggung beban paling berat?
Pemerintah berjanji, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan disertai bantuan tunai dan subsidi tambahan. Tapi janji, seperti yang sering terjadi, bisa saja hanya sekadar kata-kata yang berakhir di udara. Bila bantuan itu datang terlambat, dua atau tiga bulan setelah tarif dinaikkan, apa yang akan terjadi? Dampaknya tetap negatif. Sebab, bantuan, seperti semua yang sementara, bersifat sesaat. Sementara beban kenaikan PPN itu bertahan lebih lama---menggerus daya beli dan perlahan memaksa masyarakat menyesuaikan hidup mereka dengan realitas baru yang lebih pahit.[6]
Angka-angka mengisahkan beban itu dengan keheningan yang tegas. Bagi rumah tangga miskin, kenaikan ini berarti tambahan pengeluaran Rp101.880 per bulan---atau Rp1.222.566 setahun. Dalam kehidupan mereka yang sudah terbatas pada kebutuhan pokok, angka-angka itu punya arti lain: makanan yang lebih sedikit, pendidikan yang tertunda, atau kesehatan yang diabaikan. Tabungan yang kecil, kalau masih ada, terkikis habis. Konsumsi sehari-hari, yang semula mungkin cukup sederhana, kini terancam lebih miskin lagi.
Bagi kelompok rentan miskin, yang hanya selangkah lebih baik dari kelompok sebelumnya, situasinya tak jauh berbeda. Dengan tambahan biaya Rp153.871 per bulan, atau hampir dua juta rupiah setahun, posisi mereka yang goyah menjadi lebih genting. Sering kali, mereka hanya berjarak tipis dari garis kemiskinan. Sekali terpeleset, mereka jatuh. Mereka, yang semula berharap menabung untuk pendidikan anak atau masa depan yang sedikit lebih baik, kini hanya berjuang bertahan dari hari ke hari.
Dan bagaimana dengan kelompok menengah? Meski daya beli mereka lebih baik, angka kenaikan PPN sebesar Rp354.293 per bulan atau lebih dari empat juta setahun tetap punya dampak. Mungkin hiburan dikurangi, perjalanan ditunda, atau barang-barang mewah tak lagi dibeli. Inflasi sebesar 4,1 persen, yang berjalan beriringan dengan kenaikan PPN, menambah tekanan. Bagi mereka, mungkin ini hanya perubahan gaya hidup. Tetapi bagi kelompok miskin dan rentan miskin, inflasi itu seperti gelombang yang menghantam mereka berkali-kali---harga pangan naik, harga energi melambung, sementara pendapatan mereka tetap tak berubah.[7]
Akhirnya, ada ironi yang terlalu pahit untuk diabaikan. Kebijakan yang diklaim bertujuan memperkuat stabilitas negara, malah membebani yang paling lemah. Mereka yang sudah susah bertahan, kini harus memikul beban tambahan yang tak mereka minta, dari keputusan yang tak mereka buat. Sebab itulah, pertanyaan besar tetap menggantung: adakah kebijakan yang adil bila yang menanggung luka selalu adalah mereka yang sudah paling rapuh?
Kenaikan PPN tak hanya perkara angka di atas kertas. Ia adalah cermin yang membelah kenyataan: di satu sisi, mereka yang kuat, yang daya belinya seperti dinding kokoh tak tergoyahkan; di sisi lain, mereka yang lemah, yang kesehariannya dihitung dengan hati-hati, setiap rupiah diatur agar cukup hingga akhir bulan. Kelompok kaya mungkin hanya merasa sedikit tergelitik oleh kenaikan ini---sekadar perubahan angka pada tanda terima belanja mereka. Tapi bagi kelompok miskin, dampaknya terasa seperti beban baru yang menekan, membuat napas semakin berat. Ketimpangan ini, pelan tapi pasti, memperlebar jurang yang sudah lama ada, di mana yang kaya tetap melangkah dengan santai, sementara yang miskin semakin terdesak ke pinggir.
Jurang sosial yang makin lebar ini bukan sekadar data statistik. Ia adalah perasaan---kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan amarah---yang mengendap di kalangan mereka yang merasa beban ini tidak terbagi adil. Ketidaksetaraan ini, jika terus dibiarkan, bisa menjadi bara yang menghanguskan harmoni sosial. Mobilitas, yang semula dianggap jalan keluar, menjadi jalan buntu; mereka yang miskin semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan. Dan di tengah semua ini, ada pertanyaan yang mendesak: bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang mengklaim stabilitas, malah membuat yang lemah semakin tertindas?
Buruh, mereka yang hidupnya ditopang oleh penghasilan tetap, turut terguncang. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN menghantam daya beli mereka. Dengan gaji Rp5 juta per bulan, dan pengeluaran yang sudah hampir menyentuh Rp4,5 juta untuk kebutuhan dasar, setiap kenaikan harga menjadi pukulan yang telak. Hidup, yang tadinya sudah terasa cukup berat, menjadi seperti berjalan di atas tali yang semakin tipis.[8]
Dan kemudian ada Gen Z---generasi yang katanya adalah harapan, tapi kini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang getir. Dengan kenaikan PPN, mereka harus memutuskan: terus berbelanja dengan mengandalkan utang, berhemat dengan gaya hidup minimalis, atau mencari jalan lain seperti membeli barang di sektor informal. Doom spending, sebuah pelarian konsumtif karena kecewa pada masa depan, menjadi magnet yang menarik mereka ke pusaran utang. Bonus demografi yang dulu dirayakan dengan optimisme, kini tampak seperti ancaman, sebuah bencana yang mungkin tak bisa dihindari.
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal persentase atau proyeksi ekonomi. Ia adalah soal manusia, soal mereka yang harus berhadapan dengan realitas baru yang tak mereka pilih, soal generasi yang bertanya-tanya apakah harapan masih layak diperjuangkan. Dan kita, yang menyaksikan semua ini, hanya bisa bertanya: apa harga sebenarnya dari stabilitas yang disebut-sebut itu?
Barangkali ada jalan lain yang lebih adil, lebih bijak, dibanding sekadar menaikkan PPN menjadi 12%. Jalan itu mungkin adalah pajak yang berbicara tentang tanggung jawab: pajak karbon untuk mengekang emisi yang mencekik bumi, pajak kekayaan yang menyentuh mereka yang hartanya berlimpah, atau pajak windfall yang menyasar keuntungan luar biasa dari sektor-sektor seperti tambang dan sawit. Bukankah lebih masuk akal membebankan pajak pada mereka yang kuat, yang mampu menanggung beban lebih besar, ketimbang menambah beban mereka yang bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-hari pun harus menghitung dengan cermat?
Pemerintah juga bisa memilih untuk menutup lubang-lubang bocor yang selama ini tak terurus: pajak dari sektor sawit yang kerap luput, atau transaksi digital lintas negara yang melaju tanpa jejak. Kebijakan ini tidak hanya adil, tetapi juga menunjukkan kepekaan terhadap realitas yang dihadapi masyarakat. Bahwa mereka yang berada di puncak piramida ekonomi punya tanggung jawab lebih besar daripada mereka yang tertatih-tatih di dasarnya.
Namun, keadilan ini tak cukup hanya soal siapa yang dipajaki. Reformasi sistem perpajakan harus menjadi prioritas. Memperluas basis pajak, menciptakan efisiensi dalam pemungutan, dan memastikan bahwa setiap rupiah yang terhimpun benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ini bukan hanya tentang menambah penerimaan negara, tetapi tentang memastikan bahwa beban itu terbagi secara proporsional. Sebab, di tengah hiruk-pikuk angka dan kebijakan, ada wajah-wajah yang tak boleh diabaikan: wajah mereka yang paling rentan, yang paling terkena dampak dari setiap keputusan yang kita buat.
Referensi:
[1] https://ekonomi.bisnis.com/read/20241113/9/1815729/daya-beli-masyarakat-turun-bri-omzet-umkm-turun- hingga-60
[4] https://www.kompas.id/artikel/keputusan-pemerintah-naikkan-ppn-akan-picu-kenaikan-inflasi
[5] Data dan angka disarikan dari temuan riset celios.co.id. (https://celios.co.id/ppn-12-pukulan-telak-bagi-dompet-gen-z-dan-masyarakat-menengah-ke-bawah/)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H