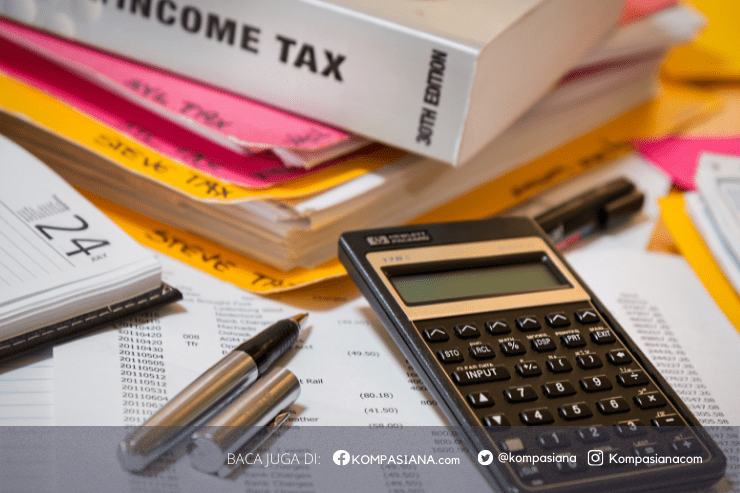Semua ini adalah catatan tentang paradoks: sebuah kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan, tetapi justru mengguncang. Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun tajam: dalam upaya memperbaiki anggaran, siapa yang sesungguhnya menanggung beban paling berat?
Pemerintah berjanji, kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan disertai bantuan tunai dan subsidi tambahan. Tapi janji, seperti yang sering terjadi, bisa saja hanya sekadar kata-kata yang berakhir di udara. Bila bantuan itu datang terlambat, dua atau tiga bulan setelah tarif dinaikkan, apa yang akan terjadi? Dampaknya tetap negatif. Sebab, bantuan, seperti semua yang sementara, bersifat sesaat. Sementara beban kenaikan PPN itu bertahan lebih lama---menggerus daya beli dan perlahan memaksa masyarakat menyesuaikan hidup mereka dengan realitas baru yang lebih pahit.[6]
Angka-angka mengisahkan beban itu dengan keheningan yang tegas. Bagi rumah tangga miskin, kenaikan ini berarti tambahan pengeluaran Rp101.880 per bulan---atau Rp1.222.566 setahun. Dalam kehidupan mereka yang sudah terbatas pada kebutuhan pokok, angka-angka itu punya arti lain: makanan yang lebih sedikit, pendidikan yang tertunda, atau kesehatan yang diabaikan. Tabungan yang kecil, kalau masih ada, terkikis habis. Konsumsi sehari-hari, yang semula mungkin cukup sederhana, kini terancam lebih miskin lagi.
Bagi kelompok rentan miskin, yang hanya selangkah lebih baik dari kelompok sebelumnya, situasinya tak jauh berbeda. Dengan tambahan biaya Rp153.871 per bulan, atau hampir dua juta rupiah setahun, posisi mereka yang goyah menjadi lebih genting. Sering kali, mereka hanya berjarak tipis dari garis kemiskinan. Sekali terpeleset, mereka jatuh. Mereka, yang semula berharap menabung untuk pendidikan anak atau masa depan yang sedikit lebih baik, kini hanya berjuang bertahan dari hari ke hari.
Dan bagaimana dengan kelompok menengah? Meski daya beli mereka lebih baik, angka kenaikan PPN sebesar Rp354.293 per bulan atau lebih dari empat juta setahun tetap punya dampak. Mungkin hiburan dikurangi, perjalanan ditunda, atau barang-barang mewah tak lagi dibeli. Inflasi sebesar 4,1 persen, yang berjalan beriringan dengan kenaikan PPN, menambah tekanan. Bagi mereka, mungkin ini hanya perubahan gaya hidup. Tetapi bagi kelompok miskin dan rentan miskin, inflasi itu seperti gelombang yang menghantam mereka berkali-kali---harga pangan naik, harga energi melambung, sementara pendapatan mereka tetap tak berubah.[7]
Akhirnya, ada ironi yang terlalu pahit untuk diabaikan. Kebijakan yang diklaim bertujuan memperkuat stabilitas negara, malah membebani yang paling lemah. Mereka yang sudah susah bertahan, kini harus memikul beban tambahan yang tak mereka minta, dari keputusan yang tak mereka buat. Sebab itulah, pertanyaan besar tetap menggantung: adakah kebijakan yang adil bila yang menanggung luka selalu adalah mereka yang sudah paling rapuh?
Kenaikan PPN tak hanya perkara angka di atas kertas. Ia adalah cermin yang membelah kenyataan: di satu sisi, mereka yang kuat, yang daya belinya seperti dinding kokoh tak tergoyahkan; di sisi lain, mereka yang lemah, yang kesehariannya dihitung dengan hati-hati, setiap rupiah diatur agar cukup hingga akhir bulan. Kelompok kaya mungkin hanya merasa sedikit tergelitik oleh kenaikan ini---sekadar perubahan angka pada tanda terima belanja mereka. Tapi bagi kelompok miskin, dampaknya terasa seperti beban baru yang menekan, membuat napas semakin berat. Ketimpangan ini, pelan tapi pasti, memperlebar jurang yang sudah lama ada, di mana yang kaya tetap melangkah dengan santai, sementara yang miskin semakin terdesak ke pinggir.
Jurang sosial yang makin lebar ini bukan sekadar data statistik. Ia adalah perasaan---kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan amarah---yang mengendap di kalangan mereka yang merasa beban ini tidak terbagi adil. Ketidaksetaraan ini, jika terus dibiarkan, bisa menjadi bara yang menghanguskan harmoni sosial. Mobilitas, yang semula dianggap jalan keluar, menjadi jalan buntu; mereka yang miskin semakin sulit keluar dari jerat kemiskinan. Dan di tengah semua ini, ada pertanyaan yang mendesak: bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang mengklaim stabilitas, malah membuat yang lemah semakin tertindas?
Buruh, mereka yang hidupnya ditopang oleh penghasilan tetap, turut terguncang. Kenaikan harga barang dan jasa akibat PPN menghantam daya beli mereka. Dengan gaji Rp5 juta per bulan, dan pengeluaran yang sudah hampir menyentuh Rp4,5 juta untuk kebutuhan dasar, setiap kenaikan harga menjadi pukulan yang telak. Hidup, yang tadinya sudah terasa cukup berat, menjadi seperti berjalan di atas tali yang semakin tipis.[8]
Dan kemudian ada Gen Z---generasi yang katanya adalah harapan, tapi kini dihadapkan pada pilihan-pilihan yang getir. Dengan kenaikan PPN, mereka harus memutuskan: terus berbelanja dengan mengandalkan utang, berhemat dengan gaya hidup minimalis, atau mencari jalan lain seperti membeli barang di sektor informal. Doom spending, sebuah pelarian konsumtif karena kecewa pada masa depan, menjadi magnet yang menarik mereka ke pusaran utang. Bonus demografi yang dulu dirayakan dengan optimisme, kini tampak seperti ancaman, sebuah bencana yang mungkin tak bisa dihindari.