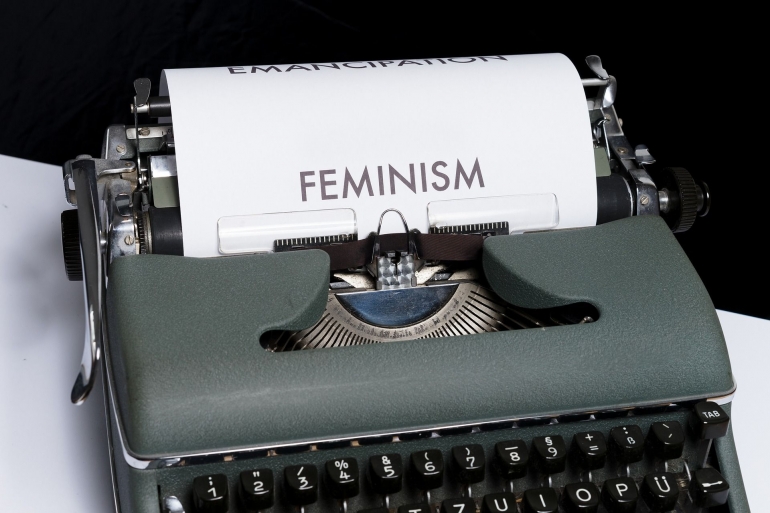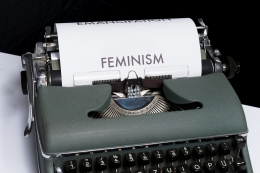Jika ada yang membedakan gerakan mahasiswa hari ini dengan zaman dulu, barangkali, ada pada media untuk meyampaikannnya.
Pergerakan mahasiswa kini, dengan beragam persoalan, bisa kita nikmati diskursusnya --paling tidak di media sosial.
Para mahasiswa, meski tampak satu arah, mulai berani menyampaikan gagasannya hingga mengampanyekan apa yang menurut mereka penting untuk dipejuangkan.
Barangkali itu juga yang membuat media sosial kini diisi dengan satu masalah ke masalah lainnya; dari satu kasus ke kasus lainnya. Itulah dialektika mahasiswa hari ini.
Dari beragam percakapan antarmahasiswa yang ada di Kompasiana, kami coba rangkum bagaimana sikap hingga pandangan mereka terhadap kasus atau persoalan yang kini terjadi di masyarakat.
1. [Warta Puan] Catcalling (Bukan) Bentuk Pujian untuk Perempuan!
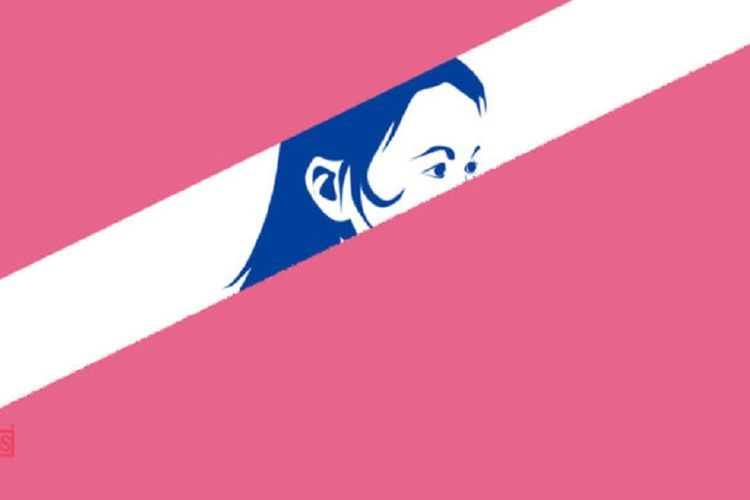
Sayangnya, menurut Kompasianer Nowie Shahabiyah, pandangan yang sama tidak didapati oleh perempuan yang menjadi korban catcalling ini.
Ya, pada akhirnya perlakuan catcalling justru membuat perempuan merasa diri dan tubuhnya dihina, dilecehkan.
Percayalah, catcalling tidak mengenal relasi pendidikan hingga sosial. Fenomena ini adalah bukti bahwa terjadinya catcalling tidak memiliki relasi dengan tingkat Pendidikan.
"Dalam hemat saya, bahwa masih sering sekali kita temui catcalling ini terjadi di instansi Pendidikan terutama universitas," tulisnya.
Pelaku catcalling, lanjutnya, bisa saja masyarakat dengan Pendidikan rendah ataupun dosen dengan tingkat Pendidikan yang tinggi. (Baca selengkapnya)
2. Feminisme Part 1: Puan yang Merayau

Kontribusi wanita untuk merdeka masih minim. Lihat saja pada kontribusi wanita dalam dunia pekerjaan di pasar tenaga kerja Indonesia. Setiap tahun masih stagnansi di angka kontribusi yang kecil.
"Pemikiran sejenis feminisme yang kontra dengan patriarki di Indonesia sendiri masih sering sekali memperoleh penolakan publik," lanjutnya.
Hal tersebut dilihat oleh Kompasianer Devidia Tri bahwa feminis dianggap sebagai perlawanan terhadap dogma, agama.
Ada saja feminis yang salah alamat dengan mendeklarasikan dirinya feminis namun kemudian menjadikan alasan untuk membenci pria. (Baca selengkapnya)
3. Standar Kecantikan, Perspektif Personal atau Konstruksi Media?

Stereotype mengenai definisi cantik lainnya, tulisnya, tampak selalu menjadi patokan dasar bagaimana seseorang menilai dan memilah perempuan bedasarkan bentuk visual yang ditampilkannya.
"Cantik boleh saja di definisikan, namun nampaknya respon terhadap perilaku seseorang seringkali dipilah-pilah bedasarkan kondisi fisik yang ditampilkan baik itu laki-laki maupun perempuan," tulis Kompasianer Aulia Marta.
Dari amatannya, hal tersebut bisa dipengaruhi oleh kontruksi dari media sosial.
Namun yang harus diketahui, standar kecantikan seharusnya tidak memberatkan perempuan hingga harus melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya dalam mengubah bentuk fisik mereka agar dapat dihargai publik.
"Perempuan Indonesia, dengan segala cantik versinya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, dan tipe wajah yang dimilikinya semuanya merupakan anugerah dari keberagaman," lanjutnya. (Baca selengkapnya)
4. Pandangan Psikologi terhadap Aksi Rasisme yang Menimpa "George Floyd" hingga Makna Pancasila di Dalamnya

Rasisme, tulis Kompasianer Cindy Carneta, dibangun di sekitar stereotip, asumsi, dan pandangan berprasangka. Namun, nyatanya rasisme bukan hanya sekadar mengenai sudut pandang berprasangka.
Lebih jelasnya, rasisme dan juga xenophobia bukanlah berakar dari faktor genetik atau evolusi.
Tindakan rasis merupakan hasil dari sifat psikologis yang lebih khusus, mekanisme pertahanan psikologis yang dipicu oleh perasaan tidak aman dan cemas dalam individu yang melaukan aksi rasisme.
"Rasisme mengganggu kemampuan kita untuk melihat orang sebagai individu, dan mengurangi kemampuan orang untuk mencapai potensi mereka," tulis Kompasianer Cindy Carneta. (Baca selengkapnya)
5. Menggugat Ketundukan Mutlak pada Orangtua

Muda, binal, hingga lupa berterimakasih, tulis Kompasianer Melathi Cantika, hampir selalu melekat pada karakter anak.
"Dari beragam tayangan, semestinya bukan hal aneh bila sanggahan atas omongan orang tua tidak lantas menjadikan anak itu menjadi tokoh antagonis dan si orang tua menjadi protagonis," lanjutnya.
Perasaan seperti itu tidak lahir begitu saja. Paling tidak, tulisnya, bisa bermula dari budaya membanding-bandingkan anaknya dengan anak tetangga, misalnya. (Baca selengkapnya)
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI