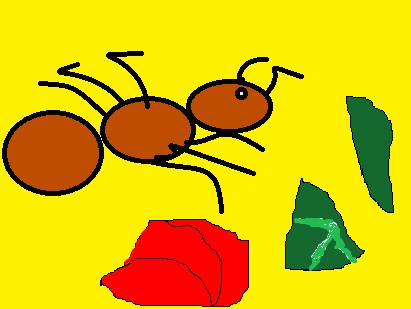“Emangnya direkrut dari mana lagi? Tempo hari yang dari kampung di Solo, senior saya di Jakarta mengajarkannya liputan?”
“Kang Alif bicaranya sudah anak Jakarta banget…angkuh dan merasa lebih pintar.” Terdengar suara lembut sekaligus sinis.
Alif menoleh. Seorang perempuan manis, mungil, rambutnya sebahu dengan kacamata. Dia mengenakan celana jins dan berdiri di kursinya mengulurkan tangan.
“Kalau begitu untuk saat ini Harum siap dipimpin oleh laki-laki yang pintar…” ucapannya enteng, bersahabat tetapi sekaligus menusuk. Masih seperti Alif yang pidato waktu mahasiswa atau sudah berubah...”
Nana Nugraha terkejut karena perempuan itu berani menyebut nama dan tidak Kang. Berarti sudah kenal sebelumnya.
“Dia Harum Semerbak Mawar, anak magang dari Jurnalistik, Fikom. Adik kelas saya,” Nana khawatir kalau Alif meledak.
“Kamu masih ingat…” Alif memandang perempuan itu karena merasa takjub sambil menyambut uluran tangannya.
Entah mengapa Alif segan terhadap perempuan itu. Matanya terus menantang matanya. Lalu Alif mendingin. Dia duduk berhadapan seperti tersihir.
“Kamu sudah jadi anak Jakarta. Jadi apa yang harus dilakukan anak kampung yang ingin belajar seperti saya.” Harum dengan dingin menatap Alif.
“Aduh, kunaon ini anak…” Nana Nugraha merasa tidak enak. Alif sudah dua tahun menjadi reporter, masih jauh jadi redaktur, tetapi tetap saja lebih senior. Alif sudah jadi reporter waktu tingkat terakhir, tanpa melalui proses magang karena dianggap sudah mahir menulis.
“Iya, kamu ikut saya ke kantor polisi kita ketemu korban dulu…” kata Alif mengeluarkan sehelai foto dan catatannya.