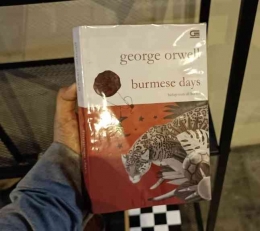Salah satu kehebatan George Orwell adalah ia lihai dalam merekam pengalaman sehari-hari menjadi sebuah karya tulis yang renyah. Dia memiliki bakat untuk menulis pengalaman umum yang orang lain juga rasakan ke dalam sastra sehingga ketika membacanya dalam hati bergumam, 'oh, ya, ya'.
Contoh karya tersebut adalah novel perdananya, Burmese Days. Novel ini diangkat dari pengalaman pribadi Eric Arthur Blair, nama asli Orwell.
Sehingga, ini dapat dikategorikan sebagai novel semi-otobiografi Orwell ketika menjadi polisi di Burma (sekarang Myanmar), sebagai seorang perwira polisi di Burma dari tahun 1922 hingga 1927. Orwell menggunakan latar fiksi Kyauktada, sebuah kota kecil di Burma Hulu.
Novel ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh beberapa penerbit. Seperti yang diterjemahkan oleh Gramedia dengan anak judul Hidup-Mati di Burma, misalnya.
Novel ini unik karena Orwell menggunakan sudut pandang penjajah sebagai narator utama, ini mungkin berbeda dengan mayoritas novel sejarah lainnya.
Novel Burmese Days terdiri dari dua puluh lima bab, dimulai dengan isu pada sebuah Klub Eropa di Burma. Pada tahun 1920-an, muncul imbauan dari Inggris Raya melalui Mr. Macgregor (Deputi Komisioner dan Sekretaris Klub) bahwa klub-klub yang ada di negara jajahan harus mengandung keterwakilan penduduk lokal. Klub Eropa Kyauktada adalah satu-satunya klub yang belum berisi anggota dari penduduk Oriental.
Istilah "oriental" (orang timur) digunakan untuk menggambarkan penduduk asli dalam novel ini, sebuah istilah umum untuk menyebut orang-orang keturunan Asia, penduduk asli, lokal. Di Indonesia, penduduk asli lebih dikenal dengan sebutan "Pribumi," atau "bumi putera."
Novel ini dinaratori dari sudut pandang John Flory, seorang pedagang kayu, juga seorang anggota Klub Eropa tersebut. Orwell menggunakan karakter Flory untuk mengeksplorasi beberapa tema besar seperti imperialisme, rasisme, dan gegar budaya.
Tapi saya tidak akan memberikan terlalu banyak bocoran, spoiler, silakan baca dan beli sendiri novelnya. Saya hanya akan mengangkat, memberikan clues tentang isu-isu menarik yang disuarakan oleh Orwell dalam novel ini.
Satu tokoh, U Pyo Kin, sangat menonjol. Dia adalah tokoh yang digambarkan bermuka dua, munafik, menyuap, dan bekerja sebagai kepala distrik. Dia memanfaatkan posisinya untuk mengisi kantongnya sendiri dengan menganiaya rakyat Kyauktada.
U Pyo Kin adalah contoh nyata pelaku korupsi dan ketidakadilan, penyuapan, yang sering kamu lihat di negara-negara berkembang, seperti Konoha.
Dan karakternya terasa cukup relevan dengan apa yang terjadi saat ini, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang saya maksudkan dengan salah satu kelihaian tingkat tinggi Orwell di muka artikel.
Emosi kita diaduk-aduk saat membaca bab demi bab dalam novel ini, membangkitkan perasaan marah, sedih, dan harap-harap cemas. Orwell menggunakan bahasa yang lugas, vulgar, kasar, dan terkadang santai untuk menggambarkan realitas imperialisme dan rasisme.
Wanita, misalnya, sering digambarkan memiliki status yang setara dengan hewan pengerat atau katak. Di sinilah kecemerlangan Orwell; meskipun bahasa yang digunakan bisa dikategorikan kasar dan vulgar, namun di ujung pena Orwell menjadi sesuatu yang sangat indah ketika dibaca.
Hal inilah yang membuat M. Febi Anggara tergelitik setelah membaca karya-karya Orwell. Dalam diskusi Klub Buku Main-Main minggu ke-67 pada Senin, 18 September 2023 lalu, ia melontarkan pertanyaan: "Mengapa Orwell menulis dengan cara seperti itu?"
"Saya tidak memiliki jawaban pasti untuk itu, tapi saya punya hipotesis," jawab Yosi Sulastri, pemantik diskusi kali ini. "Saya berhipotesis Orwell, menulis seperti itu, untuk menggambarkan situasi di Burma dengan cara yang lugas dan otentik, tidak dibuat-buat, berdasarkan pengalamannya sendiri selama lima tahun menjadi polisi di sana."
Esai Orwell yang berjudul Why I Write, mungkin dapat memberikan beberapa wawasan dan petunjuk tentang motivasinya untuk menulis dengan cara tersebut.
Bagi Orwell, politik dan karya sastranya tidak dapat dipisahkan, dan bahkan memilih untuk tidak berpolitik pun merupakan sebuah pilihan politik.
"Menurut Orwell, sastra adalah politik. Mungkin bagi kita, kata-kata yang ia gunakan terlihat kasar dan vulgar, tapi itu semua adalah politik - sebuah cara untuk menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap penindasan," ujar Firdaus, salah satu peserta diskusi lain.
Oleh karena itu, Orwell menulis Burmese Days dengan cara ini karena ia ingin menggambarkan secara visual dan berdasarkan keadaan sesungguhnya kondisi di Burma berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan.
Dia bertujuan untuk menggunakan tulisannya sebagai alat untuk mempengaruhi dunia dan menjadikannya tempat yang lebih baik, mengadvokasi cinta, pemberantasan rasisme, dan anti-imperialisme.
Lantas, apa itu imperialisme, apa perbedaan antara imperialisme dan kolonialisme? Mengapa jajahan Inggris menggunakan istilah imperialisme, dan jajahan Belanda menggunakan kolonialisme?
"Kamu bisa mendominasi sebuah negara tanpa menjajah," jawab salah satu anggota diskusi yang lainnya, Ndeye Kor.
Kolonialisme mencakup pengambilalihan wilayah asing melalui kontrol militer atau politik, sering kali termasuk pemukiman para terjajah. Imperialisme, sebaliknya, adalah penggunaan pengaruh terhadap negara lain tanpa penjajahan fisik, sering kali melalui cara-cara ekonomi dan politik.
Pernyataan Kor, "kamu bisa mendominasi sebuah negara tanpa menjajahnya," memiliki banyak contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak perlu jauh-jauh, kita sering menjumpai tengkulak atau broker yang memberikan pinjaman kepada petani atau pengrajin, tetapi sebagai imbalannya, mereka menuntut agar hasil panen atau produk dijual kepada mereka dengan harga yang ditentukan oleh tengkulak atau broker.
Ini merupakan contoh kecil dari imperialisme, sebuah konsep yang tidak diabaikan oleh Orwell. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika Burmese Days tetap relevan dan layak dibaca hingga saat ini.
Pada titik tertentu, tulisan-tulisan George Orwell, khususnya Burmese Days, menjadi bukti yang kuat akan kemampuannya untuk menangkap pengalaman hidup sehari-hari dan mengubahnya menjadi refleksi yang mendalam tentang tema-tema universal.


Mengingatkan kita akan kekuatan sastra yang tak lekang oleh waktu untuk menjelaskan kompleksitas dunia dan menginspirasi perubahan positif [mhg].
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H