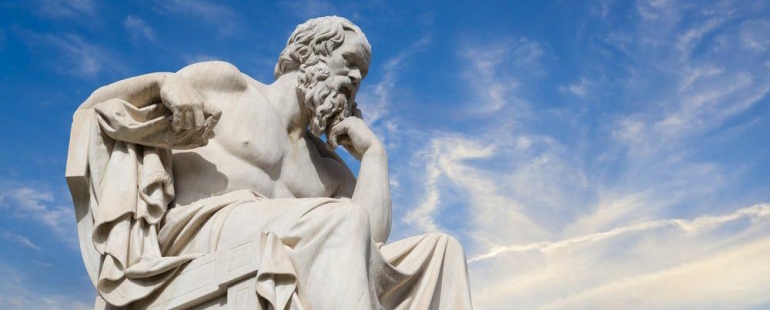Positivisme Logis cukup gigih menyerang segala yang irasional, meskipun dalam beberapa hal melenyapkan segudang apa yang paling penting dalam filsafat, yakni pernyatan-pernyataan etis yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah berdasar kaidahnya. Akibatnya, meskipun mereka menuntut keobjektifan terhadap semua hal, tapi untuk masalah etika, mereka justru terkesan sangat subjektif. Pada kondisi demikian, eksistensialisme hadir demi menandingi apa yang luput dari para penganut positivis logis. Mereka menaruh perhatian utama pada tanggung jawab dan keunikan pribadi, sangat menjunjung tinggi subjektivitas. Mereka hampir bisa dikatakan memandang curiga kerumunan, orang kebanyakan, sekawanan manusia, yang mengaburkan autensitas pribadi : diri yang sejati dan otentik.
Eksistensialisme adalah sebuah filsafat yang menyeruak dari eksplorasi yang tajam atas suasana psikologis manusia, terutama situasi-situasi yang negatif, semisal kecemasan dan rasa takut. Soren Kierkgaard, si peletak dasar eksistensialisme ini, lebih senang disebut sebagai psikolog dan seorang penyair tinimbang filsuf. Metode pencarian filosofis yang diriintisnya sebenarnya bisa kita telesuri, jauh di jaman sebelumnya kepada Plotinos. Gaya ala Plotinos adalah dengan mencoba menggali hakikat diri manusia yang positif—katakanlah jiwa, dimulai dengan ekplorasi dan analisa atas psikis manusia.
Di antara sekian penerus Eksistensialisme, barangkali Heidegger adalah yang kontroversoial. Perpaduan antara nihilisme Nietszce, dengan fenomenologi Husserl, dan mistik ala Eckhart, menjadikan filsafat Heidegger sebagai tonggak penting dalam sejarah peradaban Barat. “..Badai yang dihembuskan pemikiran Heidegger, sebagaimana badai karya Plato yang menerpa kita selama berabad-abad..” demikian tulis Hannah Arendt, murid, kekasih gelap, sekaligus inspirator bagi karya-karyanya.
Perkembangan pemkiran Heidegger tak bisa dilepaskan dari situasi jaman di kala itu. Pengalaman dirnya selama mengukuti perang dunia pertama, sangat membekas di benaknya. Apa yang dialaminya di medan tempur, di mana seorang manusia bukanlah apa-apa, seolah terlempar tanpa tahu dari mana asal dan ke mana tujuannya. Pengalaman negatif akan kecemasan dan keterlemparan inilah yang dianggap paling riil , yang oleh Heideggger diangkat sebagai motif utama, pijakan dasar bagi pemikiran filosofisnya.
Manusia dalam pandangan Heidegger adalah dasein, atau ada yang itu. Dasein disebut juga sebagai sosok yang tidak menyadari Ada, sebagai sumber eksistensinya. Persis saat manusia terlahir ke dunia, ia terlempar, hadir begitu saja dalam dunia ini (faktisitas). Manusia sebagai dasein ini terlarut dalam keseharian (besorgen), hadir bersama dengan yang lain, baik dengan perangkat teknologi yang siap pakai (zuhandenes), atau bersama dasein lainnya (mitdasein). Ia pada hakikatnya adalah sosok yang tidak mengenal dirinya sendiri yang otentik. Dari sinilah, eksistensialisme Heidegger nampak kental.
Jika eksistensialisme, mencoba menarik diri dari kerumunan orang, mencoba naik dari ketenggelaman keseharian yang banal, Heidegger pun demikian. Hanya saja, yang lebih utama dalam pandangan Heidegger, bukan lari dari kehidupan keseharian demi mencari diri yang otentik. Justru dari keseharian yang banal, seorang dasein secara sadar, harus bisa melihat Ada, sumber eksistensinya, harus bisa memandang keseharian dengan cermat, dalam, dan tembus pandang.
Tapi terkadang , ada masa di mana seorang dasein tersentakkan dengan cukup keras dri ketenggalaman kesehariannya. Momen di mana seorang dasein terputus dari rutinitas, sebagai dampak pengalaman yang menyakitkan, kehilangan sandaran diri, atau peristiwa yang mengguncang. Inilah momen yang tepat bagi seorang dasein untuk mulai mengakrabi stimmung (suasana hatinya sendiri) terutama yang berkaitan perasaan yang paling dasar ; keterasingan, kecemasan dan rasa takut, yang merangsang dirinya untuk bersegera mencari diri otentiknya, menyadari Wujud Ada sebagi sumber eksistensinya.
***
Jika Kierkgaard, beranggapan untuk mengatas kecemasan eksisensial, manusia harus melompat ke dalam iman, maka Heidegger sama sekali tidak menyentuh masalah keagamaan dalam filsafatnya. Ada, sebagai sumber eksistensi, juga tidak disebut sebagai Tuhan. Agama dalam pandangan Heidegger, justru seringkali mengaburkan keotentikan, karena agama yang dipahami adalah warisan dari kerumunan, pendapat orang tua, mapun sekadar opini publik. Lantas, kapan dasein bisa menyadari totalitas dirinya sendiri, mamahami diri yang otentik secara paripurna. Jawaban Heidegger, manakala seseorang mengalami kematian.
Saat inilah dasein mengalami totalitasnya sekaligus ketiadaannya. Tapi kematian di sini adalah kematian esistesnial, yang datang menghampiri berkali-kali, bergantung kerterbukaan dasein terhadap apa yang datang. Dasein mesti berupaya meraih otensitasnya, dengan menyadari kematian ini. dasein harus merasa cemas secara eksistensial, terhadapnya. Cemas yang menuntut sikap mengantsiipasi. Menyadari. Seperti sikap Socarets.
***