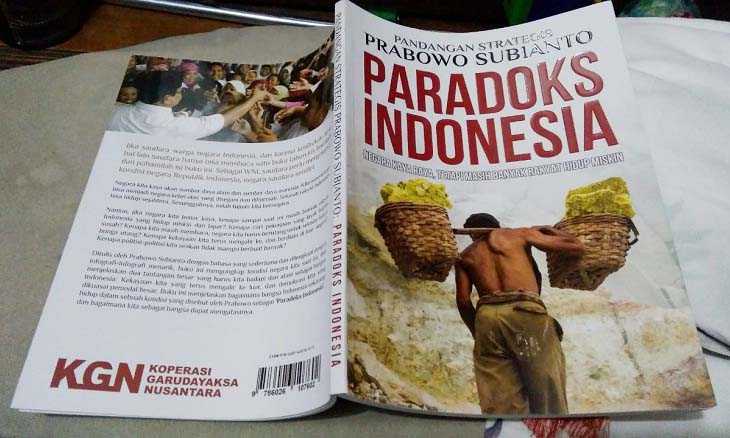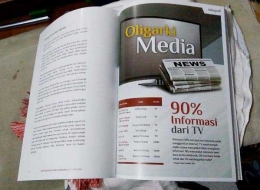Masyarakat kita berharap media netral, tidak berpihak selain ke kepentingan bangsa, tidak menjadi propagandis kepentingan tertentu.
Tulis Prabowo, saya angkat topi kepada media-media yang secara eksplisit menyatakan keberpihakan kepada partai politik, atau kandidat tertentu dalam sebuah pemilihan, atau isu politik tertentu.
Apalagi jika pernyataan keberpihakannya diulang terus-menerus, sehingga masyarakat dapat mengetahui berita yang diterbitkan berat sebelah. Jangan seolah tidak berpihak, seolah tidak bisa dibeli, tetapi menjerumuskan.
Membaca opini Prabowo soal oligarki media -- yang sengaja saya tebalkan kalimatnya -, ada dua komentar yang muncul di benak saya.
Pertama, Prabowo mungkin saja kesal, karena media massa terutama stasiun televisi kurang berpihak kepada diri (kubu)-nya.
Kedua, Prabowo boleh jadi kesal, kalau ada media massa yang mencla-mencle. Seolah independen, tapi sebenarnya justru tidak.
Dalam bahasa Prabowo, disebut kata "menjerumuskan". Saya pikir berlebihan diksi "menjerumuskan" ini.
Alasannya, "seburuk-buruknya" media massa apalagi televisi, tetap punya Kode Etik Jurnalistik yang wajib ditaati, dan, jangan lupa ada Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi dan siap meniup peluit peringatan lalu memberi kartu kuning dan merah, bila terbukti melanggar aturan.
Dua kemungkinan rasa kesal Prabowo ini, bila dikaitkan dengan masa kekinian boleh jadi bisa semakin memuncak.
Mengapa? Ya, ketika cetakan perdana buku ini diterbitkan pada Februari 2017, mungkin tak pernah ada yang menyangka kalau 20 bulan kemudian, pengusaha muda Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Capres-Cawapres dari kubu petahana, Joko Widodo--Ma'ruf Amin.
Tema besar "Paradoks Indonesia" yang disuarakan Prabowo untuk bahasan "Oligarki Media" akhirnya seolah dijawab Jokowi, dengan memunculkan tokoh muda yang baru saja berprestasi menyukseskan pesta olahraga Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang.