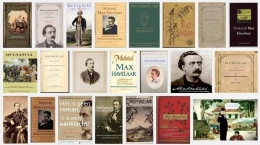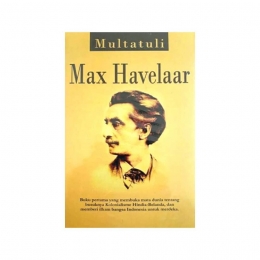Salah satu episode kolonialisme yang menuai kritik adalah ketika pemerintah melakukan usaha eksploitasi negara kolonial terhadap masyarakat bumiputra melalui sistem tanam komoditas ekspor.
Sistem yang lazim disebut sebagai cultuurstelsel atau tanam paksa (1830---1870) ini menuai reaksi keras dari pegawai pemerintah Hindia Belanda bernama Eduard Douwes Dekker (1820---1887).
Douwes Dekker mengkritik kebijakan tanam paksa yang sangat menyengsarakan bumiputra melalui novel Max Havelaar dengan nama samaran Multatuli pada tahun 1860.
Novel Max Havelaar (1860) yang sedang diulas ini memberikan gambaran menarik tentang bagaimana sebuah karya sastra dapat menyatakan pandangan ideologi dengan cara khas, implisit, dan imajinatif.
Meskipun termasuk dalam karya sastra---yang dipandang sebagai tulisan fiksi dan bualan belaka---roman tersebut rupanya menimbulkan kegelisahan di kalangan kolonialis semenjak pertama kali terbit pada 1860 dan memuncak ketika terdapat versi bahasa Inggrisnya pada 1868.
Penyebab "meledaknya" novel tersebut di pasaran pada masa itu dikarenakan dua hal, yaitu gelombang liberalisme di Eropa yang sedang mengemuka dan ketidaktahuan orang Eropa terhadap situasi di negeri koloni.
Pada tahun terbitnya novel tersebut, orang Eropa---khususnya orang Belanda---tidak memiliki pemikiran apapun terhadap negeri koloni. Mereka hanya menikmati hidup enak di Eropa tanpa pernah memikirkan datangnya keenakan yang ia rasakan tersebut; tanpa pernah memikirkan peluh keringat orang negeri koloni.
Apalagi buku tersebut ditulis berdasarkan pengalaman langsung Dekker dan menjadi buku pertama yang menggambarkan praktik kolonial, sehingga hadirnya buku tersebut seakan menggerakkan hati dan menggugah kenikmatan yang dirasakan orang Eropa bahwa terdapat ketidaknormalan di koloni---wilayah nan jauh dimata dan tidak pernah mereka bayangkan.
Ide penulisan novel ini berawal ketika Douwes Dekker melihat langsung bagaimana situasi koloni serta perilaku pejabat Belanda dan lokal yang abai terhadap taraf hidup masyarakat bumiputra.
Dengan berapi-api dan sangat antusias, penulisnya mempersembahkan kisah ini kepada saudara-saudara sebangsanya dalam bentuk novel---buku yang memperkenalkan bangsa Belanda pada pemerasan dan tirani luar biasa yang diderita oleh penduduk asli Hindia Belanda (hlm. 7).
Max Havelaar: Sebuah Catatan Sistematis
Karya Max Havelaar dari Multatuli ini berupaya membongkar skandal berupa tindakan memalukan yang dilakukan pemerintah untuk melanggengkan tindakan eksploitatifnya. Tindakan tersebut berupa pemanfaatan tradisi feodal, perilaku ketika rakyat memberikan "hadiah" kepada para raja atau elit pribumi, yang sudah terjadi di Hindia Belanda bertahun-tahun lamanya.
Alih-alih berupaya membebaskan rakyat dari tindakan tersebut, pemerintah justru malah memanfaatkan tindakan sistem feodal untuk meraup untung sebanyak- banyaknya dari rakyat.
Dengan kata lain, pemerintah kolonial malahan semakin memperkuat struktur penindasan itu melalui kebijakan pemerintah tidak langsung, yang menggunakan pimpinan tradisional dalam menjalankan birokrasi kolonial untuk meraup untung.
Kedudukan- kedudukan tradisional yang dinikmati oleh penguasa pribumi menjadi landasan penindasan rakyat di dalam struktur feodal yang digambarkannya dan menjadi dasar legitimasi kekuasan kolonialisme Belanda di Hindia Belanda (hlm. 65).
Oleh sebab itu, Multatuli menyayangkan tindakan tersebut dan menggambarkan relasi antara rakyat-elit pribumi-negara yang menurut kacamata Eropanya adalah sebuah ketidaknormalan
Secara umum sistematika penulisan novel ini dibagi ke dalam 20 bagian. Ulasan novel ini ditulis berdasarkan sudut pandang penulisan yang dibagi menjadi dua bagian. Pada bagian pertama, dimulai dari bab 1-bab 4, sudut pandang penulisan berasal dari seorang makelar kopi bernama Droogstoppel.
Penulis memunculkan tiga tokoh utama pada bagian pertama ini, antara lain Droogstoppel, Sjaalman (Kawan Droogstoppel dari Hindia Belanda), dan Ernest Stern (Anak buah Droogstoppel). Penulis menceritakan pertemuan Droogstoppel dengan Sjaalman yang kemudian meminta Droogstopel menerbitkan draft tulisannya. Seiring berjalannya waktu, meski sempat ditolak, draft tulisannya disetujui untuk diterbitkan.
Dalam bayangan Droogstoppel, karya tersebut nantinya akan berkisah mengenai perdagangan kopi dan sangat berguna untuk kelancaran usahanya. Namun, dalam proses penulisan dan penerbitan, naskah tersebut ditulis oleh Ernest Stern---pegawai Droogstoppel---dan menghasilkan judul yang tidak dibayangkan sebelumnya oleh Droogstoppel, yaitu lelang kopi maskapai dagang Belanda.
Dari sinilah babak baru penulisan novel ini dimulai. Berawal dari bab 5-bab 20, Multatuli memulai tulisan dengan sudut pandang Stern yang mengisahkan kisah hidup seorang Max Havelaar, Asisten Residen Lebak, yang menjadi saksi mata atas perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat pribumi. Kemiskinan, kelaparan, dan kesengsaraan menjadi penggambaran Havelaar terhadap kondisi di Hindia Belanda atas tindakan eksploitatif di koloni.
Dalam pengamatan lebih lanjut, rupanya, tindakan keji itu tidak hanya dilakukan oleh orang Belanda saja, tetapi terdapat orang pribumi di dalamnya.
Setelah menyurati---sebagai bentuk protes---kepada Gubernur Jenderal dan tidak ditanggapi, pada akhirnya, Havelaar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bentuk protesnya terhadap, perampasan, penganiayaan, dan diskriminasi.
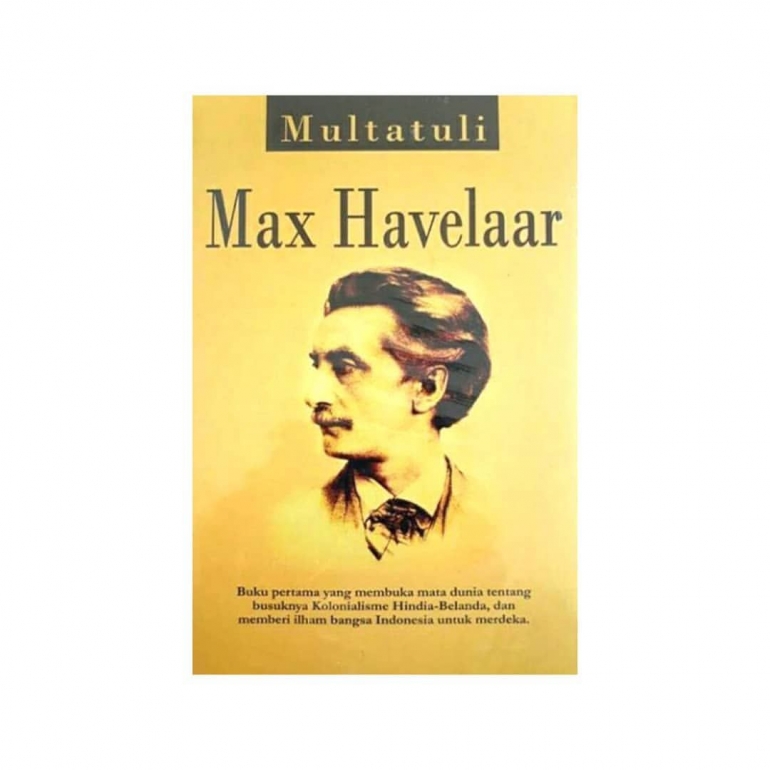
Menelisik lebih lanjut, buku ini boleh dikatakan menarik karena memberikan pendekatan berbeda dalam menyajikan keadaan di Hindia Belanda.
Alih-alih menyajikannya melalui monograf dengan pendekatan ilmu pengetahuan nan rumit, Multatuli menyajikannya dalam karya sastra sehingga mampu menembus kenyataan yang tidak nampak dipermukaan dan memungkinkan kritik lebih lanjut melalui paparan dari segi gaya bahasa, diksi, dan penokohan sembari menampilkan debat tentang kolonialisme di Hindia Belanda melalui opini dan sudut pandang tokoh.
Tidaklah mengherankan, ketika novel ini terbit dalam versi bahasa Indonesia pada medium 1970-an, Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa novel ini membunuh kolonialisme (1999).
Pendapat Pram ini sebetulnya berawal dari wawancaranya dengan salah satu media pada tahun 1999. Pram memandang bahwa Dekker telah berupaya membuka mata dan pikiran dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia serta memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk merdeka.
Ia berupaya menyadarkan bahwa mereka dijajah dibawah paradigma Jawaisme yang dimanfaatkan oleh praktik kolonial. Pram juga mengatakan bahwa gagasan Dekker dalam Max Havelaar mempunyai pengaruh tidak langsung dalam dekolonisasi Indonesia dan negara-negara di Afrika.
Namun, pendapat Pram harus kita kritisi dengan mengajukan pertanyaan berupa: Apakah Dekker menyebutkan kolonialisme itu jahat? Apakah Dekker justru menikmati kolonialisme? Atau siapa sasaran kritik Dekker, kolonialisme atau birokrasi kolonial? Pertanyaan ini cukup menarik karena cenderung mematahkan pandangan "novel pembunuh kolonialisme".
Sejatinya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab Rob Nieuwenhuys dalam Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli (2019). Sejalan dengan Nieuwenhuys, meski menggambarkan "citra antikolonial", novel dengan hampir 500 halaman tersebut tidak pernah menyarankan, menghentikan dan tidak menyerang, apalagi memberikan solusi atas persoalan kolonialisme
Multatuli justru mengkritik sistem birokrasi tradisional (Bupati Lebak) yang dianggap olehnya sebagai tindakan tidak terpuji. Salah satunya bisa dilihat dalam kasus Saidja dan Adinda di bab 17 ketika terjadi pemberian hewan kepada pemerintah, padahal kalau ditelaah perilaku tersebut adalah wajar sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin, bukan tindakan tidak terpuji sebagaimana yang diserang Dekker. Meminjam istilah Rob, bahwa Multatuli tidak memahami Jawa.
Akibat kepiawaiannya menggambarkan situasi pada masa itu, banyak pendapat yang menyebutkan bahwa novel Max Havelaar menjadi faktor besar dalam membuahi kebijakan manusiawi Hindia Belanda di tahun 1901, yakni Politik Etis. Kiranya pendapat dan frasa 'faktor besar dan membuahi' tersebut kurang tepat.
Penggambaran oleh Multatuli terhadap praktik kolonial memang benar menimbulkan kritik di kalangan parlemen Belanda, tetapi kritik tersebut tidak membawa kesejahteraan yang lebih baik justru semakin mengurangi taraf hidup masyarakat pribumi dengan lahirnya politik pintu terbuka. Oleh karena itu, frasa dan pandangan yang lebih tepat adalah 'Novel Max Havelaar memiliki pengaruh tetapi tidak membuahkan dan tidak menjadi faktor tunggal'.
Apabila melihat pada artikel dan argumentasi Deventer atas tuntutan balas budinya, ia mengkritisi tindakan tanam paksa dan praktik ekonomi liberal yang menghasilkan kas selama bertahun-tahun. Atas tulisan tersebut, kaum liberal dan religius di Negeri Belanda memaksa pemerintah negeri induk melaksanakan politik balas budi atau Politik Etis. Lagipula, perlu diketahui, tidak semua orang etis di parlemen setuju dengan Multatuli, termasuk Rob Niewenhuis, dan semakin mematahkan frasa 'faktor besar dan membuahi'.
Sebagai penutup, sejak Max Havelaar terbit sampai saat ini, perdebatan masih dalam kontestasi: novel antikolonial atau prokolonial; Multatuli atau Anti-Multatuli. Terlepas dari hal tersebut, karya berharga dari Multatuli adalah perjuangannya menuntut keadilan atas ketimpangan yang disebabkan oleh tindakan penjajahan.
Rasa solidaritas yang ditunjukkannya menandai semangat perjuangannya membela keadilan tanpa melihat perbedaan di antara masyarakat yang terkadang cenderung rasialis. Ia memandang penjajah adalah siapapun mereka yang melakukan penindasan terhadap yang lemah baik dilakukan oleh pejabat kolonial ataupun pribumi feodal. "Justru inilah kehebatan bukuku: gagasan-gagasan utamanya mustahil runtuh dibantah. Dan, semakin besar ketidaksukaan orang terhadap bukuku, semakin aku merasa senang, karena kesempatan untuk didengarkan akan jauh lebih besar lagi" (Hlm 462)
Daftar Pustaka
1. Multatuli. (2019). Max Havelaar. Jakarta: Qanita [Edisi asli buku ini berjudul Max Havelaar (1860)]
2. Niuewnhuys, Rob. (2019). Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli. Depok: Komunitas Bambu. [Edisi asli buku ini berjudul De Mythe Van Lebak (1989). Van Oorschot: Amsterdam]
Penulis
Muhammad Fakhriansyah adalah mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta. Tulisannya berfokus pada sejarah kesehatan Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI