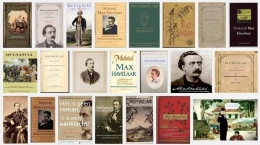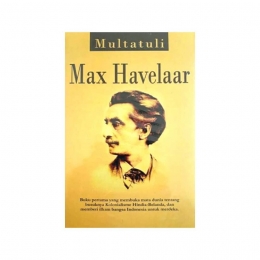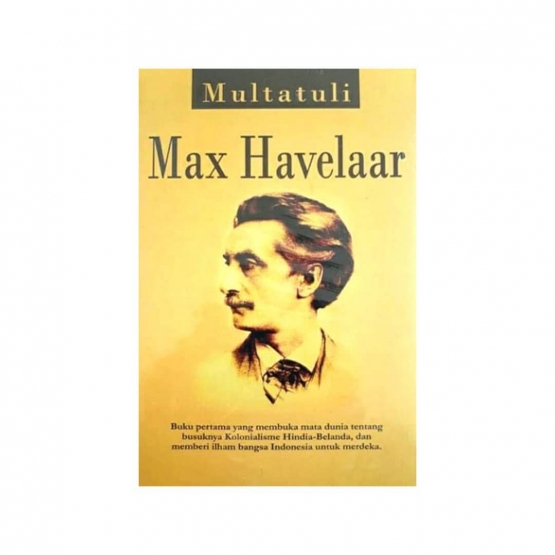
Menelisik lebih lanjut, buku ini boleh dikatakan menarik karena memberikan pendekatan berbeda dalam menyajikan keadaan di Hindia Belanda.
Alih-alih menyajikannya melalui monograf dengan pendekatan ilmu pengetahuan nan rumit, Multatuli menyajikannya dalam karya sastra sehingga mampu menembus kenyataan yang tidak nampak dipermukaan dan memungkinkan kritik lebih lanjut melalui paparan dari segi gaya bahasa, diksi, dan penokohan sembari menampilkan debat tentang kolonialisme di Hindia Belanda melalui opini dan sudut pandang tokoh.
Tidaklah mengherankan, ketika novel ini terbit dalam versi bahasa Indonesia pada medium 1970-an, Pramoedya Ananta Toer mengatakan bahwa novel ini membunuh kolonialisme (1999).
Pendapat Pram ini sebetulnya berawal dari wawancaranya dengan salah satu media pada tahun 1999. Pram memandang bahwa Dekker telah berupaya membuka mata dan pikiran dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia serta memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk merdeka.
Ia berupaya menyadarkan bahwa mereka dijajah dibawah paradigma Jawaisme yang dimanfaatkan oleh praktik kolonial. Pram juga mengatakan bahwa gagasan Dekker dalam Max Havelaar mempunyai pengaruh tidak langsung dalam dekolonisasi Indonesia dan negara-negara di Afrika.
Namun, pendapat Pram harus kita kritisi dengan mengajukan pertanyaan berupa: Apakah Dekker menyebutkan kolonialisme itu jahat? Apakah Dekker justru menikmati kolonialisme? Atau siapa sasaran kritik Dekker, kolonialisme atau birokrasi kolonial? Pertanyaan ini cukup menarik karena cenderung mematahkan pandangan "novel pembunuh kolonialisme".
Sejatinya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijawab Rob Nieuwenhuys dalam Mitos dari Lebak: Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli (2019). Sejalan dengan Nieuwenhuys, meski menggambarkan "citra antikolonial", novel dengan hampir 500 halaman tersebut tidak pernah menyarankan, menghentikan dan tidak menyerang, apalagi memberikan solusi atas persoalan kolonialisme
Multatuli justru mengkritik sistem birokrasi tradisional (Bupati Lebak) yang dianggap olehnya sebagai tindakan tidak terpuji. Salah satunya bisa dilihat dalam kasus Saidja dan Adinda di bab 17 ketika terjadi pemberian hewan kepada pemerintah, padahal kalau ditelaah perilaku tersebut adalah wajar sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin, bukan tindakan tidak terpuji sebagaimana yang diserang Dekker. Meminjam istilah Rob, bahwa Multatuli tidak memahami Jawa.
Akibat kepiawaiannya menggambarkan situasi pada masa itu, banyak pendapat yang menyebutkan bahwa novel Max Havelaar menjadi faktor besar dalam membuahi kebijakan manusiawi Hindia Belanda di tahun 1901, yakni Politik Etis. Kiranya pendapat dan frasa 'faktor besar dan membuahi' tersebut kurang tepat.
Penggambaran oleh Multatuli terhadap praktik kolonial memang benar menimbulkan kritik di kalangan parlemen Belanda, tetapi kritik tersebut tidak membawa kesejahteraan yang lebih baik justru semakin mengurangi taraf hidup masyarakat pribumi dengan lahirnya politik pintu terbuka. Oleh karena itu, frasa dan pandangan yang lebih tepat adalah 'Novel Max Havelaar memiliki pengaruh tetapi tidak membuahkan dan tidak menjadi faktor tunggal'.