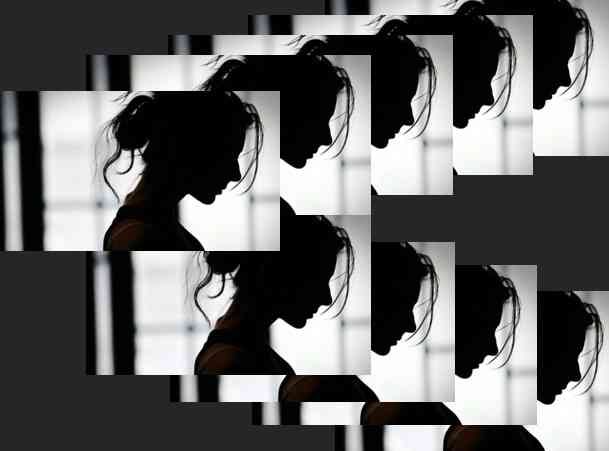Gelas-gelas itu berubah warna, dari hijau ke kuning, lalu menjadi merah. Pecah. Perempuan-perempuan yang memegang gelas-gelas itu lunglai ke tanah. Tak bernyawa. Seperti kehabisan tenaga. Tak berdaya. Tak bersuara. Keluarga bertangisan, melihat dari kejauhan. Setelah seminggu, barulah mereka bisa menjemput jenazah perempuan-perempuan itu untuk kemudian dipusarakan.
Airmata menderas di pipiku. Hanya dalam beberapa menit sejak tiba di Desa Kenangan 1, aku sudah menyaksikan cukup banyak gelas yang berubah warna dan pecah.
“Aku harus kuat untuk bisa menuliskan cerita ini dan segera memublikasikannya,” pikirku.
Sementara aku sibuk merogoh buku gawai dari ransel, sejumlah perempuan lainnya masih berdiri di Lapangan Gelas Kenangan di bibir luar dari desa itu. Mereka memegang gelas-gelas berwarna hijau, kuning, atau merah. Ada yang segera tumbang begitu gelas yang dipegangnya bertahan satu jam dalam warna merah.
Sosok-sosok baru terlihat muncul dari gerbang desa, dengan memegang gelas, dan bergabung di lapangan.
Yang bisa bertahan selama satu jam memegang gelas dan mempertahankan warnanya tetap hijau, terlihat melangkah masuk kembali ke arah Desa Kenangan 1 dan desa di sekitarnya. Gelas di tangan mereka lenyap. Wajah-wajah mereka terlihat lega sekali. Keluarga menyambut dengan suka hati dan mendampingi sampai rumah.
Aku adalah jurnalis muda dari kantor berita Cecarat – singkatan dari "cepat, canggih, akurat". Cecarat merupakan kantor berita baru dan saat ini diakui sebagai media tercanggih di dunia. Banyak yang melamar kerja di Cecarat, tetapi sedikit yang terpilih. Seleksinya amat ketat. Hanya yang dinilai benar-benar berbakat dan berkompetensi yang lolos.
Aku beruntung. Baru saja lulus sebagai doktor dalam ilmu humaniora digital, aku langsung ditawari bekerja di Cecarat. Aku getol belajar, sehingga memutuskan akan bekerja setelah menyelesaikan sekolah sampai jenjang doktoral. Sangat bersyukur bahwa warisan orangtuaku cukup banyak, sehingga tidak ada kendala biaya untuk mewujudkan impianku itu.
Ketertarikanku pada bidang humaniora berawal dari pengalaman hidup. Ibuku perempuan tangguh. Namun, suatu kali, ayahku selingkuh. Untuk soal yang satu ini, ibu rapuh. Tak mampu melupakan kepahitan itu, ibu mengakhiri hidupnya tak lama kemudian.
“Berdamai? Ya. Bersatu? Tidak,” tegas ibuku ketika ayahku meminta maaf dan memohon diberikan lagi kesempatan untuk hidup bersama.
Setahun kemudian, ayah menyusul ibu karena depresi berat. Paman dan bibi menjadi waliku.
Kemajuan teknologi mempercepat perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kini, bidang humaniora mempunyai turunan ilmu berupa Humaniora Digital. Dengan perangkat digital yang makin canggih, pendekatan humaniora menjadi lebih kompleks. Humaniora Digital adalah studi kritis yang mempertemukan disiplin ilmu yang lain, yakni teknologi digital, Seni dan Humaniora, dan komunikasi ilmiah.
Aku bersyukur menjadi doktor perempuan pertama di negaraku untuk bidang baru ini. Mungkin, Cecarat sudah membaui tapak akademikku sejak muda. Namaku memang sering muncul di media massa karena prestasi dan tulisan-tulisanku. Aku hobi menulis.
Cecarat memiliki satelit sendiri untuk mencitra berbagai fenomena di bumi, dari fenomena alam sampai fenomena buatan. Namanya Satelit Melihat. Dengan teknologi ini, aku bisa memonitor fenomena di bumi dan mengulas hal-hal menarik terkait humaniora.
Suatu kali, aku menangkap keanehan dari citra satelit. Ada area tertentu yang kadang berwarna hijau, kadang kuning atau merah.
“Benar, Bu, kami juga melihatnya. Tetapi, kami kira itu citra biasa,” kata seorang rekan ketika kuutarakan fenomena itu.
Sebagai pegelut humaniora, aku penasaran. Dari pembesaran citra bisa terbaca, area-area itu terletak di lapangan berbentuk bundar, yang terletak di tengah-tengah sejumlah pemukiman yang mengelilinginya. Tidak hanya satu lapangan. Tapi, begitu banyak. Zona-zona itu terlihat seperti pusaran-pusaran inti dari bundaran-bundaran lebih besar yang mengelilinginya.
“Cantik juga, ya, dan unik,” kata sahabatku ketika kuperlihatkan foto-foto hasil pencitraan satelit. “Mirip inti-inti sel pada jaringan yang kulihat di bawah mikroskop,” tambah karibku yang dokter itu.
Aku mengiyakan. Keputusanku makin mantap untuk terjun ke salah satu lapangan bundar itu, yang terletak di Kabupaten Beban Batin. Entah kenapa namanya demikian. Nalarku berkata, tentu berkaitan dengan masalah batin dan beban hidup.
Lapangan Gelas Kenangan dikelilingi oleh sepuluh desa. Semuanya bernama Desa Kenangan. Pembedanya cuma nomor. Jadi, ada Desa Kenangan 1, Desa Kenangan 2, dan seterusnya.
Di kabupaten yang sama, ada lapangan gelas lain dan rata-rata dikelilingi oleh sepuluh desa. Lapangan Gelas Memori, misalnya, dikelilingi oleh Desa Memori 1, Desa Memori 2, dan seterusnya. Ada juga Lapangan Gelas Akar Pahit, Lapangan Gelas Dendam, dan sebagainya.
“Menurut cerita nenek-moyang kami, daerah ini pernah terkena serapah orang sakti. Kalau punya masalah tetapi tidak mau merelakannya pergi, yang punya masalah akan tewas akibat gelas ajaib,” kata Kepala Desa Kenangan 1.
“Dengan kejadian yang kami lihat sendiri, serapah itu tampaknya benar,” tambahnya.
“Mengapa warga tidak pindah saja, Pak?” tanyaku.
“Sumpah itu melekat pada semua warga yang ada pada waktu itu dan keturunannya. Jadi, pindah pun tidak berpengaruh. Warga juga khawatir kalau kepindahan mereka malah meluaskan serapah itu ke daerah lain,” ujar kepala desa.
Meskipun sudah terjadi cukup lama, peristiwa itu terkunci dari dunia luar. Pantas saja, informasinya luput dari publik. Warga sepakat untuk tidak menceritakan kepada orang luar, dengan harapan serapah itu akan punah sendiri.
Setiap warga yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, baik karena kenangan, memori, akar pahit, dendam, maupun hal lain semacamnya, akan serta-merta mendapati gelas dalam genggamannya. Berwana, tapi tembus pandang. Modelnya sama. Sedikit berkerut dan bergaris di bagian bawah, mirip belimbing. Warga desa menyebutnya gelas belimbing.
Begitu mendapat gelas, warga sudah paham harus buru-buru ke lapangan. Jika tidak, gelas bisa pecah di rumah dan hal ini dipercaya akan membawa musibah bagi keluarga.
“Belum lama ini, seorang ibu tidak mau ke lapangan. Dia tetap di rumah. Akhirnya, semua anggota keluarganya ikut memegang gelas. Mereka jadi ribut sendiri, saling menyalahkan, dan akhirnya gelas-gelas itu pecah semua di rumah,” kata seorang warga.
“Semuanya meninggal. Kami tidak punya cara lain kecuali membiarkan dulu rumah itu seminggu, sampai mayat-mayat itu kering dan tidak bau. Baru kami kuburkan,” kata warga yang lain.
Gelas-gelas yang baru muncul bisa hijau, kuning, atau langsung merah dan sejam kemudian pecah. Tergantung pada seberapa dalam beban batin yang membekas dan terus dipikirkan oleh yang bersangkutan. Makin dipikirkan, makin memicu perubahan warna gelas dari hijau ke kuning, lalu merah.
Tidak hanya perempuan yang kedapatan memegang gelas. Laki-laki juga ada, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Mengenai usia, belum ada jawaban mengapa anak-anak tidak pernah terkena kasus serupa.
“Kami juga tidak tahu, Bu, kenapa perempuan lebih banyak. Tapi, kenyataannya memang seperti itu,” kata warga lain sembari mengintip apa yang aku torehkan di buku gawaiku.
Tulisanku viral dan mendapatkan cukup banyak respon. Muncul beragam komentar dari segala usia. Wajar. Hampir semua tangan sudah memegang kemewahan teknologi digital di era pascamodern ini. Keingintahuan mudah terjawab.
Aku terkesan. Apresiasi yang timbul umumnya tentang alinea terakhir tulisanku. Selain menghadapi permasalahan gelas, ada sisi positif dari kehidupan masyarakat di kabupaten itu. Warga bisa menjaga mulut mereka, sehingga masalah yang turun-menurun itu terkunci hanya sebatas bagian dalam dinding-dinding kabupaten.
Warga belajar untuk lebih ikhlas dalam menerima peristiwa kehidupan dan untuk memberi dukungan kepada anggota keluarga atau kerabat yang memegang gelas. Semua berharap, kutukan segera berakhir. Jika saja ada sensus beban batin di kabupaten itu, pikirku, mungkin kurva kecenderungan insiden telah melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Kita harus bersumpah untuk tidak menyakiti orang lain, apalagi orang baik, orang suci, orang sakti, atau apalah yang semacamnya," tukas rekan di meja sebelahku, setelah memberikan apresiasi terhadap karyaku. Dia langsung mengucapkan sumpahnya, lalu mengangkat dagunya dan melihat ke sekelilingnya seakan meminta orang lain mengikuti tindakannya.
Aku sendiri lega dengan semua apresiasi yang muncul. Tapi, segera aku terkesima, menangkap kedap-kedip perubahan warna hasil citra satelit pada salah satu layar dari tiga komputerku. Komputer yang satu ini sengaja kukhususkan untuk mencitra wilayah sekitar kantor.
"Itu di sini. Di kantor ini. Kenapa jadi ikut berubah-ubah warnanya?" pikirku.
Kutolehkan kepala ke sekitar. Kujumpai wajah-wajah heran dan ketakutan. Beberapa rekan tiba-tiba memegang gelas. Ada yang hijau, kuning, atau merah. Model gelasnya sama. Gelas belimbing.
Satu jam kemudian, sejumlah rekan terjatuh. Tewas. Perempuan dan laki-laki berimbang jumlahnya. Dari pengurus dapur sampai pemimpin perusahaan.
"Misterius: Ratusan Tewas Gegara Gelas" mengisi halaman suratkabar digital dan langsung viral, menandai insiden di dua kabupaten yang mengapit kantorku: Kabupaten Sombong dan Kabupaten Kuat Puji. ***
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H