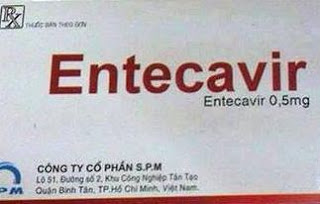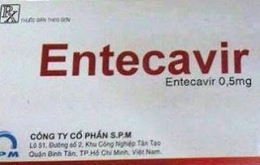Oleh : eN-Te
Seperti tertulis di deskripsi profil, saya lahir dan besar di Lamakera, sebuah kampung pesisir pantai di Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timutr (NTT). Saya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Inpres Watobuku, Lamakera. Setelah menamatkan pendidikan dasar, saya kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di luar Lamakera.
Di Lamakera waktu itu hanya ada satu sekolah jenjang pendidikan menengah yang berbasis agama, yakni MTs Swasta yang dikelola oleh Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Sementara sekolah jenjang menengah umum, setingkat SMP belum ada di Lamakera. SMP hanya terdapat di ibukota kecamatan.
Sekedar gambaran bahwa Pulau Solor terbagi menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Solor Timur dan Kecamatan Solor Barat. Kecamatan Solor Timur beribukota di Menanga, kurang lebih 8-10 km dari Lamakera ke arah barat. Sedangkan Kecamatan Solor Barat beribukota di Ritaebang.
Berdasarkan aspek sosiologis secara umum penduduk Kecamatan Solor Timur mayoritas beragama Islam. Sedangkan sebaliknya Kecamatan Solor Barat mayoritas penduduknya beragama Kristen Katholik.
Lamakera terbagi menjadi dua desa, Moton Wutun (Lamakera I) dan Watobuku (Lamakera II) merupakan kampung pesisir pantai yang 100 persen penduduknya beragama Islam. Meski demikian, warga Lamakera tidak menutup diri untuk menerima ‘warga pendatang’. ‘Warga pendatang’ ini adalah guru-guru nonmuslim yang ditugaskan pemerintah sebagai PNS untuk mengajar dan mengabdi di sekolah-sekolah dasar yang ada di Lamakera (selanjutnya guru-guru nonmuslim ini saya sebut sebagai ‘warga pendatang’ saja).
Di Lamakera terdapat dua SD, yakni SD Inpres Watobuku dan SD Negeri Lamakera. Ada satu lagi sekolah jenjang pendidikan dasar yang berbasis agama, yang juga dikelola oleh Yayasan Tarbiyah Islamiyah, yakni Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Lamakera. Dalam perkembangannya, baik MIS Lamakera dan MTs Lamakera, keduanya sudah di-takeover oleh pemerintah dan berubah status menjadi sekolah negeri, yakni MIN Lamakera dan MTs Negeri Lamakera.
Selama menempuh pendidikan di SD Inpres Watobuku, saya sudah mengenal dan diajar oleh beberapa ‘warga pendatang’. Sejak kelas IV – kelas VI, guru kelas saya adalah ‘warga pendatang’ itu. Selama di bawah bimbingan ‘warga pendatang’ itu, kami (siswa-siswa), tidak merasa ada masalah. Bahkan kami, khususnya saya merasa sangat ‘bahagia’ karena telah diajar oleh ‘warga pendatang itu’.
Ketulusan mereka untuk berbagi ilmu membuat interaksi dan relationship antara siswa dan ‘warga pendatang’ itu berjalan harmonis. Tidak ada perasaan ewuh pakewuh, perasaan risih, apalagi enggan menerima kehadiran ‘warga pendatang’ itu. Semuanya berjalan natural, tanpa ada perasaan berbeda karena alasan sektarian-primordial. Sebuah isu yang pada akhir-akhir ini menjelma menjadi isu panas, sehingga nyaris membuat negeri ini berada di ujung tebing. Di mana tenun kebangsaan ala Anies Baswean, nyaris robek menjadi centang perenang.
Ketulusan ‘warga pendatang’ itu tidak hanya ditunjukkan ketika berada di sekolah dan pada jam belajar resmi. Mereka juga tanpa merasa terbebani menyediakan waktu sore hari untuk memberikan kami pelajaran tambahan pada jadwal les sore. Itupun dilaksanakan di sekolah pula.
Kadang, dan lebih sering menyediakan pula waktu malam hari menerima kehadiran kami, murid-muridnya untuk belajar di bawah bimbingan mereka di mes guru yang menjadi rumah dinas mereka di bawah temaram lampu teplok (atau lampu pelita minyak tanah yang terbuat dari kaleng susu bekas). Sebuah ketulusan dan dedikasi, yang saat ini nyaris punah dan sulit ditemukan pada masyarakat urban di kota-kota besar.
Harus saya jelaskan pula bahwa meski sudah sejak lama isu tentang Kristenisasi ramai, tapi sejak di SD, saya tidak pernah mendengar masalah itu menjadi ‘sekat’ yang membatasi interaksi dan membangun relasi harmonis dengan ‘warga pendatang’ itu. Tidak hanya siswa dan guru-guru di sekolah saja, tapi terlihat pula di dalam kehidupan sosial lebih luas, masyarakat.
Warga Lamakera begitu terbuka dan sangat welcome menerima kehadiran ‘warga pendatang’. Warga lamakera tidak ragu apalagi menunjukkan sikap resistensi terhadap ‘warga pendatang’ itu.
Bagi warga Lamakera, tidak penting identitas sektarian dan sekat primordial. Dalam kesederhanaan, warga Lamakera berpikir bahwa tidak mungkin ‘warga pendatang’ itu hadir dengan membawa misi tertentu, misalnya program kristenisasi, selain untuk mengabdi sebagai guru. Dan warga lamakera sangat percaya bahwa anak-anak mereka tidak akan ‘tercemar’ oleh misi itu.
Dan anggapan itu tidak salah. Karena sampai hari ini, tidak ada satu pun ‘warga pendatang’ yang bertugas dan ditugaskan sebagai guru di Lamakera pernah dan berani menjalankan misi itu.
Bagi kami, warga Lamakera, isu dan sekat primordial sangat terlalu ‘mewah’ untuk diperdebatkan. Apalagi harus ‘mempersonifikasikan’ menjadi seolah-olah hantu yang menakutkan. Bagi kami, faktor-faktor sektarian-primordial bukan alasan harus menolak kehadiran dan eksistensi kelompok atau golongan lain yang berbeda dengan identitas mayoritas. Apalagi kehadiran mereka dalam rangka mencerdaskan anak-anak Lewotanah (dalam bahasa Indonesia berarti tanah air (bangsa)).
Inilah bibit-bibit awal sikap inklusif yang tumbuh mekar dan berkembang dalam diri dan pandangan saya sampai hari ini. Karena itu, bagi saya, merupakan sebuah kekonyolan yang kekanak-kanakkan, bila hari ini di mana klaim lebih beradab, tapi masih memperdebatkan dan lebih mengedepankan sikap-sikap intoleransi atas nama sektarian-primordial dalam membangun asa bersama.
Sikap inklusif semakin bertumbuh kembang ketika saya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Seperti sudah saya singgung di awal tulisan ini, bahwa setelah menamatkan pendidikan SD di Lamakera, saya melanjutkan pendidikan ke SMP di luar Lamakera. Yakni, pada sebuah sekolah negeri di Pulau Adonara (sebuah pulau yang juga merupakan gugusan pulau kecil, selain pulau Solor di dan masuk wilayah Kabupaten Flores Timur). Tepatnya di SMP Negeri Lamahala, yang juga merupakan sebuah kampung pesisir pantai di Kecamatan Adonara Timur.
SMP Negeri Lamahala merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Adonara Timur. Karena merupakan satu-satunya sekolah negeri di daerah pesisir pantai, maka SMP Negeri Lamahala juga menjadi sasaran dan tujuan orangtua ingin memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Tidak hanya berasal dari etnis dan agama tertentu, tetapi berasal dari semua etnis dan agama.
Ada Islam, Kristen Katholik, Protestan, etnis Flores (Lamaholot), Jawa, Padang, dan juga China (Tionghoa). Heterogenitas yang mencerminkan kebhinekaan sungguh terlihat di sana. Dan saya yang beretnis Lamaholot dan seorang muslim, termasuk dan tercatat sebagai salah satu siswa di SMP Negeri Lamahala pada tahun 1983-1986.
Heterogenitas etnis dan agama juga kembali saya temukan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA tahun 1986-1989. Malah semakin beragam.
Setelah tamat di SMP Negeri Lamahala, saya kemudian melanjutkan ke SMA Swasta Suryamandala. Sebuah sekolah swasta yang dikelola oleh sebuah Yayasan Kristen di Kota Waiwerang.
Kota Waiwerang merupakan ibukota Adonara Timur. Selain sebagai ibukota kecamatan, Waiwerang juga dikenal sebagai kota niaga, karena berfungsi sebagai daerah transit yang menghubungkan beberapa kota dan daerah pesisir di Flores Timur dan NTT.
Sebagai daerah transit, maka Waiwerang dikenal sebagai pusat niaga. Tentu saja sebagai pusat niaga maka penduduk Waiwerang juga sangat beragam (plural), baik dari segi etnis maupun agama. Itu juga terlihat di sekolah, SMA Suryamandala. Tidak ada perlakuan khusus dan berbeda, meski kenyataan sosial menunjukkan ada ‘etnis pendatang’ yang merupakan etnis non-pribumi, memiliki status sosial yang lebih baik karena faktor eknomi.
‘Etnis pendatang’ ini menguasai aspek ekonomi lebih dari 75%. Kondisi demikian tidak menjadi faktor pemicu lahir kecemburuan sosial. Malah sebaliknya, warga pribumi merasa ‘terbantu’ dengan kehadiran dan keberadaan ‘etnis pendatang’ ini. Tidak ada ketegangan atas nama etnis dan agama, dan juga ekonomi yang harus merusak tenun kebersamaan dalam kebhinekaan itu. Sebuah panorama yang indah, di mana sikap terbuka begitu tercermin dari interaksi sosial yang harmonis dalam masyarakat.
Semua nilai itu, secara alamiah tumbuh mekar dan berkembang, hingga menjadi bagian yang inheren dalam diri saya. Semua itu dimungkinkan, karena saya berada dan berkesempatan berinteraksi dengan beragam atnis dan agama. Sungguh harmonis dan indah. Apalagi ketika di SMA, nyaris mayoritas teman, baik sesama siswa maupun guru, adalah nonmuslim. Dan saya bergaul dan berinteraksi dengan mereka dengan begitu harmonis tanpa terbebani oleh sekat-sekat primordial.
Maka ketika belakangan, orang-orang meributkan identitas seseorang, sehingga menghalanginya untuk dipilih menjadi pemimpin, membuat nurani saya berontak. Benarkah, karena faktor primordial, sehingga seseorang meski memilki kualifikasi mumpuni untuk memimpin harus ditolak?
Nurani saya semakin tersentak ketika ada sekelompok orang atas nama keyakinan, seenak udelnya, menghakimi pihak lain sebagai ‘kafir’ (meski masih seagama dan sekayakinan), karena berbeda afiliasi politik. Menggolongkan pihak yang berbeda pilihan, sebagai orang yang tidak beriman (kafir) karena memilih calon pemimpin nonmuslim. Lebih jauh malah menolak untuk mensholatkan, jika jenazah yang meninggal itu diidentifikasi sebagai pendukung calon pemimpin nonmuslim.
Sungguh miris, ketika Indonesia sudah memasuki usia 72 tahun, peradaban dan cara berpikir masayarakatnya semakin primitif. Konservatisme dalam beragama telah menutup mata bathin untuk melihat betapa indahnya keberagaman yang dihadirkan Sang pencipta.
Saya menjadi sangat masgul hingga harus bertanya dalam gumam, mungkinkah saya (menjadi) kafir, karena membiarkan diri saya, sejak SD hingga SMA bahkan Perguruan Tinggi diajar oleh guru-guru dan dosen yang nonmuslim? Begitu pula dengan muslim lain, yang dalam hidupnya pernah berinteraksi dan mendapat bimbingan (berarti juga pernah dipimpin) dari dan oleh orang yang berbeda keyakinan. Mungkinkah juga (menjadi) kafir?
Karena itu, saya harus tegaskan bahwa sampai hari ini saya adalah genuine muslim. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kemusliman saya. Saya juga tidak peduli terhadap sebuah penilaian, sehingga harus mempertanyakan kemusliman saya. Bagi saya, kemusliman saya hanya Tuhan (Allah SWT) dan saya saja yang tahu. Tidak ada orang atau pihak manapun yang berhak ‘menghakimi’ keyakinan saya atas nama sebuah pandangan.
Wallahu a’alam bish shawab
Makassar, 25/4/2017
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI