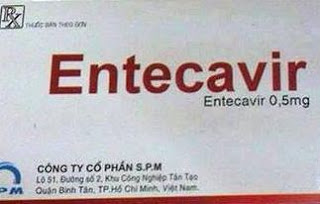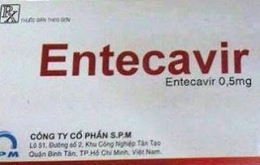Harus saya jelaskan pula bahwa meski sudah sejak lama isu tentang Kristenisasi ramai, tapi sejak di SD, saya tidak pernah mendengar masalah itu menjadi ‘sekat’ yang membatasi interaksi dan membangun relasi harmonis dengan ‘warga pendatang’ itu. Tidak hanya siswa dan guru-guru di sekolah saja, tapi terlihat pula di dalam kehidupan sosial lebih luas, masyarakat.
Warga Lamakera begitu terbuka dan sangat welcome menerima kehadiran ‘warga pendatang’. Warga lamakera tidak ragu apalagi menunjukkan sikap resistensi terhadap ‘warga pendatang’ itu.
Bagi warga Lamakera, tidak penting identitas sektarian dan sekat primordial. Dalam kesederhanaan, warga Lamakera berpikir bahwa tidak mungkin ‘warga pendatang’ itu hadir dengan membawa misi tertentu, misalnya program kristenisasi, selain untuk mengabdi sebagai guru. Dan warga lamakera sangat percaya bahwa anak-anak mereka tidak akan ‘tercemar’ oleh misi itu.
Dan anggapan itu tidak salah. Karena sampai hari ini, tidak ada satu pun ‘warga pendatang’ yang bertugas dan ditugaskan sebagai guru di Lamakera pernah dan berani menjalankan misi itu.
Bagi kami, warga Lamakera, isu dan sekat primordial sangat terlalu ‘mewah’ untuk diperdebatkan. Apalagi harus ‘mempersonifikasikan’ menjadi seolah-olah hantu yang menakutkan. Bagi kami, faktor-faktor sektarian-primordial bukan alasan harus menolak kehadiran dan eksistensi kelompok atau golongan lain yang berbeda dengan identitas mayoritas. Apalagi kehadiran mereka dalam rangka mencerdaskan anak-anak Lewotanah (dalam bahasa Indonesia berarti tanah air (bangsa)).
Inilah bibit-bibit awal sikap inklusif yang tumbuh mekar dan berkembang dalam diri dan pandangan saya sampai hari ini. Karena itu, bagi saya, merupakan sebuah kekonyolan yang kekanak-kanakkan, bila hari ini di mana klaim lebih beradab, tapi masih memperdebatkan dan lebih mengedepankan sikap-sikap intoleransi atas nama sektarian-primordial dalam membangun asa bersama.
Sikap inklusif semakin bertumbuh kembang ketika saya melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA. Seperti sudah saya singgung di awal tulisan ini, bahwa setelah menamatkan pendidikan SD di Lamakera, saya melanjutkan pendidikan ke SMP di luar Lamakera. Yakni, pada sebuah sekolah negeri di Pulau Adonara (sebuah pulau yang juga merupakan gugusan pulau kecil, selain pulau Solor di dan masuk wilayah Kabupaten Flores Timur). Tepatnya di SMP Negeri Lamahala, yang juga merupakan sebuah kampung pesisir pantai di Kecamatan Adonara Timur.
SMP Negeri Lamahala merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Adonara Timur. Karena merupakan satu-satunya sekolah negeri di daerah pesisir pantai, maka SMP Negeri Lamahala juga menjadi sasaran dan tujuan orangtua ingin memasukkan anaknya ke sekolah tersebut. Tidak hanya berasal dari etnis dan agama tertentu, tetapi berasal dari semua etnis dan agama.
Ada Islam, Kristen Katholik, Protestan, etnis Flores (Lamaholot), Jawa, Padang, dan juga China (Tionghoa). Heterogenitas yang mencerminkan kebhinekaan sungguh terlihat di sana. Dan saya yang beretnis Lamaholot dan seorang muslim, termasuk dan tercatat sebagai salah satu siswa di SMP Negeri Lamahala pada tahun 1983-1986.
Heterogenitas etnis dan agama juga kembali saya temukan ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA tahun 1986-1989. Malah semakin beragam.
Setelah tamat di SMP Negeri Lamahala, saya kemudian melanjutkan ke SMA Swasta Suryamandala. Sebuah sekolah swasta yang dikelola oleh sebuah Yayasan Kristen di Kota Waiwerang.