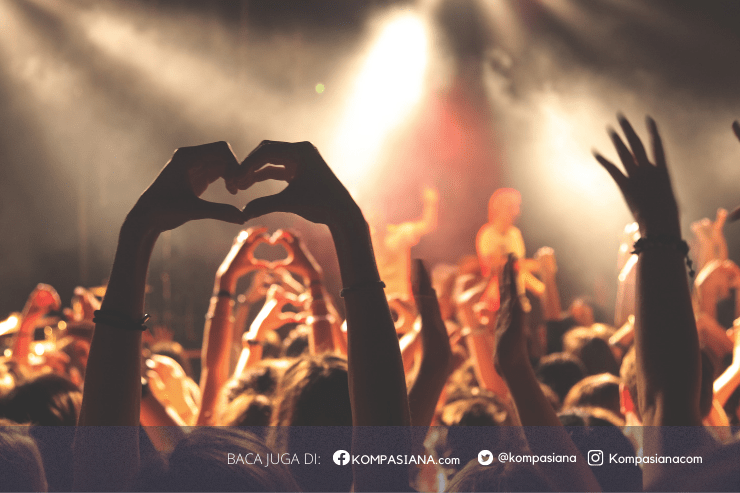Satu tahun lalu, pada tanggal yang sama 18 Desember. Kim Jonghyun meninggal. Penyebab kematian aroma beracun briket batu bara. Karbon monoksida memenuhi kamar apartemen. Jonghyun menghirupnya.
Saya bukan penggemar Jonghyun. Saya tidak mendengar lagu SHINee. Hanya setelah kematian itu diumumkan, saya sempat mendengar beberapa lagunya meski sepintas. Saya bukan juga bagian dari penggemar besar SHINee.
Akan tetapi, saya harus mengakui satu hal. Saya adalah Kim Jonghyun. Kok bisa, seorang warga Indonesia bertampang pas-pasan, tapi masih sedikit tampanlah, menyamakan dirinya kepada seorang megabintang Korea? Aneh beranak ajaib. Tetapi terimalah kenyataan ini. Saya adalah Kim Jonghyung. Saya masih hidup. I'm alive! Suka atau tidak, kebenaran itu pahit.
Seminggu setelah kematian itu, Natal tiba. Natal tahun lalu adalah pengulangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Suka cita untuk umat Nasrani. Yesus telah lahir ke dunia. Saya merayakannya, pergi ke gereja, mengirim pesan ucapan selamat Natal kepada orangtua, saudara, teman-teman, dan semua penghuni bumi yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.
Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai di bumi. Itu kira-kira pesan yang saya kirim dan saya terima saat Natal tahun lalu.
Di televisi, semua iklan juga ingin menyampaikan pesan bahwa Natal adalah suka cita. Namun, saya sekarang ini tidak mengingat satu patah kata pun homili Pastor yang memimpin misa Natal saat itu.
Karena itu, Natal tahun lalu boleh dikatakan tidak mengubah hidup saya, kecuali karena ada libur yang diberikan kantor khusus untuk saya.
Tulisan ini telah bercerita tidak karuan dan melebar kemana-mana. Baiklah, saya kembali mengingatkan Anda, para pembaca: Saya adalah Kim Jonghyun SHINee. Percaya atau tidak, silakan.
Kim Jonghyun sebagaimana diberitakan banyak media nasional dan internasional, memilih mengakhiri hidupnya karena depresi. Dugaan ini hanya pandangan terbatas yang bisa diungkapkan dan dimengerti manusia. Depresi? Tidak. Saya hanya mengenal kata sederhana: kesendirian, kesepian.
Tahun lalu, 2017, Natal itu adalah kesendirian. Uang pas-pasan. Saya pergi bermain ke kediaman teman. Lantas ia bertanya, mengapa saya tidak mudik untuk merayakan Natal bersama keluarga? Pertanyaan sederhana dan biasa bagi saya.
Ada dua alasan, duit pas-pasan dan waktu libur sangat singkat untuk bisa berkumpul bersama keluarga yang jarak rumah mereka sangat panjang dari kediaman saya saat itu. Saya tidak mungkin mudik Natal dalam kondisi keduanya. Itu mimpi buruk.
Akhirnya, saya menghabiskan Natal saat itu bersama teman saya. Ngopi dan bercengkerama. Hal biasa yang saya lakukan seperti pada hari-hari biasa.
Akan tetapi saya berpikir, saya tidak mungkin merayakan Natal dengan cara seperti ini. Oh, semua sudah terjadi. Setelah beberapa waktu bertandang ke kediaman teman, saya memutuskan untuk segera kembali ke Solo, kota yang menjadi domisili saya.
Dari sana, saya telah membuat keputusan yang akhirnya menjerat saya dalam kesendirian. Saya telah menghabiskan momen Natal seorang diri sampai pergantian Tahun 2018. Saya melampiaskan kesendirian ini melalui Twitter. Saya membuka Twitter. Oh, ternyata banyak warganet menghiasi lini masa Twitter dengan pesan suka cita.
Mereka bahagia, namun saya tidak demikian. Suka cita justru telah mendorong saya untuk selalu mengumpat. Entahlah, kepada siapapun, saya bersumpah serapah, mengutuk dunia, termasuk mengutuk diri sendiri.
Saya depresi, oh bukan, saya kesepian. Saat itu, saya juga mengetahui, ada cukup banyak orang yang merasakan hal seperti yang saya rasakan.
Jika dipikir lebih sempit, solusinya sederhana saja, jika saya memang kesepian, mengapa saya tidak berkumpul bersama mereka? Berbagi pengalaman? Hmm, saya pikir, pernyataan demikian sangat picik.
Dalam kondisi tidak menentu itu, logika menjadi sebuah racun yang merusak syaraf otak. Saya saat itu hanya berdoa dan berharap, Santa Claus datang menemui saya. Oh manisnya... Namun, Santa Claus tidak pernah datang.
Apakah pernah terlintas untuk melakukan hal berdosa itu, mengakhiri hidup? Saya harus berkata jujur, ya, hanya sepintas, ini sebenarnya lebih sangat menakutkan.
Orang-orang menghubungi saya, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Mereka melanjutkannya dengan bertanya apa saya baik-baik saja? Saya jawab, ya. Lagi-lagi, sebuah pertanyaan dan pernyataan biasa. Saya menipu diri sendiri. Alhasil, saya menambahkan dosa dalam suasana Natal.
Waktu terus berjalan hingga pesta kembang api Tahun Baru 2018 terlewati. Suka cita itu ternyata datang setelah Natal. Akan tetapi, saya mulai menghitung-hitung, pesta kembang api itu kira-kira bisa memberikan berapa banyak kado kepada mereka yang membutuhkan? Hahaha... Saya juga terlalu licik untuk berharap ini menjadi kenyataan.
Badai pasti berlalu, sehabis gelap, terbitlah terang. Saya dapat merasakan bahwa saya pernah menjadi bagian dari Kim Jonghyun. Seperti diberitakan dw.com yang mengutip Instastory Nain9, Jonghyun pernah menuliskan pesan, "Saya merasa sangat kesepian."
Saya bersyukur telah memiliki pengalaman ini. Rasanya pahit tapi ada manis-manisnya, sedikit. Jika tulisan ini dianggap menyesatkan, palsu, dan muluk-muluk, saya mengakui dan menerima semua kutukan yang dialamatkan kepada saya. Pengalaman itu membangkitkan saya.
Saya senang karena setelah ini, saya dapat mengatakan, kemiskinan, kesendirian, dan kematian bukanlah hal biasa yang wajar dilewati setiap orang. Iman dan pengalaman telah mendorong saya untuk memberontak. Kehidupan memiliki nilai, tidak ada sesuatu yang biasa meskipun semua ternyata absurd.
Semua ucapan selamat Natal dan Tahun Baru menjadi tidak bernilai. Ucapan itu amat mudah ditebak, hanya berbeda dalam beberapa kata. Karena itu, makna Natal dan Tahun Baru telah kehilangan makna.
Ungkapan duka cita terhadap kematian Jonghyun juga menjadi tidak bermakna, sebab pesan utama dari kejadian ini semua adalah kehidupan. Karbon monoksida bukanlah penyebab utama atas kematiannya. Kerangka berpikir semacam ini adalah sebuah logika kematian.
Jonghyun telah hidup kembali untuk mengajak manusia memberi nilai pada kehidupan. Manusia perlu keberanian untuk melawan kebencian sekaligus melawan kecintaan fanatik jika itu tidak memberi makna pada hidup manusia.
Manusia memberontak kepada diri sendiri untuk tidak mau tunduk pada hasrat kebencian, meski kebencian adalah hal terbaik yang manusia miliki saat ini. Manusia membutuhkan waktu dan kesabaran tinggi untuk memahami semua tregedi di dunia ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI