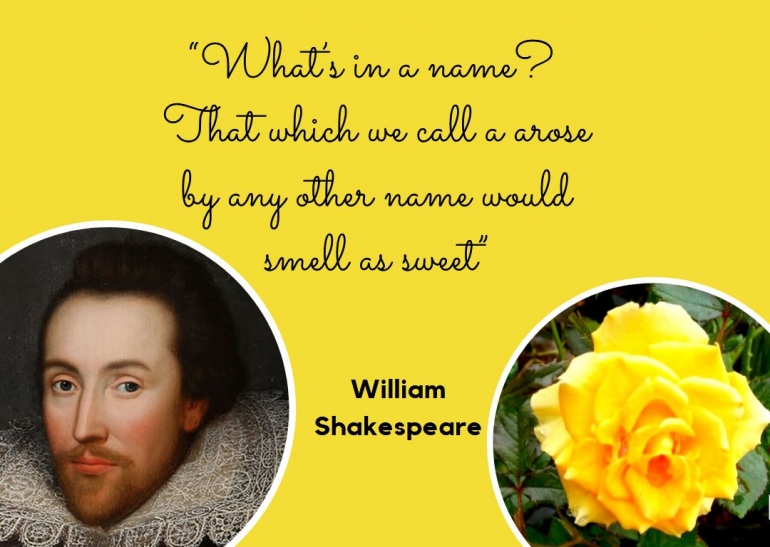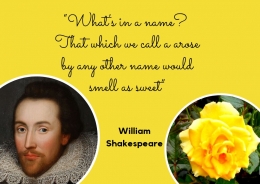Artikel ini sebenarnya penulisan ulang dari catatan kecil yang pernah saya buat di media sosial facebook dengan perbaikan di sana sini dan tambahan sejumlah referensi. Tetiba saya ingin membagikannya karena hari-hari belakangan ini saya mendapat pertanyaan terkait nama panggilan. Di lain sisi, saya juga mendapati diri saya ragu dalam memberikan sapaan yang tepat kepada orang-orang yang baru saya kenal. Ada rasa khawatir bila yang bersangkutan kurang berkenan. Sementara sebagian orang mempersilakan saya memilih sendiri nama-nama panggilan untuk mereka.
Semoga tulisan receh ini dapat memberikan inspirasi. Setidaknya menambah perbendaharaan cerita bahwa lahirnya nama panggilan seseorang bukan saja atas keinginannya tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial-budaya. Belum lagi kalau dia seorang penulis atau seniman yang acap kali memiliki nama alias, nama panggung, atau nama pena.
Baiklah, izinkan saya mengawali kisah dari percakapan virtual pada suatu pagi cerah.
Lewat pesan singkat, pagi itu saya pamer kepada seorang kawan 'Aku sarapan roti bakar nih, maklum bule!' Alih-alih setuju, si kawan malah menjawab 'Bule kok namanya Dwi'. Sontak saya tertawa menanggapi kebenaran komentar si kawan. Eit, jangan sedih dulu! Saya juga punya nama bule kok, yaitu "Claire". Keren, kan?
Sebenarnya saya memiliki banyak nickname 'nama panggilan kesayangan'. Mulai dari yang keren macam Claire sampai yang enggak banget, seperti Bejo, Limbuk, dan sebagainya. Akhirnya, sambil menikmati roti bakar dan menyeruput kopi, saya pun menuliskan tentang seluk-beluk nama panggilan tersebut.
Nama lengkap saya xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, terdiri dari 37 huruf, 5 kata dan 16 suku kata. Menurut orang-orang nama tersebut panjang seperti rangkaian kereta. Wah cocok sekali! Kebetulan sejak kecil saya paling suka naik kereta api.
"Ning" adalah potongan nama tengah saya yang menjadi panggilan sayang dalam keluarga. Oya, nama itu juga menjadi panggilan sayang dari teman-teman sepermainan di Gang Beruang-tempat tinggal masa kecil saya di Kota Lumpia. Nama itu juga diteriakkan oleh teman-teman di lingkungan gereja.
Dahulu, bila anak-anak Gang Beruang bertengkar, terbentuklah geng-geng kecil. Setiap geng akan menciptakan dan/atau menyanyikan lagu ejekan untuk anggota geng "lawan".
Ning nong ning gung pak bayan, sega jagung ora doyan. Iwak pitik duh enake, kepruk dingklik aduh Mak'e!
Lagu berbahasa Jawa itu menjadi lagu spesial untuk "mengejek" saya. Beruntung ketika itu saya masih belum kenal istilah baper.
Jumpa Lahiri dalam novel The Namesake (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Makna Sebuah Nama) mengisahkan betapa tokoh utama bernama Gogol merasa sangat terguncang dan sulit menerima ketika namanya dijadikan bahan ejekan oleh kawan-kawannya. Bahkan saat beranjak dewasa si Gogol mengganti namanya. Belakangan ia baru mengetahui bahwa ada kisah epik di balik pemberian nama tersebut. Dalam suatu kecelakaan hebat, Ashoke, ayahnya ditemukan oleh regu penolong di antara mayat-mayat berelimpangan karena ia melambai-lambaikan sobekan kertas novel karya penulis Rusia Nikolai Gogol.
Lho, kok jadi cerita tentang si Gogol. Kalau teman-teman tertarik dengan novel besutan penulis berkebangsaan India tersebut, silakan bisa ditelusuri ulasannya di sini. Sekarang kita kembali dahulu ke si Nining tadi ya?
Begitulah, kala itu pertengkaran bagi anak-anak hanyalah bumbu dalam pertemanan. Jadi, tidak terjadi keributan di antara orang tua ataupun saling melapor ke polisi, KPA, atau yang lain. Tidak lama sesudah bertengkar, pasti akan terdengar teriakan 'Ning... Nining!' dari teman-teman satu geng maupun geng lawan. Kemudian kami pun akan kembali berlarian bersama, berkejaran di pematang sawah, dan berlomba-lomba memburu keong serta belut.
Di sekolah saya dipanggil dengan nama depan yang lebih formal, yaitu Dwi. Saat duduk di bangku SD siapa pun yang berteriak memanggil Dwi, mereka itu pastilah teman-teman sekolah. Cukup efektif untuk membedakan dengan panggilan teman-teman di lingkungan rumah dan gereja. Boleh dibilang, teman-teman di sekolah jarang saling bertengkar sehingga tidak tercipta lagu ejekan. Alhasil, sampai lulus SD nama resmi saya hanyalah Dwi.
Meskipun begitu, pernah suatu kali guru di kelas 6 dengan bercanda memanggil nama belakang saya sebagai "Klaras". Kemudian beliau melanjutkan dengan sebuah nasihat begini: 'Kamu jangan mau dipanggil Klaras yo Wuk, itu sebutan lain untuk daun pisang kering'. Hahaha..., ibu guru saya itu cantik dan lucu!
Singkat cerita, jadilah saya anak SMP. Masa SMP adalah masa puber, pertemanan di antara anak-anak SMP lebih heboh dan sedikit urakan, bahkan nyaris kurang ajar. Bagaimana tidak? Pada zaman itu satu sama lain di antara kami dengan ceria dan tanpa rasa bersalah saling memanggil dengan nama orang tua (a.k.a. bapak) masing-masing.
Tahukah kamu, siapa nama panggilan kesayangan untukku? Bejo! Ya, itu sinonim untuk "Untung" yang adalah nama ayah saya.
Hanya kepala sekolah dan para guru serta teman-teman yang lembut serta imut saja yang ketika itu masih memanggil saya dengan nama Dwi. Sementara yang lain-di dalam maupun luar kelas-lebih suka memanggil saya dengan nama Bejo. Bahkan sampai hari ini, jika ada orang yang berteriak 'Jo atau Bejo' (bukan Bu Tejo, ya), dia pastilah teman satu SMP.
Saat SMA, Dwi kembali menjadi nama panggilan kesayangan untuk saya, meskipun ada beberapa teman SMP yang belum move on alias masih sayang untuk melupakan nama "Bejo".
Selama masa SMA saya sangat getol berkoresponden, hobi yang saya tekuni sejak SD. Kala itu saya memiliki banyak sahabat pena. Surat dari sahabat pena lebih banyak dilayangkan via alamat sekolah, meskipun harus rela melalui sensor kepsek (kepala sekolah).
Suatu hari saya dipanggil ke ruang kepsek gara-gara dalam suratnya sahabat pena saya ngrasani 'membicarakan' guru-gurunya. Suster Kepala yang menyensor surat tersebut, menegur dan mengatakan bahwa tindakan tersebut kurang baik. Suster meminta saya menyampaikan pada kawan saya untuk tidak mengulanginya.
Namun, sebelum melayangkan teguran, Suster Kepala sempat bingung melihat saya yang datang menghadap karena surat itu ditujukan untuk "Uwix". Saya pun menjelaskan kepada beliau bahwa nama saya di dunia sahabat pena Indonesia adalah Uwix, kependekan dari Dhuwix (a.k.a. Dwi). Suster hanya geleng-geleng kepala, tetapi raut wajahnya menyiratkan pemakluman mendalam. Nama Uwix kelak menjelma Uwie, Uwik, Wik, dll. tergantung siapa yang menyapa.
Jangan salah! Walaupun memiliki nama sekeren Uwix, kala itu ada seorang guru yang suka banget memangil saya dengan nama "Limbuk".
Sebagai informasi, Limbuk adalah salah satu tokoh dalam pewayangan, yaitu seorang abdi perempuan yang konyol. Kemungkinan ide bapak guru tersebut memanngil saya dengan nama Limbuk karena keberhasilan saya menjuarai Lomba Cerita Bohong (sekarang semacam Stand Up Comedy)

Saya tidak pernah protes, meskipun saya tidak gendut seperti si Limbuk dalam pewayangan. Ya, saya anggap panggilan tersebut sebagai tanda sayang dan penghargaan dari beliau. Nama Limbuk pun terkubur setelah saya meninggalkan bangku SMA dan jadi anak kuliahan.
Ketahuilah, Dwi adalah satu di antara nama terpopuler yang ada di Indonesia. Konon, menurut Riset Coca Cola tahun 2015, nama Dwi ada di antara 70 nama terpopuler. Dwi dalam bahasa Indonesia berarti dua, dan biasanya yang bernama Dwi adalah anak kedua. Seandainya dibentuk Komunitas Dwi boleh jadi dapat menjaring banyak anggota.
Jadi, tidak mengherankan jika di jurusan tempat saya kuliah, dalam satu kelas sedikitnya ada lima orang (laki-laki maupun perempuan) yang memiliki nama Dwi. Tiga di antaranya termasuk saya, biasa disapa 'Dwi'.
Nah, untuk mengantisipasi kesalahpahaman, teman-teman sekelas menandai setiap sosok "Dwi". Kebetulan saya mendapat panggilan 'Dwi wedok', artinya Dwi perempuan. Sebagian teman sesekali menambahkan nama baptis saya di belakang nama Dwi.
Begitu pun, pada waktu itu nama Dwi bukan satu-satunya panggilan kesayangan. Balita keponakan salah satu sahabat yang dengan riang menyambut kedatangan saya dengan menyanyi "No Duik No Cinta" (pelesetan sebuah lagu dangdut, duik dalam bahasa Jawa juga berarti duit/uang). Saya pun tidak keberatan ketika nyanyian "No Duik No Cinta" bergema setiap saya datang berkunjung.

Bekerja lalu mendapat jabatan, gaji, dan insentif itu biasa, tetapi mendapat nama baru itu cukup unik juga rasanya.
Begitulah dunia kerja ternyata juga memberi saya nama baru. Setelah sempat merantau ke luar pulau, mendaratlah saya di Jakarta. Di kantor di mana saya diterima bekerja, pimpinan bertanya, 'Siapa nama panggilanmu?' dan saya jawab 'Dwi, Pak!'
Seingat saya almarhum bos saya dulu geleng-geleng kepala pertanda kurang berkenan. Lho, kenapa tidak berkenan?
'Kemarin ada karyawan baru juga bernama Dwi. Kamu pakai nama lain saja' begitu kata bos. Kemudian bos menanyakan nama baptis saya. Ketika saya sebutkan, beliau masih juga geleng-geleng sembari melihat kembali CV saya. 'Di bawah sudah ada bagian administrasi bernama seperti itu! Sudah, kamu saya panggil Klara saja!' Sekejap saya pun terpana!
Gapapa juga sih, itu memang bagian dari nama belakang saya. Kebetulan rumah sakit tempat saya lahir juga bernama St. Klara. Begitu pun saya tetap merasa canggung. Mendapat nama panggilan baru di usia lebih dari seperempat abad sama sekali berbeda dengan mendapat hadiah baju baru. Walaupun dalam hati ingin protes, tetapi sebagai karyawan baru saya akhirnya menurut. Saya anggap itu sebagai perintah pertama bos.
Jadilah teman-teman sekantor memanggil saya Klara. Satu hal yang tidak pernah saya bayangkan adalah dampak jejaring pertemanan dan pekerjaan. Di wilayah Jabodetabek saya pun dikenal (hanya yang kenal saya, tentu saja!) dengan nama baru tersebut. Klara atau Kla.
Seperti sudah saya duga, banyak teman lama melayangkan protes. 'Alamak, banyak kali gaya kau, pindah ke Jakarta lalu kauganti nama jadi Klara. Bah, macam artis saja kutengok!' Demikian salah satu komplain dari seorang sahabat!
Karena menceritakan latar belakang munculnya nama tersebut akan menghabiskan banyak waktu (dan pulsa) maka saya pun hanya berujar santai, 'Maaf, sengaja ganti nama, aku sedang dikejar-kejar debt collector!' Si kawan pun terbahak-bahak di ujung telepon.
Protes dari sahabat karib yang lain bahkan lebih sadis. Saat reunian seorang teman berkata, 'Maaf ya, kalau mendengar nama Klara yang terbayang itu gadis cantik lemah gemulai. Nah, kenapa yang keluar tomboi macam begini ya?' Kami pun tertawa sampai perut terasa sakit.
Belum tahu si kawani ini! Sahabat pena saya yang orang bule bahkan lebih suka memanggil saya Claire. Konon lebih mudah dilafalkan karena seperti nama orang-orang di kampung mereka! Keren, euy!
Selanjutnya karena bertemu banyak anak kecil yang cadel, nama Klara pun memiliki banyak padanan, ada yang panggil Ante Awa, Tante Kelaya, dan lain-lain. Ah, pucing pala belbi!
Mungkin teman-teman akan menyebut saya orang aneh karena entah mengapa saya menyukai semua nama panggilan tersebut. Tentu saja karena saya berpikir bahwa nama-nama tersebut diberikan dengan rasa sayang tanpa didasari niat buruk.
Dalam permenungan saya menemukan bahwa ternyata setiap nama panggilan memiliki sejarah dan makna yang sangat personal. Setiap nama menandakan kehadiran saya di antara keluarga, lingkungan masyarakat,dan beragam komunitas sosial.
Banyak alasan bahwa nama adalah sebuah kekuatan dan identitas. Memang untuk urusan administrasi kependudukan, perbankan, dan sebagainya nama sesuai KTP menjadi hal mutlak. Saya sendiri pasti akan melayangkan protes jika salah dalam penulisannya.
Sementara untuk nama panggilan-sepanjang tidak bertujuan menghina-tak ada salahnya diterima dengan ikhlas. Saya pernah merasa keheranan mengetahui seseorang marah besar hanya karena pelayan Starbucks keliru menuliskan namanya pada gelas kopi pesanannya.
Dalam kehidupan bermasyarakat lintas budaya, menurut saya pengucapan kata-termasuk sebuah nama-sangat dipengaruhi oleh banyak aspek. Di antaranya adalah perbedaan bahasa, logat bicara, dan struktur bibir para pelafalnya. Jadi, alih-alih marah atau tersinggung, lebih baik diambil sisi positifnya. Boleh jadi nama panggilan tersebut memiliki makna, mungkin rasa sayang atau persahabatan.
Pernyataan William Shakespeare "What's in a name?" dalam drama Romeo and Juliet sering disalahartikan. Sebagian menerjemahkannnya 'apalah arti sebuah nama' atau 'nama itu tidak penting, tidak memiliki arti'. Ya, tentu maksudnya tidak sesederhana itu juga.
Tak ada salahnya kita melihat dari sudut pandang berbeda dalam kalimat Shakespeare yang lebih lengkap: What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Apa arti sebuah nama? Andaikata kita berikan nama lain untuk bunga mawar, ia tetap akan beraroma wangi atau memiliki wangi yang sama.
Jadi, dengan nama apa pun saya disapa, hal terpenting yang perlu saya usahakan adalah memiliki kepribadian yang baik sekaligus berkualitas. Bagaimanapun arti penting seseorang pertama-tama dilihat dari kualitas diri serta karyanya yang baik bukan hanya dari nama panggilannya.
Lebih dari kualitas baik saya juga dituntut untuk mampu menghadirkan kasih di mana pun saya berada. Meskipun hal ini sungguh tidak mudah.
Bagaimana dengan teman-teman? Adakah memiliki pengalaman serupa? Apa nama panggilan diri yang paling teman-teman sukai?
Depok, 17 Oktober 2020
Salam, Dwi Klarasari
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI