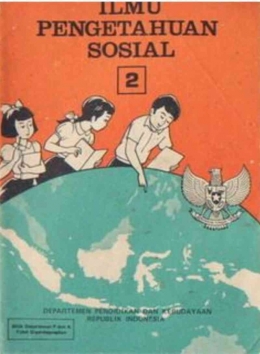Mengingat-Kembali
Mengingat-kembali bagaimana pada tahuan 1984 sampai dengan 1987 warga di desa saya berjubel menonton TVRI di setiap malam minggu merupakan cara sederhana untuk membaca-ulang bagaimana masyarakat desa belajar menyaksikan dan memaknai kehidupan modern.
Saya sendiri, pada masa itu, meskipun sudah duduk di bangku sekolah dasar, masih belum paham arti kata modern. Yang saya tahu waktu itu dari TVRI adalah bahwa di kota orang-orang mengendarai sepeda motor dan mobil, banyak gedung bertingkat, jalannya beraspal, dan para pemain film dan penyanyi memakai pakaian yang bagus.
Selain itu, anak-anak sekolah mengenakan seragam dan sepatu bagus, dan makanan di atas meja terlihat sangat enak. Indahnya kehidupan kota tentu sangat berbeda dengan keterbatasan hidup yang saya dan kawan-kawan sebaya di desa.
Masing-masing orang memang memiliki pengalaman terkait bagaimana memaknai, memimpikan, dan merasakan kehidupan modern di ruang desa pada era 80-an.
Menjadi modern dalam makna paling sederhana adalah ketika pada masa kecil ibu membelikan saya baju baru di pasar "pahing" kecamatan menjelang lebaran dan dalam banyak kesempatab berkata,"Kamu harus sekolah biar jadi anak pintar."
Belajar menjadi modern adalah ketika saya duduk di bangku SD dan para guru mengajarkan baca, tulis, serta berhitung sembari memberikan wejangan tentang pentingnya pendidikan.
Berusaha menjadi modern adalah ketika saya dan kawan- kawan menonton cantik dan tampannya para pemain film di televisi; ketika saya berkhayal suatu saat bisa berkunjung ke kota; ketika kami mengerumuni mainan yang dibawa cucu seorang tetangga dari kota; dan ketika kami mulai mengenal istilah pacar dan pacaran dari Film Cerita Akhir Pekan di TVRI.

Tulisan ini merupakan usaha untuk membaca-kembali peristiwa-peristiwa yang saya alami di masa kecil terkait pengalaman pribadi dan kolektif masyarakat dalam memaknai dan menikmati modernitas yang berlangsung di ruang desa, tepatnya di Dusun Sambiroto, Desa Karangsambigalih, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Setting 80-an saya pilih karena pada masa itulah, masyarakat desa, di satu sisi, mulai masuk ke dalam pertanian kapitalis sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan, dan, di sisi lain, mulai merasakan sebagian aspek modernitas.
Peristiwa-peristiwa masa kecil tersebut akan saya baca dengan perspektif kajian budaya dan kajian pascakolonial untuk melihat secara kritis genealogi pergeseran dan perubahan sosio-kultural yang berlangsung dalam ruang desa sebagai akibat masuknya modernitas serta pengaruhnya terhadap lokalitas dan subjektivitas masyarakat desa.
Dengan kedua perspektif tersebut, saya juga akan menganalisis berlangsungnya relasi kuasa-hegemonik modernitas serta siasat yang dijalani masyarakat desa di tengah-tengah keberantaraan kultural mereka.
Menjadi Modern dalam Bimbingan Rezim
Dalam pandangan Venn (2006:55- 57; 2000:17-19) modernitas merupakan kondisi kehidupan yang mengidealisasi hilangnya kekangan dogma tradisional yang membatasi kebebasan berpikir dan bertindak individu.
Modernitas yang berasal dari Eropa Barat menekankan pentingnya kebebasan dan kedaulatan individual, sehingga akan melahirkan usaha-usaha untuk membebaskan diri dari doktrin agama dan keyakinan, tradisi, dan kekuasaan yang dianggap membelenggu dan menghambat kemajuan.
Meskipun kehadiran modernitas tidak terlepas dari praktik kolonialisme dan kapitalisme, pesona kemajuan bagi semua manusia membuat masyarakat di seluruh belahan dunia menjadikannya orientasi untuk merasakan kemajuan dan kesejahteraan.
Pengetahuan tentang modernitas dikonstruksi dan direproduksi terus-menerus dalam praktik pemerintahan, pendidikan, ekonomi-politik, media, dan budaya. Inilah yang menjadikan modernitas sebagai pengetahuan yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia di belahan bumi manapun.
Modernitas merupakan sebuah konsep, kondisi, dan gerakan yang mampu menampung beragam tanda, cita-cita, impian, harapan, permasalahan, pergeseran, perubahan, kekecewaan, penaklukan, dan hal-hal lain yang terkesan sederhana, tetapi sebenarnya rumit dalam konteks desa.
Menjadi sederhana karena semua orang bisa merasakan diri menjadi modern, baik dalam konteks individual maupun komunal; dari usaha untuk mengenyam pendidikan sampai hasrat berbelanja produk-produk industri budaya.
Menjadi rumit ketika modernitas memunculkan pergeseran dan perubahan dalam sistem,struktur, dan praktik tradisional masyarakat karena masuknya sistem pengetahuan, kapitalisme, pendidikan, politik, sosial, dan budaya yang berasal dari kota yang berorientasi Barat ke dalam jagat- hidup sehari-hari.
Istilah Barat bukan semata merujuk pada kategori geografis, tetapi lebih merujuk pada wacana dan praktik sosio-kultural yang berasal dari negara-negara Eropa Barat dan berkembang pesat di Amerika Serikat, seperti modernitas, kapitalisme, dan liberalisme. Barat menjadi pengetahuan dan peradaban yang menggerakkan perkembangan sejarah umat manusia.

Wacana Barat masih kuat dalam pikiran masyarakat pascakolonial sebagai figur imajiner yang terus diidealisasikan, baik dalam kehidupan sehari-hari, praktik bernegara, media, maupun dalam ranah pengetahuan (Venn, 2000; Chakrabarty, 2000).
Akibat kuatnya, pengaruh Barat, sebagian nilai dan praktik tradisional yang dianggap menyesatkan, perlahan-lahan akan terpinggirkan oleh nalar modern yang membebaskan individu untuk berjuang mencapai kemajuan hidup. Maka, lokalitas masyarakat desa menjadi semakin kompleks dan tidak bisa lagi dibaca secara esensialis.
Terlepas dari kontradiksi antara kesederhanaan dan keruwetan yang ada, menjadi modern bagi masyarakat Indonesia bukanlah proses yang tiba-tiba. Modernitas yang masuk ke negeri ini melibatkan sejarah panjang sebuah kontradiksi; misi pemeradaban dan penjajahan.
Manusia-manusia Eropa yang mengaku sangat rasional, berpendidikan, berbudaya, dan beradab berusaha menguji kebenaran universal dari konsep filosofis, “aku berpikir maka aku ada” sebagai basis proyek modernitas menuju belahan-belahan bumi lain, termasuk Nusantara.
Setidaknya, terdapat sepuluh elemen Pencerahan berbasis "aku berpikir maka aku ada" yang melahirkan modernitas, yakni: nalar dan rasionalitas, empirisme, pengetahuan, universalisme, kemajuan, individualisme, toleransi, kebebasan, kesamaan umat manusia, dan sekulerisme.
Tujuan dari semua konsep tersebut adalah individualisme yang mengedepankan kebebasan individu yang terbebas dari otoritas kuasa tradisional dan agama, sehingga ia bisa mengembangkan diri berbasis pengetahuan untuk memperoleh kemajuan. Kemajuan individu menjadikan toleransi bisa berkembang, sehingga memunculkan kesamaan antarmanusia meskipun sulit terwujud (McGuigan, 1999:40-41; Venn, 2006:55-56).
Manusia Eropa Barat mewacanakan diri sebagai makhluk superior sementara manusia pribumi distereotipisasi sebagai liyan yang tidak beradab, kanibal, tidak berpendidikan, tidak beragama, tidak berbudaya, tidak berbahasa, barbar, eksotis, penuh takhayul, dan lain-lain (Said, 1978, 1994; Slemon, 1995; Bishop, 1995; Kachru, 1995; C lestin, 1996; Lidchi, 1997; Loomba, 2000:57-58; Weaver-Hightower, 2007; Mrazek, 2006:147; Brantlinger, 2009; Pennycook, 1998).
Realitasnya, misi pemeradaban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menaklukkan dan menguasai sumber daya alam wilayah taklukkan ketika revolusi industri membutuhkan ketersediaan bahan mentah. Penaklukkan dan penguasaan inilah yang melahirkan kolonialisme.
Kolonialisme merupakan kombinasi sistem dan praktik politik, militer, ekonomi, dan kultural (pendidikan/pengetahuan, agama, dan budaya) untuk menaklukkan dan mengeksploitasi sebuah wilayah beserta potensi sumberdaya alam dan masyarakatnya. Penjajah mengembangkan matrik kuasa kolonial sebagai mekanisme untuk memperkuat posisi mereka beserta modernitas dan kapitalisme (Gillen & Ghosh, 2007: 14; Tlostanova, 2008: 110-111).
Pertama, pada level ekonomi, penguasaan tanah dan eksploitasi buruh/petani yang diorientasikan untuk memproduksi komoditas sesuai permintaan pasar global. Kedua, institusi negara penjajah dan agama (Kristen) yang didirikan untuk mengontrol kekuasaan, sehingga kuasa politik dan agama tradisional dipinggirkan.
Ketiga, kontrol terhadap gender dan seksualitas untuk memperkuat kontrol ekonomi dan kekuasaan. Keempat, kontrol terhadap pengetahuan dengan prinsip- prinsip rasionalitas Barat membentuk subjektivitas baru bagi masyarakat terjajah.
Kehadiran pemerintah kolonial di wilayah jajahan tidak hanya mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat terjajah, tetapi juga menyebabkan endapan- endapan ideologis untuk mengangan dan meniru modernitas yang dipraktikkan penjajah.
Keinginan untuk meniru tersebut berasal kebiasaan diskursif penjajah yang memosisikan masyarakat terjajah sebagai anak kecil atau tabula rasa yang harus dituntun dan diajari untuk menjadi modern dengan peradaban Barat (Aschroft, 2001: 36- 52).
Kebiasaan penjajah yang memandang masyarakat terjajah secara stereotip sebagai pemalas dan pencuri, memunculkan kekerasan ideologis dan rasis yang seringkali memunculkan inferioritas psikis dan kultural (Memmi, 1975: 79- 89).
Inferioritas itulah yang menjadikan kelompok elit pribumi berhasrat untuk mendapatkan pengetahuan modern dan mengangannya sebagai ideal. Hal yang sama juga berlangsung di kelompok kelas bawah yang bermimpi menjadi modern melalui perjumpan-perjumpaan dengan para tuan kolonial (Fanon, 2008: 74).
Para elit pribumi di Hindia-Belanda sudah biasa meniru kemajuan-kemajuan Barat-kolonial melalui institusi pendidikan, militer, dan kebudayaan. Mereka ingin merasakan kemajuan atau menempati posisi sejajar dengan penjajah dan negara-negara maju lainnya (Lombard, 2000; Alisjahbana, 1998).
Sementara, mereka juga tidak bisa meninggalkan sepenuhnya nilai dan praktik tradisional yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, subjek terjajah hidup di dalam kegandaan kultural yang secara ajeg menempatkan modernitas sebagai endapan-endapan ideologis yang terus berlanjut di masa pascakolonial (Faruk, 2007: 9; Mbembe, 2001: 12; Quayson, 2000: 16-17).
Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut diperkuat oleh penerapan sistem kenegaraan hukum, ekonomi- politik, maupun pendidikan yang meniru sistem negara penjajah atau negara-negara maju lainnya karena elit-elit politik negeri ini di awal kemerdekaan adalah didikan Belanda dan sudah terbiasa dengan pemikiran Eropa dan Amerika.
Meskipun demikian, sistem negara modern yang menjamin kebebasan warga negara sebagai syarat mutlak subjektivitas modern tidak dijalankan secara menyeluruh oleh elit Republik karena adanya ketakutan hilangnya model kuasa tradisional yang sudah lama berlangsung dalam sistem feodal kerajaan.
Sebagai penerima pendidikan Eropa, para mahasiswa yang setelah Hindia-Belanda merdeka menjadi elit politik negeri ini mengagumi pemikiran Eropa. Mereka menjadi subjek di dalam ide-ide Eropa dengan bermacam posisi ideologis yang bisa merusak hirarki antara penjajah dan terjajah.
Akibatnya, banyak elit menolak ide-ide Eropa tentang subjektivitas yang tidak sesuai dengan ambisi politik mereka. Kelompok- kelompok intelektual Hindia-Belanda meresponnya dengan beragam cara, utamanya terkait implikasi ide otonomi-diri.
Apakah subjektivitas otonomi selaras dengan ide-ide Jawa tentang penguasa dan kawula yang sudah menyebar selama berabad-abad melalui tradisi lisan dan dibentuk kembali dalam terbitan-terbitan filologis teks Jawa kuno?
Soetatmo Soeriokoesoemo, salah satu pendukung nasionalisme Jawa, pada 1920 memaparkan bahwa konsep Eropa tentang kesamaan tidak selaras dengan pandangan dunia Jawa. Dia bisa menerima ide persaudaraan dalam nasionalisme, namun kesamaan menurutnya berbahaya bagi masa depan kelas priyayi Jawa. Menurutnya warisan masa lampau sangat sesuai untuk membangun masa depan negara Jawa (Sears, 2005: 335-336).
Modernitas yang tidak bisa dilepaskan dari praktik kolonialisme, nyatanya, tidak pernah dihadirkan dalam buku-buku PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa). PSPB hanya menjadi narasi dari perjuangan pahlawan-pahlawan lokal untuk melawan kekejaman penjajah dan perjuangan elit-elit politik didikan Belanda dalam memerdekakan Hindia-Belanda.
Semangat nasionalisme anti-penjajah yang digelorakan oleh para pemimpin politik negeri ini di bawah rezim Soekarno dan dilanjutkan oleh rezim Orde Baru Soeharto selalu menuduh penjajah sebagai penyebab berbagai permasalahan hidup yang dialami oleh masyarakat Indonesia.
Gandhi (1998:104-105), mengelaborasi beberapa sumber, menjelaskan bahwa nasionalisme yang demikian memang berbeda dengan nasionalisme yang tumbuh di negara industri Eropa. Nasionalisme modern lahir karena kompleksitas masyarakat industrial Eropa Barat yang membutuhkan tenaga kerja dan pemerintahan yang lebih homogen dan kooperatif.
Masyarakat industrial melahirkan kondisi-kondisi ekonomi bagi terciptanya kesadaran nasional yang dikonsolidasikan secara politis melalui negara-bangsa. Lahirinya nasionalisme sejalan dengan melemahnya sistem keyakinan lama dalam bentuk kerajaan, komunitas religius, bahasa suci/tinggi, dan kesadaran kosmologis.
Bangsa dan nasionalisme merupakan produk dari imajinasi modern melalui novel maupun surat kabar; komunitas yang terbayangkan. Jadi, bangsa dan nasionalisme merupakan proses yang terus menjadi.
Dalam konteks masyarakat Hindia-Belanda, masyarakat-terjajah di Jawa, misalnya, tidak akan bisa membayangkan kehidupan masyarakat-terjajah di Sumatera dan Borneo tanpa membaca berita di koran-koran berbahasa Melayu-rendah.
Bayangan itulah yang membentuk solidaritas dan perasaan senasib sebagai masyarakat-terjajah, sehingga melahirkan sentimen kebangsaan sebagai akar nasionalisme anti-penjajah.
Padahal, tanpa kehadiran kolonialisme, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara belum tentu ada (Budiawan, 2010). Nasionalisme anti- penjajah pada masa Soekarno ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita kolektif untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat karena elit-elit sipil dan militer sibuk bertikai.
Yang saya tangkap ketika duduk di bangku SD adalah bahwa kemajuan hidup yang dirasakan masyarakat kota dan desa merupakan prestasi kebijakan pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto yang menggantikan Soekarno setelah tragedi berdarah 1965.
Oleh para guru, Pak Harto selalu diwacanakan sebagai pahlawan karena berhasil menggagalkan kudeta politik yang katanya dilakukan PKI untuk selanjutnya memimpin negara ini dengan “senyum manis” dan proyek-proyek pembangunan, seperti intensifikasi dan diversifikasi pertanian, pendidikan, program KB, pengaspalan jalan, pembangunan waduk, pembangunan gedung-gedung bertingkat di kota, dan lain-lain.
Program-program tersebut berhasil membimbing dan mengarahkan masyarakat desa untuk mulai memasuki cara hidup dan cara pikir modern dalam kehidupan sehari-hari. TVRI sebagai televisi rezim juga secara ajeg merepresentasikan peran sentral Pak Harto dalam pembangunan dan kemajuan bangsa ini.
Bagi masyarakat desa pada era 80- an, televisi dengan TVRI sebagai stasiun tunggal sangat membantu untuk melihat dan memaknai aspek-aspek modernitas yang dijanjikan pembangunan.
Bagaimana tidak, dari kotak hitam-putih yang hanya dimiliki oleh beberapa warga-kepala desa/dusun atau orang-orang kaya- masyarakat bisa menonton kemajuan kota yang menjadi penanda utama modernitas Indonesia.
Selain itu, melalui acara berita regional, berita nasional, penyuluhan desa/pertanian, maupun laporan khusus, warga menerima pesan-pesan keberhasilan pembangunan Orba pimpinan Pak Harto.
Waktu itu, saya dan kawan-kawan sebaya serta masyarakat kebanyakan tidak pernah tahu kalau mobilisasi makna-makna terkait menjadi modern dalam arahan Orba merupakan anggitan (construction) untuk mendukung dan memperkuat kuasa rezim.
Melalui tayangan TVRI, rezim berusaha mengarahkan, mengendalikan, dan membatasi pesan pembangunan menuju modernitas sebagai kebutuhan kolektif menuju kemajuan bernegara dan berbangsa. Sebagian besar masyarakat desa tidak merisaukan ideologi kapitalisme yang diadopsi dalam pembangunanisme oleh para ekonom dan teknokrat serta pengaruh- pengaruh buruknya.
Masyarakat diberi informasi-informasi tentang pembangunan di bawah kepemimpinan Soeharto yang akan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak berani mempertanyakan perilaku militeristik rezim yang dibungkus dengan dalil-dalil demokrasi semu.

Apalagi, Soeharto dalam film-film bergenre militer, seperti Janur Kuning, tampil sebagai figur yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik ini (Irawanto, 1999). Selain itu, dalam film Pengkhianatan G 30 S PKI yang pemutaran rutinnya di TVRI berakhir setelah gerakan Reformasi 1998, ia tampil sebagai sosok yang menyelamatkan negara dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara tetap sakti.
Mengikuti pemikiran Foucauldian tentang formasi wacana (Foucault, 2002: 52-58; Hall, 1997a: 44), pembentukan dan penyebarluasan wacana tentang sosok Soeharto dan keberhasilan pembangunan Orba merupakan usaha untuk memperoleh penerimaan dan persetujuan dari masyarakat terhadap kuasa rezim.
Sistem dan praktik kuasa yang dibangun dengan memobilisasi penerimaan masyarakat dari bermacam kelas melalui pewacanaan dalam bermacam aparatus (agama/moral, pendidikan, media, dan budaya) serta implementasi kebutuhan kolektif mereka inilah yang disebut hegemoni (Gramsci, 1981; Laclau Mouffee, 1981; Boggs; 1984; Bennet, 1986; Williams, 2006; Hall, 1997b; Howson , 2008; Boothman, 2008; Fontana, 2008).
Rezim berusaha menjadi kelas pemimpin dengan cara membentuk blok historis yang terdiri dari bermacam kelas dalam masyarakat serta mengartikulasikan kepentingan mereka sehingga negosiasi kuasa tidak lagi dianggap sebagai paksaan, tetapi kebutuhan untuk maju bersama- sama (Hall, 1982; Slack, 1997).
Soeharto dan rezimnya dengan cerdas dan cerdik mampu menangkap dan mengartikulasikan kegelisahan masyarakat untuk merasakan kemajuan hidup dengan program-program pembangunan yang nyata.
Ketika Masyarakat Desa Bergerak Menuju Modernitas
Harapan untuk bisa maju, sejahtera, dan makmur, seperti yang mereka saksikan di layar TVRI, mendorong masyarakat desa mau menerima Revolusi Hijau melalui program intensifikasi dan diversifikasi pertanian seperti penggunaan bibit unggul, pemakaian pupuk kimia, percepatan proses produksi-pascaproduksi, dan distribusi hasil-hasil pertanian secara cepat.

Beroperasinya Waduk Gondang Lor di sebelah selatan desa saya pada tahun 1987 setelah diresmikan Presiden Suharto dan perbaikan sistem irigasi, penggantian alat-alat pertanian lokal seperti luku, lesung, dan lumpang dengan alat-alat pertanian modern seperti traktor, mesin perontok padi, dan huller, penggunaan bibit unggul dan pestisida, serta pemberian bantuan pertanian memang terbukti memberikan penghasilan lebih bagi para petani desa. Panen padi tidak hanya satu kali dalam setahun, tetapi bisa dua sampai tiga kali.
Dengan sisa uang hasil panen padi, para petani mulai berbelanja benda-benda modern. Masyarakat desa mulai membeli pakaian pabrikan di pasar kecamatan, meskipun dengan harga dan kualitas yang lebih rendah. Saya dan kawan-kawan dibelikan pakaian baru, meskipun hanya menjelang Idul Fitri.
Ke sekolah kami tidak lagi nyeker (tanpa mengenakan sepatu) karena sepatu berbahan karet dijual dengan harga yang terjangkau. Bagi keluarga berada membeli sepeda motor keluaran terbaru, radio, tape player maupun televisi di kota kabupaten selepas panen padi menjadi tradisi baru.
Di dusun saya, pada awal 80- an, warga yang memiliki sepeda motor dan televisi bisa dihitung dengan jari. Ketika pertanian kapitalis mulai berkembang, jumlah sepeda motor semakin bertambah. Masuknya listrik pada tahun 1987 semakin mendorong warga berada untuk membeli televisi dan tape player.
Kehadiran televisi di desa menjadi situs yang mampu mengantarkan impian dan harapan untuk menjadi modern bagi warga. Bagi masyarakat, modernitas akan membawa aspek-aspek kemajuan hidup, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang selama ini distereotipisasi sangat terbelakang, tidak bependidikan, dan tidak maju.
Memiliki benda-benda produk industri kota seperti yang banyak ditampilkan di TVRI merupakan salah satu cara mereka untuk merasakan diri menjadi modern sekaligus meningkatkan prestige di tengah-tengah masyarakat. Saya masih ingat ketika salah satu teman sebaya dari keluarga berada dibelikan sepeda BMX begitu bangga ketika saya dan kawan- kawan mengerumuninya di sekolah.
Keberhasilan Revolusi Hijau ternyata menyebabkan hilangnya beberapa tradisi dalam sistem pertanian desa. Penggunaan bibit hibrida hasil rekayasa genetik para pakar pertanian menghilangkan bibit lokal seperti Rojolele, Pandanwangi, dan Kruwing yang tahan hama sangat cocok untuk sawah tadah hujan.
Beroperasinya waduk mengubah pola tanam 1 + 2 (padi 1 kali-palawija 2 kali) menjadi 2 + 1 (padi 2 kali-palawija 1 kali) atau 3 + 0 (padi 3 kali nir palawija). Ritual-ritual pertanian seperti selamatan menjelang tandur musim tanam atau selamatan miwiti musim panen ketika hendak panen mulai hilang.
Pemberian sesajen menjelang panen ke sawah sebagai bentuk rasa syukur warga desa kepada Tuhan melalui Dewi Sri juga mulai lenyap dari tradisi pertanian. Dalam konteks ritual, tampak ada titik temu antara ajaran agama dan pembangunan. Para guru ngaji selalu mengatakan kalau membuat sesajen itu bagian dari musyrik.
Sementara, percepatan pembangunan pertanian tidak membutuhkan semua ritual itu karena yang dibutuhkan hanyalah pupuk, irigasi, dan pestisida.
Kehadiran mesin perontok padi dan huller juga ikut mengubah sistem panen dan pengolahan hasil panen di desa kami beserta tradisi yang menyertai.
Sebelum ada mesin itu, panen dilakukan dengan sistem bawon. Para buruh tani perempuan memotong padi dengan ani-ani (pemotong padi tradisional dengan sebilah pisau kecil yang dipasang di rangka kayu) dan setelah selesai akan mendapatkan imbalan beberapa ikat padi. Selama masa panen, para buruh perempuan bisa mengumpulkan padi untuk menyambung kehidupan mereka sekaligus sebagai sarana ketahanan ekonomi mereka.
Sebelum ada huller, ibu-ibu menumbuk padi di lesung dan lumpang untuk bisa mendapatkan beras dari bulir-bulir padi yang sudah kering. Waktu menumbuk padi menjadi arena kultural bertemunya ibu-ibu sambil membicarakan permasalahan hidup sehari-hari, termasuk ngrasani (bergosip) warga yang ketahuan selingkuh.
Masyarakat desa mulai menyekolahkan anak-anak mereka, paling tidak, sampai tingkat SD bagi keluarga miskin, tingkat SMP/SMA bagi keluarga menengah, dan perguruan tinggi bagi keluarga berada.
Sampai awal 90-an di dusun saya terhitung hanya ada 5 orang yang menempuh kuliah, 4 orang di perguruan tinggi swasta dan 1 orang di perguruan tinggi negeri, yakni anak Kepala Dusun (Senden). Karena merasa bangga dengan prestasi putranya yang diterima di Universitas Jember, Pak Senden membuat tasyakuran
Sebagian besar anak- anak di dusun saya hanya bersekolah sampai tingkat SMP/SMA pada akhir 80-an sampai dengan awal 90-an. Menyekolahkan anak adalah sebuah harapan dan doa agar kelak generasi penerus keluarga bisa baca- tulis dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, agar nasibnya tidak sama dengan orang tua yang hanya berprofesi sebagai petani.
Paling tidak, dengan ijazah SMP dan SMA mereka bisa menjadi pekerja pabrik atau pelayan toko di kota, seperti Surabaya. Sementara, bagi yang berijazah sarjana atau diploma, diharapkan bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil, sebuah profesi yang sangat diidamkan oleh masyarakat pada waktu itu dan berlanjut hingga saat ini. Para guru dengan telaten mengajari baca, tulis, dan hitung.

"Ini Budi, Ini Adik Budi, Ini Bapak Budi, dan Ini Ibu Budi," menjadi kalimat sehari-hari yang harus kami pelajari sewaktu duduk di kelas 1, selain "1 + 1 = 2," tentunya.
Di sela-sela pelajaran, para guru selalu mengatakan bahwa sekolah itu penting agar bisa jadi pintar, masa depan kami lebih baik, bisa maju, dan lebih makmur. Maka, bagi masyarakat desa, pendidikan merupakan rezim kebenaran yang secara ajeg mengarahkan pikiran orang tua dan anak-anak untuk menemukan kemajuan di era pembangunan.
Bagi saya dan kawan-kawan sepermainan, hal yang paling terasa dari Revolusi Hijau adalah bergantinya bahan pangan. Ketika masih menggunakan sistem pertanian tadah hujan, kami tidak sepanjang tahun bisa menikmati nasi putih karena padi hanya panen sekali dalam setahun.
Nasi jagung dan nasi gebingan (berasal dari singkong kering yang ditumbuk setengah halus dan dimasak) adalah makanan pokok ketika beras sudah habis. Setelah sistem pertanian modern berkembang, sepanjang tahun kami makan nasi putih. Nasi putih menjadi penanda lain dari kemajuan masyarakat desa.
Selain itu, makanan ringan buatan pabrik mulai biasa kami konsumsi dan perlahan-lahan menggeser selera kami terhadap thiwul (penganan dari gebingan dicampur gula merah) dan puli (penganan dari sisa nasi putih yang dihaluskan dan diberi garam bleng).
Kebiasaan memakan nasi putih belakangan menjadikan ketahanan pangan masyarakat desa sangat rentan ketika panen gagal, karena mereka sudah tidak biasa lagi mengonsumsi makanan dari bahan lain.
Masuknya listrik dalam kehidupan desa juga membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosio-kultural anak- anak. Saya dan kawan-kawan tidak perlu lagi memaksa mata untuk membaca dalam keremangan cahaya ublik (lampu berbahan minyak tanah yang dibuat dari botol).
Keterpesonaan kami terhadap bulan purnama dan cerita tentang bidadari yang tengah memangku anaknya mulai lenyap karena kami tidak lagi hidup dalam kegelapan dusun. Permainan tradisional seperti sengedan-sengedanan atau jumpritan tidak lagi kami mainkan ketika purnama karena menonton TVRI ternyata lebih mengasyikkan.
Jumpritan adalah permainan yang dilakukan anak-anak lelaki. Kami membagi diri ke dalam dua kelompok. Besar kecilnya anggota kelompok tergantung jumlah anak-anak yang hadir.
Dua orang yang menjadi pemimpin akan sut ‘suit’ (undian dengan adu jari,) yang menang akan memimpin kelompoknya untuk bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap sulit untuk ditemukan. Sementara, kelompok yang kalah akan mencari sampai ketemu.
Meskipun demikian, kami masih sering berkumpul di pelataran dengan alas tikar pandan sembari membicarakan hal-hal yang berkenan dengan kehidupan anak-anak. Yang sering kami bicarakan adalah tokoh-tokoh kartun yang waktu itu sedang nge-trend di TVRI, seperti He-Man, Micky Mouse & Donald Duck, Flash Gordon, maupun Phantom.
Film boneka Si Unyil memang kami gemari, tetapi kami jarang membincangkannya karena tidak semenarik film-film kartun buatan Amerika. Kami tidak pernah berpikir bahwa film boneka ini adalah bagian dari cara rezim untuk mengajari anak-anak hidup dalam keharmonisan keluarga, masyarakat, dan negara.
Ternyata, meskipun hidup di dusun, impian kami cenderung menembus batas-batas dusun/desa/kabupaten/provinsi/ negara, karena Barat nyatanya sudah bercokol dalam obrolan dan impian masa kecil kami.
Situs-situs Hiburan yang Memukau
Selain menjadi situs untuk merepresentasikan kepentingan rezim, TVRI juga menjadi situs yang mem- pertemukan masyarakat desa dengan budaya pop, seperti musik dan film. Secara bergantian pada setiap malam minggu, TVRI menayangkan Selekta Pop, Aneka Ria Safari, dan Kamera Ria.
Sementara, pada Minggu siang, TVRI menayangkan Album Minggu Kita. Dari keempat acara musik itulah, saya, kawan-kawan, dan masyarakat mulai menggemari lagu-lagu yang dibawakan Billbroad seperti “Anak Singkong” dan “Madu dan Racun,” Tommy J. Pisa seperti “Di Batas Kota Ini,” “Suratan,” dan “Pengantin Remaja,” Jayanti Mandasari seperti “Di Puncak Bukit Hijau,” maupun Ria Resti Fauzi seperti “Cinta Sedalam Lautan Atlantik” dan “Sepatu dari Kulit Rusa.”
Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat desa lebih menggemari lagu- lagu dangdut yang dinyanyikan Rhoma Irama, Elvi Sukaesih, Hamdan ATT, dan Meggy Z.
Bagi warga yang mempunyai tape player, mereka akan membeli kaset dari penyanyi-penyanyi yang sedang hits di TVRI. Mereka lebih suka membeli kaset bajakan yang biasanya berisi kompilasi lagu yang sedang populer karena harganya lebih murah.
Radio menjadi situs hiburan yang juga sangat populer di masa kecil saya. Program favorit yang sering saya dengarkan bersama kawan-kawan adalah sandiwara radio seperti Saur Sepuh, Tutur Tinular, Kaca Benggala, dan Misteri Gunung Merapi. Biasanya, kami berkumpul di rumah pada setiap Minggu pagi untuk mendengarkan sandiwara yang ditayangkan tujuh seri berturut-turut.
Dari sandiwara-sandiwara itulah, kami belajar tentang masa lalu fiksional yang mengajarkan tentang kebaikan yang selalu menang melawan kejahatan.
Selain itu, kami juga menggemari program Sanggar Cerita Anak-anak yang banyak memperdengarkan dongeng- dongeng lokal seperti Si Kancil, Timun Mas, dan Jaka Tarub maupun dongeng-dongeng Eropa seperti Cinderella dan Putri Tidur yang inti ceritanya juga tentang hitam- putih kehidupan.
Selain, televisi, radio, dan tape player, situs hiburan lain yang sangat terkenal waktu saya masih kelas 2 SD adalah video player yang hanya dimiliki oleh putra Pak Senden (Kepala Dusun). Dia membelinya di Lamongan. Mesin pemutar kaset video bermerk Betamax ini tentu saja mahal dan tidak ada warga lain yang memilikinya.
Tidak setiap malam minggu saya dan kawan-kawan bisa menonton video karena dia terkadang pulang dua minggu atau satu bulan sekali. Film-film Amerika (waktu itu saya belum kenal istilah Hollywood) yang paling sering diputar adalah Rambo, Commando, dan Rocky.
Adapun film buatan dalam negeri yang sering diputar adalah film horor, seperti Dendam Jum’at Kliwon dan film kaum muda seperti Macan Kampus.
Khusus untuk film Rambo, saya dan kawan-kawan benar- benar menggemarinya. Bahkan, kami sering memeragakannya ketika bermain di sawah selepas sekolah. Kami membuat bedil-bedilan (senapan mainan) dari pelepah pisang untuk beradegan seperti Rambo di rimba Vietnam.
Kami tidak pernah tahu kalau Rambo adalah film propaganda Amerika Serikat karena kalah perang di Vietnam serta medium untuk mencitrakan superioritasnya. Yang kami tahu, Rambo adalah tokoh pemberantas kebatilan.
Khusus film horor, saya dan kawan-kawan biasanya masih merasakan takut ketika pulang karena harus melewati pohon soka besar di tengah desa. Kami sering berlomba lari ketika melewati pohon tersebut karena oleh masyarakat dianggap keramat.
Meskipun saya, kawan-kawan, orang tua, dan masyarakat secara umum mulai merasakan kehidupan desa yang tengah bergerak menuju modernitas, kecintaan terhadap kesenian tradisional tetaplah tinggi. Pada era 80-an, kesenian tradisional wayang kulit, tayub, dan ludruk masih menjadi situs hiburan yang sangat digemari.
Setiap ada pertunjukan tayub, misalnya, saya dan kawan-kawan sebaya menonton bersama-sama, layaknya sebuah gank anak-anak kecil. Kami menyaksikan para tandak (penari) menari bersama tamu undangan laki-laki. Kami biasanya mengambil tempat duduk di depan. Sementara, ibu-ibu dan anak-anak perempuan duduk atau berdiri di belakang.
Keberadaan kesenian tradisional masih menjadi tanda pembeda kehidupan desa dan kota. Di desa saya, tayub merupakan kesenian favorit. Orang tua dan guru ngaji tidak pernah memarahi kami, meskipun para tandak hanya mengenakan pakaian tradisional jarik (kain panjang) dengan kain penutup dada.
Sembari melihat tayub kami sekaligus belajar gerak tari yang diperagakan tamu undangan. Pagelaran kesenian tradisional seperti tayub, wayang, dan ludruk juga menjadi berkah tersendiri bagi saya, karena ibu selalu memberikan uang untuk njajan (membeli makanan dan buah-buahan).
Meskipun menggemari kesenian tradisional, saya tidak pernah mengerti pitutur dan keadiluhungan yang direpresentasikan dalam setiap pertunjukan. Tayub hanya berupa ge- rakan-gerakan tari yang disertai dengan tradisi minum tuwak ataupun bir.
Waktu itu, saya dan kawan-kawan tidak pernah mengerti kalau tayub, seperti dijelaskan Suharto (1999), ternyata berasal dari ritus kesuburan untuk menghormati Dewi Sri.
Sementara, bahasa dan narasi wayang yang sulit, membuat saya hanya bisa mengingat nama-nama Pandawa dan beberapa Kurawa beserta stereotipisasi yang dilekatkan; Pandawa baik dan pejuang kebenaran, Kurawa jahat dan tidak beradab.
Selebihnya, saya menikmati wayang hanya sekedar sebagai situs hiburan, sekaligus sebagai kesempatan untuk memanjakan hasrat njajan, membeli makanan dan minuman.
Sama halnya, ketika kami tidak pernah mengerti makna religi dari selametan dan kondangan. Kecuali tahlilan yang kata imam di sebuah masjid untuk mengirim doa kepada orang yang meninggal.
Hal berbeda diberikan ludruk ke dalam pikiran saya. Sebagai drama rakyat yang menggunakan bahasa Jawa dialek arek (Suroboyoan), saya bisa mengikuti dan memahami cerita-ceritanya, baik yang berbasis dongeng perjuangan lokal seperti Sogol Pendekar Sumur Gemuling, Sarip Tambakoso, Joko Kendil, Joko Dolok, dan Sawunggaling maupun cerita rekaan tentang percintaan.
Selain ceritanya, saya juga sangat menggemari dagelan (lawak) sebelum lakon dimainkan. Waktu itu ada dua jenis pertunjukan ludruk, yakni pagelaran di acara hajatan (tanggapan) dan pagelaran tobong. Pagelaran tobong biasanya digelar oleh sebuah kelompok ludruk dari Mojokerto, Jombang, dan Surabaya selama satu bulan ketika musim panen tembakau.
Musim tembakau memang identik dengan uang yang banyak bagi masyarakat desa. Meskipun demikian, saya hanya diizinkan menonton oleh ibu ketika malam Minggu, karena hari-hari biasa harus belajar. Selain itu, penghematan uang adalah alasan kenapa ibu hanya memberikan izin menonton ludruk tobong pada malam minggu.
Nyatanya, bagi saya dan kawan- kawan, menikmati narasi dan bentuk seni modern ternyata lebih menyenangkan dibandingkan dengan seni tradisional. Lagu pop, film, kartun, maupun sandiwara radio lebih memesona dan bisa melambungkan angan-angan kami. Seni modern memberikan kesempatan untuk melihat dan menikmati sebuah jagat kultural di luar jagat kami sehari-hari.
Kami mulai mengenal istilah cinta dan pacaran dari lagu-lagu pop dan film cerita akhir pekan. Kami mengenal indahnya kehidupan modern kota dari tayangan berita dan film. Sementara, dari kesenian dan ritual tradisional, kami tidak mendapatkan sesuatu yang menarik karena jauh dari nalar anak-anak.
Menjadi wajar kalau kami sejak kecil lebih membayangkan yang kota, yang modern, dan yang Barat di tengah-tengah kehidupan lokal desa. Kami memang terikat dengan lokalitas seperti cerita gaib penunggu tempat keramat, tradisi gotong royong, selamatan, tradisi ngaji Al-Quran, seni tradisional, penghormatan kepada orang tua dan sesepuh dusun, maupun larangan- larangan tradisi.
Namun, imajinasi dan impian kami tidak bisa dibatasi oleh tradisi tersebut, karena kami memang lebih menggemari film kartun, lagu-lagu pop, dan film cerita akhir pekan.
Berusaha Menjadi Modern Tanpa Perlu Sepenuhnya Modern
Masa kecil saya, orang tua, kawan- kawan, dan warga lainnya di era 80- an dengan beragam peristiwa sosio- kultural yang terjadi merupakan penanda perjumpaan lokalitas dan modernitas sebagai akibat kuatnya pengaruh ekonomi-politik pembangunanisme Orba.
Ekonomi-politik saya pahami dalam konsep Marxian (Marx, 1991, 1992; Lebowitz, 2002; Wood, 2003), yakni relasi antara struktur dasar (base structure) dan struktur supra (superstructure). Tesis utama yang diusung adalah bahwa basis ekonomi (struktur dasar) akan menentukan struktur supra yang di dalamnya termasuk persoalan ideologi, agama, relasi sosial, politik, maupun budaya.
Kelas pemodal yang ditopang rezim negara dengan kemampuan modal dan alat produksinya mampu menggerakkan mekanisme dan moda produksi yang melibatkan kreator dan buruh dalam organisasi dan praktik kerja untuk menciptakan benda industrial yang mempunyai nila guna dan tukar serta bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya melalui proses sirkulasi, distribusi, dan konsumsi.
Proses tersebut mendorong terjadinya perubahan orientasi ideologi masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur dan praktik sosio-kultural.
Menjadi modern sebagai dampak dari kolonialisme dan pembangunanisme merupakan orientasi yang mengakibatkan pergeseran dan perubahan kehidupan masyarakat desa. Meskipun demikian, menjadi modern pada masa itu tetap tidak meninggalkan sepenuhnya tradisi. Kami tetap patuh kepada orang tua, meskipun kami sudah terbiasa menonton keliaran para tokoh kartun.
Kami masih mencintai kesenian tradisional tanpa disuruh, meskipun tidak paham sepenuhnya apa-apa yang dinarasikan. Para bapak masih sering cangkrukkan atau jagongan di warung atau gardu dusun membicarakan masalah-masalah aktual, seperti pertanian dan keamanan, meskipun dari pertengahan sampai akhir 80-an intensitasnya mulai berkurang karena televisi menghadirkan pesona lain.
Weber (dikutip dalam Heath, 2004:672) menggunakan istilah "hilangnya daya magis" atau "pesona dunia" (Entzauberung/ disenchantment/ demagicalization) untuk menggambarkan sebuah kondisi sosio-kultural tempat masyarakat yang mengalami modernisasi lebih menggunakan rasionalitas dan pengetahuan sebagai pijakan dalam memandang dunia.
Akibatnya, pesona-pesona dunia (seperti keyakinan terhadap magis, kekuatan alam, dan lain-lain) perlahan-lahan akan hilang dari nilai, institusi sosial, dan praksis kultural masyarakat.
Weber, tentu, melihat realitas tersebut dalam masyarakat industrial. Sementara, bagi masyarakat desa, pesona-pesona dunia desa tidak hilang sepenuhnya, karena modernitas juga tidak menguasai kami secara penuh meskipun punya potensi hegemonik dalam menggerakkan orientasi dan praksis kultural desa.
Sebagai formasi diskursif yang dibangun dari beragam wacana di televisi, pendidikan, dan program-program pembangunan pemerintah, modernitas memang berhasil menggeser dan mengubah sebagian tradisi-seperti pertanian serta gaya dan cara berpakaian- serta memperkuat orientasi terhadap kemajuan berbasis rasionalitas/pendidikan dan kekuatan ekonomi.
Namun, perubahan dan pergeseran orientasi tersebut tidak menjadikan kearifan-kearifan lokal hilang sepenuhnya. Bahkan, kearifan lokal yang oleh pikiran rasional-Barat dan agama dikatakan takhayul, tidak ilmiah, dan musyrik, masih hidup dalam masyarakat.
Tradisi nyadran (sedekah bumi/bersih desa) masih dilakukan satu tahun sekali, dengan menggelar ritual persembahan di tempat pedanyangan dusun pada pagi hari dan pada malam harinya digelar pertunjukan tayub atau wayang.
Ketika saya malas sekolah, misalnya, ibu akan pergi ke rumah Pakde yang seorang penganut kebatinan (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) untuk meminta air putih yang sudah diberi doa agar saya mau pergi ke sekolah. Maka, pola pikir modern tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadirkan dari orientasi menjadi modern masyarakat desa.
Kondisi sosio-kultural masyarakat desa di era 80-an yang tengah bergerak menuju modernitasditengah-tengah lokalitas mereka memang sesuai dengan penggambaran teoretis tentang ambivalensi, peniruan, pengejekan, dan hibriditas kultural.
Bhabha (1994) melihat kolonialisme-dalam konteks tulisan ini modernitas-memang menjadikan masyarakat sebagai subjek masuk ke dalam jejaring kuasa yang membuat mereka tampak tidakbisaberbuatapa-apa.
Namun, di tengah-tengah kondisi itu, mereka bisa memandang dan meniru sebagian budaya modern yang memunculkan ambivalensi kultural karena mereka masih menjalankan sebagian budaya lokal. Artinya, peniruan itu tidak sepenuhnya. Kuasa modernitas tidak bisa sepenuhnya memengaruhi kehidupan masyarakat desa, meskipun menjadikan lokalitas tidak bisa dikatakan murni lagi.
Mereka meniru untuk bisa survive dan tidak takluk sepenuhnya-sebuah “pengejekan” (mockery). Ambivalensi dan peniruan/pengejekan akan menghasilkan hibriditas kultural, nilai, dan praktik modern bertemu dengan nilai dan praktik lokal karena kondisi zaman memang menjadikannya seperti itu. Hibriditas menyebabkan lokalitas mengalami keretakan; tidak utuh lagi, tetapi tidak hancur.
Mereka tidak menolak modernitas, tetapi tidak menyukai nilai dan praktik modernitas yang bertentangan secara biner dengan tradisionalisme. Keutamaan rasionalitas, sekulerisasi (pemisahan agama dan kuasa politik), dan menguatnya individualisme merupakan proyek modernitas yang dimaknai-ulang oleh masyarakat desa karena mereka masih menjalankan sebagian nilai dan praktik tradisional.
Dalam pemahaman Canclini (1995:12-13), terdapat empat proyek modernitas. Proyek emansipasi merupakan bentuk dan praktik sekulerisasi ranah kultural, produksi ekspresi-diri dan regulasi-diri dari praktik simbolik, sehingga bisa berkembang dalam pasar otonom. Rasionalisasi kehidupan sosial dan meningkatnya individualisme merupakan bagian dari proyek ini.
Proyek ekspansif merupakan tendensi modernitas untuk memperluas pengetahuan dan penguasaan terhadap alam, produksi, sirkulasi, dan konsumsi. Dalam kapitalisme, ekspansi ini didorong oleh peningkatan keuntungan; tetapi dalam makna yang lebih luas ia termanifestasi dalam promosi penemuan saintifik dan pengembangan industrial.
Proyek renovasi melibatkan kedua aspek tersebut, yang saling melengkapi. Di satu sisi, memenuhi peningkatan ajeg dan inovasi yang disesuaikan dengan relasi pada alam dan masyarakat yang dibebaskan dari petuah- petuah suci, di sisi lain, mereformulasikan secara kontinyu tanda-tanda pembedaan yang dipakai oleh konsumsi massa.
Proyek demokratisasi merupakan gerakan modernitas yang diyakini dalam pendidikan, penyebaran seni, dan pengetahuan terspesialisasikan untuk meraih evolusi rasional dan moral.
Proyek modernitas, nyatanya, tidak mampu mengubah secara menyeluruh masyarakat desa. Nilai-nilai tradisional sudah mengakar kuat dalam kedirian masyarakat desa, sehingga nilai-nilai modern yang masuk tidak bisa menghilangkan mereka.
Kehadiran modernitas di desa, dengan demikian, tidak bisa berjalan mulus dan terbuka bagi permasalahan di dalamnya ketika harus berhadapan dengan nilai tradisional; tidak bisa berkuasa dan berpengaruh sepenuhnya.
Keinginan untuk mendapatkan kemakmuran secara individual, misalnya, tidak bisa menghapus tradisi gotong royong, baik dalam hal membersihkan desa, hajatan, maupun kematian.
Keyakinan anak sebagai amanah menjadikan para orang tua di desa merasa perlu bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Setinggi-tingginya pendidikan dan pekerjaan anak mereka di kota, orang tua tetap tidak akan melepaskan mereka sepenuhnya, termasuk dalam hal pernikahan.
Sejatinya, masalah tersebut tidak hanya terjadi di masyarakat desa di Indonesia pada era 80-an. Pada masyarakat Barat yang sudah terkenal modern, seperti Amerika Serikat, nilai-nilai konservatif tidak bisa hilang sepenuhnya.
Featherstone (2006:459) menjelaskan bahwa istilah modernitas dan konsep-konsep turunannya, seperti sekularisme, demokrasi, teknologi, negara-bangsa, kewarganegaraan, industrialisasi, urbanisasi, superioritas epistemologis pengetahuan, otonomi pikiran dan hukum, keberadaan ruang publik, hak asasi manusia, bermacam kebebasan fundamental, dan individualisme, sebenarnya masih sangat terbuka untuk dipermasalahkan.
Di negara-negara modern, nilai-nilai residual/tradisional masih hidup dan bermutasi karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh institusi politik di AS memang sekuler, tetapi agama, meskipun secara teknis merupakan ruang terpisah dari negara, terus menempati tempat utama baik secara simbolis maupun pada level legitimasi. Pengaruh penolakan sistem keyakinan dalam sejarah modernitas belum sepenuhnya mapan.
Keberantaraan kultural tersebut lebih disebabkan oleh kontestasi narasi yang berlangsung dalam ruang kultural desa; antara narasi tentang pesona dunia desa melalui cerita-cerita lisan dan konsensus dalam masyarakat dan modernitas melalui TVRI dan program-program pemerintah lainnya.
Kontestasi inilah yang menjadikan cara pandang masyarakat tidak bisa dikatakan utuh; masyarakat sebagai subjek menjadi terpecah. Meskipun sejak kecil anak-anak menonton TVRI, dalam saat bersamaan mereka juga selalu menyaksikan atau didongengi oleh orang tua tentang nilai-nilai tradisional yang harus tetap dijaga, di manapun mereka berada kelak.
Cara mereka memaknai, memandang, dan mengalami jagat sosial dan kultural mereka tidak akan lepas dari batasan alur cerita yang berkembang dalam narasi budaya, baik yang dihadirkan narasi kota atau narasi desa. Maka, masyarakat desa menjadi subjek yang hidup dalam keberantaraan kultural, tidak hanya dalam hal praksis tetapi juga orientasi hidup.
Paling tidak, keberantaraan kultural tersebut masih menjadikan masyarakat meyakini dan menjalankan sebagian nilai dan praktik tradisional, meskipun sebagian yang lain sudah hilang dari ruang kultural desa.
Mekipun, masyarakat desa masih bisa memainkan keberantaraan kultural, modernitas dan rezim pembangunan Orde Baru telah memasukkan mereka ke dalam relasi ketergantungan dengan jagat-luar- desa, yakni kota.
Masyarakat memang tidak pernah mendapatkan pelajaran tentang kapitalisme, tetapi mereka harus membiasakan diri dengan harga padi dan beras yang sangat tergantung kepada Bulog dan permintaan pasar. Mereka juga semakin terbiasa dengan pupuk dan pestisida. Anak- anak dan kaum remaja semakin nyaman dengan pakaian-pakaian modern dari kota.
Sepeda motor menjadi impian masyarakat. Artinya, dalam bentuk yang sangat se- derhana, kapitalisme telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat desa, karena ia bukan lagi ideologi yang harus ditakuti. Kapitalisme bertransformasi sebagai nilai dan mekanisme yang bisa membimbing masyarakat desa mewujudkan impian-impian sederhana tentang menjadi modern.
Kapitalisme dan modernitas itulah yang terus mereproduksi endapan-endapan ideologis terhadap Barat (oksidentalisme)[vi] dalam benak masyarakat desa, meskipun jarak mereka dengan negara-negara Barat sangatlah jauh. Barat tidak perlu hadir sebagai institusi, tetapi hadir sebagai nilai dan mekanisme yang terus menggerakkan masyarakat.
Tidak bisa disangkal lagi, masuknya masyarakat desa ke dalam jejaring mo- dernitas, meskipun tidak sepenuhnya, adalah kontribusi terbesar rezim Orba. Bagaimanapun juga, TVRI, percepatan industri, Revolusi Hijau, pengaspalan jalan, listrik, dan “Keluarga Budi”, berhasil menggerakkan masyarakat menuju modernitas.
Pilihan ekonomi- politik pembangunanisme dengan mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi, percepatan industri dan pertanian, serta stabilitas keamanan dan integrasi, menyebabkan pergeseran atau perubahan orientasi dan praktik sosio- kultural desa. TVRI menjadi situs yang memudahkan masyarkat desa bersentuhan dengan pembangunan dan modernitas dalam arahan rezim negara.
Percepatan industri di kota membutuhkan perluasan pasar sampai ke tingkat desa. Revolusi Hijau menjadi senjata andalan untuk bisa mempercepat laju perkembangan masyarakat desa dengan sistem pertanian modern.
Pengaspalan jalan mempertinggi mobilitas masyarakat desa ke kota, sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan benda-benda modern dari kota kabupaten atau kecamatan. Kesempatan memperoleh pendidikan, paling tidak sampai ke tingkat dasar dan menengah/SMP-SMA, menjadikan pikiran-pikiran modern bersemi dalam pikiran generasi muda desa.
Kesadaran masyarakat desa untuk tetap mempraktikkan sebagian kearifan lokal, meskipun mereka menjalankan sebagian budaya modern, menunjukkan bahwa mereka berhasil mengganggu kuasa-hegemonik modernitas. Namun, kondisi tersebut ternyata bersifat koinsiden dengan kepentingan rezim untuk meredam potensi kritis dan subversif masyarakat desa.
Kepentingan stabilitas keamanan dan integrasi sosial untuk mempercepat pembangunan bertemu dengan kecenderungan ke-hidupan harmonis desa. Modernitas yang diinginkan rezim, dengan kata lain, memang tidak sepenuhnya memunculkan kebebasan dalam hal subjektivitas.
Rezim berkepentingan memelihara budaya lokal yang bisa mendukung pembangunan melalui kampanye pentingnya budaya nasional sebagai identitas bangsa maupun Penataran P-4.
Selain itu, kehadiran aparat keamanan sampai di tingkat desa (Babinsa, misalnya) menjadikan masyarakat tidak punya keberanian untuk membicarakan keburukan program pemerintah. Ketika ada penolakan terhadap penggunaan bibit hibrida, misalnya, para petani akan segera dipanggil atau didatangi aparat.
Simpulan
Dari uraian tentang cerita masa kecil dan beberap aanalisis, terdapat beberapa cara pandang yang bisa digunakan untuk melihat formasi diskursif modernitas yang memengaruhi gerak kehidupan masyarakat desa pada era 80-an.
Pertama, peran ekonomi-politik pembangunanisme berhasil membiasakan masyarakat dengan orientasi kemajuan, ke- kota-an, budaya populer, pertanian kapitalis, dan pendidikan, sehingga mereka benar- benar masuk ke dalam kuasa modernitas.
Kedua, keberakaran tradisionalisme yang dinarasikan secara turun-temurun dalam institusi keluarga maupun sosial, menjadikan masyarakat tidak menerima nilai-nilai modern sepenuhnya seperti individualisme. Ketiga, ambivalensi dan hibriditas kultural berlangsung tidak hanya dalam ranah praksis, tetapi juga dalam ranah pikiran/ orientasi.
Keempat, ambivalensi dan hibriditas kultural tersebut tetap menjadikan modernitas sebagai endapan-endapan ideologis dalam imajinasi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kelima, rezim negara dengan aparatus intelektualnya menjadikan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi-politik yang mampu menggerakkan masyarakat ke arah modernitas, tetapi tetap berada dalam keterbatasan subjektivitas.
Dengan cara pandang tersebut, lokalitas tidak bisa lagi dipahami sebagai keutuhan yangterus-menerusterjaga. Secaragenealogis, sejak Soeharto mulai memimpin negeri ini, masyarakat sudah mulai diajak memandang kemajuan dengan politik pintu-terbukanya. Era 80-an menjadi penanda sebuah fase masyarakat desa yang tengah bergerak menuju modernitas.
Sebagian nilai dan praktik kultural juga mengalami pergeseran atauperubahan. Pascakolonialitas masyarakat desa, menjadikan lokalitas semakin kompleks dengan kehadiran modernitas yang menjadi warga baru bagi kehidupan tradisional masyarakat.
Pascakolonialitas merupakan kondisi kultural dalam masyarakat selepas penjajahan yang selalu diwarnai ambivalensi dan kesadaran ganda. Kesadaran untuk mentransformasi yang Barat/yang modern ke dalam yang Timur/yang tradisional sebenarnya bisa menjadi kekuatan bagi masyarakat poskolonial untuk mengganggu kemapanan epistemologis modernitas Barat (Radhakrisnan, 2003:1-2).
Namun, pascakolonialitas bisa menjadi makna dan praktik yang menyulitkan, ketika masyarakat susah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kuasa Barat, sebagaimana yang berlangsung dalam masa kolonial (Gandhi, 1998: 5-7).
Dalam masyarakat desa era 80-an, keretakan lokalitas memang telah berlangsung, tetapi belum bisa sepenuhnya menghancurkan bangunan-bangunan konsensual-komunal yang sudah mengakar dalam tradisi masyarakat lokal.
Yang perlu diperhatikan, perkembangan sosio-kultural masyarakat desa tidaklah mandeg, tetapi terus bergerak dan men- ciptakan narasi-narasi baru yang lebih kompleks pada periode-periode berikutnya dengan modernitas tetaplah berkuasa dalam ruang kultural desa.
Subjektivitas masyarakat desa terus bergerak dan berubah secara dinamis karena selepas era 80-an budaya modern semakin masuk ke dalam pikiran, imajinasi, impian, dan praktik sosio-kultural.
Maka, mendeskripsikan masyarakat desa dan lokalitas mereka dalam perspektif esensialisme dan keadilihungan-normatif merupakan kekonyolan akademis di tengah-tengah bising suara motor dan mobil, khusuknya warga di depan televisi, semakin sedikitnya penonton kesenian tradisional, semakin megahnya rumah- rumah tembok, hilangnya permainan tradisional, migrasi generasi muda ke kota, dan peristiwa-peristiwa lainnya.
Sekuat apapun usaha para birokrat rezim pascareformasi, akademisi, dan budayawan menggali kearifan lokal sebagai jatidiri dan karakter bangsa dalam forum seminar, simposium, konferensi, maupun proyek, kenyataannya, masyarakat desa dan lokalitas telah, tengah, dan akan terus bergerak menuju mondernitas karena sistem ekonomi-politik yang diterapkan sejak Orba memang lebih mengarahkan mereka ke dalam kehidupan modern.
Menurut saya, usaha membaca secara kritis lokalitas yang semakin kompleks di tengah-tengah kuasa modernitas bisa menjadi alternatif pilihan politis-akademis untuk terus membongkar dan mengurai persoalan-persoalan mendasar dalam lokalitas.
Pilihan itu mungkin akan lebih baik dari pada harus terus-menerus menjadi komprador rezim yang kenyataannya tidak pernah bersungguh-sungguh memperjuangkan budaya lokal.
Daftar Bacaan
Alisjahbana, St. Takdir. 1998. “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru.” Dalam Achdiat K. Mihardja (Ed). Polemik Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
Aschroft, Bill. 2001. Post-colonial Future: Transformation of Postcolonial Culture. London: Continuum.
Bennet, Tony. 1986. “Introduction: the turn to Gramsci.” Dalam Tony Bennet, Colin Mercer, & Janet Woollacott (Eds). Popular Culture and Social Relation. Philadelphia: The Open University Press.
Bhabha, Hommi K. 1994. The Location of Culture. London: Routledge.
Bishop, Alan J. 1995. “Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism.” Dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (Eds). The Post-colonial Studies Reader. London: Routledge.
Boggs, Carl. 1984. The Two Revolution: Gramsci and the Dilemas of Western Marxism. Boston: South End Press.
Boothman, Derek. 2008. “Hegemony: Political and Linguistic Sources for Gramsci s Concept of Hegemony.” Dalam Richard Howson & Kylie Smith (Eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Brantlinger, Patrick. 2009. Victorian Literature and Postcolonial Studies. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Budiawan. 2010. “Pengantar.” Dalam Budiawan (Ed). Ambivalensi: Post-kolonialisme Membedah Musik sampai Agama di Indonesia. Yogyakarta: Jalasutra.
Canclini, Nestor Garcia. 1995. Hybrid Cultures: Strategies for Entering and Leaving Modernity. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Clestin, Roger. 1996. From Cannibals to Radicals: Figures and Limits of Exoticism. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Chakrabarty, Dipesh. 2000. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton University Press.
Fanon, Franz. 2008. Black Skin White Mask. London: Pluto Press.
Faruk. 2007. Belenggu Pasca-kolonial: Hegemoni dan Resistensi dalam Sastra Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Focault, Michel. 2002. Arkeologi Pengetahuan. (Terj. oleh H.M. Mochtar Zoerni). Yogyakarta: Qalam.
Fontana, Benedetto. 2008. “Hegemony and Power in Gramsci.” Dalam Richard Howson & Kylie Smith (Eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Gandhi, Leela. 1998. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. New South Wales: Allen Unwin Publishing.
Gillen, Paul & Devleena Ghosh. 2007. Colonialism and Modernity. Sydney: UNSW Press.
Gramsci, Antonio. 1981. “Class, Culture, and Hegemony.” Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, Janet Woolacott (Eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Hall, Stuart. 1997a. “The Work of Re- presentation.” Dalam Stuart Hall (Ed). Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication in association with The Open University.
Hall, Stuart. 1997b. “Gramsci s Relevance for The Study of Race and Ethnicity.” Dalam David Morley Kuan-Hsing Chen (Eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
Hall, Stuart. 1982. “The Rediscovery of Ideology: Return of the Repressed in Media Studies.” Dalam Michael Gurevitch, Tonny Bennet, James Curran, and Janet Woollacott (Eds). Culture, Society, and the Media. London: Metheun.
Heath, Joseph. 2004. “Liberalization, Modernization, Westernization.” Philosophy and Social Criticism, vol. 30 (5-6).
Howson, Richard & Kylie Smith. 2008. “Hegemony and the Operation of Consensus and Coercion.” Dalam Richard Howson & Kylie Smith (Eds). Hegemony: Studies in Consensus and Coercion. London: Routledge.
Irawanto, Budi. 1999. Film Ideologi dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia (Analisis Semiotik terhadap Enam Djam di Jogja, Janur Kuning, dan Serangan Fajar). Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
Kachru, Braj B. 1995. “The Alchemy of English.” Dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, & Helen Tiffin (Eds). The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge.
Laclau, Ernesto Chantal Mouffe. 1981. “Hegemony and Ideology in Gramsci.” Dalam Tony Bennett, Graham Martin, Collin Mercer, & Janet Woolacott (Eds). Culture, Ideology, and Social Process. Batsford: The Open University Press.
Lombard, Denys. 2000. Nusa Jawa: Silang Budaya, Batas-batas Pembaratan (Terj. Winarsih P.A., dkk.). Jakarta: Penerbit Gramedia.
Loomba, Ani. 2000. Colonialism/Post-colonialism. London: Routledge.
Lebowitz, Michael.2002. “Karl Marx: The Needs of Capital vs. The Needs of Human Beings.” Dalam Douglas Dowd (Ed). Understanding Capitalism: from Karl Marx to Amartya Sen. London: Pluto Press.
Lidchi, Henrietta. 1997. “The Poetics and The Politics of Exhibiting Other Culture.” Dalam Stuart Hall (Ed). Representation, Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publications in association with The Open University.
Marx, Karl. 1991. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 3 (English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in Association with New Left Review.
Marx, Karl. 1992. The Capital: A Critique of Political Econnomy Volume 2 (English trans. David Fernbach). London: Penguin Books in Association with New Left Review.
Mbembe, Achille. 2001. On Postcolony. Berkeley: University of California Press.
McGuigan, Jim. 1999. Modernity and Postmodern Culture. London: Sage Publications.
Memmi, Albert. 1975. The Colonizer and The Colonized. New York: Beacon Press.
Mignolo, Walter D. Madina Tlostanova. 2008. “The Logic of Coloniality and the Limits of Postcoloniality.” Dalam Revathi Krishnaswamy & John C. Hawley (Eds). The Postcolonial and the Global. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Mrazek, Rudolf.2006. Engineers of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Pennycook, Alastair. 1998. English and The Discourses of Colonialism. London: Routledge.
Quayson, Ato. 2000. Postcolonialism: Theory, Practice or Process? London: Polity Press.
Radhakrisnan, R. 2003. Theory in Uneven World. Victoria: Blackwell Publishing.
Said, Edward W. 1978. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. London: Penguin Books.
Said, Edward W. 1994. Culture and Imperialism. New York: Vintage Books.
Sears, Lauire J. 2005. “Intellectuals, Theosophy, an Failed Narratives of the Nation in Late Colonial Java.” Dalam Henry Schwarz & Sangeeta Ray (Eds). A Companion to Postcolonial Studies. Malden (USA): Blackwell Publising.
Slack, Jennifer Daryl. 1997. “The Theory and Method of Articulation in Cultural Studies.” Dalam David Morley & Kuan-Hsing Chen (eds). Stuart Hall, Critical Dialogue in Cultural Studies. London: Routledge.
Slemon, Stephen. 1995. “The Scramble for Postcolonialism.” Dalam Bill Aschroft, Garret Griffiths, Helen Tiffin (eds). The Post-colonial Studies Reader. London: Routledge.
Soeharto, Ben. 1999. Tayub: Pertunjukan dan Ritus Kesuburan. Jakarta: MSPI.
Venn, Couze. 2006. The Postcolonial Challenge: Toward Alternative Worlds. London: Sage Publications.
Venn, Couze. 2000. Occidentalism: Modernity and Subjectivity. London: Sage Publications.
Mike Featherstone. 2006. “Modernity.” Theory, Culture, & Society, vol. 23(2-3).
Wood, Ellen Meiksins.2002. The Origin of Capitalism: A Longer View. London: Verso.
Weaver-Hightower, Rebecca. 2007. Empire Islands: Castaways, Cannibals, and Fantasies of Conquest. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Williams, Raymond. 2006. “Base/ Superstructure in Marxist Cultural Theory.” Dalam Meenakshi Gigi Douglas M. Kellner (Eds). Media and Cultural Studies Key Works. Victoria: Blackwell Publishing.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H