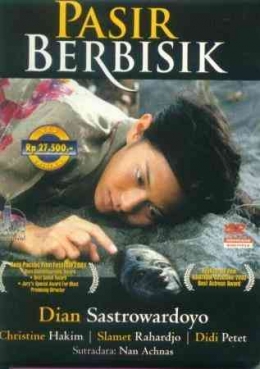Film ini dengan cermat menceritakan dengan detil bagaimana liku-liku kehidupan gelandangan dan tukang becak yang sangat problematis. Namun, yang harus diperhatikan adalah ketidakberanian untuk memotret secara lebih jauh betapa kebijakan pembangunan nasional telah menyebabkan kondisi itu terjadi.
Film ini pun berakhir dengan ending yang membahagiakan semua pihak. Selalu ada solusi, selalu ada kebahagiaan, sebuah pesan tunggal kehidupan yang menjadi semangat rezim Orba.
Di samping itu film-film yang dengan jeli mengkritisi ketidakadilan yang diperoleh orang miskin, kelas subordinat, harus dirubah sebelum diedarkan karena dianggap menjelek-jelekkan pemerintah maupun aparat penegak hukum yang saat itu terbukti sangat korup.
Film Perawan Desa (1978) yang menceritakan tentang seorang gadis dari Yogya yang diperkosa oleh sekelompok anak muda kota, anak para pejabat, harus merubah alur cerita hingga ending-nya, karena dianggap tidak sesuai dengan budaya bangsa, meskipun sebenarnya cenderung untuk menutupi kebusukan penegak hukum.
Cerita awalnya sebenarnya bertutur tentang tokoh perempuan yang malah dipenjara oleh polisi karena dianggap membuat isu perkosaan. Sementara para pemerkosa masih bebas. Setelah melalui BSF, ending cerita itu diubah, di mana para pemerkosa mendapat kecelakaan dan tokoh perempuan memperoleh masa depan yang cerah dengan menjadi perawat.
Uniknya, dalam FFI 1980, film ini mendapat penghargaan sebagai Film Terbaik karena dianggap menceritakan perjuangan sosial rakyat kecil untuk memperoleh keadilan (Sen & Hill, 2000: 143-147).
Ironisnya lagi, nilai-nilai ideal dari aturan-aturan yang ada ternyata banyak dilanggar sendiri oleh "para sineas pesanan" pemegang modal yang sekedar ingin memperoleh keuntungan dengan memenuhi tanggung jawab aturan impor film yang mensyaratkan perusahaan importir membuat film demi menggairahkan industri perfilman.

Akibatnya, pada era 90-an film Indonesia dipenuhi dengan booming film bergenre ‘sek-kesek ala metropolis’ yang banyak mengeksploitasi perempuan. LSF, ternyata hanya bisa bersilat lidah dan mempertahankan kebenarannya dengan kondisi seperti itu. LSF semata-mata menjadi aparatus hegemonik bermata dua.
Di satu sisi mereka sangat membatasi kreativitas para sineas Indonesia dengan beragam aturan yang selalu dikatakan mengedepankan budaya bangsa dan standar moralitas. Di sisi lain, mungkin karena desakan memajukan industri film tanah air, mereka tetap saja membolehkan film-film yang nyata-nyata mengedepankan seksualitas, kekerasan, maupun mistis.
Lalu, masih perlukah mengatasnamakan budaya bangsa dalam konteks penyensoran film, kalau institusi LSF sendiri tidak bisa merumuskan dengan benar apa itu budaya bangsa?