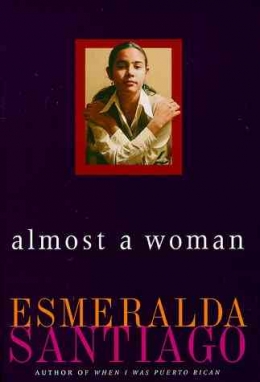Ketika memutuskan untuk berkencan dengan banyak lelaki dan mengabaikan perkataan ibunya, Negi sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan tradisi anak muda Barat dalam memaknai cinta. Larangan ibunya adalah suara otoritas keluarga dan nilai-nilai Puerto Rico, yang menganggap kencan pranikah salah.
Di antara masyarskat Latin terdapat pandangan ideal bahwa perempun harus menjaga keperawanannya sampai pernikahan dan perempuan yang aktif secara seksual di luar hubungan cinta dianggap tidak baik (Wright, 2014: 248-249).
Oleh karena itu, banyak orang tua imigran Puerto Rico di AS mengirimkan gadis remaja ke keluarga atau kerabat di Puerto Rico agar mereka tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas (Prez, 2002: 39-40).
Bagi Negi, kebebasan seksual harus dirayakan dan dinikmati tanpa harus mengindahkan batasan tradisional dalam budaya ibu. Wacana kebebasan seksual ini menjadi isu dominan dalam banyak karya sastra diasporik, karena menjadi wacana dan praktik stereotip yang membedakan dengan tradisi di negara asalnya.
Namun, ini tidak berarti bahwa sebagai seorang perempuan muda Puerto Rico, Negi sama sekali mengabaikan dan meninggalkan budaya Puerto Rico. Ia mendapat pelajaran budaya dari Mami dan neneknya, sehingga meskipun terpaksa, Negi juga memiliki pemahaman tentang budaya ibu dan tanah air.
Kehidupan di daerah kantong Puerto Rico di AS juga meningkatkan ikatannya dengan beragam budaya Puerto Rico. Realitas diskursif ini juga dapat dijumpai dalam kehidupan pemuda Puerto Rico di AS, di mana meski sudah terbiasa dengan tradisi Amerika, mereka tetap memiliki solidaritas dengan tanah air sehingga tidak sepenuhnya menjadi bagian dari masyarakat politik dan budaya Amerika (Estrella & Kelley, 2017).
Apa yang menarik untuk dicatat adalah kenyataan bahwa betapapun banyak budaya kulit putih yang dijalani oleh Negi, ia tetap dipandang sebagai Liyan dan tidak pernah bisa menjadi bagian utuh dari masyarakat kulit putih. Keheranan supervisor-nya di sekolah pertunjukan ketika dia mengetahui bahwa Negi tidak memiliki aksen Puerto Rico membuatnya merasa tersinggung.
Lebih dari sekali aku diberitahu bahwa aku tidak "terdengar" seperti orang Puerto Rico. "Kamu tidak memiliki aksen," Tuan Merton, salah satu supervisor, berkomentar, dan aku menjelaskan tentang seni pertunjukan dan tuturan standar. Ketika ia menyiratkan bahwa aku tidak 'bertindak' layaknya warga Puerto Rico, aku menelan hinaan itu.
"Mungkin Anda belum cukup bertemu dengan kami," kataku, sedih karena ia terkejut warga Puerto Rico bisa menjadi perempuan yang kompeten dan berbicara bahasa Inggris dengan baik. (Santiago, 2012: 68)
Usahanya untuk berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika kulit putih dan upaya lain untuk mengapropriasi budaya anak muda Amerika bukanlah perjuangan yang mudah. Sementara, dalam sekolah pertunjukan, ketelitian aksen merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi agar dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran.
Jadi, ketika Tuan Merton mengungkapkan keheranannya, itu sama saja dengan mengatakan bahwa warga Puerto Rico sejati tidak layak untuk dapat berbicara dan berbudaya seperti orang kulit putih. Tentu saja, keberadaan Tuan Merton berkorelasi dengan otoritas dan mayoritas orang kulit putih Amerika yang melihat imigran sebagai masalah sosio-kultural.