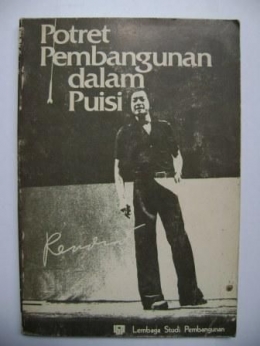Sebagai produk diskursif, makna-makna yang sudah ada tersebut berhubungan dengan topik-topik partikular, menunjukkan subjek siapa yang sedang diposisikan dalam teks, hal-hal apa yang dihadirkan dan tidak dihadirkan, apa yang layak digambarkan dan tidak layak, dan bagaimana otoritas kuasa dihadirkan dalam permainan tekstual yang menghasilkan wacana serta terhubung dengan wacana-wacana di luar teks tersebut.
Kehadiran wacana di dalam teks puisi, tentu, bukan sekedar menjadi pilihan individual penyair, tetapi juga berjalin-kelindan dengan sesuatu yang bersifat publik. Bagaimanapun juga, penyair hidup di tengah-tengah galaksi wacana yang mempengaruhi subjektivitasnya sebagai manusia kreatif dan menggunakan bahasa publik pula sebagai alat ekspresi tersebut.
Dalam kondisi demikian, puisi bukan hanya menjadi formasi diskursif dari konstruksi wacana atau pengetahuan tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Lebih dari itu, puisi yang sudah dipublikasikan adalah 'milik publik'. Wimsatt & Beardsley (dikutip dalam Besley, 1990: 16) mengatakan puisi bukan lagi milik penyair semenjak kelahirannya karena ia beranjak menuju "dunia", melampaui segala kekuatan yang dimaksudkan untuknya atau yang hendak mengendalikannya.
Puisi menjadi milik publik karena ia menubuh dalam bahasa (sebuah kepemilikan istimewa dari publik) dan juga bercerita tentang manusia, masyarakat, dan kompleksitas permasalahannya. Pengarang memang masih berhak menyematkan namanya di halaman sampul sebagai penanda kehadirannya.
Namun, ia tidak bisa lagi mengarahkan dan mengendalikan tafsir ataupun eksplorasi wacana yang ada di dalamnya karya-karyanya oleh para peneliti. Ia cukup menghadirkan puisi dan biarkan keragaman makna dan wacana menjadi tugas pembaca dan peneliti untuk mengungkap.
Kemenyatuan puisi dengan sesuatu yang bernama publik, baik terkait permasalahan, wacana maupun bahasa ungkap yang digunakan, menjadikannya tidak bisa dipisahkan dari persoalan ideologi. Dalam kerangka Marxian, ideologi dipahami sebagai keyakinan, perspektif, atau pemikiran tertentu yang menjadi penuntun laku individu-individu dalam meng-ada di sebuh masyarakat. Mengikuti sudut pandang deterministik, ideologi menjadi sistem keyakinan yang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan eksploitatif sebuah kelas dominan terhadap kelas-kelas subordinat; "ide kelas penguasa adalah ide untuk menguasai".
Marx and Engel (2006: 9) menegaskan bahwa ide kelas penguasa akan selalu diarahkan menjadi ide yang menguasai karena mereka memiliki alat dan kemampuan produksi mental melalui pengetahuan, filsafat, moral, wacana, dan lain-lain yang bisa disebarluaskan ke tengah-tengah massa yang tidak memiliki kecukupan alat dan kemampuan produksi.
Ideologi, kemudian, sangat ditentukan oleh struktur-basis dalam sebuah masyarakat di mana kelas pemodal atau kelas penguasalah yang mengendalikan. Ide yang menguasai merupakan ekspresi ideal dari relasi-relasi material yang selalu menguntungkan dominasi kelas penguasa.
Tentu saja, sudut pandang tersebut perlu dielaborasi lagi dalam kaitannya dengan pengkajian puisi atau karya-karya sastra lainnya, khususnya terkait bagaimana cara ideologi beroperasi dalam karya sastrawi. Mengapa? Pemaknaan ideologi tersebut berangkat dari kesadaran praksis, sementara, karya puisi adalah produk kebahasaan yang sudah mengalami proses mimesis, mediasi, dan diskursif, sehingga untuk membacanya kita perlu memiliki kerangka baru terkait ideologi secara dinamis.
Ideologi bukanlah sesuatu yang bersifat dogmatis dan menggurui berupa jargon atau kampanye yang terang benderan di dalam sebuah karya. Sebagai sebuah kerangka berpikir atau cara pandang terkait sesuatu,
ideologi dituliskan dalam wacana-wacana spesifik, ranah penggunaan bahasa, cara tertentu untuk berbicara (dan menulis serta berpikir). Sebuah wacana melibatkan asumsi-asumsi terbagi tertentu yang muncul dalam formulasi yang mengkarakterisasinya. Wacana tentang kehendak bersama, misalnya, jelas berbeda dengan wacana fisika modern, sehingga beberapa formulasi dari satu wacana bisa berkonflik dengan formulasi wacana lain.
Ideologi dituliskan dalam wacana dalam makna bahwa ia secara literer ditulis atau diomongkan di dalamnya; ia bukanlah elemen terpisah yang eksis secara independen dalam beberapa ranah bebas-mengambang dari ide-ide dan sesudah itu menubuh dalam kata-kata, melaikan sebuah cara berpikir, berbicara, dan mengalami. (Besley, 1991: 5)
Sesederhana atau se-njlimet apapun diksi, se-kompleks apapun metafor yang diambil, se-panjang apapun baitnya, puisi tetaplah tuturan dalam bentuk tulis yang digunakan seorang penyair untuk merangkai ideologi yang tidak lagi tampak sebagai sebuah keyakinan bersama.