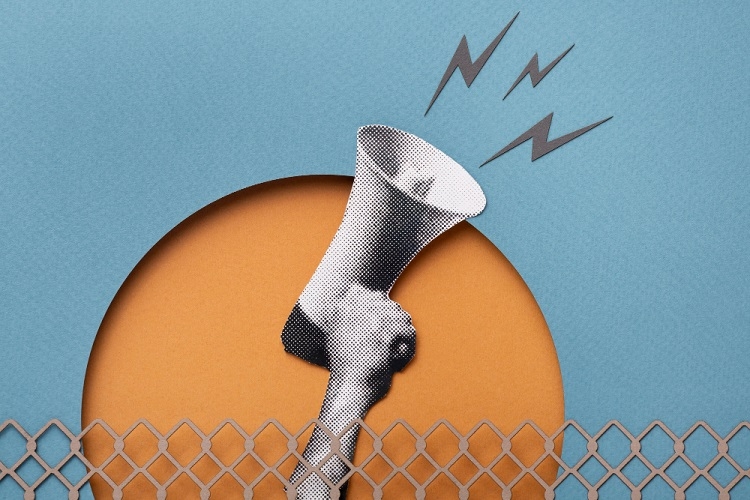Indonesia -- negara multi-etnis dengan 17.000 pulau, dengan garis pantai sepanjang 98.000 kilometer, berpenduduk 270 juta, dengan jumlah pengguna internet mencapai 196,7 juta orang (73,7 persen dari total penduduk) di kwartal kedua tahun 2020[1] -- menghadapi situasi pelik terkait demokrasi.
Selain menghadapi kemunduran demokrasi dan menghadapi tantangan korupsi sistemik dan melemahnya lembaga antikorupsi, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas, konflik di Wilayah Papua, penggunaan undang-undang pencemaran nama baik dan penodaan agama yang dipolitisir, tetapi juga menghadapi masalah di ranah digital seperti penyebaran disinformasi online, penyebaran ujaran kebencian, serangan digital dalam bentuk online trolling, doxing, dan pelecehan dunia maya yang merusak demokrasi.
Pelbagai situasi pelik terhadap demokrasi tersebut akhirnya memberi dampak buruk pada kehidupan demokrasi. Di Indonesia, kemunduran demokrasi sudah dimulai sejak tahun 2016.
Jika kita cermati indeks demokrasi dari laporan tahunan The Economist Intelligence Unit, pada tahun 2016 Indonesia masih menduduki peringkat ke-48 dari 167 negara yang diteliti. Namun kemudian, indeks demokrasi Indonesia mengalami penurunan selama empat tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, indeks demokrasi turun ke peringkat 64 dengan skor 6,30 -- peringkat terendah sejak 2008, masuk dalam kategori "demokrasi cacat".[2]
Tulisan ini hendak menyoroti bagaimana demokrasi memburuk di ranah mayantara dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk memulihkannya agar menjadi ruang demokrasi Indonesia yang maju.
Sejumlah Persoalan
Di mayantara, belakangan ini polisi gencar melakukan patroli siber untuk mencari aktivis dan kelompok kritis yang dituding telah menghina negara atau presiden.
Dengan menggunakan undang-undang tentang internet yang karet, para aktivis yang menggunakan akun media sosial mereka untuk mengekspresikan protes atas pernyataan pejabat publik atau kebijakan yang dikeluarkan Negara harus berurusan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau mengganggu ketertiban umum dan menciptakan keonaran.
Bahkan di masa pandemi Covid-19, tindakan polisi tidak berhenti melakukan aktivitasnya, bahkan kondisinya semakin parah dari tahun sebelumnya. Situasi pandemi Covid-19 menciptakan momen di mana aparat penegak hukum menggunakan situasi tersebut sebagai alasan untuk membungkam kebebasan berpendapat secara berlebihan dengan menggunakan UU ITE dan peraturan lainnya untuk mengekang kebebasan berekspresi.
Berdasarkan data Direktorat Kejahatan Siber Polri, pada tahun 2020 sebanyak 4.790 orang diperiksa. Jumlah yang diperiksa polisi meningkat sekitar 4 persen atau 204 orang jika dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari data tersebut, 1.794 laporan kasus pencemaran nama baik, 404 kasus asusila, 223 laporan tentang ujaran kebencian, 197 laporan berita bohong, dan 135 laporan ancaman secara daring.
Banyaknya mereka yang diinvestigasi oleh polisi siber menunjukkan bahwa situasi kebebasan berekspresi daring di Indonesia berada di bawah pengawasan berat yang sering berujung pada pembungkaman bagi mereka yang berbeda pendapat, terutama mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah.
Sekalipun banyak pihak menyoroti kinerja kepolisian yang kurang jernih dalam memilah kasus-kasus yang terjadi, namun persoalannya tidak sesederhana itu. Bukan hanya polisi yang perlu disoroti, tetapi kelompok masyarakat sipil percaya bahwa norma pengaturan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan sejumlah pasal bermasalah di dalam UU ITE yang justru menjadi kendala serius bagi kebebasan berekspresi di mayantara.
Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE, merupakan duplikasi pasal 310, 311, 315, 317, 318, 319 KUHP. Ketentuan ini menghilangkan gradasi hinaan (fitnah, fitnah, laster, dsb). Dalam KUHP, istilah 'penghinaan' merupakan judul bab tersendiri yang bentuk perbuatannya terdiri dari enam bentuk tindak pidana, yaitu penodaan agama, penodaan agama dengan surat, fitnah, hinaan ringan, aduan palsu atau aduan fitnah, dan fitnah. tindakan.
Sementara itu, dalam UU ITE, tidak ada kategorisasi delik penghinaan. Pasal pencemaran nama baik juga seharusnya dirumuskan dengan sangat jelas mengacu pada Pasal 19(3) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik dan diberi kesempatan untuk membela kebenaran/verifikasi (Komentar Umum Komisi HAM PBB Nomor 34).
Komentar Umum PBB Nomor 34 ini merekomendasikan penghapusan pencemaran nama baik, jika tidak memungkinkan, pencemaran nama baik hanya diperbolehkan untuk kasus-kasus yang paling serius dengan ancaman bukan dipenjara. Hal ini berdampak pada spektrum tindakan atau ekspresi yang sangat luas yang dapat dijerat dengan ketentuan pasal ini yang kemudian mengakibatkan kerancuan dalam pelaksanaannya.
Dalam penerapannya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE sering dijadikan alat balas dendam digunakan untuk kelompok yang lebih berkuasa atau berkuasa. Mereka yang dilaporkan bukan hanya individu, tetapi juga produk jurnalistik dan hasil penelitian ikut dilaporkan. Tampak nyata, terjadi perluasan penafsiran Pasal 27 ayat (3) yang sering digunakan untuk menjerat penghinaan yang ditujukan kepada perusahaan dan lembaga negara. Dengan adanya pasal ini berpotensi menjerat ekspresi sah yang dikeluarkan untuk kepentingan publik karena tidak mengenal pengecualian dan membatasi hak berekspresi dan berpendapat.
Misalnya, Saiful Mahdi, dosen universitas di Universitas Syiah Kuala, pada April 2020, divonis tiga bulan penjara dan denda berdasarkan Pasal 27 (3) UU ITE untuk pesan WhatsApp yang kritis terhadap proses rekrutmen di Universitas Syiah Kuala
Atau pada kasus pelaporan Marco Kusumawijaya, seorang aktivis lingkungan, yang dilaporkan ke polisi dengan pasal yang sama oleh perusahaan Pantai Indah Kapuk, setelah menulis posting Twitter yang mengatakan PIK (Rumah Perumahan di Jakarta Utara) mengambil pasir dari pantai Bangka.
Hal yang sama juga ditemukan pada persoalan mengatur ujaran kebencian di mayantara. Jumlah orang yang diperiksa polisi, kemudian ditangkap dengan pasal-pasal ujaran kebencian selama pandemi memang menunjukkan peningkatan.
Namun yang ditemukan dalam kasus-kasus tersebut, tak sedikit pengguna media sosial yang sebenarnya mengungkapkan kekesalan betapa lambat dan tidak jelasnya pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 justru kemudian dituding telah menyebarkan disinformasi terkait COVID-19 dan menimbulkan kebencian pada pemerintah.
Salah satu contoh kasus yang menonjol, terjadi pada Wira Pratama di Kepulauan Riau, Sumatera, yang ditangkap setelah mengunggah meme bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun Facebook-nya. Dia melengkapinya dengan mengingatkan agar tidak korupsi anggaran COVID-19. Ia mengaku hanya bermaksud mengingatkan pemerintah untuk serius menangani pandemi. Namun, dia ditangkap polisi pada 8 April 2020. Dia diduga menyebarkan kebencian dan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Wira Pratama dijerat pasal 28 (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.
Sekali lagi, pokok persoalannya bukan hanya pada penerapan aturan ini di tangan aparat penegak hukum, tetapi ada persoalan juga dalam rumusan norma pengaturan di dalam UU ITE dan aturan hukum yang berlaku tentang ujaran kebencian di Indonesia.
Yang juga perlu mendapat perhatian publik adalah bagaimana upaya menghadapi penyebaran disinformasi yang dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok yang berseberangan. Manipulasi informasi, baik yang dilakukan dengan mengerahkan pasukan siber untuk memelintir informasi ataupun dengan bantuan teknologi komputasional, menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dengan kehati-hatian.
Tidak ada tindakan tegas pada praktik semacam ini justru banyak menajamkan polarisasi politik di dalam masyarakat yang kemudian dapat berujung pada pemecahbelahan lapisan masyarakat untuk keuntungan sekelompok elit politik dalam kontestasi pilkada atau pemilihan umum.
Persoalan-persoalan yang muncul ini tak cukup hanya diatasi dengan menerbitkan Surat Kesepatan Bersama antara ketiga lembaga yakni Kemkominfo, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung. Karena SKB tiga lembaga tidak dapat membendung arus pemolisian narasi, propaganda komputasional dan represi pada kelompok kritis yang justru menjadi batu sandungan dalam proses komunikasi politik yang terjadi di mayantara.
Pemulihan Ruang Demokrasi Harus Dilakukan Segera
Memburuknya ruang demokrasi di mayantara bermula dari ketidaksiapan dalam membendung otoritarianisme digital, yakni penggunaan teknologi digital oleh rezim otoriter untuk mengawasi, menekan, dan memanipulasi populasi domestik dan asing. (Alina Poliyakova, 2019). Keberadaan teknologi informasi dipandang secara positivistik, tanpa melihat bahwa teknologi yang sama bila digunakan oleh kelompok otoriter justru dapat memperburuk ruang demokrasi, menjadi semakin illiberal atau bahkan menjadi putar balik haluan menuju pada otoritarianisme.
Cina dan Rusia menjadi kiblat utama dalam penerapan teknologi informasi yang bertujuan untuk membendung demokrasi. Bila Cina menggunakan penerapan teknologi canggih, Rusia mengarusutamakan penyebaran disinformasi sebagai cara untuk melemahkan demokrasi. Melihat pada apa terjadi belakangan ini, apa yang terjadi di Indonesia sedikit banyak merupakan gabungan cara-cara menyempitkan ruang demokrasi di mayantara.
Tiga indikator bagaimana otoritarisme digital terjadi di ranah mayantara Indonesia dapat dilihat dari praktik sensor daring, pengawasan digital, dan pemutusan internet yang terjadi cukup lama.
Maka kunci utama untuk dapat memulihkan ruang demokrasi agar makin menjauhi otoritarianisme digital adalah mengganti perspektif pendekatan terhadap teknologi informasi ini.
Pertama, mendekati kemajuan teknologi informasi ini bukan dengan pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan hanya menghasilkan pembatasan-pembatasan yang justru tidak mengembangkan demokrasi, tetapi alih-alih menghalang-halangi upaya warga untuk menyampaikan pendapat dan pikiran di ranah mayantara.
Tak dapat dipungkiri, yang terjadi adalah merebaknya ketakutan, justru bukan memanfaatkan ruang demokrasi yang telah diperluas di ranah mayantara ini. Sebagai ganti pendekatan keamanan, Indonesia dapat mengedepankan pendekatan hak asasi atau pemenuhan hak konstitusional warga.
Kedua, untuk menghadapi kebangkitan Otoritarianisme Digital di Indonesia, kelompok organisasi masyarakat sipil perlu senantiasa menguji regulasi-regulasi internet dan tindakan-tindakan yang membatasi hak digital lewat jalur hukum. Batu uji hukum internasional dapat digunakan untuk mematahkan jeruji yang terlanjur membatasi ruang gerak warga.
Karena itu, UU ITE yang memuat sejumlah pasal bermasalah perlu segera didorong agar direvisi oleh para pembuat kebijakan. Begitu pula dengan hukum-hukum yang selama ini dianggap menjadi batu sandungan demokrasi.
Ketiga, orientasi pengaturan di mayantara perlu berubah dan berpusat pada manusia (human-center approach), bukan berbasis pada teknologi informasi atau pada ekonomi digital yang selama ini perusahaan-perusahaan teknologi raksasa menjalankan surveillance marketing dengan cara melanggar hak-hak privasi warga.
Dengan menjalankan sejumlah rekomendasi ini, pemulihan ruang mayantara dapat berangsur-angsur mengembalikan demokrasi digital menjadi panggung bagi pelaksanaan demokrasi deliberatif yang memberi hak yang sama bagi setiap warga dalam mengembangkan Indonesia menuju negara yang maju.
Denpasar, 10 Januari 2022
* Dimuat dalam buku kumpulan tulisan Mata Air Indonesia Maju: Sebuah Bunga Rampai Tulisan Untuk Cak Imin, Gramedia, 2022
[1] Laporan Kwartal 2 tahun 2020 APJII https://apjii.or.id/content/read/39/521/Laporan-Survei-Internet-APJII-2019---2020-%5BQ2%5D
[2] The Economist Intelligence Unit, "Democracy Index 2020: In sickness and in health?", 2020
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H