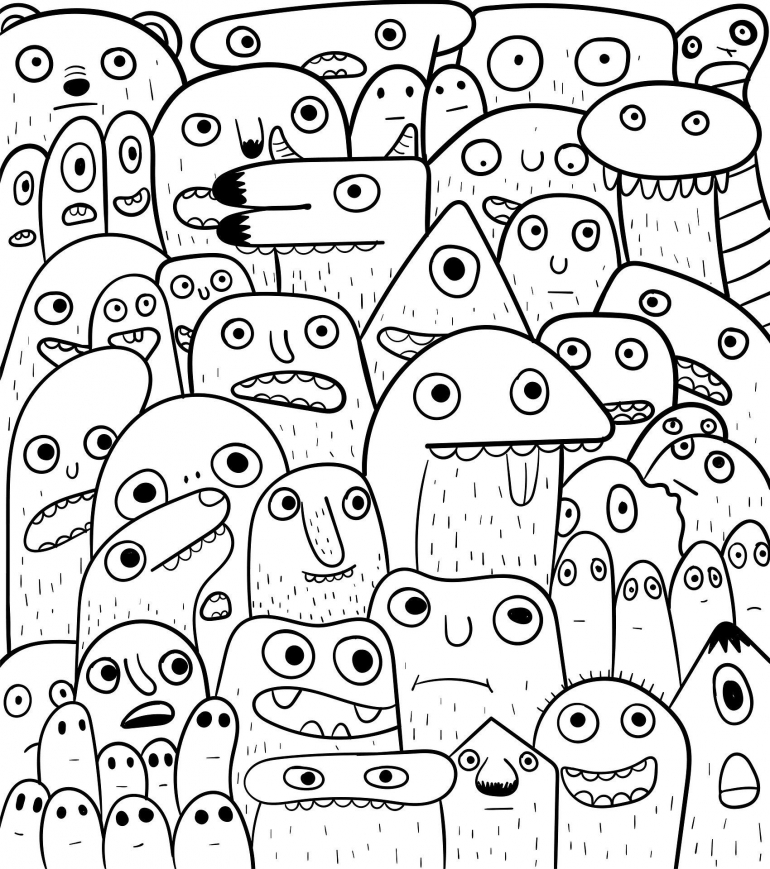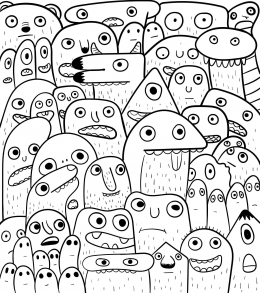Tangan kanan bergetar hebat. Berguncang tanpa kendali. Cairan merambati urat-urat, menembus batas atas. Deras.
Perasaan diperlakukan tidak benar memancur, menyala-nyala di dalam kepala. Pertentangan pendapat berderai-derai, memercikkan satu pertanyaan.
“Sebentar, sebentar! Jadi, kau tidak semufakat dengan usulan tadi?”
Lawan bicara pada telepon genggam seberang menyahut, “bukan begitu. Itu terlalu umum. Kita perlu men-deliver sebuah badan, semacam komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.”
Keterangan berikutnya disampaikan dengan terbata-bata. Saluran melalui aplikasi bertukar pesan tanpa pulsa itu memang kurang bagus. Saya menjawab dengan kata-kata singkat, hmmm, ooh, begitu ya, dan seterusnya.
Saya berusaha keras meredam emosi, agar tekanan darah –dalam arti sesungguhnya—tidak meninggi. Hipertensi adalah pemicu timbulnya penyakit kronis pada diri saya.
Itu membuat emosi mudah tergugah. Sensitif. Perasaan sangat mudah terpancing, kendati disebabkan oleh perihal sederhana. Tertawa tak tertahankan, bila ada sedikit saja hal lucu. Sedih berlebih, ketika trenyuh hati. Marah hebat, saat ada yang menyinggung perasaan.
Selanjutnya, saya tidak lagi melontarkan argumen kepada Gustavo.
Kawan sekolah itu sejak dulu senantiasa berdandan stylish, cenderung flamboyan, dan besar cakap. Gustavo memiliki selera tinggi, senang menjalankan gaya hidup berlebih, meniru-niru orang-orang yang berada di kelompok kaya. Tipikal orang pemanjat tangga sosial di awang-awang atau mengasosiasikan diri dengan social superiors.
Dus, seiring dengan itu ia kerap meremehkan lawan bicara yang dianggap lebih rendah dari padanya. Juga merasa dirinya lebih pintar, sehingga dalam banyak percakapan tidak mau kalah omong.
Saya mengenali kebiasaannya melembungkan dada. Bermegah dalam kata-kata dengan banyak keinginan muluk. Tidak mau mengembangkan usaha secara perlahan, konvensional, dan butuh perjuangan.
“Jangan mengusulkan business as usual! Buatlah grand design bombastis, menghasilkan uang banyak sekaligus.”
Ada selang waktu lumayan panjang Gustavo dan saya berada dalam sebuah institusi pekerjaan. Usulan untuk menjalankan sebuah usaha pemasokan, yang menurut hemat saya mampu mendatangkan pendapatan rutin, ditanggapi dengan mengangkat kepalanya.
“Kecil ya! Cuma seratus lima puluh juta per bulan.”
Ia demikian terobsesi kepada proyek pertama, dengan hasil enam koma satu miliar dalam tempo kurang dari dua tahun.
Lain waktu, menimbang bahwa kereta rel listrik sudah sedemikian bagus, tertib, dan rapi, berbeda keadaan pada waktu zaman rezim otoritarian berkuasa, saya mengusulkan strategi branding. Menggunakan gerbong KRL sebagai media placement bagi promosi produk-produk.
“Enggak mau. Begini, suatu ketika saya nongkrong bareng Dirut kereta. Gak bakalan terlihat deh! Gerbong terlalu cepat bergerak,” sergah Gustavo menciutkan nyali.
Akhirnya, saya bersusah-susah merakit sebuah rencana bagus tentang ekshibisi, berkaitan dengan perusahaan milik negara. Proyek itu berpotensi meraup keuntungan miliaran. Gustavo senang.
Ia memiliki akses kepada seorang menteri dan petinggi lainnya, katanya. Bermodalkan konsep keren dan koneksi bagus, ia merangkul kawannya sebagai penyandang dana.
Selebriti tersebut menyetor empat ratus juta rupiah. Mencatatkan bahagian empat puluh persen di dalam akta pendirian perusahaan. Sedangkan Gustavo menempati posisi pemegang saham mayoritas. Enam puluh persen!
Tidak sampai setengah tahun, kongsi tersebut bubar. Permodalan tergerus oleh gaji dewan direksi, manajer, dan operasional kantor di kawasan perkantoran elite. Ditambah pembiayaan untuk gaya hidup mewah Gustavo.
Saya merakit lagi rencana bisnis baru. Terpental. Lalu mereka-reka lagi rencana strategis anyar demi memenuhi kehendak Gustavo yang tidak sepenuhnya saya pahami. Ditolak lagi dengan rangkaian kata sepanjang rel kereta listrik.
Serasa empat ratus usulan dibuat, empat ratus kali pula ditolak.
Jalan buntu membuat saya membuka pintu keluar: mengucapkan akhirul kata kepada Gustavo. Demi merintis usaha baru, yaitu kegiatan mencari makan dengan menjalankan business as usual.
Lama. Lama sekali tak terdengar berita tentang Gustavo, sampai sebuah panggilan tak terjawab tertulis di layar telepon genggam. Segera saya memijit gambar telepon berwarna hijau, ”halo. Sori tadi gak keangkat. Ada berita apa nih?”
“Bagaimana kabarmu? Lama menghilang. Sibuk apa sekarang?”
“Di rumah saja. Jadi penulis. Tahulah penyakit yang saya derita.”
“Ya, ya, ya aku paham. Semoga lekas membaik.”
“Kunci pemulihan adalah semangat dalam diri kita.”
Selanjutnya, Gustavo menyampaikan nasihat dan rasa keprihatinan mendalam. Saya senang mendengar basa-basi panjangnya.
“Oh ya, kawan kita, Fauzi juga menderita penyakit sama denganmu.”
“Saya tahu. Gak sampai parah. Sempat dilarikan ke RS Gatot Subroto, sehingga penyumbatan dalam kepala segera diatasi.”
Gustavo berkata pelan, “sebetulnya, seusai tugas sebagai duta besar, Fauzi ditawari jabatan komisaris Perusahaan Negara Pembuat Perlengkapan Militer. Tapi ia menolak, merasa tidak elok sebab istrinya telah menjadi komisaris Bank Pelat Merah.”
Saya, “ooh. Terus?”
Gustavo bersemangat, “begini. Tadinya Fauzi menjabat sebagai wakil rakyat komisi I, bidang pertahanan dan luar negeri. Terus jadi Dubes. Pensiun gak jadi apa-apa. Hanya sebagai anggota Tim Sosialisasi Ciptaker ke masyarakat luar negeri. Cuman begitu saja. Kayak gak ada kerjaan.”
“Jadi, maumu bagaimana?”
Seperti biasa, Gustavo panjang lebar menerangkan latar belakang pemikirannya. Seperti biasa, saya mengiyakan.
Tidak seluruh perkataannya dapat saya mengerti. Ujung-ujungnya, Gustavo ingin 'memberikan pekerjaan' kepada Fauzi.
“Kita perlu men-deliver sebuah badan atau komite.”
“Oh, begitu. Kalau usulan saya, menyangkut perbaikan komunikasi politik. Selama ini saya memandang bahwa kebijakan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat awam, meski ada kementerian komunikasi. Artinya, substansi kebijakan tidak diutarakan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang banyak. Bahasa elitis untuk lapisan elite.”
Gustavo memotong, “terlalu umum. Usulkan komite spesifik, semacam komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.”
“Kasih saya waktu,” kepala mulai pening.
Percakapan melalui aplikasi bertukar pesan tanpa pulsa menghabiskan waktu empat puluh lima menit. Perbincangan pagi itu membuat kening berkerut.
Kali ini gaya hidup Gustavo berkembang pesat. Tingkatan pembicaraannya kian tinggi, mencapai kelompok atas yang tidak terjangkau oleh alam pikir saya. Pembicaraan mengenai negara.
Seharian saya berpikir keras, bahkan lebih keras dibanding ketika dalam proses menghasilkan sebuah artikel. Akhirnya, saya berhasil menelurkan gagasan dalam sebuah gambaran singkat. Kerangka pemikiran terdiri dari:
- Fenomena di masyarakat;
- Dukungan Keadaan;
- Realitas yang terjadi;
- Big Picture, yakni kehendak besar Presiden ketika dilantik;
- Hipotesis; Dan
- Konklusi berupa upaya-upaya mesti dilakukan. Ujung akhir merupakan pembentukan suatu lembaga sampiran, sesuai undang-undang berlaku (badan, komite, komisi, dan lain sebagainya).
Konsep tersebut segera saya kirimkan ke nomor telepon Gustavo. Masih contreng ganda berwarna abu-abu. Esok hari ketika ayam jantan berkokok, kendati matahari belum menguapkan embun pada dedaunan, Gustavo menelepon.
“Itu bagus, tapi terlalu umum. Kita perlu memberikan arahan kepada Fauzi. Kita juga mesti menyiapkan kendaraan, semacam komite. Begitu. Usulan kamu terlalu umum.”
Mendengar bahwa konsep saya diremehkan dan direndahkan, aliran darah merambat cepat ke kepala. Telapak, pergelangan, dan keseluruhan lengan kanan bergetar tidak terkendali.
“Itu dibuat berdasarkan kacamata masyarakat biasa. Hal lumrah yang dirasakan oleh man on the street.”
Gustavo menyela, “tapi bukan seperti itu yang diinginkan.”
“Maumu seperti apa?”
“Ya sesuatu yang bisa dibawa ke panel para petinggi politik. Dibuat dalam bahasa sophisticated. Ada komite. Contoh nyata: Jokowi menunjuk Luhut pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Seperti itu.”
Saya menjawab dengan kata-kata singkat, hmmm, ooh, begitu ya, dan seterusnya. Mengatur napas, berusaha keras meredam emosi, menahan tekanan darah tidak meninggi. Agar tidak kolaps lebih parah.
“Sebentar, sebentar! Jadi, kau tidak semufakat dengan usulan tadi?”
Suara Gustavo meninggi, “iya, bukan seperti itu! Mesti dibuat lebih konkret, sebagai kendaraan Fauzi ke tingkatan lebih tinggi.”
Sekali lagi saya menarik napas, berujar dengan sabar, “baiklah. Saat ini saya memang berada di persepsi orang biasa, berkeinginan merasakan hasil nyata dari produk politik. Saya tidak mampu lagi berpikir secara elitis. Maafkan saya. Terima kasih atas perhatian selama ini.”
Saya mengucapkan salam, lalu memijit gambar telepon berwarna merah pada layar telepon genggam. Kali ini saya tidak mau meladeni Gustavo yang snob.
Capek!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H