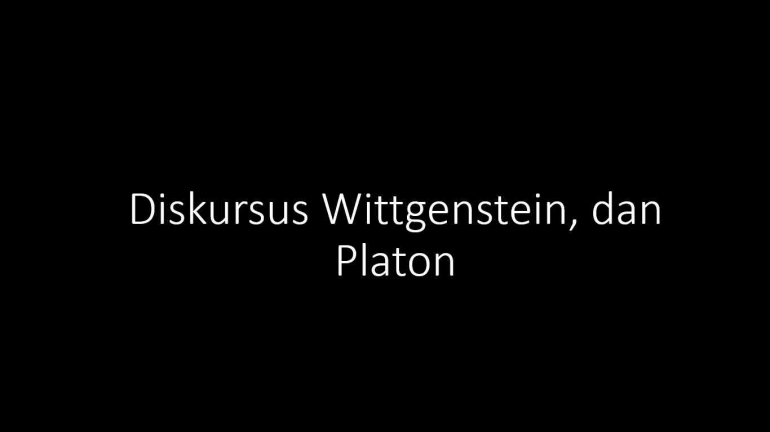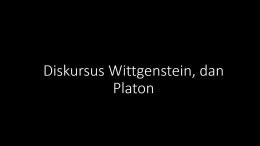Dengan demikian, dalam metafora, cita-cita religius dan sebagai cita-cita "spiritualitas murni" dibandingkan dengan cahaya putih, sedangkan cita-cita budaya yang berbeda dibandingkan dengan cahaya berwarna yang dihasilkan ketika cahaya murni bersinar melalui kaca berwarna merah. Dengan perbandingan ini saja, seni dan sains dikaitkan dengan ketidakjelasan dan ketidakjelasan, agama dengan spiritualitas dan kebenaran murni.
Selama zaman budaya ada dan mampu memberikan sesuatu kepada orang-orang, orang menganggapnya sebagai yang benar, yang mutlak - untuk itu cahaya tidak mengetahui budaya pada dasarnya hanyalah refleksi dari cahaya yang berdiri di atasnya, dari yang benar-benar spiritual. Orang-orang yang tetap berada dalam cahaya dengan budaya dan ilmu pengetahuan hampir tidak ada keinginan untuk cahaya yang murni dan mutlak.
Kesamaan dengan alegori gua Platon tidak salah lagi, di mana mereka yang tinggal di gua gelap yang belum pernah melihat cahaya siang tidak melewatkannya, melainkan menganggap pandangan hal-hal yang muncul dari keberadaan gelap mereka sebagai yang benar. Wittgenstein mentransfer perbedaan antara pengetahuan yang benar dan yang salah, atau antara kenyataan dan penampilan, pada perbedaan antara pandangan yang berhubungan dengan agama dan budaya: sementara orang yang berbudaya melihat dunia melalui cahaya merah jambu, orang yang religius melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. cahaya yang murni dan tidak berkabut.
Platon berbicara tentang berbagai cara orang memandang sesuatu, yang merupakan milik mereka, tergantung pada disposisi alami mereka. Perenungan mereka yang tinggal di gua-gua yang gelap mirip dengan orang-orang yang digambarkan oleh Wittgenstein, yang puas dengan seni dan sains dan karena itu hanya tinggal di bagian terbatas dari ruang yang sebenarnya. Hanya penglihatan cahaya yang memungkinkan segala sesuatu dikenali dalam kebenarannya, yang menunjukkan apa yang dapat diakses melalui perspektif yang lebih rendah hanya sebagai bayangan bayangan atau gambar arketipe.
Menurut Platon , cahaya hanya dapat mengenali jiwa ketika ia berpikir, setelah ia naik ke sudut pandang yang lebih tinggi dan mengenali dunia itu sendiri. Namun, pemandangan cahaya bisa begitu kuat sehingga penonton ingin melarikan diri lagi karena dia tidak tahan dengan cahaya itu. Wittgenstein menulis bagaimana beberapa orang yang mencoba menerobos guci bel menjulurkan kepalanya ke belakang. Dan entri buku harian dari akhir 1930-an menyatakan manusia normal tidak dapat bertahan melihat kesempurnaan, yang sesuai dengan penggambaran cahaya oleh Platon sebagai simbol gagasan gagasan atau gagasan tentang kebaikan - ketuhanan.
Dengan kedua pemikir tersebut, cahaya yang sebenarnya menurut Platon "ide tentang kebaikan" hanya dicapai dengan susah payah dan dengan mengatasi rintangan. Begitu seseorang melihat gagasan tentang yang baik, ia mengakui itu adalah "penyebab segala sesuatu yang benar dan indah untuk semua orang, menghasilkan cahaya tampak dan matahari yang menjadi sandarannya, tetapi yang terlihat itu sendiri sebagai penguasa. kebenaran dan Memproduksi akal, dan siapa pun yang ingin bertindak secara rasional, baik dalam urusannya sendiri atau dalam urusan publik, harus melihat ini" (teks pada Politeia, 517c) .
Dengan cara yang mirip dengan penamaan Platon n tentang gagasan tentang kebaikan sebagai tujuan tertinggi yang harus diperjuangkan manusia, Wittgenstein kadang-kadang menyamakan yang baik dan yang ilahi dan menganggap kesetaraan ini sebagai dasar etikanya.
Dalam metafora lonceng kaca, cahaya putih murni tidak hanya berarti religius, tetapi spiritualitas itu sendiri dan dapat dibandingkan dengan cahaya yang dijelaskan oleh Platon , yang hanya dapat dipahami dengan berpikir. Pemikiran ini, bagaimanapun, tidak diskursif, analitis, tetapi "mengamati" dan dapat ditugaskan ke "teori".
Yang baik bukanlah keberadaan, tetapi melampauinya (teks buku Republik Politea, 509b). Mirip dengan metafora Wittgenstein tentang lonceng kaca, cahaya murni sebagai simbol keilahian dan dengan demikian kebaikan mengalahkan semua nilai budaya dan dengan demikian semua pengetahuan berdasarkan sains.
Menurut Platon , banyak orang hanya bisa melihat makhluk dengan kesulitan, yang lain hidup dari penampilan tanpa melihat apa adanya. Dalam metaforanya tentang guci lonceng, Wittgenstein mengeluh kebanyakan orang puas dengan seni dan sains tanpa harus mendekati "cahaya murni". Melankolis dan humor, yang tidak ada hubungannya dengan kesedihan dan kebahagiaan, adalah konsekuensi yang menyerang orang-orang itu.
Yang diberi nama oleh Platon sesuai dengan "cahaya spiritual murni" di Wittgenstein, dan Platon menggambarkan keberadaan melalui metafora cahaya. Melalui kekuatan roh, "jiwa berbulu" mengapung di wilayah yang lebih tinggi dan dengan cara tertentu mencapai bagian dalam cahaya atau keilahian, yang diidentifikasi oleh Platon dengan yang indah, baik, dan bijaksana. Tidak ada penyair yang pernah bernyanyi tentang "ruang superheavenly" ini sebagaimana mestinya.