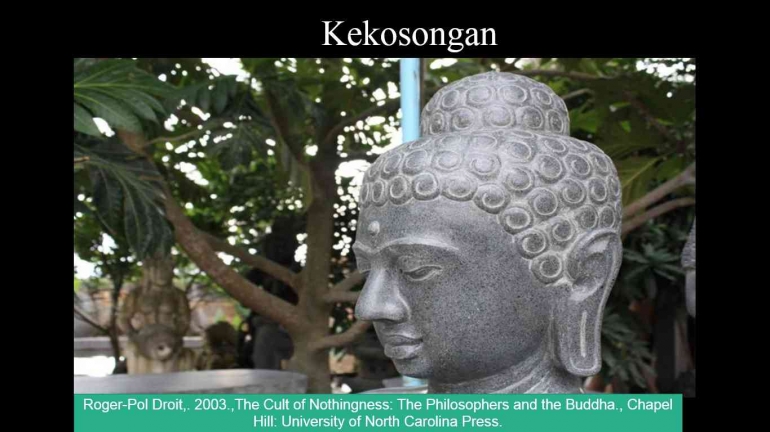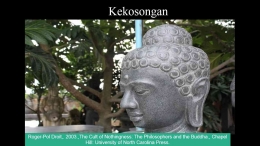Apa Itu Buddisme [22] Kekosongan
Ajaran Buddha saat ini menikmati, di negara-negara Barat, arus simpati tertentu. Lebih dari sekedar agama, sering dianggap sebagai filosofi yang menganjurkan detasemen tertentu dan berusaha untuk menyembuhkan dari semua siksaan yang disebabkan oleh keberadaan ; kebijaksanaan, dengan cara. Namun, abad ke-19 melihat, kadang-kadang dengan ngeri, doktrin Buddha sebagai ekspresi keinginan untuk penghancuran dan daya tarik untuk kehancuran. Apa yang sebenarnya menakutkan ! Bukankah Buddhisme merusak fondasi masyarakat dan moralitas?
Namun, secara bertahap, gambar Buddha diubah menjadi tampak lebih tidak berbahaya menjelang akhir abad terakhir, sebelum merayu orang-orang sezaman kita. Ini adalah pertama kalinya penerimaan Buddhisme ini, terutama dari tahun 1820 hingga 1890, yang diceritakan Roger-Pol Droit kaya dan jelas.
Pertama-tama harus diingat penemuan Barat tentang doktrin Buddha relatif baru. Akhir abad ke-18 melihat perkembangan studi India dan filologi Sansekerta, tetapi baru pada awal abad ke-19 kita dapat, dari terjemahan teks yang disebarluaskan di Asia, menyusun kembali ajaran Buddha. itu doktrin tertentu (kata "Buddhisme" hanya muncul sekitar tahun 1820). Sebelum ini, Sang Buddha dilihat sebagai berhala yang tidak jelas yang muncul dari "dunia primitif" dan secara membingungkan disamakan dengan dewa-dewa lain. Sekarang, seperti halnya India dan Brahmanisme telah mempesona dan menarik Barat yang romantis, demikian pula Buddhisme, setelah "penemuannya", tampak mengerikan dan menimbulkan kekhawatiran.
Di Jerman, Hegel (1770-1831), yang pertama, yang mendefinisikan Buddhisme sebagai agama di mana manusia harus menjadi bukan apa-apa untuk kembali ke ketiadaan yang darinya segala sesuatu akan datang. Namun para ahli dari Timur telah memperingatkan terhadap interpretasi semacam itu dengan menekankan perbedaan antara nirvna , yang diterjemahkan sebagai "ketenangan yang dalam", dan pemusnahan. Tetapi bagi Hegel, asosiasi Buddhisme dan ketiadaan tidak sepenuhnya negatif, karena dalam sistemnya ketiadaan adalah setara dengan "Keberadaan murni", dari Menjadi bebas dari semua tekad.
Oleh karena itu tidak ada pertanyaan di sini untuk menjadikan ketiadaan sebagai lawan mutlak dari Wujud, tetapi mengidentifikasinya dengan Wujud yang tidak terbatas. Akibatnya, agama Buddha : Tuhan jelas bukan apa-apa, tetapi dalam arti Dia adalah Wujud yang mutlak tak tentu. Jadi, Buddhisme sama sekali tidak mewakili di matanya pemusnahan semua yang ada. Namun, dalam pengertian inilah kata-kata filsuf, terlepas dari konteksnya, akan ditafsirkan.
Di Prancis, dari karya-karya Eugene Burnouf (1801-1852), ketakutan agama Buddha benar-benar dimulai. Namun, sarjana yang memiliki studi Buddhis yang sangat maju ini tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi setelahnya. Analisisnya tentang agama Buddha tentu saja condong ke arah tesis tentang pemujaan kehampaan. Tapi kata-katanya terukur : itu meninggalkan ruang untuk kehati-hatian dan menyerukan studi yang lebih mendalam.
Namun, peringatan ini tidak dihormati dan Sang Buddha melihat dirinya diubah oleh para pembacanya menjadi orang-orangan sawah nihilistik. Kami kemudian menyaksikan protes nyata terhadap "ancaman" timur ini. Agama Buddha dibebani dengan kesalahan yang mengerikan, agama yang menjijikkan, doktrin yang tidak masuk akal, dan sistem yang mengerikan... Tidak ada hinaan yang luput darinya. Dengan mengidentifikasi Buddha dengan Setan, umat Katolik bahkan meyakinkan diri mereka sendiri tentang perlunya kembali untuk menginjili Timur ini yang kultus ketiadaannya menentang semua akal sehat dan berisiko merusak fondasi masyarakat.
Filsuf Victor Cousin (1792-1867), salah satu yang paling berpengaruh, yang menciptakan ungkapan "kultus kehampaan" untuk menunjuk agama Buddha. Dia adalah salah satu orang pertama yang diyakinkan tentang keberadaan teks-teks filosofis sejati di India. Oleh karena itu, seseorang mungkin mengharapkan sambutan yang lebih hangat terhadap agama Buddha darinya. Tetapi gagasan pemusnahan mengganggunya. Tidak dapat dimengerti baginya seseorang dapat memiliki satu-satunya tujuan untuk menjadi tidak lebih.
Hasrat atau keinginan tidak bisa menginginkan penindasannya sendiri. Jadi, terlepas dari ketertarikannya pada filosofi Timur, dia tidak pernah berhenti mengutuk "anti-agama" yang ada di matanya sebagai Buddhisme. Muridnya, Barthelemy Saint-Hilaire, tokoh besar lainnya di Universitas Prancis, mengikutinya dalam kecaman ini. Pada saat yang sama yakin agama Buddha hanyalah kultus kehampaan dan seorang manusia tidak dapat menginginkan kehampaan, ia mempertanyakan kepemilikan umat Buddha dalam spesies manusia. !
Pemikir Arthur de Gobineau (1816-1882) tidak ketinggalan membuat pemikirannya. Untuk yang terakhir, pencampuran ras dengan kawin silang melahirkan degenerasi ras superior dan mau tidak mau membawa umat manusia ke ketiadaan. Namun, di matanya, umat Buddha tidak hanya ingin menekan kasta Brahmana, tetapi mengusulkan untuk memusnahkan struktur hierarki apa pun dalam masyarakat. Jadi agama Buddha menambahkan kehampaan rasial di masa depan ancaman kehampaan sosial.
Dihadapkan dengan penolakan umum terhadap agama Buddha pada paruh pertama abad ke-19, berdirilah sosok Arthur Schopenhauer (1788-1860). Jauh dari melihat dalam doktrin Sang Buddha apa pun selain kultus kehampaan, yang terakhir memujinya justru karena menganjurkan kultus semacam itu. Sebab, bagi seorang pesimis seperti Schopenhauer, keinginan untuk hidup masing-masing dari kita tidak masuk akal dan hanya bisa membawa penderitaan : selalu menimbulkan kebutuhan baru yang tidak pernah bisa dipenuhi sepenuhnya. Inilah sebabnya mengapa ia menganggap perlu untuk melepaskan keinginan untuk memperpanjang kehidupan dan dengan demikian menemukan dalam agama Buddha tema-tema tertentu dari filosofi pesimisnya.
Jika, selama masa hidup Schopenhauer, hanya sedikit orang yang tidak ditakuti oleh agama Buddha, tahun-tahun setelah kematiannya (tahun 1860) melihat citra agama Timur ini secara bertahap menjadi lebih tidak menyinggung. Bagi Hippolyte Taine (1828-1895), misalnya, tidak ada yang menakutkan tentang agama Buddha. Tentu saja, di matanya, memang ada kultus kehampaan, tetapi agama ini dicirikan terutama oleh belas kasihnya. Pembacaan ini inovatif, karena memungkinkan pemulihan hubungan dengan Kekristenan, bahkan jika cinta Kristen tampak baginya "lebih terukur dan lebih sehat".
Apresiasinya terhadap agama Buddha tetap paradoks : jika dia melihat di dalamnya faktor kedamaian dan ketenangan, itu Nietzsche (1844-1900) menganggap agama Buddha kurang maksimal mendukung perkembangan daya kreatif individu.
Namun, bagi filosof ini, justru terserah kepada setiap orang untuk mengembangkan daya kreatifnya. Ini melibatkan mengatakan "ya" untuk hidup dalam totalitasnya, termasuk rasa sakit. Jadi tidak ada pertanyaan tentang lebih memilih kemalasan daripada tindakan, perdamaian daripada konflik atau penolakan semangat penaklukan. Karena itu, bagi Nietzsche, Buddhisme hanya bisa tampak sebagai tanda kelemahan. Tentu saja, itu tidak untuk dikutuk sepenuhnya : sebuah doktrin yang tidak berbicara tentang yang melampaui dan tentang transendensi menunjukkan banyak kejernihan. Faktanya tetap di mata Buddhisme Nietzsche, seperti halnya Kekristenan, adalah usaha negasi kehidupan. Jadi dia menyesal kami berada di bawah pengaruhnya.
Pada akhir abad ke-19, beberapa penulis, yang dipengaruhi oleh Schopenhauer, membuka diri terhadap ajaran Buddha. Diambil oleh melankolis, mereka menemukan diri mereka dalam doktrin ini yang menganjurkan penolakan tertentu dalam menghadapi kehidupan. Buddhisme kehilangan sosoknya yang menakutkan. Kami bahkan melupakan ketiadaan. Kemudian, studi ilmiah berkembang dengan baik, tidak ada yang melihat agama Buddha sebagai kultus kehampaan. Abad ke-19 akhirnya berhenti takut..
Di sini, digambarkan dengan sangat ringkas, artikulasi utama dari konstitusi "Buddhisme imajiner" ini sebagaimana dilacak kepada kita secara rinci oleh Roger-Pol Droit dalam buku yang sangat instruktif ini. Eropa tidak segera memahami agama Buddha bukanlah pemusnahan jiwa, tetapi ketenangannya yang dalam, sikap apatisnya yang sempurna. Dia bingung keheningan dan negasi, suspensi dan penolakan, atau bahkan abstain dan kehancuran. Kecuali, seperti yang disarankan Roger-Pol Droit dalam kesimpulannya, dia tidak ingin mengerti.
Lagi pula, bukankah citra Buddhisme ini adalah citra yang diberikan Eropa pada dirinya sendiri tanpa mengakuinya? Apa yang dia takutkan adalah pembubarannya sendiri. Dia melihat dirinya menjadi masyarakat tanpa Tuhan, tanpa kelas, tanpa energi vital. Bayangan kekacauannya sendiri menghantuinya. Jadi dia mencoba menangkal kekuatan negatif yang menyiksanya dengan menciptakan ajaran Buddha yang sepadan dengan fobianya.
Pada akhir abad kedelapan belas, terjemahan-terjemahan baru teks-teks India menarik perhatian para intelektual Eropa, memunculkan harapan akan Renaisans lain yang lebih besar daripada yang dihasilkan dari penemuan kembali teks-teks Yunani pada akhir abad pertengahan. Tapi itu tidak pernah terjadi. Sekitar tahun 1820, ketika penelitian ilmiah pertama kali mengklarifikasi perbedaan dari Brahmanisme, "Buddhisme" menjadi dibangun sebagai agama yang, secara menakjubkan, memuja ketiadaan, dan komentator Eropa bereaksi dengan sikap luar biasa.
Sekali lagi Buku Roger-Pol Droit,. 2003.,The Cult of Nothingness: The Philosophers and the Buddha dimana ada "Hipotesis yang paling masuk akal adalah ada sesuatu tentang praktik Buddhis yang teliti yang menghasilkan jenis kebahagiaan yang manusia semua mencarinya.
Hasil ilmiah seperti itu menunjukkan persepsi yang agak berbeda tentang agama Buddha daripada pemahaman yang membuat ngeri orang Barat di sebagian besar abad kesembilan belas. Agama Buddha saat ini biasanya dilihat sebagai semacam terapi pragmatis yang menyembuhkan atau mengurangi penderitaan, tetapi dari sekitar tahun 1820 hingga 1890-periode fokus untuk buku Droit--Eropa dihantui oleh mimpi buruk agama alternatif yang menyangkal keberadaan dan merekomendasikan pemusnahan
Tema buddha dan kultus Ketiadaan merangkum dan menganalisis sejarah (salah) pemahaman ini. Dia menyimpulkan itu tidak ada hubungannya dengan keadaan dasar studi Buddhis selama periode itu daripada dengan ketakutan Eropa tentang nihilisme yang baru mulai, yang kemudian akan matang menjadi kengerian abad kedua puluh. "Mengira mereka sedang membicarakan Sang Buddha, orang Barat sedang membicarakan diri mereka sendiri".
Agama Buddha lebih cocok dengan persamaannya tentang Wujud murni dengan Ketiadaan murni. Dalam sistem Hegel persamaan ini menandakan munculnya interioritas, "kurangnya tekad" yang tidak benar-benar ateistik atau nihilistik dalam pengertian modern- lebih seperti teologi negatif mistik buku l'histoire du Buddhisme indien (1844) sangat berpengaruh karena memberikan studi pertama yang ketat tentang ajaran Buddha, sehingga membawa studi Buddhis ke tingkat kecanggihan baru, tetapi yang dengan kuat menetapkan momok nihilistik: meskipun membuat kualifikasi yang hati-hati karena pengetahuan Barat yang masih terbatas, Burnouf tidak segan-segan menyamakan nirwana dengan pemusnahan total.
Teks-teks Sanskerta layak mendapat perhatian filosofis Barat, bagaimanapun mengikuti dalam bereaksi terhadap sistem Buddhis. Schopenhauer menemukan dalam Buddhisme banyak tema favoritnya - penolakan, welas asih, negasi dari keinginan untuk hidup tetapi relatif terlambat membuat diskursusnya. Namun, aneksasinya terhadap prinsip-prinsip Buddhis membawa tantangan Buddhis kembali ke Eropa, dari konversi misionaris hingga menangkal nihilisme yang tumbuh di dalam negeri. Namun, sebagai filsuf, Schopenhauer berhati-hati untuk mengatakan nirwana hanya bisa menjadi ketiadaan "bagi kita", karena sudut pandang keberadaan kita sendiri tidak memungkinkan untuk mengatakan apa-apa lagi tentangnya.
Pemahaman nihilistik tentang Buddhisme memiliki dampak signifikan pada Essay on the Inequality of the Human Races (1853) karya Arthur de Gobineau, yang akan menjadi sangat berpengaruh bagi Nazi dan rasis abad kedua puluh lainnya. Bagi Gobineau, umat manusia bergegas menuju kebinasaan dan kehampaan karena degenerasi yang disebabkan oleh percampuran ras. Dia memandang agama Buddha sebagai upaya orang-orang yang lebih rendah untuk menggulingkan para Brahmana Arya yang secara ras lebih unggul. Kegagalan upaya ini - fakta agama Buddha sebagian besar dihilangkan dari India - agak tidak konsisten dengan pesimisme historisnya sendiri, yang menerima kemunduran yang tak terhindarkan; tetapi mungkin telah mendorong Nazi untuk mencoba program pemusnahan mereka sendiri demi kemurnian ras.
Nietzsche menerima pandangan Buddhisme sebagai cita-cita kehampaan, meskipun baginya itu adalah kesamaan dengan Kekristenan, bukan perbedaan, itulah masalahnya. Terlepas dari nilai Buddhisme yang tidak diragukan orang barat sebagai cara hidup yang moderat dan higienis yang menyangkal transendensi dan memandang dunia dari perspektif psikologis dan fisiologis yang lebih ketat, pada akhirnya pilihannya adalah antara Buddhisme, Schopenhauer, India, kelemahan, dan ketidakaktifan yang damai, atau kekuatan, konflik Eropa, rasa sakit, dan tragedi. Penyebaran agama Buddha di Eropa sangat disayangkan, Nietzsche percaya, karena "Nostalgia untuk ketiadaan adalah negasi dari kebijaksanaan tragis, kebalikannya".
Sekitar tahun 1864 pandangan pemusnahan terhadap agama Buddha mulai menurun. Carl F. Koppen's The Religion of the Buddha (1857-59), sangat berpengaruh pada tahun 1860-an dan 70-an, menekankan revolusi etika Buddha, yang menegaskan pembebasan manusia dan menyatakan kesetaraan manusia. Meskipun ketertarikan sastra dengan pemujaan terhadap ketiadaan terus berlanjut, pada awal tahun 1890-an penekanannya adalah pada agama Buddha sebagai jalan pengetahuan dan kebijaksanaan, pandangan "neo-Buddha".
Di tempat apologetika Kristen, ada kecenderungan yang berkembang untuk menganggap agama-agama yang berbeda sebagai konvergen, seperti yang dikatakan Vivekananda di Parlemen Agama Dunia tahun 1893 (walaupun di tempat lain ia membayangkan agama Buddha bertanggung jawab atas berbagai kemerosotan spiritual). Seperti yang diringkas Droit: "Pemujaan kehampaan telah berakhir; Waktu perang akan segera tiba. Pemujaan kehampaan lainnya telah dimulai".
Dia berpendapat secara persuasif masalah yang dipertaruhkan selalu identitas Eropa sendiri. Dengan "Buddhisme" Eropa membangun sebuah cermin di mana ia tidak berani mengenali dirinya sendiri. Di sini mungkin Droit dapat memperkuat kasusnya dengan lebih banyak refleksi tentang Darwin, kematian Tuhan, dan harapan/ketakutan Eropa sendiri akan agama Akal tanpa transendensi.
"Ketika pertanyaan tentang Buddha muncul, itu adalah ateisme orang Eropa yang benar-benar dipertanyakan. Tidak ada yang benar-benar percaya, dan hampir tidak ada yang pernah mengatakan, kepercayaan umat Buddha di belahan dunia lain sedang pergi. datang dan mendatangkan malapetaka di antara jiwa-jiwa Barat. Itu bukanlah pertobatan, korosi, 'kontaminasi' dalam bentuk apa pun yang mengancam, yang datang dari luar. Di Eropa sendirilah musuh, dan bahaya, berada untuk ditemukan.
Hal ini bukan hanya ancaman terhadap fondasi sistem kepercayaan pribadi seseorang, tetapi tantangan yang mengancam untuk tatanan sosial. "Ketiadaan keteraturan berhubungan dengan ketiadaan keberadaan. Sekali lagi, ketiadaan ini tidak setara dengan ketiadaan yang murni dan yang paling sederhana. Bisa jadi hal membatalkan dan mengacaukan. Mungkin bisa atau tidak ia berbahaya karena ia hancur, ia meratakan, ia menghasut anarki".
Tragisnya, penurunan pandangan nihilistik Buddhisme disertai dengan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari nihilisme yang lebih aktif di abad berikutnya, dengan lebih dari seratus juta orang tewas perang, dua pertiga di antaranya sipil non-pejuang.
Mungkin budaya barat memandang Buddhisme telah menjadi jenis terapi pragmatis dan non-metafisik yang mengurangi penderitaan. Tetapi seberapa yakinkah kita tentang pandangan ini, mengingat seberapa baik pandangan itu mencerminkan pemahaman diri pragmatis, anti-metafisika, terapeutik Barat postmodern sendiri?
Jika manusia tidak dapat melompati bayangan kita sendiri, haruskah manusia menyerah pada "salah tafsir" terhadap agama Buddha yang selalu mencerminkan prasangka kita sendiri? Atau apakah "Buddhisme" lebih baik dipahami sebagai sejarah interpretasi yang masih berlanjut? Interpretasi yang harus mencerminkan prasangka kita karena mencerminkan kebutuhan kita sendiri.
Citasi: Roger-Pol Droit,. 2003.,The Cult of Nothingness: The Philosophers and the Buddha., Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H