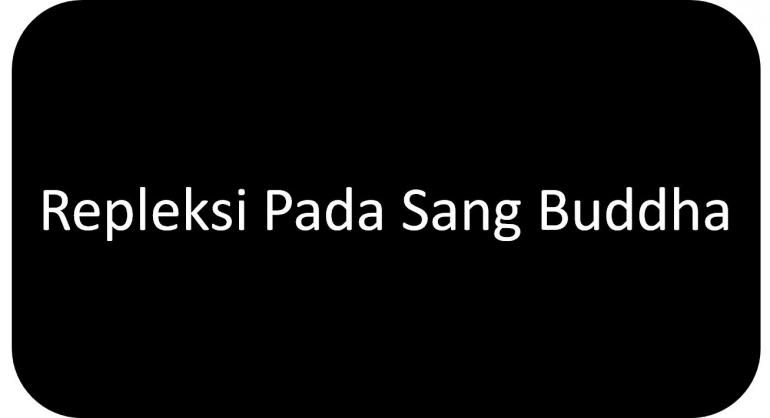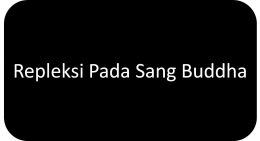Repleksi Pada Sang Buddha
Segala sesuatu yang tunduk pada asal mula tunduk pada pembubaran," memperingatkan Sang Buddha, dengan penuh wawasan menaungi Hukum Kedua Termodinamika (kecenderungan yang tak terhindarkan dari suatu sistem menuju kekacauan) dengan cara yang kesederhanaannya akan mengesankan bahkan seorang fisikawan modern sekalipun.
Hukum anitya ini, atau 'ketidakkekalan', menyatakan semua keberadaan kontingen bersifat sementara. Segala sesuatu dalam keadaan fluks yang tak berkesudahan, terus-menerus berubah menjadi sesuatu yang lain, membusuk dan menata ulang secara kekal, dan tidak ada yang bertahan selamanya.
Objek material hanyalah konfigurasi sesaat dari sebab, efek, bagian, proses, kondisi, bentuk, nama, fungsi. Konfigurasi ulang secara terus-menerus, tidak ada yang dalam kondisi persis seperti di instan sebelumnya. Tidak ada yang statis, apalagi yang permanen, yang tak dapat dibatalkan terlibat dalam tarian menggoda yang tak berkesudahan, sebuah proses evolusi tanpa batas yang tidak pernah mengarah pada makhluk yang tidak berubah.
Meskipun keinginan yang kuat memaksa manusia untuk melihat kenyataan sebagai stabil, ketidakkekalan tetap ada, tanpa ampun mengirimkan pembunuh waktu untuk mengambil semua hal. Seperti yang dinyatakan dalam epigram Heraclitean populer, perubahan adalah satu-satunya yang konstan.
Doktrin Buddhis tentang ketidakkekalan tidak boleh disalahartikan sebagai nihilisme. Keberadaan dunia itu sendiri tidak dipertanyakan; tetapi karena metamorfosis protean konstan dari kosmos, hukum anitya menjadikan tidak mungkin akurat dan abadi, dan dengan demikian deskripsi yang bermakna tentang fenomena individu.
Sebuah ilusi disulap ketika manusia mengambil 'foto' dunia sesaat, yang secara keliru menyarankan kontinuitas bentuk dan esensi, padahal sebenarnya satu-satunya kontinuitas adalah proses perubahan kaleidoskopik. Begitu manusia menganalisis sesuatu, merumuskan uraian verbal atau representasi mental darinya, waktu telah membatalkan konseptualisasi phantasmic ini.
Dengan demikian, deskripsi atau label tidak menangkap sepenggal kenyataan yang bermakna, melainkan memaksakan distorsi pada pandangan dan pemahaman manusia tentang proses tersebut. Dunia seperti yang manusia kenal atau seperti yang manusia pikir manusia tahu - sedikit lebih dari penyederhanaan yang tersimpan dalam ingatan manusia yang keliru - sebuah lukisan yang secara ideal berusaha menangkap kemiripan keabadian dari yang fana, jika hanya untuk sesaat.
Pengetahuan, oleh karena itu, adalah perbendaharaan perkiraan konseptualisasi kami: sebuah album foto yang berisi representasi realitas kami, semuanya ketinggalan jaman. Kebijaksanaan, sebaliknya, tidak berasal dari pengetahuan tentang keadaan tertentu, melainkan dari pemahaman tentang proses perubahan.
Hukum Buddha tentang ketidakkekalan ada di mana-mana, mengatur semua skala keberadaan: molekul, geologis, dan bahkan kosmologis. Pada waktunya, lautan yang kuat menghancurkan batu-batu adamantine menjadi pasir terbaik; sungai halus menorehkan ngarai jauh ke dalam kerak bumi. Bahkan raksasa Himalaya tidak kebal terhadap efek anitya , layu satu milimeter setiap tahun, tidak mampu menahan abrasi elemen yang tak kenal lelah.
Dengan cara ini barisan gunung berubah menjadi tanah, menjadi makanan bagi tumbuh-tumbuhan, yang merupakan makanan herbivora, yang kemudian dikonsumsi oleh predator semuanya akan binasa, akhirnya kembali ke sumbernya, diserap kembali oleh tanaman dan direinkarnasi sebagai tumbuh-tumbuhan sekaligus lagi, selamanya berpartisipasi dalam siklus pertumbuhan.
Mumi sufi abad ke-13 Rumi secara puitis merenungkan implikasi eksistensial dari proses ini: Saya mati sebagai mineral dan menjadi tanaman, Saya mati sebagai tanaman dan bangkit menjadi binatang, Saya mati sebagai binatang dan saya adalah manusia. Mengapa saya harus takut? Kapan aku kurang mati?
Tetapi bahkan matahari kita, penyedia energi yang menopang siklus ini, pada akhirnya akan menghabiskan bahan bakar nuklirnya, mengakhiri proses regenerasi. Dan bintang-bintang yang lebih besar menunggu nasib yang lebih spektakuler, mendingin dan dengan cepat runtuh pada diri mereka sendiri hanya untuk meledak sebagai supernova, tanpa pamrih mendistribusikan daging mereka ke dalam kekosongan ruang, tanpa ragu menghasilkan elemen-elemen berat yang pada akhirnya akan melahirkan lebih banyak planet, asteroid dan nebula.
"Seorang anak di dalam rahim," tulis Kahlil Gibran, "tidak lama setelah lahir daripada kembali ke bumi - begitulah nasib manusia, nasib bangsa-bangsa dan matahari, bulan, dan bintang-bintang." para Daois dengan sungguh-sungguh menegaskan, apakah manusia hidup di "dunia debu" di mana semua orang pada akhirnya akan hancur dan meledak menuju ketiadaan. Seperti yang dikatakan oleh Guru (Yesus) dalam Injil Maria Magdalena : "Semua yang dilahirkan, semua yang diciptakan, semua yang tersusun, akan terurai." Sutra Intan Buddha menawarkan meditasi yang penuh pemikiran ini:
Dengan demikian kamu akan memikirkan semua dunia yang singkat ini, Bintang saat fajar, gelembung di sungai, Kilatan petir di awan musim panas: Lampu yang berkedip-kedip, hantu, dan mimpi.
Tetapi perenungan kesembilan seperti itu menakutkan kita, karena manusia menyadari manusia tunduk pada hukum anitya yang tak kenal ampun. Dengan realisasi mengerikan dari kerentanan manusia ini, hidup menjadi tidak nyaman, tidak nyaman, karena membawa ke permukaan suatu kebenaran yang manusia semua kenal: fakta mengerikan segala yang telah manusia peroleh dan peroleh dan capai, semua harta manusia yang berharga, manusia berhala material dan artefak, semua orang yang manusia kenal, hubungan manusia yang paling intim dan dihargai, semua orang yang manusia cintai bahkan diri manusia sendiri pasti akan menyerah pada waktu, akan memburuk, larut, berakhir, berhenti, lenyap, binasa, mati. Manusia semua sangat mengenal pengetahuan hidup itu rapuh dan terbatas, keberadaan yang berharga hanyalah kilatan kilat, sebuah mimpi:
"Seperti tetesan embun di ujung rumput akan cepat lenyap saat matahari terbit dan tidak akan bertahan lama; demikian pula kehidupan manusia seperti setetes embun. Ini pendek, terbatas, dan singkat; itu penuh dengan penderitaan, penuh kesengsaraan ... tidak seorang pun yang dilahirkan dapat lolos dari maut. "(Bhikkhu Bodhi, Dalam Kata-Kata Sang Buddha)
Di sini, di Anguttara Nikaya , Sang Buddha dengan terang-terangan menggambarkan keadaan universal dengan sentimen yang mengingatkan manusia pada Thomas Hobbes, yang dalam perayaannya Leviathan menyatakan kehidupan manusia sebagai "soliter, miskin, jahat, kasar dan pendek ." Demikian pula saudara lelaki dari Nabi Isa bertanya, "Apa hidupmu? Kamu hanyalah kabut yang muncul sebentar dan kemudian lenyap "( Injil Nasrani Yakobus 4:14).
Jelas, masalah ketidakkekalan bukanlah hal baru. Sifatnya yang tak henti-hentinya menonjol dalam literatur yang mencapai lebih dari tiga milenium, seperti yang manusia lihat dari ratapan Utnapishtim dalam Epik Babilonia kuno Gilgames: Tetapi hidup manusia itu singkat; setiap saat
itu bisa patah, seperti buluh di canebrake. Pria muda yang tampan, wanita muda yang cantik di masa jayanya, kematian datang dan menyeret mereka pergi. Padahal tidak ada yang melihat wajah kematian atau mendengar suara kematian, tiba-tiba, kejam, kematian menghancurkan kita, manusia semua, tua atau muda.
"Bagaimana manusia bisa merasa aman," seru Ashvagosha dalam Buddhacharita , "ketika dari rahim dan seterusnya kematian mengikuti manusia seperti seorang pembunuh dengan pedang terangkat?"
Dan dengan demikian manusia menemukan diri manusia diperbudak, tanpa ampun disiksa oleh kenyataan kejam yang tidak ada yang abadi : "Seseorang harus mati .Makhluk rasional apa, yang tahu tentang usia tua, kematian dan penyakit, dapat berdiri atau duduk dengan tenang atau tidurnya, jauh lebih sedikit tertawa; Mengingat dunia ini sementara, pikiranku tidak dapat menemukan kesenangan dalam [hedonisme], Usia tua, penyakit, dan kematian jika hal-hal ini tidak ada, saya harus menemukan kesenangan saya pada benda-benda yang menyenangkan pikiran.
Kesendirian ini mengabadikan mungkin penyelidikan eksistensial yang paling bertanggung jawab atas perjalanan filosofis Buddha yang sulit. Apa yang bisa lebih menantang secara eksistensial untuk dihadapi daripada kematian - untuk mengakui setiap makhluk hidup dalam proses kematian yang seketika itu lahir? Hidup adalah perjalanan satu arah yang naas menuju pelenyapan takdir yang tak terhindarkan ditangkap dengan suram dalam ringkasan Heidegger tentang kondisi manusia sebagai kematian .
Kefanaan dan kefanaan adalah iblis-iblis yang tidak memiliki belas kasihan yang terus-menerus melecehkan dan membuat trauma jiwa. Mereka adalah masalah mendasar kembar dari kondisi manusia, karena manusia tahu tidak hanya suatu hari kehidupan akan tiba-tiba terhenti secara tidak resmi, tetapi manusia tidak dapat mencapai kesenangan atau keamanan permanen dalam kehidupan.
Dengan cara ini penderitaan manusia saat ini, bukan hanya kefanaan kita, tidak dapat dilepaskan dengan hukum ketidakkekalan, karena bahkan ketika manusia membenamkan diri dalam kesenangan saat euforia, imajinasi manusia mengintip ke masa depan, yang menghasilkan kecemasan (bahkan jika hanya halus atau tidak sadar) merampok manusia dari kesenangan intrinsik manusia di sini dan sekarang dengan mengejek manusia dengan ancaman transformasi yang selalu ada.
Mengatakan anitya mengilhami hidup dengan penderitaan bukanlah sama dengan menyatakan setiap segi kehidupan atau setiap pengalaman manusia menyedihkan.
Agama Buddha dengan mudah mengakui hidup ini penuh dengan kesenangan dan kesenangan dari keanekaragaman yang tak terbatas. Sebaliknya, doktrin Sang Buddha menjelaskan penderitaan tidak dapat dihindari muncul ketika manusia menggunakan keinginan manusia dalam upaya untuk mengabaikan atau meniadakan anitya ,
Dia mengatakan kemampuan manusia untuk mengekstrak kenikmatan dari saat ini sangat dilemahkan karena manusia terlalu terbebani dengan perjuangan manusia untuk memahami dan berpegang teguh pada hal-hal, kewalahan dengan upaya kompulsif manusia untuk menimbun semua yang manusia hargai, sudah khawatir kehilangan apa yang baru saja manusia dapatkan . Seperti yang diminta oleh Kahlil Gibran, "Untuk apa harta milik Anda selain barang-barang yang Anda simpan dan jaga karena takut Anda mungkin membutuhkannya besok?"
William Blake menulis dalam The Marriage of Heaven and Hell: Raungan singa, raungan serigala, amukan lautan badai, dan pedang yang merusak, adalah bagian keabadian yang terlalu besar untuk mata manusia.
Kami hanya tidak mampu berurusan dengan kekejaman realitas, Blake menyimpulkan; dan karena itu kami terlibat dalam pemberontakan Sisyphean, perjuangan sia-sia namun abadi untuk melawan ketidakkekalan: sebuah Wille zur Macht , sebagaimana Friedrich Nietzsche menyebutnya - sebuah 'keinginan untuk berkuasa'.
Keinginan untuk berkuasa adalah dorongan tak tertahankan untuk secara aktif menguasai lingkungan manusia dengan memaksakan ketertiban dan keabadian yang mementingkan diri sendiri meskipun perintah yang kondisional, dan oleh karena itu ilusi.
Filsuf dan sejarawan Prancis abad ke-20 Michel Foucault setuju dengan penilaian terakhir ini, melihat keinginan untuk berkuasa sebagai dorongan untuk membuat kekekalan menjadi permanen: kecenderungan putus asa dan menyedihkan untuk berpegang teguh dan menangkap perubahan atau kehilangan yang akan membuat manusia menderita.
Sementara Nietzsche mengidentifikasi keinginan untuk berkuasa sebagai penggerak utama yang mendasari semua usaha manusia, psikolog Alfred Adler seperti halnya Buddha sebaliknya mengimplikasikannya sebagai dorongan neurotik yang dihasilkan dari rasa rendah diri dan ketidakberdayaan yang ditimbulkan dari tinggal di alam semesta di luar kendali kita, di mana waktu perlahan tapi pasti menghancurkan semua.
Memahami ketidakkekalan dan hubungan emosional dan eksistensial manusia dengannya adalah langkah penting dalam membebaskan diri manusia dari siklus penderitaan yang tampaknya tak berkesudahan.
Dengan keras kepala menolak untuk menghadapi anitya bukanlah pilihan yang layak: taktik ini tidak akan meniadakan kebenaran ketidakkekalan, dan dalam penundaan kita, manusia hanya akan menemukan diri manusia sedikit kurang siap untuk menghadapi kekejaman hidup yang tak terhitung.
Bahkan jika ketidaktahuan dan hedonisme tampaknya memberi manusia perlindungan eksistensial untuk sementara waktu, dan manusia dengan aman merangkum diri manusia sendiri dalam batas sebuah istana kesenangan yang penuh hiasan, cepat atau lambat manusia harus menjelajah di luar batas pelindung tembok dan pengalamannya. kenyataan hidup seperti yang pada akhirnya dilakukan Pangeran Siddhartha Gotama, yang menjadi Buddha.
Hukum yang berubah-ubah dari anitya secara tidak mandat mengamanatkan manusia mengalami daya pikat dan tidak menyenangkan, baik yang menguntungkan maupun yang ofensif. "Sesungguhnya segala sesuatu bergerak dalam dirimu dalam setengah-pelukan konstan," Kahlil Gibran memberi tahu kami: "yang diinginkan dan yang ditakuti, yang menjijikkan dan dihargai, yang dikejar dan apa yang akan kau hindari."
Kecuali manusia merangkul kedua sisi realitas dengan kasih sayang yang sama, manusia tidak akan pernah hidup dengan puas atau damai. Sebaliknya manusia akan menemukan diri manusia tanpa henti melarikan diri dari satu hal dan secara kompulsif mengejar yang lain, tanpa daya diperbudak oleh reaksi manusia terhadap keadaan manusia yang selalu berfluktuasi.
Oleh karena itu, Sang Buddha dengan bijaksana menyarankan manusia untuk tidak menjadi terlalu tergila-gila dengan, atau terlalu bingung dengan, serangkaian kondisi, baik itu kebahagiaan atau penyakit - karena putaran lain dari roda keberuntungan hanya beberapa saat lagi.
Manusia tidak bisa menghapus satu ekstrem tanpa mengorbankan yang lain tidak mungkin ada gagasan tentang welas asih tanpa antitesis kekejamannya; tidak ada konsepsi kebijaksanaan yang tidak ada dari kebodohan; tidak ada pemahaman tentang kebaikan tanpa kontras dari kejahatan.
Pasangan-pasangan ini bergantung satu sama lain untuk keberadaan mereka: kedua kutub itu diperlukan untuk jalinan realitas konseptual kebencian dan keputusasaan menentukan cinta dan kebahagiaan; pahitnya kehilangan membuat manisnya sukacita mendapatkan; kekecewaan kegagalan membuat manusia intim dengan kepuasan kesuksesan; kebosanan melahirkan kegembiraan; keinginan manusia memperkenalkan manusia pada kepuasan kita; dan kefanaan manusia yang menjijikkan dan rapuh inilah yang membuat manusia menggiurkan keindahan hidup.
Hanya ketika manusia dengan acuh tak acuh menerima hukum ketidakkekalan yang tak terhindarkan manusia bisa mulai menghargai totalitas pengalaman. Karena tanpa kesengsaraan yang menyiksa kehidupan begitu banyak mencurahkan bagi kita, kesenangan yang disayangi akan sama sekali tanpa nilai, dikurangi menjadi sekadar dangkal. "Dia yang belum memandang kesedihan," Gibran mengingatkan manusia dengan halus, "tidak akan pernah melihat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H