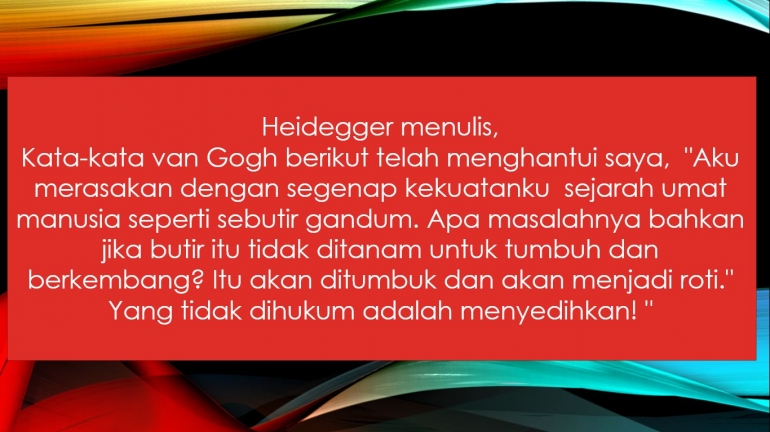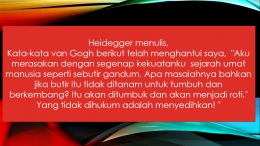Kebenaran Itu Belum Ada, yang Ada Adalah Pergeseran Perspektivisme *]
Diperlukan berpikir dan bertindak dalam Krisis dan kritik memiliki akar yang sama, dan nasib yang sama. "Krisis" menunjuk saat ketika suatu negara atau sistem mengalami transformasi yang tiba-tiba dan menentukan mengarah pada periode ketidakstabilan, jika bukan kekacauan.
Dengan demikian, hal itu menandakan perubahan signifikan dari keadaan keseimbangan (mungkin relatif), dan munculnya masa depan yang terbuka dan tidak pasti, yang dengan sendirinya menghasilkan tingkat risiko, ketegangan, dan bahkan konflik yang tidak biasa.
Tetapi masalahnya adalah krisis telah ada di mana-mana, jika tidak biasa (yang tidak berarti tidak berbahaya atau tidak menyakitkan): hidup manusia diselingi oleh krisis yang bersifat finansial (krisis teknologi, krisis subprime, krisis utang pribadi atau kedaulatan), lingkungan, ke manusian (krisis migrasi dan pengungsian), atau budaya (krisis pendidikan, krisis identitas, krisis multikulturalisme).
Umur manusia, tampaknya, telah menjadi salah satu krisis permanen, dan krisis sebagai pengecualian abadi, normalitas abnormal baru, harus beradaptasi, dan mencoba dan "mengelola." Ini akan menjadi wajah baru ke manusian modern.
Manusia percaya, kritik adalah sikap (atau etos) dan metode yang menganalisis sifat transformasi semacam itu, sementara menolak untuk menerima begitu saja, atau memang melihatnya sebagai hal yang tak terhindarkan.
Ia melakukannya bukan melalui komitmen langsung pada kausalitas historis, tetapi melalui upaya sistematis problematisasi, yang berupaya mengekstraksi kondisi-kondisi kemunculan peristiwa-peristiwa semacam itu, dan membedakan antara masalah-masalah yang diajukan dengan baik dan buruk. Manusia ditekan untuk bertindak oleh urgensi mencekik dari masalah serius, krisis, dan memperbanyak keadaan darurat.
Tetapi bagaimana jika paradigma intelektual manusia cara manusia merumuskan dan memahami masalah-masalah ini sebagai hal yang kritis tidak mempersiapkan landasan untuk solusi yang langgeng, tetapi lebih merupakan mekanisme bisu yang tanpa henti mereproduksi krisis sebagai krisis permanen?
Ini merupakan alasan mengapa, di luar kemampuan diagnosa belaka, kritik adalah usaha etis dan politis: kritik menolak status quo dan sangat lelah dengan mereka yang, pada masa krisis, berbicara tentang 'titik-titik putus' dan 'tingkat tidak berkelanjutan' (dari imigrasi, ketidakamanan, utang) untuk memaksakan tindakan yang tidak perlu dan terkadang berbahaya (keamanan, kontrol, penghematan).
Alih-alih, berupaya memunculkan, dan, tentang, pengaruh politis dari tanggung jawab, solidaritas, dan keramahtamahan, untuk berbicara atas nama kesetaraan dan kesopanan, dan terhadap perpecahan, ketidaksetaraan, dan proses pengucilan yang dihasilkan oleh bentuk-bentuk kekuasaan yang terlibat dengannya.
Dengan demikian, memahami kritik dalam arti yang ada dalam pikiran Michel Foucault ketika dia berbicara tentang peran filsafat dalam memahami siapa manusia sekarang, daripada menemukan kebenaran universal dan trans-historis.
Sebagai diagnosa manusia saat ini, filsafat berkenaan dengan menghindari dua ekstrem, dan dua cara berhubungan dengan sejarah: di satu sisi, yang diungkapkan oleh Hegel ketika mengatakan, seperti burung hantu Minerva, filsafat "hanya melebarkan sayapnya saja dengan jatuhnya senja, "yaitu, ketika peristiwa telah terjadi; di sisi lain, jurnalisme kontemporer, semakin dipaksa mengikuti temporalitas media sosial sesaat dan segera, dan kenyataan yang diukur dalam nanodetik dan dinilai dalam 145 karakter. Di antara kedua ekstrem itu, ada ruang untuk bentuk jurnalisme filosofis, atau cara mendamaikan potensi kritis dan klinis filsafat dengan peristiwa dan kekuatan yang membentuk masa kini.
Filsafat telah mengalami banyak krisis. Ketika misalnya kaum Sofis mengancam kemungkinan kebijaksanaan (pengetahuan untuk kepentingannya sendiri), Socrates, Platon, dan Aristotle menanggapi ancaman itu dengan filosofi krisis mereka. Ketika kemungkinan pengetahuan baru tentang alam terancam oleh tradisi, Ren Descartes datang dengan keraguan universal dan filosofi kesadarannya.
Ketika David Hume mengancam validitas objektif fisika dan matematika sebagai ilmu pengetahuan, Immanuel Kant merespons dengan filosofi transendentalnya. Ketika Schelling dan Hegel sedang mengedit Journal der Philosophie di Jena, keduanya merasakan panggilan dari takdir untuk mengatasi masalah filsafat refleksi.
Ketika keinginan tak terpuaskan dan keserakahan egois merajalela di abad ke-5 SM di Cina, kegelapan kritis ini menyerukan filosofi Lao Tzu. Ketika kekacauan sosial dan kekacauan politik mengancam fondasi moralitas dan pemerintahan, Konfusius menanggapi situasi dengan filosofi moralnya. Ketika retorika dan perselisihan adalah hal biasa, Chuang Tzu yang merespons krisis dengan visinya yang jelas akan kebebasan.
Dalam sejarah filsafat Barat, para filsuf besar tidak pernah gagal untuk memiliki kesadaran diri yang eksplisit akan krisis saat itu. Dengan kesadaran diri akan krisis, yang maksudkan adalah kesadaran diri, bagi filsuf itu, pendekatan filosofis tradisional atau yang berlaku saat ini dan pemahaman tentang realitas jelas tidak lagi dapat dipertahankan dan dengan demikian tidak akan kemana-mana. Mereka merasakan urgensi yang kuat untuk melakukan sesuatu tentang hal itu dan memiliki kesadaran akut akan tanggung jawab sendiri untuk mengatasi krisis yang mereka hadapi.
Namun, krisis filsafat di era pasca-Hegelian, yaitu, sejak pertengahan abad ke-19 , sama sekali berbeda dari krisis filsafat di masa lalu. Betapa radikal konfrontasi para pemikir ini dengan tradisi mereka sebelumnya, selalu ada kesinambungan yang tak terputus. Singkatnya, kontinuitas ini adalah iman yang tak tertandingi dalam Nalar Barat sebagai prinsip realitas dan kriteria utama untuk penyelidikan filosofis.
Nihilisme Eropa pada abad ke-19 tidak lain adalah seruan eksplisit untuk keputusasaan dalam kesia-siaan Rasionalitas barat. Pada abad ke-19 di Eropa, dasar yang telah dikembangkan sejarah Barat selama ribuan tahun, yaitu fondasi budaya, agama, filsafat, dan seni, runtuh. Tanah yang menjadi sandaran keberadaan manusia benar-benar terguncang dan keberadaan manusia sendiri menjadi dipertanyakan. Krisis itu memang tentang Rasionalitas barat.
Adalah Hegel yang mencatat realitas berada dalam dinamika, perubahan abadi melalui perjuangan prinsip-prinsip yang berlawanan dan rekonsiliasi mereka, dan realitas itu adalah nama untuk totalitas proses historis dari interaksi manusia dengan alam, manusia lain, bangsa dan seni, agama dan filsafat. Hegel adalah filsuf yang mampu menunjukkan berdasarkan negasi (dan dengan demikian mediasi), bukan Memahami (yaitu, pemikiran diskursif), tetapi "Alasan" dalam arti unik Hegel sendiri mampu menangkap realitas dinamis dalam proses perubahan.
Dia sangat tahu , pada akhir Pendahuluan edisi kedua Die Wissenschaft der Logik (Ilmu Logika), Hegel menulis, mengungkapkan keraguannya yang serius tentang kemungkinan ditempati dengan "ketenangan tanpa gairah dalam satu-satunya pengejaran kognitif berpikir." Seminggu kemudian, 14 November 1831, Hegel meninggal karena kolera. Kematian Hegel yang menyedihkan ini adalah peristiwa yang sangat simbolis untuk pengembangan lebih lanjut dari filsafat Barat.
Memang, dalam filsafat Hegel, sejarah filosofi Barat sebelumnya, yaitu sejarah Filsafat Barat yang secara konsisten menjadikan Akal sebagai satu-satunya prinsip dasar dan paling mendasar untuk pengetahuan dan realitas, seharusnya berakhir.
Di satu sisi berakhir di satu sisi filsafat Hegel adalah penyelesaian (die Vollendung ) dari sejarah Filsafat Barat dalam mengaktualisasikan tesis Parmenides tentang identitas Nalar dan Wujud, Pengetahuan dan Realitas, dengan cara yang paling konkret dan akomodatif.
Oleh karena itu, melalui proses aktualisasi ini, gagasan Hegel tentang Nalar bukan lagi yang bersifat diskursif, tetapi kemudian mencakup elemen-elemen realitas Rasional dan Irasional pada saat yang sama dan memediasinya dengan negasi pada suatu kesatuan yang tinggi dan diartikulasikan.
Di sisi lain, sistem Hegel merupakan penutup filsafat Barat dalam arti filsafat Hegel adalah keseluruhan eskatologis yang mengintegrasikan seluruh pengembangan filsafat sebelumnya di Barat. Sungguh ironis , pada saat kesatuan roh Eropa diwujudkan dalam filsafat Hegel, kesatuan itu berdiri tepat di sebelah keruntuhannya sendiri.
Menurut para ilmuwan, Hegel dan Goethe adalah dua raksasa terakhir integrasi budaya Eropa dari belle epoche . Yang cukup menarik, mereka berdua menjelang akhir hidup mereka dengan tajam merasa mereka berdiri pada titik balik dari akhir zaman yang baik dari keharmonisan yang benar-benar rukun untuk mengantisipasi era yang sama sekali baru.
Era baru Eropa tiba tepat di "situasi spiritual" di mana cita-cita budaya, tujuan, persatuan, atau makna hidup tidak dapat ditemukan lagi. Itu adalah Nihilisme Eropa yang dinamai Nietzsche sebagai Logic of Decay and Disrupt. Feuerbach menulis dalam Kata Pengantar untuk " Gedanken ber Tod und Unsterblichkeit" diterbitkan secara anonim di Nurnberg pada tahun 1830, Eropa berdiri pada titik balik kritis dari akhir sejarah manusia yang ada hingga awal kehidupan baru dan mengungkapkan keterasingan diri dari manusia dari diri sendiri melalui metafisika tradisional Kekristenan dan menganjurkan antropologi filosofis akan memulihkan eksistensi manusia dari selfalienation-nya atas dasar cinta dalam "Das Wesen des Christentums" (1841).
Bruno Bauer menunjukkan dalam bukunya "Die Russen und das Germanische Volk" (1853) kehancuran filsafat, ketidakberartian kehidupan akademik, penghancuran teologi ada di mana-mana, dan apa pun yang dapat mengklaim tempat dalam sejarah dunia telah diambil tempatnya. oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah perdagangan teknis, perbudakan politik dan ekonomi, keputusasaan untuk visi masa depan, dan tidak adanya moralitas.
Proudhon meramalkan hegemoni proletar di Qu'est-ce-que la Proprit? (1840). Marx berpisah dari pemikiran spekulatif Hegel dengan nama Praksis Sosial, seperti halnya Kierkegaard dengan nama Tindakan Etis. Adalah Marx yang menunjukkan kebenaran borjuis tidak memiliki komitmen penuh semangat.
Dalam menghadapi aturan dan eksploitasi dunia melalui kemajuan teknologi dan penemuan, Marx melihat sebagai konsekuensi yang diperlukan dari kontrol Western Reason, keterasingan diri manusia dari diri sendiri dalam industrialisasi massa.
Namun, dengan menggeser penyelesaian eskatologis dari sejarah Barat ke masyarakat komunis masa depan, Marx berusaha memberikan harapan dan visi bagi kaum proletar yang dieksploitasi dan, dengan memberikan teorisasi metafisik, ekonomi-ekonomi untuk revolusi proletar, ia berupaya menunjukkan kemungkinan menuju komunisme sebagai yang perlu dan tak terhindarkan.
Namun, harus menunggu, lebih dari satu setengah abad untuk melihat apa ilusi besar visi Marx untuk Revolusi Proletar sebagai satu-satunya cara pembebasan alienasi diri manusia dan eksploitasi kemanusiaan.
Nihilisme Eropa mulai menjadi "mode" di pertengahan abad ke-19 di Prancis oleh Flaubert (misalnya novel yang direncanakan Bourvard et Pecuchet) dan Baudelaire (puisi yang direncanakan berjudul Le Fin du Monde).
Eropa akan diliputi oleh Materialisme Amerika dan oleh aturan massa yang bodoh, sementara M. Bourvard berpendapat Eropa akan diremajakan oleh Asia melalui ilmu-ilmu baru dan teknologi dan manusia pada akhirnya akan menghabiskan semua sumber daya di Planet Bumi dan karenanya bermigrasi ke planet lain.
Dunia akan berakhir, demikian uraian Baudelaire; manusia akan dihancurkan oleh Kemajuan Peradaban Modern yang manusia yakini telah manusia jalani. hanya menemukan ilusi dan annui besar di masa lalu dan tidak menemukan harapan untuk masa depan. Manusia dapat menciptakan surga buatan untuk menikmati kesenangan dekaden secara menyeluruh.
Silsilah Nihilisme Eropa berlanjut dengan Kierkegaard, Dostoyevsky, dan Nietzsche. Mereka memperjelas penolakan kategoris mereka atas konsekuensi historis dari Sejarah dan Peradaban Barat, yang sering kali disertai upaya kritis untuk menciptakan visi baru bagi reformasi mendasar nasib manusia.
Meskipun Kierkegaard memiliki sedikit pengaruh di antara para filsuf pada zamannya sampai Jaspers dan Heidegger menemukan kembali kelebihannya, Kierkegaard menghadapi hasil filsafat Hegel dan menantang Alasan dalam Filsafat Barat. Jelas bagi Kierkegaard Rasionalitas barat adalah penyebab dari masyarakat Protestan borjuis yang menipu dan dekaden. Pemikiran filosofisnya berpusat di semanusiar keberadaan telanjang individu yang berdiri sendiri di depan Tuhan dan "meningkatkan negativitas absolut dari ironi Romantis menjadi lompatan iman yang putus asa!"
Dalam Diaries Penulis , Dostoyevsky mengolok-olok pada tahun 1890 seorang Rusia Eurofit yang menyatakan Rusia harus meniru Eropa Barat demi kemajuan teknologi, sementara yang terakhir, menurut Dostoyevsky, belum menyelesaikan masalah sendiri dan berdiri selangkah di depan jatuh.
Pada tahun 1910, Tolstoy secara radikal mengkritik Peradaban Eropa karena tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri tetapi meracuni Afrika, India, Cina dan Jepang dengan gembira melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dari logika barat.
Pada awal abad ke-20, dalam bentuk kritik, ironi, dan skepsis, Nihilisme yang menentang dan menyangkal Rasionalitas barat dengan Sejarahnya, menjadi satu-satunya "iman" nyata yang mungkin dimiliki oleh para intelektual Eropa. Melalui imajinasi kreatif, membangun dunia ke manusian yang sejati dengan menulis seorang romawi tidak lagi layak dilakukan oleh para penulis Eropa: Mereka sekarang hanya mampu menganalisis perjuangan Intelek, reaksi Roh, perselisihan sosial dan keputusasaan.
Sebagai pengganti membangun alam semesta ke manusian yang bermakna, Proust, Gide, Thomas Mann, Huxley, Marleaux, Lawrence, Joyce. Hanya bisa memediasi kebenaran yang putus asa tentang ketiadaan dan kekosongan nilai. Nihilisme yang sama dapat dilihat dalam gerakan seni plastik pada paruh pertama abad ke-20 seperti Dadaisme, Ekspresionisme, Fauvisme, dan Kubisme. Semua dari mereka adalah ekspresi yang jelas bertentangan dengan Alasan Eropa dan nilai-nilai tradisionalnya.
Nietzsche menempati tempat yang unik dalam sejarah Peradaban Barat serta di antara para Nihilis abad ke-19 dan ke-20. Nietzsche adalah filsuf Eropa pertama yang secara aktif menilai dan secara radikal menghadapi Rasionalitas barat dan seluruh Sejarah budaya Barat. Nihilisme Nietzsche harus diambil sebagai semangat subyektif yang ditinggikan secara positif dari pencarian filosofis otentik dalam tugasnya adalah secara aktif mengatasi ketiadaan yang lahir dari Krisis Kematian Allah Kristen.
Justru karena ia memiliki wawasan yang menembus ke dalam Ketiadaan nilai-nilai, Kebermaknaan eksistensi manusia, dan Kematian Tuhan sebagai konsekuensi dari pembusukan Sejarah dan Budaya Barat, Nietzsche mampu menegaskan secara tegas "Keinginan untuk Berkuasa" sebagai Transvaluasi semua Nilai dan menyebut Zarathustra sebagai Penakluk Ketiadaan dan Tuhan, yaitu sebagai Penakluk Nihilisme Eropa.
Nihilisme otentik dapat didefinisikan sebagai Logika yang menembus nilai tertinggi moralitas Kristen dengan penerimaan penuh kasih sayang dari semua yang menipu, palsu dan nihil. Nihilisme Nietzsche adalah menciptakan seperangkat nilai baru dalam menghadapi hilangnya total nilai-nilai lama. Dari kebenaran sementara dan satu-satunya dari Nihilisme radikal ini sebagai lenyapnya iman kepada Tuhan dan moralitas, tampak "tidak ada yang benar, jadi semuanya diizinkan!"
Kebebasan untuk Segala Sesuatu dan Tidak Ada Ini adalah Keinginan untuk menginginkan segalanya dan meninggalkan segalanya pada saat yang bersamaan. Di sini manusia menemukan petunjuk yang sangat sugestif untuk solusi baru untuk masalah manusia, yang akan dibahas pada bagian akhir.
Perang Dunia I adalah perjuangan terakhir dan penyelesaian Rasionalitas barat Tradisional melawan filosofi Nihilistik Le-Fin-de-Ciecle dan merupakan penyelesaian dari yang terakhir. Menurut Max Scheler dalam "Der Genius des Krieges" (1915), Perang Dunia I adalah awal dari suatu tatanan baru atau awal dari Kematian Eropa, dan tidak ada yang lain. Namun demikian, itu adalah kesimpulan Scheler wali tersebut (yaitu, sebuah organisasi) untuk menciptakan dan mempertahankan tatanan baru Budaya Eropa tidak ditemukan. Paling tidak pasti Perang Dunia I berfungsi sebagai pembagian antara dua periode.
Para filsuf yang telah berpegang pada Rasionalitas barat tradisional dan menjadikannya sebagai urusan serius mereka untuk menyelidiki dasar ilmu-ilmu lain, terpaksa mengakui kepada diri mereka sendiri dan orang lain (seperti para siswa mereka) ketidakberdayaan dan absurditas dari pencarian mereka. Filsafat ilmu dan analisis linguistik berfungsi sebagai model untuk ini.
Bertentangan dengan itu, ada sekelompok filsuf yang memiliki sikap yang sama dalam melakukan filsafat. Pendekatan mereka disebut Fenomenologi dan tujuan mereka adalah mendekati kenyataan sebagaimana adanya. Tokoh utama adalah Edmund Husserl, Max Scheler dan Martin Heidegger.
Husserl dan Scheler adalah senior, sedangkan Heidegger adalah yang termuda dan bisa disebut "pengikut mereka" setidaknya pada tahap awal dalam pengembangan gerakan ini. Di antara orang-orang sezaman Heidegger, Karl Jaspers adalah filsuf lain yang memiliki kepedulian yang sama yang mendekati filsafat dari psikopatologi dan sangat dipengaruhi oleh Kierkegaard, Nietzsche dan van Gogh.
Sementara Husserl kurang terpengaruh, baik Scheler dan Heidegger sangat dipengaruhi oleh Kierkegaard dan Nietzsche dalam mencetak filosofi mereka. Selanjutnya Hlderlin, van Gogh, dan Rilke memiliki dampak besar pada Heidegger. Ada teolog yang secara serius menerima tantangan yang diangkat oleh Nietzsche dan filosofinya dan mereka berdiri di bawah pengaruh oleh Kierkegaard. Para teolog revolusioner itu adalah Karl Barth, Rudolf Bultmann, Martin Buber, dan Paul Tillich.
Hampir semua dari mereka memiliki pengalaman tangan pertama dari Perang Dunia I sebagai pengalaman primordial mereka. Dengan kepekaan yang tajam dan pemahaman mendalam, mereka secara eksplisit menyadari krisis Alasan dan Budaya Barat dan mengambil sikap mereka terhadap krisis-krisis itu dalam berbagai cara.
The Crisis karya Husserl, Der Genius des Krieges dari Schuss, dan Vom Umsturze der Werte, Being and Time Heidegger, Die Geistige Situation der Zeit dari Jaspers, untuk beberapa contoh, adalah ungkapan subjektif yang jelas dari reaksi para filsuf terhadap krisis tersebut. Fokus tematis yang umum bagi semua pengejaran para filsuf dan teolog ini adalah, betapa berbedanya mereka, jelas dipengaruhi oleh keprihatinan mereka tentang makna eksistensi individu manusia yang konkret dan nasibnya dalam menghadapi krisis-krisis ini.
Husserl merasa tidak terhindarkan untuk berhadapan dengan tirani Rasionalitas barat dalam bidang filsafat, ilmu, teknologi, dan industri sejak Galileo. Ia telah menciptakan representasi realitas sepihak, abstrak, dan terdistorsi melalui pengukuran numerik dan telah mengasingkan manusia dari dunia kehidupan yang konkret. Lebih jauh, perkembangan historis dari Rasionalitas barat menghalangi manusia untuk mengalami dunia kehidupan yang sebenarnya.
Meskipun Husserl mengklaim fenomenologi transendental sebagai telos dari logika barat untuk mengatasi aporia, ironisnya upaya tekun Husserl untuk secara radikal kembali ke realitas yang lebih primordial terus mengungkapkan cakrawala baru di mana subjektivitas transendental gagal untuk sepenuhnya mengungkapkan dirinya sendiri dan sebaliknya mengekspos dirinya sebagai tidak dapat diklarifikasi oleh Alasan.
Kerusakan (Scheitern) dari pendekatan Husserl ini melambangkan nasib Rasionalitas barat di abad ke-20. Sementara Scheler mencoba Transvaluasi Nilai dan dia akhirnya tidak melangkah lebih jauh dari sekadar memberikan dasar etika bagi teologi Katolik mungkin karena kematiannya yang dini. Jaspers dituntun untuk membangun sistem metafisik das Umgreifende (Encompassing).
Martin Heidegger sangat menyadari masalah ini dari pendekatan Husserl oleh Alasan dan keterbatasan filsafat kesadaran Husserl dan ia mencari status ontologis subjektivitas transendental ini sebagai landasan utama bagi semua dalam temporalitas (yaitu ketiadaan) dari keberadaan manusia yang konkret dan terus mengembangkan ontologi dasar.
Namun, terlepas dari pertanyaan filosofis ini, Heidegger rupanya tertarik pada ketiadaan menjadi yang terutama dari pengalaman pribadinya yang primordial tentang situasi di dan setelah Perang Dunia I. Menurut Karl Lowith, seorang mahasiswa Heidegger, mengirimi surat pada tahun 1923, di mana Heidegger menulis,
Kata-kata van Gogh berikut telah menghantui saya, "Aku merasakan dengan segenap kekuatanku sejarah umat manusia seperti sebutir gandum. Apa masalahnya bahkan jika butir itu tidak ditanam untuk tumbuh dan berkembang? Itu akan ditumbuk dan akan menjadi roti." Yang tidak dihukum adalah menyedihkan! "
Heidegger seharusnya menulis lebih lanjut, ... perlu , di tengah-tengah dunia kehancuran total, manusia memperoleh bagi diri manusia iman yang tak tergoyahkan pada "satu hal yang perlu," mengabaikan kata-kata dan perbuatan orang-orang yang pandai mengukur waktu dengan kronometer dan sebagainya.
Heidegger secara eksplisit sadar nasib Rasionalitas barat, yang membawanya kemudian untuk kembali ke Pra-Socrates. Di sisi lain, dari pemikirannya sendiri tentang nasib dalam kaitannya dengan keberadaan, keputusan dan situasi Jerman, itu mungkin konsekuensi yang tak terhindarkan Heidegger menemukan kewajibannya sendiri dalam Sosialisme Nasional. Filosofi eksistensial Heidegger, tentu saja radikal dan inovatif, berhenti mengungkapkan pendekatan kepada dunia, sebagaimana adanya.
Perang Dunia II berakhir dengan dua bom atom yang meledak di Hiroshima dan Nagasaki seolah-olah mereka adalah hantu Rasionalitas barat. Melalui kehancuran kota-kota dan budaya Jerman dan universitas ditutup, para filsuf Perancis yang mengikuti langkah fenomenologi dan filsafat eksistensial muncul lebih aktif di dunia filsafat.
Tiga teman sekelas di atasan normal l'ecole, Maurice Merleau -Ponty, Jean-Paul Sartre dan Simonne de Beauvoir mengejar fenomenologi di bawah pengaruh Hegel-Marx, Husserl dan Heidegger. Dalam filsafat Perancis seperti halnya dalam filsafat Jepang, tubuh dan perwujudan menjadi tema penyelidikan fenomenologis dan keasyikan ini membayangi masalah bagaimana berurusan dengan Rasionalitas barat dan takdirnya, meskipun masalah tubuh dapat memberikan terobosan dalam pendekatan tematik;
Pada 1960-an manusia temukan di Michel Foucault Nihilism of Reason to Western History. Mengikuti Nietzsche, pendekatan Foucault terhadap filsafat sebagai dugaan positivisme dan Nihilisme mengambil kedok kaum sofis. Itu datang untuk mencapai penghancuran sejarah dan pengungkapan Alasan melalui bayangannya pada saat yang sama.
Melalui kemahiran strategi "dekonstruksi," Derrida berusaha untuk "melarikan diri" dari kontrol licik dan penguasaan Rasionalitas barat atau logo dalam pemikiran Barat melalui penangguhan yang ambigu.
Untuk melepaskan diri dari prinsip identitas (= Alasan) manusia harus meradikalisasi fenomenologi sedemikian rupa sehingga segala sesuatu berada di dalam yang lain, yaitu, dalam dirinya sendiri harus dihilangkan dan yang sama adalah yang lain, jadi jika manusia dapat meminjam ekspresi Hegelian, yang satu melihat diri sendiri hanya di wajah yang lain.
Dengan melakukan itu, manusia mengarah pada perspektivisme di mana misalnya gambar pada cermin dapat dikenali sejauh gambar adalah cermin dan cermin adalah gambar. Jadi aslinya gambar tidak, tetapi tidak lain adalah gambar.
Upaya Nietzscheans Prancis ini untuk mengatasi Nihilisme Eropa berada dalam kerangka bahasa dan tradisi historis mereka sendiri. Jika ini harus menjadi satu-satunya konsekuensi dari Sejarah Budaya Barat, filosofi krisis masih akan tetap menjadi filosofi dalam krisis. Niat mereka memang mulia, namun apa yang mereka lakukan sebagai filosofi krisis sangat sedikit di luar sofistic dalam upaya untuk mengatasi tirani Rasionalitas barat.
Karena itu, manusia harus terus mencari filosofi krisis manusia, sebuah alternatif untuk dan di luar upaya kaum post-modernis Prancis. Alih-alih menghindari, manusia harus secara filosofis menghadapi dan mengatasi tirani Nalar yang telah manusia lihat dimanifestasikan dalam reaksi-reaksi filosofis itu sebagai Nihilisme.
Ketika selama Renaisans, diBarat menemukan Jalan Rasional untuk mengukur dan mengendalikan alam (lingkungan ) dengan perangkat matematika, yang disebut teknik he, yaitu alat untuk keberadaan, mampu menjadi teknologi.
Ketika Gerakan Pencerahan menetapkan Alasan dan memvalidasi potensinya dalam mengejar pengetahuan hanya sebagai cara praktis untuk mengendalikan alam, ini telah memungkinkan manusia untuk membuat mesin produksi massal untuk menduplikasi alat canggih yang tak terbatas untuk massa. Semakin manusia merencanakan untuk menduplikasi mereka, semakin manusia merangsang hasrat dan keserakahan buatan manusia untuk mengkonsumsinya.
Untuk perangkat inovatif, implementasi yang lebih efisien telah menjadi tujuan utama Western Reason (yang kembali ke salah satu motif utama Pencerahan). Dengan kekuatan Nalar yang luar biasa, ditakdirkan untuk memperbaiki bahasa semata-mata dalam eksploitasi realitas sebagai alat yang paling berguna untuk penghidupan dan kenyamanan.
Sejak Renaissance, alam semesta, yaitu kenyataan, telah dianggap tertutup. Sebagai pencari pengetahuan (filsuf dalam arti asli) dari alam, manusia harus menggunakan Alasan untuk "menguraikan simbol-simbol dari Manusia itu," seperti yang dikatakan Galileo. Dalam pengejaran ini, bahasa yang dirancang secara rasional saja dapat mengungkapkan realitas hanya sebagai alat raksasa.
Ilusi besar Alasan Eropa adalah membuat manusia semua percaya objektivitas adalah kenyataan sebagaimana adanya. Namun, beberapa filsuf sensitif abad ke-17 seperti Pascal, Liebniz dan bahkan Berkeley sudah sadar akan bahaya ini dan menunjukkan penyebab utama (penjelasan) kausalitas haruslah teleologis. Dengan jelas mengakui keterbatasan Nalar, Pascal menemukan kalkulator biner, yang, di luar kemauannya, kemudian membuka jalan menuju rasionalisasi realitas tanpa syarat.
Namun pendekatan non-dan anti-Rasional itu, tidak pernah menjadi filsafat Barat arus utama dalam pencariannya akan kenyataan. Titik penentu datang pada Pencerahan di abad ke-18 di Prancis dan Jerman. Terlepas dari protes Rousseau, Reason diabadikan sebagai satu-satunya kedaulatan untuk mendekati kenyataan.
Namun demikian, tradisi anti-Rasionalisme itu tetap hidup di Barat. Pada pergantian abad ke-20, Henri Bergson dan Max Scheler muncul sebagai penantang tradisi filsafat yang tidak lazim di Barat ini. Terhadap obyektifikasi dan materialisasi realitas, Bergson melihat realita sejati dalam waktu dan berperang melawan Reason dengan mengurangi jarak waktu agar realitas primordial menyingkapkan dirinya kepada manusia. Filsafatnya diterima dengan cukup baik pada suatu waktu dan bahkan memberikan pengaruh besar pada Marcel Proust dan penulis-penulis Barat lainnya.
Scheler melihat realitas tidak tertutup (geschlossen) atau objek kebencian (Weltha), tetapi ia memang terbuka oleh keberadaannya sendiri. Ini adalah sikap manusia, menurut Scheler, yang dengannya, melalui lapisan-lapisan selubung Nalar, realitas tertutup dan tertutup bagi manusia.
Fenomenologi Scheler adalah daya tarik bagi manusia semua yang tertutup oleh bahasa, ilmu pengetahuan modern, dan filsafat Alasan manusia harus sadar akan realitas primordial yang terbuka dan otentik.
Pendekatan Scheler meresmikan mata Martin Heidegger pada potensi mengatasi filsafat kesadaran Husserl (inilah sebabnya Heidegger mendedikasikan Kant und das Problem der Metaphysik untuknya Max Scheler) dan Heidegger sekali lagi terjebak dalam jurang bahasa oleh hermeneutika Wujud (Die Hermeneutik des Seins, sebagaimana Heidegger menyebutnya).
Mungkin karena kekuatan yang luar biasa dari Nalar dan Sejarahnya, Scheler tidak dapat benar-benar mengejar wahyu nobel ini ke potensi penuh untuk mengatasi Nihilisme Eropa.
Tidak ada artinya dan bahkan sia-sia untuk sepenuhnya menolak atau mengabaikan Rasionalitas barat. Namun mungkin yang paling penting dari semua tugas manusia sebagai filsuf saat ini adalah untuk mengeksplorasi pendekatan filosofis yang akan membebaskan manusia dari tirani Rasionalitas barat dengan memuatnya dalam fungsi yang sesuai dan memungkinkan manusia untuk selaras dengan realitas primordial. Bagaimana ini mungkin?
Semacam "pemberontakan" seperti itu terhadap Rasionalitas barat seperti yang dicoba oleh kaum postmodernis Prancis tentu bukan urusan manusia. Manusia harus mencari cakrawala, atau "Pemahaman Hebat" sebagaimana disebut Chuang Tzu, di mana Alasan tidak perlu digunakan untuk "mengalami dan selaras dengan" realitas primordial di mana ia akan menemukan tempat dan perannya sendiri.
Di satu sisi, manusia dapat menggali banyak wawasan yang manusia butuhkan untuk penyelidikan manusia dalam filosofi tradisi "sesat" Barat. Di sisi lain, manusia menemukan model potensial untuk dedikasi filosofis manusia pada realitas terbuka dalam pendekatan Zen di Timur. Biarkan saya jelaskan.
Adalah Parmenides yang mengusulkan Identitas Menjadi dan Mengetahui yang terkenal. Satu-satunya hasil positif dari Rasionalitas barat dan Sejarahnya adalah Dialektika Hegel yang mencapai tujuan akhir filsafat ini dengan memediasi berbagai pemahaman sepihak ke dalam kesatuan aufgehobene (sublated).
Itu adalah asumsi Alasan Eropa Realitas dan Pengetahuan dipisahkan dan harus disatukan menjadi satu. Atau lebih tepatnya, karena Alasan Eropa yang menduduki "ruang" antara Realitas dan Pengetahuan dengan menganggap dirinya sebagai cara khusus untuk Mengetahui, Menjadi, dan Mengetahui akan tampak terpisah.
Konsep "Objek" atau "Gegenstand" secara tak terelakkan menyiratkan "Subjek," sebagai objek selalu merupakan objek untuk subjek tertentu. Oleh karena itu, mudah untuk melihat bagaimanapun , objektivitas adalah kesepakatan intersubjektif di antara semua subjek. Alih-alih Menjadi itu sendiri, segera setelah konsep "Objek" diperkenalkan untuk memahami Being, Subjek harus diperkenalkan sebagai agen pengetahuan, yang harus berbeda dari Being itu sendiri.
Agen ini disebut "Diri" yang bertentangan dengan Objek untuk memanipulasi dan mengendalikannya. Justru Reason (whichs yang membedakan dan memanipulasi, dengan demikian bahasa atau nama (lS) harus memainkan peran sarana dominan. Setelah dibedakan, itu harus disatukan. Tidak heran perlu memiliki mediasi setelah mediasi, sebagai Hegel akhirnya tercapai.
Bagaimana manusia bisa "mengurung" Obyek-Subjek, semua mediasi dan akhirnya Akal itu sendiri?. Bagi Scheler, reduksi fenomenologislah yang merupakan proses untuk mencapai metamorfosis sikap manusia dengan menarik manusia menjauh dari menghubungkan diri manusia dengan kenyataan melalui lapisan mediasi prasangka duniawi dan filosofis dari Rasionalitas barat untuk segera membuktikan kenyataan terbuka sebagaimana adanya.
Bagi Zen, untuk memecahkan singkatnya Alasan, sering kali ko-an digunakan. Ko-an adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nalar. Ko-an paling terkenal di Barat adalah, "Apa suara tepukan satu tangan?" Zen menyangkal bahasa yang hanya terbatas pada penggunaan duniawi dan praktis . Bahasa dalam pengertian ini adalah asal dari perbedaan dan sumber dari keinginan dan kemelekatan manusia. Ini adalah bahasa yang menciptakan Diri dan Obyeknya dan membuat keinginan Diri dan melampirkan padanya pada saat yang sama.
Sebagai pengganti pemahaman teoritis, Zen menuntut praktik, yaitu mediasi Zen. Sejak kelahiran manusia, atau bahkan melalui banyak kelahiran kembali dalam hal ini, manusia dipaksa untuk menumbuhkan perbedaan dan keinginan dari Diri. Disiplin mediasi Zen yang paling parah, bagaimana artifisialnya itu muncul, dapat menjadi cara yang efektif untuk menangkal semua pembelajaran itu. Untuk membebaskan manusia dari perban budaya dan kecerdasan ini, cara khotbah manusia yang biasa dan biasa melalui lapisan-lapisan mediasi dengan realitas adalah tujuan dan proses meditasi Zen.
Pengalaman satori atau kebangmanusian Zen adalah sekilas ke realitas tanpa mediasi seperti itu. Ini adalah pengalaman di mana tidak ada kenyataan yang disembunyikan dalam penutupan, tetapi mengungkapkan dirinya dalam pengungkapan terbuka. Pengalaman satori adalah kesadaran di mana tidak ada Subjek atau Obyek. Sebaliknya, itu adalah pengalaman yang benar-benar tidak memediasi dan murni di mana realitas mengungkapkan dirinya sebagaimana adanya.
Realitas primordial telah dan terbuka dan siap untuk mengungkapkan dirinya sebagaimana adanya. Dan adalah bagian integral dari kenyataan ini. Namun, manusialah manusia, yang menciptakan keretakan dan perbedaan dan menghasilkan mediasi. Manusialah yang merancang alat dan teknologi untuk mengasingkan diri dari diri manusia sendiri. Ego manusia yang mendorong manusia ke Nihilisme itu dan putus asa.
Adalah kesalahpahaman manusia realitas harus menjadi Entitas. Seperti yang dikatakan Scheler, Ketakutan akan Kekacauan yang ingin memaksakan keteraturan dan struktur dalam kenyataan. Ini adalah Ketakutan Tak Ada yang mendalilkan Entitas dengan perbedaan. Ketika menyadari pengetahuan adalah kekuatan (di Yunani Kuno), memasukkan perantaraan ke dalam Knowing. Dengan demikian perbedaan menjadi absolut dan realitas diperintahkan. Manusia tidak dapat mengingat manusialah, manusia, mendorong perbedaan, jelas realitas primordial adalah Tidak Ada.
Namun, pendekatan terhadap realitas tidak menuntut penghapusan perbedaan. Karena dalam pendekatan , perbedaan "dikurung" tidak berdaya. Hanya dalam kedagingan manusia, perbedaan adalah penggunaan praktis. Jadi sebagai ganti mediasi, manusia harus sekali lagi mengalami kenyataan, sebagaimana adanya. Nihilisme dihasilkan dari pembedaan dan dari mengira Tidak Ada untuk Menjadi.
Selama korelasi antara melihat dan yang kasat mata, pendengaran dan yang terdengar, menggenggam dan berwujud, tetap mutlak, selama keterikatan manusia pada Ego tetap ada, selama Nalar adalah satu-satunya cara untuk mendekati kenyataan, masih ada Nihilisme. Selama metafisika tetap ontologi, manusia terus dihantui oleh kekosongan nilai dan dikendalikan oleh Alasan.
Namun, begitu manusia mampu "melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak terdengar, memahami yang tak berwujud," seperti yang ditunjukkan oleh Lao Tzu, dan akhirnya begitu manusia tidak belajar untuk "mengendalikan," dan belajar untuk membiarkan semuanya berjalan dalam pencarian pertanyaan manusia, metafisika menjadi m-ontologi (studi tentang Tidak Ada).
Alih-alih Nihilisme, Filsafat Sejati yang murni tidak muncul segera setelah manusia mulai belajar untuk "mempercepat pikiran manusia," seperti yang dikatakan Chuang Tzu dan mengalami diri manusia sebagai satu dengan kenyataan.
*] Bahan dan catatan kuliah Filsafat Ilmu, Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana Jakarta, 2017.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H