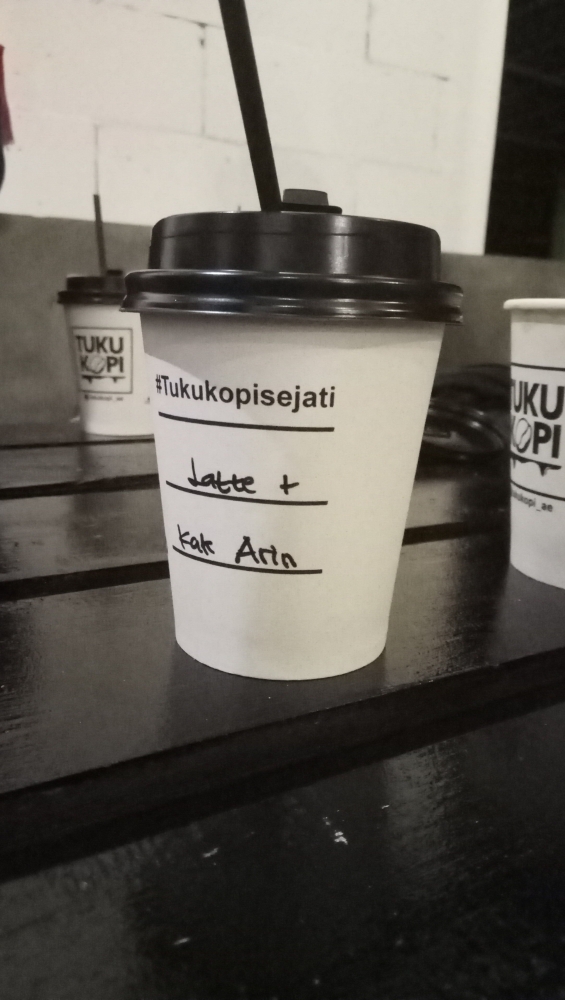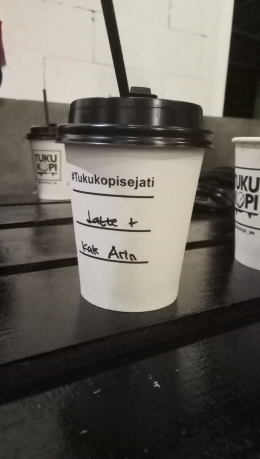Perjuangan kelas yang dilakukan oleh Karl Marx dan Engels saya kira tidak akan menemukan jalan keberhasilan. Dalam Manifesto Komunis sudah dibicarakan fakta historis mengenai kelas-kelas antagonisme sejak zaman Romawi hingga zaman modern. Faktanya, dari sejumlah antagonisme, hanya tertinggal dua kelas antagonisme dalam dunia modern, yaitu borjuasi dan proletariat.
Keberadaan kelas-kelas tersebut dipupuk oleh kaum borjuasi modern, sehingga tumbuh subur mencipta 'kelas' yang semakin jelas. Sebenarnya, istilah kelas ini baru populer dalam bahasa Inggris dan Eropa Barat ketika revolusi industri. Gagasan tentang kelas ini digunakan oleh para sejarawan dunia untuk mempelajari evolusi di belahan bumi Eropa modern.
Akan tetapi, kelas yang dimaksud oleh Marx dan Engels dalam Manifesto adalah kelas dalam pengertian sosial. Kelas sosial semakin mencipta jembatan pemisah antara si miskin dengan si kaya. Lebih tepatnya, kelas yang dimaksud kedua tokoh tersebut merujuk pada hubungan ekonomi, yakni tentang pekerjaan dan pendapatan seseorang.
Telah kita ketahui bahwa hubungan ekonomi erat kaitannya dengan soal komiditi. Komoditas menjadi akar persoalan produksi. Karena menurut Marx dalam Das Capital, kemakmuran dalam sebuah masyarakat ditentukan oleh corak produksi kapitalis. Corak produksi kapitalis inilah yang sebenarnya sangat berpengaruh pada persoalan-persoalan ekonomi lainnya seperti sewa, tenaga kerja, nilai lebih, keuntungan, dan harga produksi.
Harry Cleaver yang juga mengkaji pemikiran Karl Marx tentang komoditi, memberikan jawaban atas mengapa Marx memulai kajiannya dengan bahasan komoditi. Harry menjawab, karena komoditi bagi Marx merupakan hal yang paling dasar dari kapital. Inilah mengapa, Marx menjelaskan bahwa kemakmuran kaum borjuasi menampakkan dirinya dalam wujud komoditi.
Artinya, hal yang fundamental bagi kapital adalah bagaimana mencetak untung yang berlipat, dan bukan membangun hubungan dengan pihak lain dan pasar. Sehingga, corak kapitalis dalam proses produksilah yang dipakai untuk menjembatani keuntungan itu. Bagaimana sebuah komoditas ditampilkan dengan intervensi faktor lain, seperti nilai alat produksi, nilai tenaga, nilai suasana, dan nilai kenyamanan yang ditawarkan.
Saya jadi berpikir, mungkin inilah yang membuat nilai segelas kopi akan berbeda harganya apabila dijual di caf modern daripada sekedar di warung kopi biasa di trotoar jalan.
Hal ini menyebabkan kopi yang dipercaya sebagai ruang rakyat akan berubah menjadi hegemoni ketika masuk dalam ruang kaca. Yakni ruang dengan tampilan mewah dan diolah dengan cara yang bagi saya tidak lumrah serta menggunakan alat produksi berupa mesin-mesin mahal.
Beberapa waktu yang lalu, saya diajak ngopi oleh kawan saya di sebuah caf di kota saya tinggal. Saya cek menunya, dan saya tidak menemukan angka bersahabat kecuali hanya satu menu yaitu kopi ampas alias kopi hitam biasa.
Karena saya tidak minum kopi hitam (dengan alasan medis), maka saya memesan Latte Original. Jujur, saya tidak pernah minum kopi dengan nama-nama aneh semacam itu.
Bukan karena saya tidak mampu membelinya, akan tetapi bagi saya sangat sayang apabila uang belasan hingga puluhan ribu yang saya hasilkan dari kerja seharian hanya untuk membayar segelas kopi. Dan ternyata saya paham, bukan kopinya yang mahal, akan tetapi 'ruang' yang ditawarkanlah yang membuat segelas kopi menjadi mahal.
Inilah mengapa harga kopi yang saya beli itu lumayan tidak lumrah bagi saya. Mengingat saya hidup di sebuah kota kecil, yang ternyata semakin menjamur pula warung kopi maupun caf yang menawarkan ruang mewah. Sehingga memengaruhi nilai jual segelas kopi.
Masalah ruang telah mengintervensi nilai komoditas kopi. Karena nilai kopi akan mengalami perubahan seiring dengan ruang dimana ia dijual. Pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kapital, karena mereka tentu akan merubah segala sesuatu yang disukai masyarakat banyak. Dan tentu saja akan menjelmakannya sebagai barang yang lebih bernilai tinggi.
Tindakan kapital akan diterima apabila berjalan sesuai dengan proporsi sewajarnya. Akan tetapi perlu diingat, kapital akan tampak membahayakan ketika komoditas berubah kemasan dan menciptakan 'kelas'. Akan lebih terlihat mengerikan apabila kopi sebagai komoditas dan barang konsumsi masyarakat akan dimasuki 'gengsi'.
Ternyata, kopi yang saya percaya sebagai ruang diskusi telah menciptakan apa yang disebut Karl Marx sebagai kelas sosial. Padahal kata pepatah, "di depan kopi semua adalah sama". Akan tetapi, kopi yang menjadi teman diskusi itu akan membuat orang (baca: proletar) tidak fokus berdiskusi, tapi sibuk memikirkan bagaimana membayar kopi yang ia pesan.
Kopi dan mungkin juga komoditas lain, awalnya hanya merupakan bahan produksi yang tak beitu bernilai tinggi yang mengalami kenaikan kelas. Selain kopi, juga banyak komoditas yang memanfaatkan ruang sehingga menjadi naik kelas seperti segelas kopi yang menjadi mahal jika dijual di Starbuck.
Misalnya, ketela pohon yang tumbuh di lahan-lahan miring pegunungan dengan harga sangat murah itu disulap menjadi barang konsumsi yang siap dibandrol dengan gengsi. Sego thiwul yang sangat murah apabila beli di desa saya, menjadi lebih mahal apabila dijual di restoran mewah tingkat atas. Dan juga, gethuk yang dijual di pasar tradisional seharga dua ribu rupiah akan melonjak menjadi puluhan ribu rupiah jika ditempatkan di etalase-etalase kaca kelas atas.
Jadi, sebenarnya komoditas itu tetaplah barang ndeso yang menjadi mahal ketika dikemas dan diletakkan di ruang-ruang kaca kedap suara. Sementara itu kelas sosial tercipta karena gengsi.
Sedangkan gengsi adalah jualannya kapitalisme yang paling laku. Kata teman diskusi saya, kapitalisme tidak pernah benar-benar menjual hakekat barang suatu komoditas.
Padahal hakekat kopi, bagi orang awam seperti saya, adalah perekat untuk menemani duduknya sekumpulan orang yang ingin menikmati waktu, dimana waktu itu memang sengaja diluangkan.
Akan sangat sayang sekali bagi saya, dan mungkin orang-orang yang sepemikiran dengan saya, uang yang diperoleh dari keringat seharian, hanya untuk membayar segelas kopi di caf kapital. Pernyataan ini jangan dijawab dengan asumsi "Kalau begitu tidak perlu ngopi."
Bukan budaya ngopi yang saya kritik. Saya tahu bahwa aktivitas ngopi bisa disebut ibadah oleh sebagian orang, karena dari forum itulah inspirasi, ide-ide besar bisa lahir.
Akan tetapi, dimana ngopi telah berubah alat sebagai ajang gengsi bagi orang-orang yang tidak mengetahui hakekat ngopi itu sendiri. Kopi itu ada dua hal yang harus diketahui, kopi untuk dinikmati atau kopi untuk ajang gengsi.
Gengsi itulah yang menciptakan budaya ngopi menjadi ada kelas-kelasnya. Ada istilah ngopinya kelas atas alias kaum borjuasi sama ngopinya kelas bawah alias proletariat. Dari sini dapat dilihat bahwa ternyata segala sesuatu bisa dikapitalisasi. Salah satunya yang manjur dikapitalisasi adalah sikap konsumtif masyarakat.
Bagi para pecinta kopi, mungkin hal semacam itu bukanlah persoalan besar. Tapi menurut saya, justru kopi kehilangan ruh-nya apabila menciptakan kelas sosial. Kopi dipercaya sebagai barang konsumsi yang merakyat, telah kehilangan jati dirinya, karena ia nyata menunjukkan keberpihakannya pada kapital. Kopi telah menciptakan stratifikasi sosial di antara kita, Sayang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H