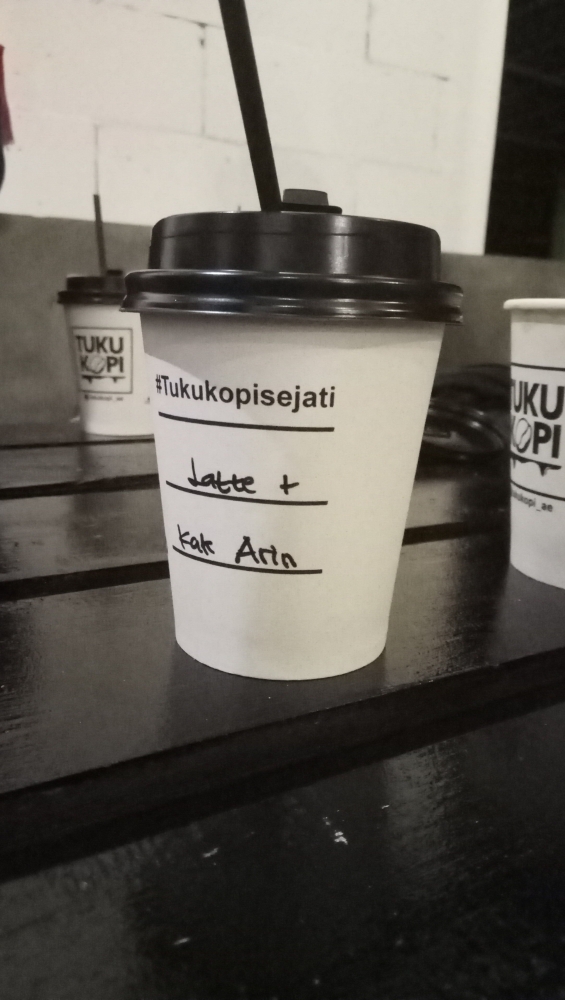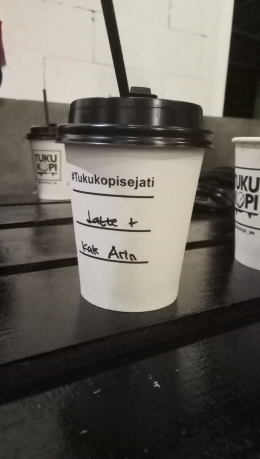Inilah mengapa harga kopi yang saya beli itu lumayan tidak lumrah bagi saya. Mengingat saya hidup di sebuah kota kecil, yang ternyata semakin menjamur pula warung kopi maupun caf yang menawarkan ruang mewah. Sehingga memengaruhi nilai jual segelas kopi.
Masalah ruang telah mengintervensi nilai komoditas kopi. Karena nilai kopi akan mengalami perubahan seiring dengan ruang dimana ia dijual. Pemanfaatan ruang ini dilakukan oleh kapital, karena mereka tentu akan merubah segala sesuatu yang disukai masyarakat banyak. Dan tentu saja akan menjelmakannya sebagai barang yang lebih bernilai tinggi.
Tindakan kapital akan diterima apabila berjalan sesuai dengan proporsi sewajarnya. Akan tetapi perlu diingat, kapital akan tampak membahayakan ketika komoditas berubah kemasan dan menciptakan 'kelas'. Akan lebih terlihat mengerikan apabila kopi sebagai komoditas dan barang konsumsi masyarakat akan dimasuki 'gengsi'.
Ternyata, kopi yang saya percaya sebagai ruang diskusi telah menciptakan apa yang disebut Karl Marx sebagai kelas sosial. Padahal kata pepatah, "di depan kopi semua adalah sama". Akan tetapi, kopi yang menjadi teman diskusi itu akan membuat orang (baca: proletar) tidak fokus berdiskusi, tapi sibuk memikirkan bagaimana membayar kopi yang ia pesan.
Kopi dan mungkin juga komoditas lain, awalnya hanya merupakan bahan produksi yang tak beitu bernilai tinggi yang mengalami kenaikan kelas. Selain kopi, juga banyak komoditas yang memanfaatkan ruang sehingga menjadi naik kelas seperti segelas kopi yang menjadi mahal jika dijual di Starbuck.
Misalnya, ketela pohon yang tumbuh di lahan-lahan miring pegunungan dengan harga sangat murah itu disulap menjadi barang konsumsi yang siap dibandrol dengan gengsi. Sego thiwul yang sangat murah apabila beli di desa saya, menjadi lebih mahal apabila dijual di restoran mewah tingkat atas. Dan juga, gethuk yang dijual di pasar tradisional seharga dua ribu rupiah akan melonjak menjadi puluhan ribu rupiah jika ditempatkan di etalase-etalase kaca kelas atas.
Jadi, sebenarnya komoditas itu tetaplah barang ndeso yang menjadi mahal ketika dikemas dan diletakkan di ruang-ruang kaca kedap suara. Sementara itu kelas sosial tercipta karena gengsi.
Sedangkan gengsi adalah jualannya kapitalisme yang paling laku. Kata teman diskusi saya, kapitalisme tidak pernah benar-benar menjual hakekat barang suatu komoditas.
Padahal hakekat kopi, bagi orang awam seperti saya, adalah perekat untuk menemani duduknya sekumpulan orang yang ingin menikmati waktu, dimana waktu itu memang sengaja diluangkan.
Akan sangat sayang sekali bagi saya, dan mungkin orang-orang yang sepemikiran dengan saya, uang yang diperoleh dari keringat seharian, hanya untuk membayar segelas kopi di caf kapital. Pernyataan ini jangan dijawab dengan asumsi "Kalau begitu tidak perlu ngopi."
Bukan budaya ngopi yang saya kritik. Saya tahu bahwa aktivitas ngopi bisa disebut ibadah oleh sebagian orang, karena dari forum itulah inspirasi, ide-ide besar bisa lahir.