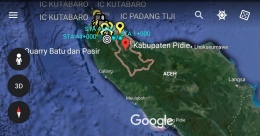Namun, situasi politik nasional berubah. Isu tentang orang asing dan etnis menggema. Kemudian opini publik pada saat itu sudah mengarah ke rasisme. Etnis Tionghoa menjadi satu-satunya sasaran kebencian.
Itu terjadi sekitar tahun 50-an, saat negara ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dalam tekanan politik, akhirnya keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1956.
PP tersebut menegaskan kembali tentang aktivitas orang asing, termasuk keberadaan dan domisili etnis Tionghoa. Isinya adalah, melarang orang Tionghoa berdagang di bawah tingkat kabupaten.
Peraturan ini memaksa orang Tionghoa yang tinggal di desa pun harus pindah ke daerah pada level kabupaten, karena berdagang di tingkat kecamatan dan desa merupakan suatu pelanggaran.
Akibat larangan tersebut, Latief dan keluarga hijrah ke Kota Sigli, Kabupaten Pidie. Sejak di kota, profesinya beralih, dari penjual pakaian menjadi peracik kopi.
Lalu, membuka kedai kopi "Ie Leube". Nama ini menurut Jhony, sebagai kenangan untuk mengingatkan bahwa keluarga mereka pernah tinggal di Desa Ie Leubeu.
Sekilas tentang Jhony, sosok yang menjadi inspirasi bertahan dalam toleransi yang "kental". Membentuk hubungan sosial dalam komunitas masyarakat Muslem mayoritas.
Kedai kopi Ie Leube bertahan hingga saat ini, meski dikepung oleh puluhan cafe-cafe besar dengan mesin pengolah kopi yang canggih.
Ie Leubeu tetap masih memiliki langganan penikmat biji kopi lokal Tangse, diracik sendiri oleh Jhony secara tradisional.
Dalam "perang bisnis kopi" jaman kekinian, keberadaan Jhony menjadi catatan terhadap makna toleransi bahwa, perbedaan itu sesuatu yang patut dihargai.
Pada saat Aceh dirundung perang politik pun, Jhony dan etnis Tionghoa lainnya masih merasa aman dan sama sekali tidak terusik. Meski di berbagai pelosok Aceh, letusan senjata kerap terjadi.