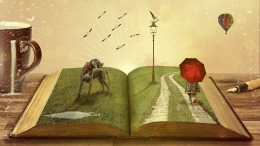Hewan, tumbuhan dan manusia sama-sama tumbuh mengikuti alur evolusi yang bersifat alamiah.
Berawal dari benih yang terjaga di dalam perut/tanah, syahdan mulai terbentuk bagian-bagian tubuh, sampai tiba fase akhir di mana tubuh tersebut keluar dari tempat persembunyiannya yang aman untuk melihat dunia.
Namun, dari kedua mahluk tadi, hanya mahluk hidup yang terakhir saja yang dapat menguasai dan merubah alam.
Seorang anak manusia baru akan mampu melakukan perubahan terhadap alam (baik atau buruknya tergantung pada proses pembelajaran yang pernah diberikan) dengan diawali serangkaian tahapan sosialisasi primer.
Sosiolog Amerika Serikat, George Herbert Mead, memberikan tahapan sosialisasi sebagai berikut:
Pertama, Tahap Persiapan (Preparatory Stage): Merupakan proses awal bagi seorang anak untuk mengenal lingkungan sekitarnya, dan memahami diri dengan meniru perkataan orang lain meski tidak sempurna.
Kedua, Tahap Meniru (Play Stage): Kondisi di mana anak sudah mampu meniru, serta dapat mengetahui peran orang lain (Ayah, ibu, kakak, adik, dsb) dengan baik.
Ketiga, Tahap Siap Bertindak (Game Stage): Anak mulai sadar dalam mengambil peran dalam lingkungan, serta bertanggung jawab atas perbuatannya.
Keempat, Tahap Penerimaan Norma Kolektif (Generalized Stage): Akhir perkembangan seorang "anak" ditandai dengan kemampuannya menempatkan diri didalam masyarakat luas.
Dengan begitu statusnya menjadi "dewasa" sebab mengamini adanya suatu peraturan dan pengetahuan baru di luar lingkungan kecilnya.
Agar tujuan dapat tercapai dengan sempurna proses sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: represif (orangtua sebagai pusat sosialisasi sehingga keinginan orang tua menjadi penting) dan partisipatoris (kebalikan dari ciri represif).
Sosialisasi primer yang terjadi didalam keluarga dengan begitu memiliki pengaruh yang sangat besar, sebab menjadi titik awal dalam mencetak pemuda-pemudi berbudi pekerti luhur atau bisa saja sebaliknya.
Lantas, bagaimana jika seorang anak hidup tanpa memiliki orangtua?
Pertanyaan tersebut tentunya mudah untuk dijawab oleh seorang alumnus dari studi Sosiologi, Psikologi dan ilmu lainnya yang berkaitan. Meski begitu, memberi jawaban saja rasanya kurang pantas jika tidak dibarengi dengan implementasi.
Absennya figur orangtua dalam kehidupan anak memang bukan menjadi fenomena baru bagi masyarakat.
Kita yang sadar betul mengenai proses tumbuh kembang anak, mungkin akan terbayang mengenai kondisi seorang anak yang tumbuh tanpa kehadiran kedua orangtua atau anak yang memiliki orangtua lengkap, akan tetapi orangtua tidak berhasil memenuhi aspek psikologis dan sosiologis si anak tersebut.
Berbagai faktor penyebab seorang anak kehilangan sosok orangtua, seperti: disorganisasi keluarga (perceraian), konflik, kematian sebab Covid-19, dsb yang secara eksplisit menghilangkan fungsi kontrol, kasih sayang, pendidikan, dsb.
Seorang anak tanpa pengawasan orangtua akan bebas memilih aturan dan pergaulan. Tanpa kasih sayang akan terbentuk pribadi yang kasar dan pembenci. Dan, anak tanpa pengetahuan akan merugikan diri sendiri sekaligus bangsanya.
Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah maupun lembaga sosial secara preventif membangun panti asuhan sebagai program andalan, saat kerabat dari orangtua si anak enggan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Anak-anak yang berhasil ditampung oleh panti atau yayasan jumlahnya pun tidak sedikit.
Kementerian Sosial (24/8/2021) dalam publikasinya menunjukkan jumlah anak binaan yang terdapat di 3.914 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tercatat per Mei 2021, yakni: berjumlah 191.696 anak yang terbagi menjadi 33.085 anak yatim, 7.160 piatu, dan yatim piatu 3.936. dengan jumlah total 44.181 jiwa.
Menurut hemat penulis, ikhtiar pemerintah dan lembaga sosial untuk menciptakan generasi mendatang di rasa belum cukup. Pasalnya, masih banyak anak-anak di sekililing kita yang tidak berada dalam lingkungan panti asuhan. Untuk itu, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung, khususnya para pemuda.
Pemilihan penulis pada pemuda bukan bermaksud mengecilkan keterlibatan golongan tua. Meski keduanya sama-sama pernah melalui proses sosialisasi primer dan sekunder, akan tetapi yang pertama (pemuda) lebih revolusioner dan memiliki waktu luang yang cukup untuk mengamalkan sensitivitasnya terhadap anak-anak yang nasibnya kurang beruntung, bukan malah khidmat dalam renungan belaka.
Alasan lainnya, penulis sering menemukan kata "pemuda" pada isi buku, jurnal, artikel dalam topik pergerakan nasional.
Kata "pemuda" sendiri menjadi awal kalimat dalam satu kalimat utuh yang jika dituliskan kembali menjadi "Pemuda sebagai agent of change".
Pernyataan tersebut memang bukan sebuah rekaan tanpa dasar. Tinta sejarah pernah mencatat bahwa pemuda memiliki andil yang begitu besar dalam proses kemerdekaan Indonesia---pada zaman pra-kemerdekaan, pemuda selalu identik dengan golongan yang mengenyam bangku pendidikan Belanda.
Ir. Soekarno mengakui pentingnya keterlibatan pemuda dalam menentukan arah peradaban bangsa, seperti yang pernah dikatakannya: "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 Pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia".
Pertanyaannya, siapa itu pemuda?
Secara terminologi kata "pemuda" sendiri memiliki banyak pengertian dari berbagai aspek. Penulis memilih definisi "pemuda" dalam aspek politis yang penulis dapatkan di dalam buku Taufik Abdullah (1994). Beliau mengartikan "pemuda" sebagai generasi baru dalam sebuah komunitas masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
Jika kita merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, definisi pemuda tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) bertuliskan: Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.
Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pemuda adalah manusia yang berumur 16 tahun ke atas, ditandai dengan kematangan berpikir serta memahami baik atau buruknya suatu perbuatan, dan progresif. Perihal kematangan berpikir, penulis mengartikannya sebagai ekuilibrium; antara pengetahuan dengan moral, sebagai syarat mutlak dalam menciptakan sebuah perubahan yang lebih baik.
Pengamalan pengalaman
Tidak dapat dipungkiri, seorang anak seringkali melebarkan koneksi pertemanan di tempat tinggal. Mereka berusaha mengenal anak-anak lain---yang kelak menjadi teman main---dari ujung ke ujung kampung. Tidak ketinggalan mereka pun mengadopsi atau mempertahankan ajaran keluarga dari nilai dan norma yang berlaku di lingkungan baru. Selain itu, kultur yang terdapat di lingkungan seperti: Bahasa, gaya hidup, dsb juga dapat mempengaruhi mereka.
Menurut Peter Berger dan Luckman tahap tersebut adalah proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi.
Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama.
Menengok kondisi anak tanpa orang tua yang sempat kita bahas diawal, urgensi saat ini dalam melanjutkan membangun peradaban bangsa yang lebih baik nyatanya memang tampak jelas sedari dulu, yakni dengan merawat anak-anak sejak dini agar memiliki budi pekerti yang luhur, khususnya anak-anak kurang beruntung---seperti sudah dijelaskan di atas---yang rentan sekali terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang seperti: kriminalitas, pelacuran, terorisme (doktrin), dsb.
Upaya menyelamatkan anak-anak dari pengaruh buruk yang ada di lingkungan, yakni dengan mengambil alih kekosongan figur orangtua seperti: memberi/mengontrol norma dan moral yang baik, memberi rasa aman dari gangguan orang lain, memberi kasih sayang atau bila perlu menafkahi lahir dan batin sekaligus (adopsi).
Pemenuhan psikososiologis secara utuh nyatanya memang sulit dilakukan oleh pemuda, meski tidak jarang juga, kita sering temukan pemuda tangguh yang berani mengadopsi anak-anak yang tidak memiliki atau yang sengaja ditelantarkan oleh orangtua.
Kita paham betul keterbatasan pemuda yang meski memiliki waktu luang, namun kelonggaran tersebut tidak sepenuhnya kosong sebab terbagi-bagi dalam rutinitas keseharian mereka yang lumrah kita ketahui seperti: bermain, olahraga, kerja/kuliah/keluarga, dsb.
Dengan begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua pemuda memiliki kepedulian pada permasalahan anak-anak korban disorganisasi keluarga atau lainnya yang ada di lingkungan mereka.
Untuk memulihkan beberapa fungsi keluarga yang telah luput dari diri anak, pemuda yang konsen pada masalah tersebut dapat berangkat dari pengalaman hidup mereka sendiri. Penulis memberikan tiga contoh pengalaman hidup yang dirasa memiliki pengaruh besar jika dibangkitkan kembali dan diamalkan kepada anak, yakni:
Pertama, para pemuda yang mendapatkan kasih sayang di dalam keluarga dapat disalurkan kembali kepada anak-anak. Misal, dengan mendengarkan keluh kesah anak dan mau menanggapi dengan menggunakan tutur kata yang halus.
Kedua, pergumulan pemuda di lingkungan masyarakat tempat mereka tinggal, di mana mereka mengetahui betul kondisi fisik (wilayah) serta seluk beluk pergaulan dan bahkan watak beberapa atau malah seluruh warga, menempatkan pemuda sebagai navigator andal bagi proses sosialisasi tahap lanjut bagi anak-anak.
Dengan menggunakan pendekatan persuasif, pemuda lantas mengajak atau membimbing anak agar menjauhkan orang-orang yang memiliki perangai buruk (pecandu narkoba, pemabuk, dsb) atau tempat-tempat negatif.
Ketiga, mencegah anak tercebur kedalam keburukan yang pernah diperbuat pemuda melalui penanaman nilai dan norma religius secara masif agar proses internalisasi dapat diterima dengan baik. Juga, melatih anak agar mampu berpikir kedepan atas setiap perbuatan yang pernah atau akan mereka lakukan melalui metode sebab-akibat.
Hasil yang akan diterima atas pengamalan dari ketiga cara tadi tidak dapat penulis tuangkan dalam paragraf selanjutnya, sebab masing-masing dari kita memiliki niat yang kadang berubah-ubah. Jika niatnya lurus dan mantap, hasil berupa perubahan yang lebih baik akan tercapai, yakni regenerasi yang cakap.
Yang pasti, dari ketiga cara diatas dapat menunjukkan kepada kita bahwa kepedulian tidak melulu soal uang. Hal-hal kecil seperti pengalaman hidup yang terasa manis atau pahit sekalipun, dapat bernilai tinggi dan bermanfaat bagi orang lain.
Hanya orang-orang brilian---bermodalkan perangkat naluri berupa sensitivitas dan dipadukan dengan pengetahuan juga idealisme. Kepaduan tersebut akan mampu membuat pemuda memilah-milah rutinitas yang nantinya menjadi prioritas--menanggalkan segala kepentingan pribadi demi masa depan peradaban bangsa.
Mereka lah segelintir orang yang disebut-sebut oleh Ir. Soekarno dalam pernyataannya tentang sepuluh pemuda (angka sepuluh lebih kecil daripada seribu). Pemuda-pemudi ideal gemar menyibukkan diri dengan terjun langsung merawat masa depan anak bangsa, sampai melupakan dalih klasik perihal mandat konstitusi yang hanya mewajibkan pemerintah untuk menjamin kebutuhan anak-anak korban disorganisasi keluarga dan anak korban lainnya.
Referensi
Abdullah, Taufik. 1994. Pemuda dan Perubahan Sosial: LP3S. Jakarta
Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana. Jakarta
Ritzer, George. 2014. Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Subadi, Tjipto. 2008. Sosiologi: BP-FKIP UMS. Surakarta
www.who.int/southeastasia/activities/adolescent-health
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009
https://kemensos.go.id/perlindungan-anak-yang-kehilangan-orangtua-akibat-covid-19
https://kemensos.go.id/kemensos-berikan-perlindungan-kepada-4-jutaan-anak-yatim-piatu
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI