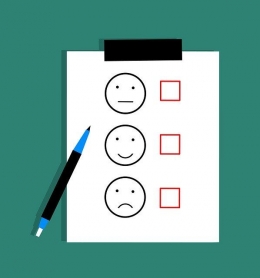"Udah buka twitter? Lagi ramai #tukangngibulnaiktahta, Bang!"
Usai maghrib, kubaca satu pesan melalui WA dari seorang teman yang suka mengamati isu-isu kekinian. Karena masih suasana berbuka, aku balas saja pesan itu dengan emoji senyuman. Tak berselang lama, kembali aku dapatkan pesan dari orang yang sama. Sesaat dahiku berkerut.
"Aku lempar ke grup, ya?"
"Untuk apa?"
"Biar..."
"Udah! Jangan ikutan jadi tukang stempel! Bahas yang lain aja, yuk?"
Tak lagi ada balasan. Pun tak ada pembahasan di WAG anak muda Kota Curup yang kuikuti. Gak tahu kalau di grup lain. Aku jadi penasaran, akhirnya kusimak cuitan netizen yang maha benar dengan segala kepintarannya. Hiks...
Reaksiku? Seperti sebelum-sebelumnya. Ada tawa, terkadang senyum sendiri, juga hadir perasaan miris plus prihatin. Ingatanku kembali pada satu puisi yang ditulis Taufik Ismail tahun 1998, kemudian judul yang sama dijadikan judul sampul buku kumpulan puisi, "Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia." (Yayasan Indonesia, 2000).
Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Dua baris itu, kukira menjadi reaksi senyap yang bisa kutuliskan, usai membaca cuitan dengan tagar seperti yang dikirim oleh temanku tadi.
Tak bermaksud membahas puisi Taufik Ismal. Hanya saja, versiku, kritikan sosial yang diajukan netizen, "kurang cantik" dibandingkan barisan kata-kata pedas yang terpahat dalam puisi Malu (Aku) Jadi Orang Indonesia. Dengan bahasa kampung, kusebut sebagai "tukang stempel".

Jika meminjam konsep kritik sastra, dengan alasan media sosial adalah budaya tulis. Maka setidaknya ada 4 Alur kritik sosial yang terbangun. Aku tulis saja, ya?
Pertama. Kritik sebagai Cermin Kehidupan.
Lontaran kritik diajukan berdasarkan dari hal yang dirasakan atau dialami oleh pemilik kriitikan. Mungkin saja ojek online yang sepi penumpang, pedagang takjil yang sepi pembeli atau pengusaha yang keberatan mesti memberikan THR, padahal situasi saat ini, curva pendapatannya melandai, jika malu mengakui ada penurunan.
Sah? Lah iya! Kan mereka merasakan langsung. Bakalan rada susah, ketika itu terlontar di media sosial. Cerminan kehidupan pribadi itu menjadi cerminan orang banyak. Penderitaan diri sendiri,menjadi penderitaan bersama. Siapa yang salah? Tak ada! Wong dunia maya tanpa batas, jadi "bola liar" kritik itu bisa melintas secara bebas.
Kedua. Kritik sebagai Ekspresi dari Pikiran, Perasaan dan Pengalaman.
Dalam hal itu, kritikan tak harus dialami atau dirasakan langsung oleh pemilik kritik. Mungkin saja kritikan itu bersandarkan dari bidang keilmuan yang dimiliki. Semisal keriuhan pemaknaan ulang dari "Mudik" dan "Pulang Kampung". Atau perbedaan dan persamaan antara "dilarung" dengan "dibuang ke laut"?
Ketiga. Kritik dengan Pendekatan Objektivitas.
Kritikan yang dilontarkan, lebih mendahulukan nilai-nilai objektifitas pemberi kritik. Semisal, semasa pemilu berada di kubu A, jika kemudian ternyata ada kebijakan non pupulis yang diambil. Ia bisa saja berseberangan. Tak peduli anggapan plinplan dan sebagainya.
Pertanyaannya, akan terbentur pada nilai objektivitas versi siapa? Sila simak di berbagai media cetak maupun elektronik. Semua berargumentasi dengan pengakuan objektif tanpa keberpihakan. Menurut siapa? Tentu saja versi masing-masing, kan?
Sama dengan poin kedua? Garis tipisnya pada pengaruh lingkungan dan kondisi sosial saat kritikan itu dilontarkan.
Keempat. Kritik sebagai Pendekatan Pragmatis
Yaitu kritik yang dipandang sebagai alat, media atau sarana untuk menyampaikan pesan atau tujuan tertentu. Alur ini, memiliki kecenderungan argumentasi yang bermuatan "menggeser atau bahkah menjatuhkan".
Semisal, yang dikritik bukan konten dan konteks dari kebijakan seseorang. Tapi isi kritikan melebar pada pribadi, orang terdekat bahkan masa lalu seseorang. Pernah membaca kritikan dengan argumentasi bernada seperti ini, kan?

Waktu jaman menulis skripsi dulu, aku diajari pakem teks yang mesti ada pada bab terakhir, "penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif, demi kesempurnaan penelitian ini." Ada yang pernah menulis kalimat seperti ini di skripsi?
Secara sadar dan "seenake dewe", kita mengharapkan kritik itu yang konstruktif (membangun). Walaupun kita tahu dan mengerti, kritik dan saran itu tak pernah ada. Kecuali di ruangan sidang skripsi. Setelah itu, berjilid skripsi terbiar disusun rapi dan berdebu. Hiks...
Nah, Alih-alih melakukan kritik secara adem seperti pakem yang diajarkan (Kukira, malah sejak Sekolah Dasar, tah?) dalam pendidikan moral dan pekerti. Letusan dan lontaran kritikan sekarang, pedas, tegas, cadas dan lebih disukai jika bernada lugas dan keras! Kata cerdas, tertinggal jauh di belakang.
Terus? Jika ternyata, setelah melontar kritik seperti itu, kemudian ternyata keliru? Pilihannya diam, atau mengajukan permintaan maaf dengan diam-diam, tah?
Balik lagi kepada dua baris puisi dari Taufik Ismail yang kukutip di atas. Mungkin, kita tak perlu lagi malu mengaku jadi orang Indonesia. Anggap saja, hal-hal aneh yang terjadi, sebagai kelucuan-kelucuan dalam dinamika berbangsa dan bernegara.
"Tekadang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai "kelucuan" bangsanya!"
Demikianlah.
Selalu sehat. Namastee!
Curup, 12.05.2020
[ditulis untuk Kompasiana]
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI