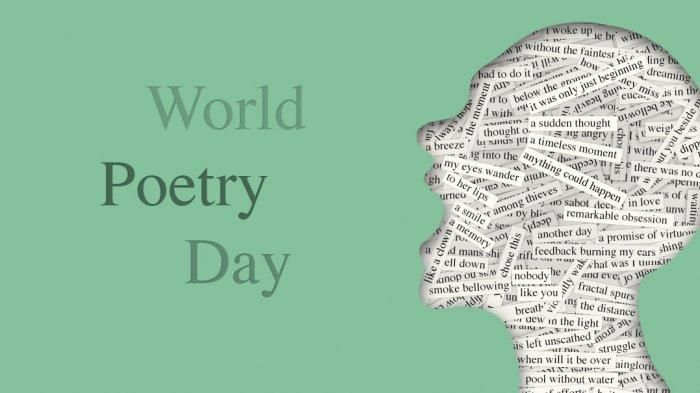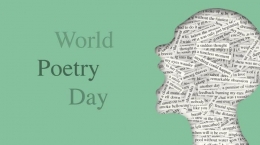Tanggal hari ini, 21 Maret disah oleh UNESCO sebagai hari puisi sedunia (World Poetry Day). Ditetapkan pertama kali pada 21 Maret 1999. Untuk Hari Puisi Nasional diperingati setiap tanggal 28 April.
Momentum ini menyisipkan, setidaknya tiga pertanyaan. Pertama. Siapa yang berhak merayakannya? Kedua. Bagaimana cara merayakannya? Ketiga. Masihkah merayakan berarti memaknai puisi?
Mari berlari pada titian tanya yang pertama. Siapa yang berhak merayakan?
Apakah para penulis puisi? Orang-orang yang dijuluki sastrawan, kah? Orang yang telah mendapat penghargaan, para pemenang lomba, para penulis dan pemilik buku puisi, kah? Bagaimana dengan para pembaca dan penikmat puisi?
Kukira, tak ada keberanian satu atau sekelompok orang untuk mengakui sebagai pihak yang paling berhak merayakan hari puisi. Ada aturan "tak tertulis", ketika sesama penggiat puisi, tak akan menduduki kepala dan wajah pemuisi yang lain.
Jika pun ada acara perayaan, maka ukuran "senioritas" (usia dan jumlah karya) yang membuat seseorang dinaikkan setingkat lebih tinggi, dan didahulukan selangkah lebih maju untuk tampil dan duduk di depan.
Coba kita menari pada undakan Tanya yang kedua. Bagaimana cara merayakannya?
Tak ada tabuh genderang yang mengisi sudut-sudut sunyi dengan berpuisi. Belum kudengar refleksi dari para pemuisi sebagai sebuah pidato kebudayaan untuk menyikapi arus global dan riak fenomena sosial saat ini.
Pilihan yang murah dan meriah adalah dengan kembali menulis puisi, atau merayakannya dengan membaca beraneka ragam puisi. Baik karya sendiri atau karya para maestro, atau memposting ulang, puisi utuh, sebagian atau cuplikan lirik dari karya mereka di media sosial.
Kemudian barisan lirik dan larik serta bunyi puisi-puisi itu kembali bersembunyi di antara langit-langit bumi. Atau, setidaknya bertengger sepi dan rapi di antara rak-rak perpustakaan yang dingin dan sunyi.
Saat mencari jawaban pada tangga tanya ketiga. Apatah dengan merayakan berarti memaknai?