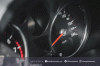Pembahasan terkait kendaraan/mobil listrik belakangan semakin marak, apalagi sejak Perpres No. 55/2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan telah diresmikan di bulan Agustus 2019.
Sejatinya mobil listrik sudah mulai digaungkan di Amerika sejak 1890an lengkap dengan prototipe nya yang saat itu masih menyerupai kereta kencana. Mobil listrik memang menawarkan keuntungan dibandingkan mobil berbahan bakar konvensional, seperti lebih ramah lingkungan dan tidak berisik.
Berbagai macam upaya telah dicoba di berbagai belahan dunia untuk membawa mobil listrik ke pasar. Walaupun kebanyakan orang mengakui dalam hati bahwa mobil listrik lebih baik untuk lingkungan dan untuk masa depan dibandingkan mobil berbahan bakar konvensional, adopsi penggunaan mobil listrik di pasar sangatlah rendah.
1
Di tahun 1990, General Motors (GM) memperkenalkan rancangan mobil listrik bernama EV1. Bak gayung bersambut, California Air Resource Board (CARB) memberikan mandat untuk produksi dan penjualan mobil dengan nol emisi (Zero Emissions Vehicles -- ZEV) sebagai sebuah persyaratan terhadap 7 produsen mobil utama di Amerika Serikat.
Kemudian di tahun 1996 GM mulai memproduksi dan memasarkan EV1. Pemasaran EV1 dilakukan melalui perjanjian leasing terbatas, yang pada awalnya diperuntukan untuk warga di Los Angeles, California, serta Phoenix dan Tucson, Arizona. Mandat tersebut juga menetapkan bahwa per tahun 1998 2% dari kendaraan yang dijual di California haruslah kendaraan dengan nol emisi, meningkat menjadi 5% target di 2001 dan 10% di 2003.
Selain EV1 keluaran GM, produsen mobil lainnya juga segera menawarkan mobil listrik mereka, seperti Nissan Altra EV, Honda EV Plus, dan Toyota RAV4 EV. Sayangnya semua program ini ditinggalkan di awal tahun 2000 karena berbagai macam kesulitan perundang-undangan dan hukum serta dari sisi konsumen yang tidak tertarik dengan biaya leasing yang tinggi, jarak tempuh yang terbatas serta belum memadainya infrastruktur untuk pengisian daya.
Dirangkum dari the Wide Lens, sebuah buku dari Ron Adner, ada 6 permasalahan yang menyebabkan kendaraan listrik dianggap sulit untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar konvensional.
1. Harga beli yang mahal
Alasan ekonomis yang banyak didengungkan untuk membeli EV adalah harga per kilometer yang lebih murah dibandingkan dengan bensin. Studi yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM menunjukkan untuk jarak tempuh 100km, mobil berbahan bakar RON (Research Octane Number) 88 menghabiskan biaya Rp 50.385 dengan asumsi tingkat konsumsi bahan bakar 13 kilometer per liter.
Selain itu, mobil berbaha bakar RON 90 menghabiskan biaya Rp 60 ribu, RON 92 sebesar Rp80 ribu, dan RON 98 Rp 94 ribu dengan harga per liter RON 88 Rp6.550, RON 90 Rp7.800, RON 92 Rp10.400, dan RON 98 Rp12.250.
Sementara itu, dengan jarak tempuh yang sama dan asumsi tarif listrik Rp1.650- Rp2.450 per kWh, mobil listrik Mitsubishi i-Miev butuh Rp24.668, Nissan Leaf Rp38.895, Hyundai Ioniq Rp35.787, dan Kia Soul EV Rp41.810. Biaya yang dikeluarkan setiap mobil listrik akan berbeda tergantung pada ukurannya. Masih berdasarkan data Kementrian ESDM, Jaguar i-Pace disebut butuh Rp55.274, Tesla Model S Rp46.468, BMW i3 Rp40.125, dan Hyundai Kona Rp40.070. Dengan demikian, dengan menggunakan mobil listrik, biaya yang dikeluarkan akan lebih hemat +/- 50%.
Harga mobil listrik sendiri cukup bervariasi. Mitsubishi i-Miev misalnya, di pasaran Jepang, harganya berkisar antara 291 -- 336. Informasi yang beredar menyebutkan, harganya dapat mencapai 500an juta jika di pasarkan di Indonesia. Sementara itu untuk kelas Tesla, harganya dapat dipastikan di atas 1M.
2. Jarak tempuh yang terbatas
Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan jarak yang dapat ditempuh untuk 1 siklus baterai. Mitsubishi i-Miev memiliki jarak tempuh maksimal 160km di Jepang atau 100km saja untuk pasar Amerika. Bluebird yang juga sudah menjajal mobil listrik untuk armada nya menyimpulkan jarak tempuh baik Tesla atau BYD rute kombinasi di jalanan Jakarta skitar 300-an km.
Sementara itu dengan metode fast charging, waktu yang dibutuhkan untuk pengisian ulang daya adalah 1 -- 2 jam. Inovasi untuk baterai yang lebih efisien tentunya akan terus dilakukan. Dengan teknologi V3 Supercharging, Tesla mengklaim waktu pengisian batere dengan jarak tempuh 120km hanyalah 5 menit.
Jarak tempuh ini tentunya tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh hitungan jarak dalam km. Faktor-faktor lainnya seperti medan atau area (jalan aspal vs berbukit), beban yang dibawa mobil (ringan vs berat), penggunaan pendingin (AC) juga tentuya akan mempengaruhi jarak tempuh baterai atau waktu pemakaian baterai.
Berdasarkan asumsi 300km untuk 1 siklus baterai, maka apabila dalam sehari pergi pulang kantor serta antar anak sekolah mencapai 60km, maka setiap 5hari sekali baterai harus diisi ulang.
3. Ketersediaan Infrastruktur pengisian daya
Permasalahan berikutnya adalah ketersediaan infrastruktur untuk pengisian daya, khususnya untuk perjalanan yang jauh. Jarak 300km kurang lebih sama dengan jarak tempuh Jakarta -- Tegal. Yang artinya, di Pulau Jawa saja, untuk mencapai Semarang, Yogyakarta ataupun Surabaya, dapat dipastikan di tengah perjalanan harus dilakukan pengisian daya.
Untuk budaya masyarakat Indonesia yang cukup sering berpergian ke luar kota atau mudik di hari raya, infrastruktur harus dibangun, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di sepanjang jalur perjalanan.
Perlu dipertimbangkan juga apabila telah diadopsi secara massal, maka EV akan menggantikan jumlah mobil yang saat ini tersedia. Sehingga berapa banyak charging point yang harus disediakan di setiap charging station dan waktu pengisian daya yang diperlukan haruslah dipertimbangkan.
Seberapa cepat adopsi EV juga akan dipengaruhi ketersediaan infrastruktur ini, yang tentunya bukan lagi chicken-egg problem, karena tanpa adanya infrastruktur yang memadai, terlalu naif untuk mengharapkan adopsi EV akan cepat.
4. Nilai jual kembali (resale)
Permasalahan ini seringkali jarang muncul di permukaan. Seperti kita ketahui, baterai memiliki umur yang terbatas yang dapat diukur dari seberapa banyak pengisian telah dilakukan. Untuk setiap pengguna handphone atau smartphone tentunya menyadari bahwa semakin sering kita menggunakan, baterai akan habis semakin cepat. Dan setiap tahunnya, performa baterai kita menurun.
Di sisi lain, kita juga familiar dengan membeli mobil baru, menggunakannya selama kurang lebih 5 tahun, kemudian menjualnya dan membeli mobil baru.
Lalu, bagaimana dengan nilai jual EV second dan kualitas baterai EV second? Ditambah lagi industri EV dan baterai yang terus menerus melakukan inovasi.
Baterai EV produksi tahun 2010 atau 2014 mungkin sudah kalah jauh dengan produksi tahun 2019. Lalu jika baterai saja yang diganti, apakah aka nada isu kompatibilitas baterai produksi tahun 2019 dengan EV produksi 2010 misalnya.
5. Penghematan yang terbatas karena jarak tempuh yang terbatas
Keuntungan dari sisi ekonomis penggunaan EV adalah harga per km yang lebih murah jika dibandingkan dengan bahan bakar konvensional. Pertanyaannya kemudian adalah jika jarak tempuh terbatas dan EV hanya digunakan di dalam kota, maka akan tetap tercipta ketergantungan untuk mobil konvensional dan keuntungan EV dari sisi bahan bakar tidak akan terealisasi dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai break-even-point dibandingkan dengan membeli mobil konvensional.
6. Kapasitas jaringan listrik
Apakah jaringan listrik yang kita miliki saat ini cukup memadai dan mampu menopang industri EV apabila sudah terjadi adopsi massal? Sebelum adanya EV saja, negara kita sudah cukup berjuang untuk memberikan pasokan listrik yang memadai di kota2 besar. Jakarta contohnya, dalam 3 bulan terakhir, berapa kali Jakarta mati lampu? Berapa kali Jakarta kebakaran?
Hal-hal ini tentunya harus dipertimbangkan. Pemerintah, PLN dan instituti manapun yang nantinya akan menjalankan inisiatif ini harus memiliki contingency plan yang baik yang dapat menjamin penyediaan layanan dasar seperti kelistrikan akan tetap berjalan normal.
Faktor lain yang perlu disimulasikan adalah perilaku masyarakat. Apabila masyarakat sudah mulai menggunakan EV, waktu yang ideal untuk mengisi daya adalah pada saat di rumah selepas pulang kerja atau semasa di kantor.
Perlu dipastikan jaringan listrik yang dikembangkan nantinya akan dapat menahan shock yang mungkin timbul apabila permintaan begitu melonjak di waktu-waktu tertentu. Jangan sampai aliran daya berkurang atau bahkan terjadi black-out.
Teknologi seperti smart grid mungkin dapat mengubah perilaku masyarakat. Akan tetapi smart grid memiliki permasalahannya sendiri terkait dengan adopsi dan implementasi yang akan mengubah pola bisnis dan juga layanan sistem kelistrikan di Indonesia dan sepertinya juga bukanlah suatu perkara mudah.
Tanpa bermaksud pesimis, kiranya tulisan ini dapat menjadi bahan kajian yang lebih mendalam untuk mensukseskan penetrasi dan keberlangsungan EV di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H