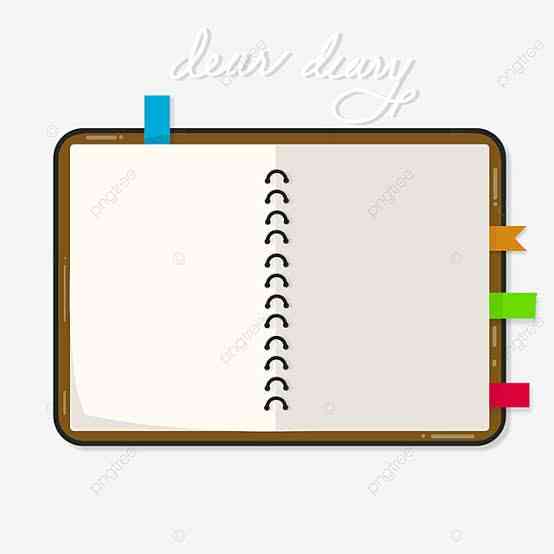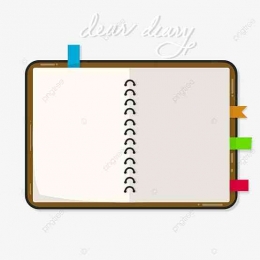"Aku bisa saja membayar semuanya sendiri, tapi itu akan membuatmu tidak punya rasa memiliki."
Itulah kalimat yang terucap, ketika suatu saat aku menyatakan agak keberatan diminta ikut patungan. Biasanya, aku memang tidak keberatan membantu, selama itu memang penting dan ada dananya.
Sekalipun ide patungan itu datang mendadak, selama segala sesuatunya masih masuk akal, itu bukan masalah. Tapi, kali ini aku dengan jujur menyatakan keberatan, karena aku mulai merasakan, kebiasaan ini agak konyol jika terlalu dituruti begitu saja.
Dalam angka pemasukan yang masih belum stabil, bisa menabung barang sedikit adalah satu berkat. Masalahnya, ketika hal-hal seperti ini mulai datang seenaknya dan angkanya semakin besar, lama-lama tidak akan ada tempat untuk tabungan, apalagi membeli kebutuhan pribadi yang butuh dana ekstra.
Kalau tidak waspada, hasil kerja selama ini pun bisa tergerus habis tanpa sempat dipakai. Persis seperti abrasi di pantai: pelan tapi pasti menggerus daratan.
Secara budaya, situasi yang aku lihat ini sebenarnya bukan hal baru. Ketika kita bisa membantu, kadang ada yang dengan seenaknya memanfaatkan sampai akhirnya "menginjak".
Prosesnya kadang sangat sangat halus, jadi kadang kita harus membuat kejutan.
Sebelum tiba-tiba kena injak, pijakan itu aku pakai duluan.
Dulu, aku belajar dari pengalaman saat dapat beasiswa semasa kuliah. Nilainya waktu itu cukup besar, tapi ludes untuk membayar berbagai biaya selama setahun terakhir masa kuliah, termasuk ongkos KKN di desa.
Aku ingat, saking hematnya, aku hanya makan dua kali sehari, dan mengerjakan skripsi sambil menahan lapar. Mentang-mentang dapat beasiswa, kesannya jadi serba lepas tangan.
Maka, ketika perilaku serupa datang lagi, memori itu langsung menjadi alarm peringatan yang berbunyi paling cerewet.
Apa boleh buat, aku terpaksa membeli ponsel baru, setengah tahun lebih cepat dari rencana awal. Kebetulan, ponsel yang lama memang sudah mulai bermasalah, setelah empat tahun digunakan.
Persetan dengan komentar "mendang-mending" dari orang yang tidak berpandangan objektif, kecuali mereka mau membelikan. Meski memang karena faktor kebutuhan, jujur saja, aku sedikit mengikuti insting, yang biasa muncul saat ada yang tidak biasa.
Jika dipadukan dengan doa dan pertimbangan matang, insting bawaan ini memang sangat ampuh, karena selalu mengarahkan ke arah yang tepat.
Makanya, ketika ada ide patungan dadakan yang di luar jangkauan, dengan santainya aku menjawab:
"Untung aku sudah ganti hp baru."
Coba kalau belum, mungkin uangnya sudah dipakai duluan untuk rencana patungan dadakan yang lain.
Entah apa dan berapa nilainya, yang jelas aku bisa saja tidak sempat membeli ponsel baru, di saat pekerjaan menuntut kondisi ponsel yang prima, baik dari segi memori atau kinerja.
Andai itu terjadi, ketika kondisinya semakin gawat, aku pasti tetap akan disalahkan, karena dianggap tidak becus menjaga barang milik sendiri. Bonusnya cuma kata-kata beracun yang berusaha menghadirkan rasa bersalah.
Di sisi lain, aku juga heran, karena kadang diminta bantu patungan, walau hanya bekerja di rumah, mengais sedikit demi sedikit remah rupiah.
Aku pernah dikatai "malas" dan sejenisnya, tapi toh tetap diminta bantuan untuk patungan. Mungkin, ini yang disebut "standar ganda". Tidak ada rasa malu, karena bisa berubah sikap dengan enaknya setelah memberi label begitu rupa.
Tapi, kalau boleh jujur, situasinya belakangan mulai sedikit menakutkan, karena aku seperti tidak boleh lengah barang sedikit saja. Jangankan uang, hadiah poin belanja online yang belum terpakai pun bisa kena injak.
Pada poin tertentu, uang memang bisa menghadirkan "standar ganda". Kalau jumlahnya banyak, mungkin "standar ganda" itu bisa dimengerti.
Bagaimana kalau masih pas-pasan? Rasanya aneh sekali. Apakah punya sedikit pemasukan untuk ditabung itu sebuah dosa? Apakah menikmati hasil kerja sendiri itu dilarang?
Kalau bekerja tapi tidak ada yang bisa ditabung, bahkan angka minusnya semakin besar, bukankah itu adalah sebentuk pemiskinan?
Aku hanya bisa bersyukur, karena ada yang menyebutku orang berkategori tengah-tengah alias biasa. Konon katanya, aku "tidak bodoh tapi tidak pintar".
Buat sebagian orang, mungkin ini sebuah pertanda buruk, tapi buatku ini pertanda baik. Aku sendiri memang hanya ingin hidup, bekerja, berkeluarga dan mati secara biasa.
Berada di satu titik ekstrem selalu berbahaya. Terlalu bodoh rawan dimanipulasi, terlalu pintar bisa membuat seseorang jadi manipulator handal. Sudah terlalu banyak contohnya,mereka ada di mana-mana
Dear Diary,
Terima kasih sudah boleh mendengar semua yang ingin kukatakan. Mungkin, ini akan membuatku terlihat seperti seorang yang menempuh jalan pedang yang sangat sunyi.
Tapi, inilah satu jalan untuk belajar lebih berani berkata "tidak", disaat "tidak" memang jadi jawaban yang tepat, supaya bisa tetap waspada, tanpa kehilangan nyali di lingkungan yang terlalu dominan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H