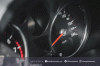[caption caption="Ilustrasi Konvoi Jalanan"][/caption]
Menjadi Bagian dari Massa
Mungkin sebagian besar dari kita pernah berada di sebuah kerumunan. Kerumunan di sini diartikan sebagai sebuah kumpulan individu yang bersifat spontan dan tidak permanen, disatukan oleh sebuah insiden atau peristiwa yang sama dan di lokasi yang sama, misalnya sama-sama menonton dangdut, ikut memperhatikan ketika terjadi kecelakaan di jalan atau ikut mengejar orang yang diteriaki copet di pasar (Milgram, 1977). Apa yang kita lakukan saat itu adalah berpikir, berpendapat dan bertindak seperti orang yang lain dalam kerumunan itu. Kemudian kita akan pergi mengurus kembali urusan kita, kita ke rumah atau bertemu teman-teman lalu menceritakan apa yang dilihat seolah kita tahu persis apa yang terjadi barusan.
Kita juga pasti pernah menjadi bagian dari massa, massa diartikan sebagai kerumunan yang tidak bergerak sendiri melainkan digerakkan atau dimobilisasi, asalnya heterogen namun tampil cenderung homogen, dan diikat oleh sebuah identitas yang sama meskipun secara pribadi tidak saling mengenal. Singkatnya, massa adalah kerumunan yang terorganisir (Davis, 1960). Saat kita hadir sebagai suporter sebuah tim sepakbola, ikut demonstrasi, atau ikut pawai oleh komunitas sepeda motor saat itulah kita menjadin bagian dari sebuah kelompok massa.
Saya teringat saat masih muda saya ikut kampanye sebuah partai politik, bermodal kaos partai hasil pembagian dan sepeda motor yang dilepas peredamnya, saya bergabung dengan kelompok besar yang lain lalu konvoy sepanjang jalan memperdengarkan raungan knalpot yang memekakkan telinga. Yang saya rasakan saat itu adalah kepuasan karena bisa ikut merayakan kebebasan berekspresi, namun ada rasa yang lebih pribadi yakni menikmati kekuasaan. Dalam massa ini, saya merasa aman, meski knalpot saya membuat orang marah namun dia tak akan berani menghentikan saya. Tentu saja karena jumlah kami banyak.
Pada kesempatan lain, saat sudah lebih tua, saya juga pernah mengikuti sebuah rombongan resmi tamu negara. Saya menjadi bagian dari tim tamu negara tersebut. Sesuai perundangan, kami memang harus dikawal oleh vorijder polisi sampai tujuan dan kembali. Maka melesatlah kami dengan kecepatan tinggi melibas semua jalan, raungan sirine memaksa semua orang berhenti dan menyingkir. Kadang saya jengkel ketika rombongan harus berjalan pelan karena terhalang kereta kuda dan ibu-ibu kikuk yang naik motor sambil membawa anak-anaknya, pada akhirnya mereka terpaksa tersuruk-suruk ke pinggir jalan karena tak tahan dengan klakson yang terus dibunyikan. Sungguh kuasa itu nikmat. Namun setelah melihat kejadian itu -kusir yang panik karena harus mengatur kudanya serta ibu yang ketakutan dan hampir jatuh dari motor- ada rasa tak enak dalam hati saya. Mereka lah yang setiap hari lewat jalan itu, ya kuda ya motor, apa salah mereka kok harus tersingkir? Itu lah perasaan saya, ada rasa bersalah yang muncul apalagi jika ingat, saya pun pernah dalam posisi si kusir dan ibu tadi dan saat itu rasanya ingin saya melempar konvoi yang lewat itu dengan batu. Saya yang tentu bukan orang penting dalam rombongan itu tiba-tiba merasa jadi bagian orang penting yang harus mendapat keistimewaan.
Berkaca dari peristiwa Jogja
Sejak akhir minggu lalu media ramai oleh perdebatan soal aksi pengadangan oleh pesepeda terhadap rombongan konvoi Harley Davidson yang sedang punya hajat di Jogja. Meski ujungnya sudah berakhir baik antara aktivis pesepeda dengan pengikut konvoy HD namun ada sebuah pelajaran yang sayang jika dibuang begitu saja.
Perilaku konvoi, apapun itu, pasti melewatkan jumlah yang banyak. Jumlah banyak membutuhkan pengaturan agar tidak bersinggungan dengan kepentingan publik yang lain secara luas. Apapun konvoi itu, baik sepeda, andong, sepeda motor, mobil bahkan rombongan kematian pun tentu akan berdampak secara luas karena menggunakan sarana jalan umum yang digunakan oleh siapa saja mulai dari pejalan kaki sampai pengendara mobil besar. Kenapa terjadi insiden pun semua orang sudah tahu berkat informasi yang berjalan cepat dan luas, namun yang kemudian membuat persoalan membesar adalah adanya reaksi yang muncul baik dari pengendara HD maupun dari kepolisian. Reaksi ini adalah ketidakterimaan atas kritik dan aksi pengadangan itu dari peserta konvoi dan kengototan polisi bahwa mereka sudah benar dalam melakukan tindakan pengawalan yang dirilis di akun Facebook Divisi Humas Mabes Polri. Terlepas dari betapa multiinterpretasinya pasal yang digunakan, kita semua sudah tahu dan karena itu tidak akan dibahas di sini.
Yang kemudian dipojokkan adalah kelompok atau klub penggemar Harley Davidson. Kelompok ini bukanlah sebuah organisasi yang tidak terorganisir, pun juga bukan kelompok yang sering terlibat kriminalitas di jalan layaknya begal motor, kelompok ini juga sering melakukan kegiatan sosial yang bersifat karitatif. Latar belakang pengendaranya beragam namun dominasinya adalah pengusaha dan pensiunan polisi, pejabat dan kalangan artis, namun tak sedikit juga adalah warga biasa. Secara pendidikan juga bukan dari kalangan tak berpendidikan saya pikir. Singkatnya, mereka bukan orang jahat.
Lalu mengapa nama kelompok Harley Davidson begitu buruk? stigma yang umum adalah arogan dan ugal-ugalan, orang kaya sok kuasa, dan seenaknya di jalan (sumber dari berbagai media). Namanya juga stigma, jadi biasanya bersifat generalis. Tapi di sisi lain muncul pertanyaan, mengapa orang-orang baik ini menjadi agresif ketika di jalan atau saat dikritik oleh pesepeda dan warga masyarakat? Lalu kenapa pula polisi malah defensif dan keukeuh menyodorkan pasal untuk menjustifikasi langkahnya? Sebaiknya kita mencoba memahami perilaku massa secara lebih dalam, dan entitas massa ini tidak hanya klub HD melainkan massa apa pun itu.
Deindivuasi dalam massa dan kecenderungan agresi
Paling tidak ada dua variabel yang menurut saya mempengaruhi perilaku orang di jalan khususnya ketika berada di tengah massa. Yang pertama adalah adanya fenomena deindividuasi, sedangkan yang kedua adalah karakter pribadi otoritarian. Kedua variabel inilah yang membentuk sifat pribadi apabila berada dalam suatu kelompok massa.
Dari perspektif psikologi, deindividuasi berarti hilangnya kesadaran seseorang sebagai seorang individu dalam kelompok (Manstead & Hewstone, 1996). Maka tak heran apabila seorang yang mengalami deindividuasi ini lebih mengedepankan “kita” daripada “aku”, selebihnya ia akan mengikuti norma maupun perilaku kelompoknya. Konsekuensi dari “kita” yang dominan ini kemudian adalah fenomena anonim atau menghilangnya individu digantikan dengan identitas kelompok. Anonimitas mengarah pada berkurangnya tanggung jawab pribadi. Sama seperti saya saat ikut konvoi kampanye, saya berani karena banyak temannya, makanya peserta kampanye saat itu berani memukul orang yang tidak mengacungkan jarinya seperti mereka. Semakin besar sebuah kelompok massa, maka semakin kecil identitas diri. Akan lebih parah lagi apabila deindividuasi ini mengarah pada kriminalitas karena seseorang dalam kelompok besar tidak akan merasa bersalah ketika melakukan tindakan agresi karena dianggapnya sebagai sikap kelompok.
Variabel kedua adalah kontribusi “kepribadian otoritarian” yakni suatu bentuk kepribadian individu yang ditunjukkan dengan karakteristik kepatuhan yang berlebihan pada penguasa, tunduk pada otoritas, kaku pada perilaku konvensional dan mengambil sikap bermusuhan dengan orang yang berbeda atau minoritas (Altameyer dalam Taylor, Peplau dan Sears, 1994). Yang terjadi pada individu dengan karakter seperti ini adalah berusaha mencari figur penguasa karena ingin menikmati kekuasaan juga. Perilaku inilah yang akan menemukan muaranya dengan deindividuasi di atas menghasilkan pribadi anonim yang nyaman dalam kelompok, agresif terhadap kelompok lain yang dianggap lebih rendah, namun sangat taat pada perintah penguasa.
Kombinasi antara dua variabel ini yakni deinviduasi dan pribadi otoritarian akan menghasilkan manifestasi agresi. Hal inilah yang terkadang tanpa kita sadari terjadi pada kita saat tengah berada dalam suatu massa, saat identitas kita terlarut oleh identitas kelompok dan secara pribadi kita merasa nyaman dan terlindungi karena ada otoritas yang membela kita maka kita seolah mendapat kebebasan besar untuk menentukan siapa yang rendah dan siapa yang tinggi. Kelompok yang rendah layak disingkirkan karena hanya mengganggu kemapanan. Namun perasaan ini akan hilang ketika tidak berada di dalam kelompok, seseorang dapat berubah menjadi ayah yang sangat lembut pada anak-anaknya, pemuda yang sangat santun pada orang tua, atau seorang wanita yang sangat ramah dan simpatik pada semua temannya. Semua tergantung dari sejauh mana tingkat anonimitas serta seberapa otoritarian kah pribadinya.
Kembali ke jalan, suguhan hirarki kekerasan tampak jelas di sana, pejalan kaki disingkirkan motor bebek, motor bebek disingkirkan motor besar, motor disingkirkan mobil, mobil disingkirkan mobil sport, dan seterusnya. Saya berani taruhan bahwa konvoi kelompok paling “kuat” ini pun akan minggir ketika ada rombongan polisi atau tentara lewat meskipun mungkin hanya rombongan pengantar pengantin saja atau sepulang latihan, yang tentu saja tak ada urgensinya untuk mendapat prioritas. Hal ini dikarenakan pada konformitas mereka pada otoritas. Tentara dan polisi adalah pemegang otoritas, karena itu harus dihormati atau ditakuti.
Solusi atau Masalah
Di ujung tulisan ini, polisi akan menjadi muaranya. Kenapa begitu, karena polisi memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku yang potensial negatif di atas atau membiarkan potensi berbahaya itu?
Apa yang terjadi pada insiden Jogja justru menempatkan polisi menjadi bahan kritik karena reaksi polisi saat insiden justru abai dengan pelanggaran di depan matanya, saat mendapat kritik kemudian justru polisi defensif di balik pasal karet. Dalam hal ini justru yang dilakukan Ketua HDCI Jogja Gatot Kurniawan dan Komjen (Purn) Nanan Sukarna sebagai Ketua IMI dengan meminta maaf dan memberikan teguran pada anggotanya yang melanggar aturan adalah sangat simpatik. Kenapa polisi tidak melakukan ini?
Rasanya praktik pembelaan diri serta menutup diri terhadap kritik dan masukan masyarakat ini bukan bahan kampanye yang bagus untuk Polri untuk mewujudkan Grand Strategy Polri 2005-2025. Grand strategy ini telah dua periode berlalu: 2005-2010 untuk trust building, 2010-2015 untuk kemitraan yang kuat, dan 2016-2025 menuju pelayanan yang efektif dan efisien. Kenyataannya, untuk mendapat simpati baik dan trust dari masyarakat pun Polri belum mampu (Kompas, 4 Mei 2015). Bukan saatnya lagi polisi bertindak otoriter dalam menginterpretasikan perundangan tanpa mengindahkan peran atau masukan masyarakat. Polisi semakin dituntut untuk profesional namun di sisi lain juga membuka diri terhadap partisipasi masyarakat agar kemitraan dengan masyarakat dapat diwujudkan. Bukankah ini merupakan cita-cita Polri?
Mengatasi perilaku agresi
Lalu bagaimana cara mengurangi munculknya agresi yang dilakukan massa ini, dalam hal ini termasuk semua jenis konvoi jalanan baik moge, mobil, sepeda motor, atau sepeda sekalipun? Kita tidak bisa melarang orang berkumpul dan berinteraksi dalam komunitas, namun sebaiknya semua menjadi mitra bagi pihak keamanan agar bisa dipantau aktivitasnya. Dan bila melihat penjelasan pada variabel kepribadian otoritarian di atas, usaha untuk mengurangi tendensi agresi adalah penggunaan otoritas secara konsisten. Dalam hal ini penggunaan polisi adalah untuk menjaga konsistensi penegakan hukum untuk mengatur perilaku massa. Oleh karena itu pasal bahwa polisi berhak melakukan pengawalan konvoi memang masuk akal namun bukan dalam kerangka memberi previlese kepada sekelompok orang dan mengorbankan kepentingan umum. Justru target yang ditertibkan seharusnya massa konvoi, bukan masyarakat pengguna jalan lain. Polisi jelas punya wewenang dan kuasa untuk itu, tak ada yang bisa membantah.
Keberadaan penegak hukum adalah wakil otoritas, dan massa sangat menjunjung tinggi aturan dan menghormati figur pemegang otoritas, maka polisi dan pemegang otorita lain harus menjalankan aturan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, jangan memberikan keistimewaan karena justru seolah akan “membenarkan” apapun tindakan mereka. Dengan model ini niscaya mereka akan mengikuti. Pelajaran dari insiden Jogja menunjukkan sebaliknya dimana polisi menjadi semata pembuka jalan dan memberikan teladan untuk mengabaikan aturan lalu lintas, yang tentu saja diikuti oleh massa yang mengikutinya.
Ke depan kita mengharapkan polisi dapat menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional. Kita sangat mengapresiasi ketika polisi bekerja keras mengatur kepadatan saat lebaran misalnya, demikian juga saat polisi mengawal demonstran agar tak ada ekses ke masyarakat umum. Hal yang sama juga kita harapkan pada tugas pengawalan kelompok konvoi jalanan karena kita tentu mengharapkan jalanan yang aman dan tertib untuk semua orang (ll)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H