Orang tua kita sering menasehati kita, belajar yang rajin, biar pinter, nanti bakal jadi orang sukses. Tapi Clifton Dan Rath,dari Harvard University meneliti tentang Emosi Positif, lebih tepatnya mencari hubungan antara IQ tinggi dengan tingkat kebahagiaan dan kesuksesan. Dan mereka menemukan sesuatu istimewa tersebut.
Pertanyaan kuncinya, apakah sebaiknya kita mendidik anak pintar atau anak bahagia?. Jika harus memilih salah satu, pastilah setiap orang tua akan menjawab, "anak bahagia".
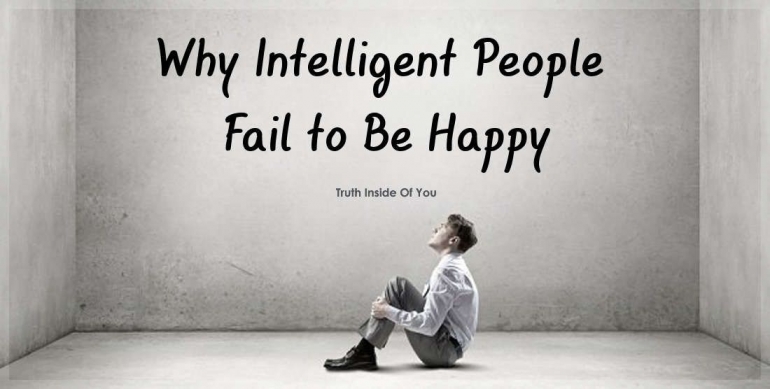
Dengan kata lain prioritas dari mendidik adalah membuat anak bahagia. Buat apa pintar, cerdas tapi tidak bahagia. Bagaimanapun bahagia tidak dilarang meskipun IQ kita "jongkok".
Bahagia atau pintar

Jadi apa sebenarnya harapan kita ketika memasukan anak kesekolah dan mendapatkan pendidikan?.Ada tiga hal yang harus menjadi titik fokus perhatian kita, dalam proses pendidikan, salah satunya untuk membuat anak-anak tak sekedar punya IQ tinggi, tapi juga punya karakter untuk menjadi sukses.
Pertama; melejitkan daya ke-manusiaan dengan memiliki kreatifitas dan daya imajinasi. Semakin tinggi kedua faktor itu, membantu manusia menciptakan banyak gagasan yang semakin memudahkan hidup mereka. Anak-anak tidak hanya harus sehat mental, namun juga harus sehat sosial. Anak-anak yang berinteraksi lebin intensif dengan lingkungan sekitar akan memiliki sikap yang lebih dinamis, fleksibel, dan penuh imajinasi. Daripada anak-anak yang terkurung dan hanya bergaul dengan lingkungan terbatas.
Kedua; meningkatkan kecerdasan untuk hidup yang lebih baik. Seperti di sampaikan Robert Kiyosaki, ada kecenderungan anak-anak yang bernilai C justru lebih banyak menjadi pemimpin bagi anak-anak bernilai A. Karena faktor karakter C yang cenderung tidak terbebani dengan persoalan mendasar, seperti ketakutan gagal. Sedangkan anak-anak bernilai tinggi cenderung terbiasa untuk takut gagal karena terbiasa dengan ukuran-ukuran yang kaku tentang nilai saja.
Ketiga; agar setiap manusia memiliki karakter-moralitas yang baik. Apa yang lebih berharga dari sebuah moralitas yang baik yang diterima langit dan bumi. Meskipun ada asumsi yang mengatakan untuk sukses harus "banyak bersikap intoleran", karena terlalu toleran membuat semua "otorisasi" berjalan lambat. Dalam banyak realitas yang terjadi, pada akhirnya sikap dan emosi positif justru yang bisa membuatnya lebih bahagia di atas kesuksesan yang diraihnya.
Dengan catatan itu, anak cerdas tanpa karakter-moralitas, bisa menjadi sebab ia tidak hanya bisa gagal tapi juga tidak dapat mencapai kesuksesan. Jika ia tidak "merusak" orang lain, dengan karakternya yang buruk, ia merusak mentalitas dirinya sendiri. Jadi bisa saja anak yang pintar, belum tentu ia bahagia. Jangankan kebahagiaan, kesuksesan saja ternyata tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kepintaran.
Lebih tepatnya, penelitian Clifton dan Ruth ingin menjelaskan, kesuksesan tak ada hubungan sama sekali dengan kepintaran dengan ukuran IQ. Karakter-moralitas yang positif, menjadi emosi positif yang membangun kebahagiaan dan kesuksesan itu. Jadi anak-anak pintar dengan karakter tertentu berpeluang menjadi lebih bahagia, dibandingkan anak yang kurang pintar, tanpa karakter positif.
Pintar dengan dukungan karakter

Masih ingat dengan cerita " sekolah rimba", ketika kucing, bebek, diharuskan melakukan kegiatan yang sama. Memanjat, berenang, terbang. Apa yang terjadi, kucing yang mahir memanjat, tidak berdaya ketika harus berenang, apalagi terbang.
Demikian juga bebek, ketika harus memanjat. Mendorong mereka menjadi lebih pintar dengan cara tidak bijaksana, yang memaksa (push parenting atau pusch teaching) mengakibatkan anak-anak kehilangan peluang untuk memiliki karakter yang mendukungnya untuk bahagia dan pintar.
Anak kehilangan kemampuannya, untuk mengontrol dirinya sendiri, kejujuran dan integritas, tanggungjawab, dn kesiapan menghadapi perubahan dan keterbukaan ide-ide baru.
Karakter harus dibangun dalam proses yang panjang dan lama, baru bisa terinternalisasi menjadi "habit". Butuh kenyamanan bukan "tekanan" seperti kisah "sekolah rimba".
Tekanan-tekanan akibat proses belajar mengajar yang kaku di se,kolah, di rumah dan dalam lingkungan bermain menganggu Self esteem atau harga diri anak-anak sebagai syarat utama pendidikan membangun karakter.
Sistem pembelajaran konvensional di sekolah yang menempatkan guru sebagai "penguasa" yang tidak dapat dibantah, mengkritik, memaksa, bahkan mengabaikan anak-anak adalah salah satu kesalahan laten yang juga berkontribusi menyebabkan hilangnya anak-anak pemberani yang dengan cepat dapat bereaksi untuk menunjuk tangan jika di beri kesempatan bertanya,kehilangan karakter positifnya.
Pernahkan kita menyadari mengapa guru-guru kita kebingungan, ketika anak-anak menjadi vacum dikelas?. Sejak lama, anak-anak telah kehilangan self esteem-harga diri, sebagai seorang anak-anak yang merdeka.
Tekanan-tekanan dari lingkungan, termasuk sekolah,menyebabkan kehilangan karakter positif itu semakin akut seiring naik di jenjang sekolah lebih tinggi. Di TK ia diajari untuk "membebek", di SD, tak bisa menulis dan membaca adalah anak bodoh.
Di SMP, SMA dan bahkan PT, anak-anak kita menjadi para pengecut, yang sekedar bertanya saja bisa dianggap sebagai kesalahan dan kebodohan, karena sejak awal, anak-anak dengan "pertanyaan lugu" disamakan dengan "pertanyaan bodoh".
Harus ada perubahan paradigma yang tidak hanya mendorong anak-anak sekedar menjadi pintar dengan ukuran nilai dan IQ, karena anak-anak pintar tanpa memilik karakter yagn kuat untuk sukses, juga mengalami kesulitan yang sama besarnya dengan mereka yang ber-IQ rendah. Bahkan anak-anak ber-IQ rendah bisa saja lebih memiliki potensi untuk sukses jika mereka didukung oleh karakter-karakter yang dapat melahirkan Emosi Positif, seperti temuan Clifton dan Rath.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H










