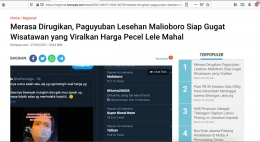Seorang wisatawan belum lama ini membagikan pengalaman kulinernya di Yogyakarta. Lewat media sosial ia mengeluhkan harga pecel lele yang sangat mahal di Malioboro. Dianggap merugikan reputasi Malioboro dan PKL di tempat tersebut, Paguyuban Lesehan Malioboro berencana menuntut sang wisatawan. Sebab kejadiannya dianggap bukan di Malioboro, tapi di "sirip Malioboro". Penjualnya juga belum menjadi anggota paguyuban.
Sebenarnya sudah kerap hal ini terjadi. Yakni pengalaman wisatawan yang merasa kena "getok harga" saat jajan di Malioboro.
Sekarang tentang pecel lele yang dianggap overprice karena setiap komponennya, mulai dari nasi, lele, dan lalapan dihargai cukup tinggi. Pro dan kontra bermunculan. Aspek yang diperdebatkan bukan hanya harganya yang Rp37.000, tapi juga sikap pembeli dan penjualnya.
Berbagai sudut pandang menjadi landasan argumentasi. Ada yang menganggap harga Rp37.000 tidak terlalu mahal dengan menimbang status dan gengsi Malioboro sebagai ikon wisata terbesar di Yogyakarta. Sedangkan sebagian orang menilai harga tersebut kurang wajar.
Ada yang mengkritik pembeli karena tidak memperhatikan harganya secara detail. Apalagi jika ia tak menanyakan dulu harganya sebelum memutuskan jajan. Jika sudah bertanya dan tidak cocok karena dianggap kemahalan, tinggalkan tempat tersebut.
Ada yang menganggap harga tersebut mestinya tidak terlalu dipermasalahkan jika memang sudah sebesar itu harga yang ditetapkan sejak awal oleh penjual. Pembeli tak bisa protes jika sudah menikmati pecel lelenya.
Yang jadi masalah ialah jika pembeli tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya dari sang penjual ketika kejadian. Wajar jika pembeli merasa terjebak.
Kurang tepat menyalahkan pembeli jika ia tidak bertanya detail sebelum memesan. Bertanya harga memang perlu. Namun, apakah kita juga akan menanyakan atau memikirkan harga irisan timun dan bawang goreng jika memesan nasi goreng? Rasanya tidak lazim harga sepiring nasi goreng dihitung berdasarkan banyaknya potongan timun dan jumlah tebaran bawang goreng di atasnya.
Sama halnya harga pecel lele. Lazimnya di Yogyakarta harga pecel lele sudah termasuk lalapan dan sambal. Ada pula yang sudah termasuk nasi. Kecuali jika pembeli menambah porsi nasi dan lalapan.
Penjual memang boleh menentukan harga masing-masing komponen hidangannya. Tidak terlalu masalah kalau dengan cara itu penjual ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Kita pun sudah sering punya pengalaman memesan makanan yang harga nasi, lauk dan pelengkapnya masing-masing dihitung terpisah. Seperti halnya jika kita memesan minuman kekinian yang harganya bisa berbeda-beda tergantung ukuran gelas, jenis topping dan banyaknya topping yang ditambahkan. Kita menganggap wajar cara penghitungan harga seperti itu.
Tapi berbeda makna jika penjual sengaja kurang terbuka soal harga sehingga pembeli tidak mengetahui perbedaan "harga lele", "harga seporsi pecel lele", dan "harga seporsi pecel lele lengkap dengan nasi, lalapan, dan minuman".
Ada cara untuk mengukur apakah harga pecel lele ini bisa diterima sebagai kewajaran atau memang ada praktik yang sengaja dilakukan oleh penjual untuk "mengerjai" pembeli. Yakni, dengan menghimpun pengalaman orang-orang yang pernah jajan di penjual yang sama dalam rentang waktu yang berdekatan, khususnya sebelum dan sesudah korban jajan di tempat tersebut.
Barangkali ini akan mendorong munculnya lebih banyak "testimoni". Harapannya bisa diketahui apakah harga yang ditetapkan kepada para pembeli lainnya juga sama. Akan diketahui pula sejauh mana penjual "konsisten" menerapkan cara penghitungan harga yang sama kepada para pembeli.
Kalaupun ada yang mencoba melakukan "social experiment" untuk mengulang kejadian dengan sengaja jajan di tempat tersebut, memesan menu yang sama, lalu menanyakan detail harganya lebih dulu, maka bisa diukur pula sejauh mana kesalahan pembeli atau sejauh mana kejujuran penjual.
Cara demikian rasanya lebih tepat dibanding argumen-argumen yang seolah-olah ingin membela harga mahal kuliner di Malioboro. Pendapat bahwa Malioboro merupakan tempat wisata yang terkenal sehingga wajar jika harga makanannya mahal, justru bisa melanggengkan praktik "getok harga" atau "jebakan harga" di Malioboro.
Demikian pula argumen bahwa biaya sewa lapak di kawasan Malioboro tidak murah sehingga pantas kalau harga kuliner di sana ditetapkan lebih mahal. Bahkan, ada argumen yang mencoba menghubungkan harga mahal dengan efek pandemi lewat pesan bijak, "Guys, kalau makan di PKL tolong jangan protes harganya ya. Mereka sedang kesulitan karena pandemi Covid-19".
Argumen-argumen pembelaan tersebut meski ada unsur kebenarannya, tapi seolah ingin meminta masyarakat untuk memaklumi jika ada penjual yang memasang harga sangat mahal dengan tidak terbuka lebih dulu kepada pembeli.
Di sisi lain kurang tepat pula jika langsung mengarahkan pandangan buruk ke PKL dan pengusaha kuliner di Malioboro secara umum. Setidaknya di tempat ini masih ada pecel sayur seharga Rp10.000 dan nasi kucing Rp2000.
Oleh karena itu, sang wisatawan atau pembeli ini juga perlu bersikap sejujurnya. Apakah ia benar-benar tidak tahu harga pecel lele yang dipesan atau sebenarnya ia sudah tahu sebelumnya, tapi baru menyesal setelah menikmatinya. Jika demikian maka tidak pantas ia merasa diperdaya. Bahwa harga mahal benar adanya, tapi pembeli telah menyadari dan memilihnya.

Soal rencana menggugat sang wisatawan atau pembeli yang mengeluh di media sosial, lebih baik pihak-pihak di Malioboro memperbaiki pengawasan dan membangun sistem pengaduan yang efektif. Sebab selain kisruh pecel lele ini, sudah banyak pengalaman serupa yang mempersoalkan harga kuliner di Malioboro.
Perlu dievaluasi sejauh mana Malioboro yang selama ini dibanggakan sebagai destinasi wisata utama, termasuk wisata kuliner, sudah memiliki "saluran konsumen" untuk menerima keluhan wisatawan.
Semacam nomor hotline mestinya tersedia dan bisa diakses atau diketahui oleh pengunjung Malioboro secara mudah. Perlu juga memaksimalkan fungsi pusat informasi turis yang ada agar bisa menjadi posko pengaduan yang berfungsi dengan baik.
Mengeluh di media sosial akhirnya menjadi pilihan wisatawan, salah satunya karena tidak jelas ke mana mereka perlu mengadu jika merasa dirugikan. Belum pasti pula apakah aduannya akan ditanggapi atau malah akan mendapat jawaban: "Kalau nggak mau mahal, jangan jajan di sini", "Lokasi menentukan harga", dan sejenisnya.
Jangan sampai ada kesan "Wisata Kuliner Malioboro Hanya untuk Para Sultan". Artinya orang yang dompetnya tipis dilarang jajan di Malioboro. Kalau tetap jajan, pembeli dilarang protes. Seperti halnya dilarang mengkritik Jogja jika KTP nya bukan KTP DIY.