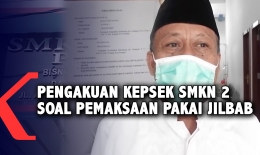"Guru di Indonesia, mulai dari jenjang TK sampai SMA/Madrasah memiliki pandangan intoleran dan radikal yang tinggi. Sebanyak 33 % di antaranya setuju menganjurkan berperang untuk mewujudkan negara Islam".
Begitulah temuan umum dari studi dan survei yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah pada 2018 silam. Temuan yang mengejutkan karena proporsi guru yang memiliki kecenderungan intoleran dan radikalis ternyata cukup besar. Namun, tidak terlalu mengherankan sebab indikasinya telah tampak sejak lama.
Pada sebuah kesempatan di Universitas Gadjah Mada, Suhardi Alius yang saat itu menjabat kepala BNPT mengungkapkan bahwa intoleransi dan radikalisme telah menyebar luas di tengah masyarakat, termasuk ke lembaga pendidikan. Bahkan, seorang anak PAUD bisa memiliki sikap intoleran dengan tidak mau bersosialisasi karena menganggap orang lain sebagai kafir.
Maka dari itu kasus di SMK 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim mengenakan jilbab bukanlah persoalan baru. Penyimpangan yang dibungkus aturan sekolah dengan dalih melindungi akhlak, kearifan lokal dan menghindari gigitan nyamuk, pada dasarnya merupakan praktik intoleransi yang terakumulasi sejak lama.
Pabrik Intoleransi
Tak bisa dielak bahwa intoleransi telah merembes ke dalam ruang-ruang kelas. Paparannya menjangkiti kaum pendidik dan menular kepada para murid.
Ironis. Sekolah yang mestinya menjadi lembaga pengajaran dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, multikulturalisme, serta moderasi beragama, justru mempraktikkan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila.
Kasus SMK 2 Padang hanya segelintir contoh dari praktik serupa yang terus berulang di berbagai tempat. Banyak contoh lainnya. Antara lain tentang guru di Jakarta yang menganjurkan murid-muridnya untuk tidak memilih siswa nonmuslim dalam pemilihan OSIS.
Kemudian pada 2019 di Gunung Kidul, Yogyakarta, sebuah sekolah dasar juga menjadi sorotan karena mewajibkan murid-muridnya mengenakan pakaian muslim. Sebelumnya di Banyuwangi seorang murid terpaksa gagal mendaftar ke SMP negeri karena sekolah tersebut mewajibkan semua siswi menggunakan jilbab.
Ada pula penolakan upacara bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya di sebuah sekolah. Lalu kontroversi seruan "Tepuk Tangan Anak Saleh" yang liriknya diubah dan dinyayikan menjadi "Islam Yes, Kafir No". Tak boleh dilupakan tentang ajaran-ajaran intoleran dan radikal yang disisipkan ke dalam materi buku pelajaran sekolah.
Semua itu mengisyaratkan tingginya potensi intoleransi di lingkungan sekolah. Ada kecenderungan sekolah telah menjadi salah satu pabrik intoleransi. Tempat di mana bibit pandangan-pandangan intoleran bersemi, tumbuh, disebarkan hingga membuahkan perilaku serta praktik intoleran.
Tingginya potensi intoleransi di sekolah ikut dipengaruhi oleh sistem kebijakan yang melahirkan produk-produk berupa aturan sekolah. Tak jarang kepala daerah dan elit-elit politik di daerah mendukung penerapan aturan-aturan yang mengarah ke praktik diskriminasi dan intoleransi.
Kasus SMK 2 Padang adalah salah satu contohnya. Dengan alasan aturan sekolah semacam itu sudah ada sejak lama sehingga harus ditaati, pihak-pihak terkait menolak dianggap memaksa siswi non-muslim untuk mengenakan jilbab.
Argumen bahwa beberapa siswi nonmuslim bersedia mematuhi dijadikan pembenaran untuk mengharuskan siswi lainnya melakukan hal yang sama. Padahal, kebebasan terkait keyakinan keagamaan seseorang tak bisa dibatasi berdasarkan ukuran jumlah.

Potensi sekolah menjadi pabrik intoleransi juga tak lepas dari lingkungan lembaga pendidikan yang mirip dengan miniatur kehidupan di tengah masyarakat. Dengan demikian faktor-faktor yang mendorong praktik intoleransi di tengah masyarakat juga terbawa ke sekolah.
Misalnya faktor kepentingan agama. Secara mudah dapat dijelaskan bahwa kehendak syiar agama telah mendorong guru maupun murid untuk melakukan tindakan demi memperkuat pengaruh dan eksistensi kelompoknya. Begitu pula faktor di luar kepentingan keagamaan, misalnya kecemburuan ekonomi dan prasangka ras yang sering memicu praktik diskriminasi lalu berlanjut ke sikap intoleran.
Pada saat yang sama banyak celah ruang di lingkungan sekolah yang bisa menjadi saluran intoleransi. Mulai dari kegiatan ekstrakurikuler, belajar kelompok, pemilihan ketua kelas dan OSIS, hingga aturan seragam. Ekspresi dan kontaminasi paham intoleran sering kali bermula dan menyebar dari ruang-ruang tersebut.
Bersumber dari Guru
Intoleransi di sekolah merupakan praktik sistemik dengan guru menjadi salah satu sumber penyebarannya. Melalui materi pelajaran dan kegiatan, guru di sekolah kerap mengajarkan berbagai bentuk sikap, perkataan dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Kecenderungan guru di Indonesia menjadi sumber intoleransi terungkap dalam survei PPIM. Menurut hasil survei tersebut 21% guru tidak setuju kalau ada tetangga nonmuslim yang menyelenggarakan acara keagamaan di rumah mereka.
Sebanyak 29% guru juga tertarik menandatangi petisi menolak kepala dinas pendidikan yang berbeda agama. Sedangkan 34% guru cenderung menolak pendirian sekolah berbasis agama lain di lingkungannya.
Pandangan intoleran guru telah berkembang mengarah radikalisme. Sebanyak 33% guru setuju untuk menganjurkan orang berperang untuk mewujudkan negara Islam. Bahkan, 29% guru setuju untuk berjihad ke Irak dan Suriah.
Angka-angka di atas merupakan indikator bahwa diperlukan evaluasi pada guru-guru di Indonesia, terutama guru yang memiliki pandangan intoleran. Mengingat pandangan intoleran merupakan benih bagi radikalisme dan radikalisme yang dipupuk akan bertransformasi menjadi terorisme, maka penanganan guru yang berpandangan intoleran harus menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Selama ini publik tak pernah tahu tindakan tegas apa yang dikenakan pada guru yang menghasut muridnya untuk tidak memilih murid nonmuslim sebagai ketua OSIS. Kita juga jarang mendengar adanya sanksi dengan efek jera yang diberikan kepada guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, maupun pejabat terkait yang menyokong praktik intoleransi di lembaga pendidikan.
Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan membentuk saluran pengaduan intoleransi di lembaga pendidikan merupakan kabar baik. Namun itu belum cukup. Sekadar teguran juga tak efektif karena sumbernya masih dibiarkan apa adanya.
Harus ada intervensi yang tegas dan sistematis untuk menangani kecenderungan fenomena intoleransi di sekolah agar lembaga pendidikan tak menjadi pabrik intoleransi. Sebab sekolah dan guru memiliki peran yang sangat strategis dalam pembentukan nilai-nilai serta pemikiran murid sebagai generasi penerus bangsa.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI