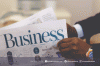Besok tanggal 30 Oktober 1946 satoe hari jang mengandoeng sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoeblik Indonesia sebagai satoe-satoenja alat pembajaran jang sah. Moelai poekoel 12 tengah malam nanti, oeang Djepang jang selama ini beredar sebagai oeang jang sah, tidak lakoe lagi. Beserta dengan uang Djepang itoe ikoet poela tidak lakoe oeang Javasche bank. Dengan ini toetoeplah soeatoe masa dalam sedjarah keoeangan Repoeblik Indonesia. Masa jang penoeh dengan penderitaan dan kesoekaran bagi rakjat kita!
Pidato Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta tanggal 29 Oktober 1946[1]
Wacana Redenominasi rupiah kembali mengemuka pada pertengahan tahun 2019 dalam sesi uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti di DPR. Namun wacana yang pertama kali digulirkan di akhir tahun 2010 oleh Bank Indonesia atau hampir satu desawarsa yang lalu itu masih harus menempuh proses yang panjang untuk dapat mulai diimplementasikan, apalagi sampai saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Redenominasi, sebagai syarat mutlak mewujudkan hal tersebut, belum masuk ke dalam pembahasan di DPR.
Berbagai resiko yang sangat mungkin timbul dari implementasi Redenominasi itu benar-benar membuat semua pihak begitu hati-hati menyikapi hal tersebut. Resiko yang mungkin timbul itu diantaranya adalah kepanikan dan kebingungan masyarakat yang belum paham terhadap hakikat redenominasi yang sebenarnya hanya berupa penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Ada kekhawatiran jika redenominasi disikapi sebagai sanering yang merupakan kebijakan pemotongan nilai uang yang akan berdampak pada pemotongan daya beli masyarakat.
Selain itu resiko lainnya yang dikhawatirkan adalah inflasi yang timbul akibat sikap pembulatan harga barang ke atas seiring denominasi yang diakibatkan ketiadaan uang dalam satuan sen. Contoh, harga barang senilai Rp1.100 akan menjadi Rp1,1 setelah redenominasi. Apabila, tidak ada ketersediaan mata uang baru satuan sen, harga barang akan mengalami pembulatan menjadi Rp2 sehingga mengalami kenaikan hampir 100%.[2]
Namun sebenarnya resiko-resiko tersebut bukan sesuatu yang perlu disikapi secara paranoid. Dalam kenyataannya di masyarakat redenominasi semu bahkan sudah terjadi secara alami. Banyak pelaku usaha resto, caf dan lain-lain baik online maupun offline ketika menawarkan harga barang maupun jasa yang menulis harga ribuan dengan huruf K. huruf K sendiri mewakili arti Kilo dan Kilo sendiri berarti seribu dalam Bahasa Yunani. Sebagai contoh Rp10.000,- ditulis dengan 10K dan banyak orang yang sudah paham hal yang demikian.
Hal ini dapat terjadi karena terlalu banyaknya nominal dalam rupiah secara tanpa sadar dianggap sudah tidak sederhana sehingga merupakan suatu fakta jika redenominasi adalah suatu kebutuhan. Keadaan ini yang disebut dalam asas hukum dengan Het Recht Hinkt achter de feiten aan : hukum selalu tertinggal dari fakta yang muncul di masyarakat.
Karena Fakta yang telah berbicara sendiri (Res Ipsa Loquitur) bahwa redenominasi adalah kebutuhan, maka perdebatan tentang redenominasi sudah harus diakhiri. Yang harus dilakukan adalah bagaimana terhadap resiko yang mungkin timbul, bisa diambil langkah yang tepat untuk mengantisipasinya. Langkah ini dapat dilakukan pada masa transisi sebelum redominasi benar-benar diterapkan sehingga proses redenominasi dapat berjalan tanpa ada gejolak yang berarti.
Dua Sisi Mata Uang
Uang kartal atau uang yang secara fisik diterbitkan oleh bank sentral adalah mata uang yang memilki karakter yang khas. Baik uang kartal berbahan kertas maupun uang kartal berbahan logam pasti memiliki dua sisi. Keberadaan dua sisi ini dapat dimanfaatkan dalam proses transisi redenominasi untuk mempengaruhi psikologis masyarakat bahwa redenominasi adalah bukan sanering.
Pemanfaatan dua sisi mata uang dalam masa transisi redenominasi itu adalah dengan cara Bank Indonesia menerbitkan uang kartal edisi baru atau bisa disebut dengan Rupiah Edisi Baru disingkat REB. Pada satu sisi uang REB dicantumkan nominal yang sekarang berlaku dan membakukan simbol Rp sebelum angka dalam setiap sisi tersebut sehingga akan tertulis yaitu Rp25, Rp50 Rp100, Rp200, Rp500, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000 dan Rp200.000.
Kemudian pada sisi yang lain REB tersebut dicantumkan nominal redominasi dimana untuk membedakan antara nilai nominal yang berlaku sekarang simbol Rp diganti menjadi REB dan ditempatkan setelah angka sehingga menjadi sebagai berikut : Rp1000 = 1REB, Rp2000 = 2REB, Rp5000 = 5REB, Rp Rp10.000 = 10REB, Rp20.000 = 20REB, Rp50.000 = 50REB, Rp100.000 = 100REB dan Rp200.000 = 200REB.
Sementara untuk nominal Rp25, Rp50, Rp100, Rp200, Rp500 dirubah nilainya menjadi sen sehingga ditulis dengan kode SEB (Sen Edisi Baru) sehingga menjadi 2.5SEB, 5SEB, 10SEB, 50SEB. Hal ini karena berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU 7/2011), satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
Salah seorang pejabat BI pada tahun 2017 lalu sempat mengeluarkan pernyataan bahwa BI akan menerbitkan mata uang mata transisi. Uang transisi yang dimaksud adalah uang dengan gambar yang serupa, namun angka nol dalam nominal tersebut akan diubah. (detik.com, 26/7/2017) Namun tentu jika demikian saja, hal tersebut tidak akan cukup. Harus ada karakter yang istimewa dari mata uang transisi yang benar-benar mampu memberi pengaruh secara psikologis kepada masyarakat bahwa redenominasi hanya penyederhanaan angka bukan pemotongan nilai. Karakter itu oleh karenanya harus mampu mengakomodir segala resiko yang timbul dari proses redenominasi.
Karakter tersebut secara langsung dapat terwakili mata uang model REB sebagaimana telah dijelaskan diatas. Dengan adanya 2 nominal yang berbeda pada 2 sisi dari satu mata uang, masyarakat akan dibiasakan untuk berfikir bahwa antara nilai nominal dalam rupiah edisi lama (REL) dengan nominal dalam REB adalah sesuatu yang sama. Begitu pula dengan adanya SEB pada salah satu model REB, maka kekhawatiran inflasi akibat pembulatan ke atas bisa diminimalisir.
Syaratnya adalah dalam masa transisi ini REL lama harus tetap diedarkan. Artinya penerbitan REB harus dilakukan tanpa menarik REL yang beredar. Bahkan REL harus tetap diterbitkan. Misal REB diterbitkan hanya setengah dari jumlah uang baru yang diedarkan oleh BI sehingga pada masa fase transisi ini REL tetap dipertahankan peredarannya. Pada masa ini di masyarakat akan terdapat REL dan REB tanpa perbedaan penggunaan sama sekali
Masa ini dapat ditentukan lamanya misal dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam masa ini REL dengan REB harus dibiarkan berbaur sehingga orang akan terbiasa membeli sesuatu dengan REL tapi mendapat pengembalian REB dan begitu sebaliknya. Selain itu, penulisan segala laporan & catatan transaksi keuangan dalam masa transisi awal harus tetap mempertahankan penulisan dengan pola lama.
Penggunaan REB benar-benar hanya digunakan dalam transaksi tunai sebagai fase awal mempengaruhi psikologi masyarakat. Dengan cara demikian pada setiap uang kartal dari REB yang beredar akan secara perlahan memberi pengaruh psikologis pada setiap pemegangnya bahwa antara Rp1000 = 1REB adalah satu nilai yang sama dan demikian juga dengan nominal lainnya.
Untuk efektivitas REB sebagai mata uang transisi, harus pula masa transisi ini dibagi ke dalam beberapa fase sampai redenominasi benar-benar final. Fase pertama, adalah fase sosialiasi dalam jangka waktu tertentu semisal 1 tahun. Fase kedua, adalah fase dimana REB mulai diedarkan dan hanya digunakan dalam transaksi tunai.
Fase ketiga, fase dimana nominal dalam satu sisi REB yang menggunakan nilai redenominasi mulai digunakan dalam transaksi non tunai serta digunakan pula dalam berbagai laporan dan catatan transaksi keuangan namun tetap dengan menyertakan pencatatan dengan model lama yaitu dengan nominal redenominasi disandingkan dengan nominal tanpa redenominasi.
Fase keempat, fase dimana nominal redenominasi dalam REB digunakan dalam transaksi tunai dan non tunai serta laporan dan catatan transaksi keuangan secara tunggal tanpa dibareng nominal lama. fase kelima adalah fase terakhir ketika satu sisi dari REB yang masih menggunakan nominal lama diganti sepenuhnya dengan nominal redenominasi.
Secara hukum penggunaan istilah REB ini tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan apapun. Hal ini karena UU 7/2011 hanya menentukan bahwa mata uang Indonesia adalah Rupiah. Penggunaan istilah rupiah edisi baru oleh karenanya tidak mengubah mata uang Indonesia, tetapi hanya menambahkan suatu istilah yang memudahkan penggunaan redenominasi di masa transisi.
Dalam 25 tahun ke depan jika seluruh tahapan sukses dilaksanakan maka menjelang perayaan seabad Indonesia merdeka di tahun 2045 Indonesia akan memiliki mata uang yang bukan hanya sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara yang dapat dibanggakan sehingga hari dimana tutupnya suatu masa penuh penderitaan dan kesukaran bagi rakyat Indonesia sebagaimana diharapkan Bung Hatta 73 tahun lalu menjelang diterbitkan Uang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 benar-benar tuntas diwujudkan.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI